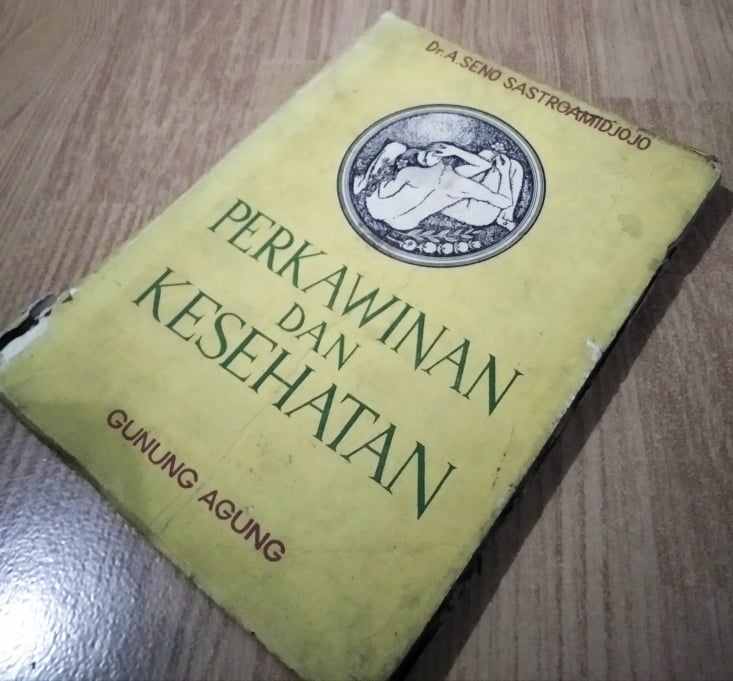Islam bisa diterima di masyarakat secara luas di Nusantara khususnya Jawa melalui beberapa spektrum, salah satunya menggunakan wayang dalam menyampaikan ajaran Islam. Wayang seperti yang kita pahami bersama sebagai salah satu metode yang digunakan oleh para Wali Songo untuk menyampaikan ajaran Islam melalui proses akulturasikan ajaran Islam dengan kebudayaan. Atau sering kita kenal dengan istilah Jowo digowo, Arab digarap.
Namun, seperti yang kita ketahui bersama jagad dunia sosial media akhir-akhir ini banyak memunculkan polemik keagamaan terkait ajakan pemusnahan wayang yang dilakukan salah satu penceramah, ustad yang tidak familiar bagi masyarakat Indonesia. Baginya, wayang tidak sesuai dengan kaidah Islam, Islam yang harus dijadikan tradisi, bukan malah sebaliknya menjadikan tradisi sebagai Islam, harus kita tinggalkan dan lebih baik dimusnahkan, kurang lebih demikian yang disampaikan dalam dakwahnya.
Sebelum menyampaikan hal demikian seyogyanya seorang dai terlebih dulu memahami secara mendalam konsep Islam seperti apa yang ada di dalam wayang Jawa. Kita pahami bersama bahwa di dalam wayang konsep tasawuf, khususnya tasawuf falsafi sangat melekat, seperti yang dibenarkan oleh Ibn Arabi, al-Jili, Suhrawardi, Buhanpuri dan lain sebagainya. Ajaran seperti ittihad, hulul, dan wadah al-wujud sangat mempengaruhi keberislaman masyarakat Jawa yang disebarkan melalui wayang.
Selain itu harus diingat bahwa wayang merupakan tradisi keraton dan keraton Jawa Tengah yang menampilkan diri sebagai sosok yang membela kesalehan Islam normatif baik ideal keagamaan ataupun secara sosial. Jadi kalau wayang beserta ajarannya dinisbatkan kepada ajaran sebelum Islam dalam hal ini Hindu dan Budha itu tidak mungkin. Kenyataan ini sudah begitu jelas dan gamblang terkait keislaman wayang adalah Islam yang bercorak tasawuf atau ajaran esoteris Islam. dengan artian bahwa ajaran tasawuf dapat ditampilkan dalam dunia pewayangan.
Kita lihat misalnya hubungan manusia dengan Tuhan dalam konsep Islam Jawa dapat dilihat melalui hubungan dalang dengan wayang-Nya. Mark R. Woodward menandaskan bahwa Allah bagaikan dalang, sedangkan ciptaan-Nya, termasuk manusia tidak lebih dari pada seorang boneka wayang di layar (Mark R.Woodward, 1999:48). Dengan begitu wayang sangat tergantung kepada cara dalang mempermainkannya begitu juga dengan manusia yang bergantung kepada Tuhan-nya.
Bahkan hubungan wayang dengan dalang bagaikan hubungan manusia dengan Tuhan ditandaskan dalam Serat Dewaruci dalam pupuh Megatruh:
Kelir jaga gumelar wayang pinanggung// adapun makhluk Ing Widi// gedebog bantal wedung// belencong andam Ing urip// gamelan gending Ing lakon.
Artinya: Kelir jagad itu yang kelihatan, wayang-wayang yang ditancapkan dikiri dan kanan// menggambarkan golongan makhluk-makhluk Tuhan// Batang pisang ialah bumi// Blencong adalah lampu kehidupan// Gamelan adalah keserasian antara peristiwa-peristiwa.
Makna teks di atas diartikan sebagai simbol bahwa Tuhan yang mahatahu sebagai dalang yang luhur, pencipta yang agung. Dimaksud dalang yang luhur adalah yang menentukan lakon, perjalanan hidup manusia, yakni Tuhan yang tersembunyi di balik peristiwa. Semua yang ada di dunia ini hanyalah ciptaan Tuhan semesta alam, manusia sebagai wayang tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengikuti gerak ontis yang sudah ditulis oleh sang dalang.
Bagi Sudirman Tebba, dalam pelakonan wayang, sebelum dilahirkan di dunia, nasib perjalanan hidupnya sudah ditentukan terlebih dahulu (Tebba, 2007:206). Islam mengajarkan ketika roh sudah ditiupkan dalam janin sang ibu pada usia empat bulan, segala yang akan terjadi di kemudian hari terhadap wayang baik jodo, pati, rejeki sudah dimaktubkan dalam lauhul mahfudz. Dengan begitu sebelum wayang digerakkan ke atas kelir, alur ceritanya sudah selesai disusun sebagai lakon.
Bahkan terkait hubungan antara dalang dengan wayang dipertegas oleh Serat Dewaruci dalam pupuh Dhandhanggula:
Umpamane ki dalang lan ringgit// lir mayangga lawan kang amurba// anilih sinilih reke// tan nyata kalihipun// lamun ora silih-sihilih// kalawan kang amurba// wayange puniku// mangkana gusti kaula// nora nyata yen data silih-sinilih// Allah lawan Muhkamad.
Artinya: dalang dan wayang-wayang itu// seperti bayangan dan pencipta// ada pengaruh timbal balik// bila pengaruh timbal balik// antara pencipta dan bayangan-Nya tidak ada// keduanya tidak nyata// demikian juga antara Gusti dan kawula// tanpa adanya pengaruh timbal balik keduanya tidak menampilkan diri// seperti Allah dan Muhammad.
Dengan begitu jelaslah sudah, hubungan wayang dengan dalang menggambarkan manifestasi paham manunggaling kawula-Gusti. Gusti dan kawula, Tuhan dan manusia, yang digambarkan hubungan antara dalang dan wayang berhadap-hadapan dalam hubungan yang kait mengait, saling tergantung, yang satu tak dapat ada tanpa yang lain. Bila tiada Gusti, maka tidak ada kawula. Jadi pandangan umum mengenai Gusti dan kawula, pencipta dan ciptaan-Nya mengenai Allah dan Muhammad, dicairkan dan dijadikan sesuatu yang nisbi, yang tidak dapat merupakan kenyataan muktahir.
Paham semacam demikian tentunya hanya ada di dalam ajaran Islam, yang tergambar dengan jelas dalam bingkai tasawuf falsafi. Kecerdasan para penyiar Islam Nusantara khususnya di Jawa, bisa mengakulturasikan ajaran Islam dengan kebudayaan, supaya Islam bisa diterima masyarakat secara luas. Hal ini saya rasa yang harus dimiliki oleh setiap pendakwah dalam menyebarkan ajaran Islam. Sebab, seorang pendakwah bukan hanya cerdas dalam intelektual, melainkan juga harus cerdas dalam spiritual.
Kecerdasan spiritual ini yang akan menjadikan seorang pendakwah memahami Islam dengan segala aspeknya secara universal. Bukan malah sebaliknya memerangi sesuatu hal yang dianggapnya tidak ada di dalam kebudayaan Timur Islam (Arab), bahkan mengharuskan dimusnahkan kebudayaan setempat tanpa memahami sosial kebudayaan yang mereka ajak dalam kebaikan. Para wali dulu, dengan gerakan tasawuf falsafi dan sunni membuat ramuan baru yang menjadi pandangan dunia Jawa yang akhirnya membentuk konsep etika Jawa. Hal ini yang harus dilanjutkan oleh pendakwah di era sekarang.