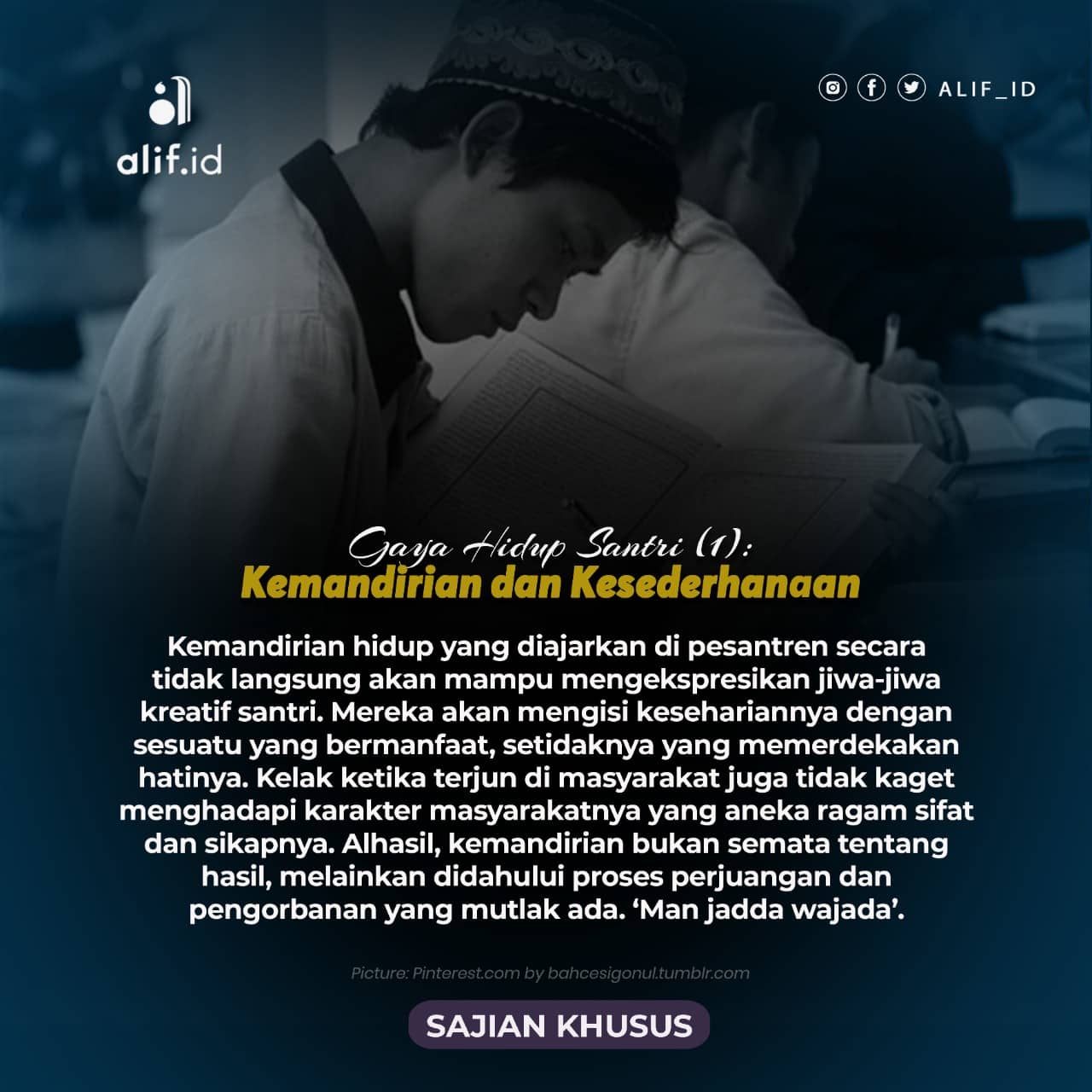Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Rabi’ul Awal atau yang disebut juga dengan istilah bulan Maulud. Momentum sakral kelahiran Rasulullah Saw. Tepatnya tahun ke 1443 atas bangkitnya semangat umat Islam untuk berhijrah. Selamat atas kedewasaan usianya, atau juga bisa dikatakan cukup tua. Sayangnya ada yang berbeda dengan peringatan Maulid Nabi tahun ini. Gegap gempita mengenang bulan kelahiran Sang Nabi dibatasi. Pandemi virus corona ini belum sepenuhnya pergi dari muka bumi.
Segala aspek kehidupan belum bebas sepenuhnya. Dalam hal ini pesantren adalah yang paling berani mengambil jalan ninjanya dengan ‘mendirikan negara di dalam negara’. Pesantren mencoba membebaskan diri dengan menciptakan kebijakan berani dalam mengatur tata kelola hidup para penghuninya. Tentu setelah mempertimbangkan berbagai konsekuensinya.
Iya, pesantren adalah di antara sedikit sekali lembaga pendidikan yang berani menerapkan kebijakan tegas memberlangsungkan pembelajaran tatap muka di era new normal hari ini. Tindakan ini diambil dengan catatan khusus bahwa kaum pesantren memang tidak lagi terkoneksi dengan dunia luar, dan juga setelah melalui proses karantina serta protokol kesehatan ketat agar memastikan bahwa virus berbahaya tidak masuk ke dalamnya.
Pesantren sendiri identik dengan sisi unik yang membedakannya dengan kehidupan pada umumnya. Para santri selalu dituntun, atau lebih tepatnya dipaksa dan dituntut untuk melakukan hal-hal yang bernilai ibadah. Dalam hal ini, tanggung jawab mendidiknya dibebankan kepada para pengurus, sementara para orang tua hanya berkewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya dan mengiriminya doa. Tentu juga bukan hak para orang tua untuk melakukan intervensi atas kebijakan-kebijakannya, karena pesantren memiliki standard aturan tersendiri yang diberlakukan di sana.
Segala bentuk kebijakan yang diberlakukan di pesantren adalah hasil ikhtiyar para pengurus dan telah mendapatkan restu dan persetujuan dari kiai pimpinannya. Jadi, bukan hal etis jika ada wali santri yang meragukan kebijakan pesantren, apalagi sampai melibatkan polisi demi menuntut ketidakterimaan atas jeraan hukum atau perlakuan yang diasumsi kurang manusiawi yang dijalani anaknya.
Wajar bukan?. Untuk memperoleh apa yang dicitakannya, manusia hanya perlu berusaha. Sebesar bagaimana perjuangan yang dilakukannya, maka itu sebanding dengan hasil yang kelak didapatkannya. Prinsipnya, aktivitas hidup yang manusia lakukan di muka dunia hanya dua, jika tidak maksiat, ya taat, tidak lebih.
Konsekuensinya, untuk melakukan aktivitas yang bernilai ketaatan, manusia harus mengarahkan perilakunya pada hal yang berpotensi melahirkan ketaatan. Dalam konsep ulama, ada istilah mempersedikit makan, mengurangi tidur dan mengurangi intensitas berbicara. Merealisasikannya, konon Syekhona Kholil ketika mesantren di Makah hanya makan kulit semangka. Tujuannya, agar tidak kekenyangan dan memudahkannya fokus untuk belajar dan mencerna materi pelajaran.
Lha saya kurang bisa menahan lapar. Terus bagaimana? Yang terpenting adalah bagaimana badanmu tidak menunaikan tuntutan nafsu untuk bermaksiat. Dalam hal ini pesantren tidak merasa cukup hanya dengan mencegah santri dari berbuat dosa, melainkan juga menuntunnya untuk memperbanyak beribadah. Salat berjamaah, menghapal bait-bait qasidah, berpuasa sunah, membatasi jatah makan dan sebagainya. Pesantren membentengi seminimal mungkin agar para santri terbiasa dengan prilaku dan komitmen mengisi harinya dengan baik.
Suatu ketika ada seorang ibu-ibu wali santri yang hendak menyambangi putra yang dititipkannya di pesantren asuhan Kanjeng Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Sebagaimana lazimnya pesantren, di situ si anak tersebut dididik untuk melakukan tirakat, mujahadah dan lelaku sebagaimana yang telah dipraktikkan para ulama saleh terdahulu.
Di pesantren si ibu pun menjumpai putranya dalam keadaan kurus kering dan tampak sedang menikmati roti kering. Melihat kenyataan di pesantren yang semacam ini, si ibu pun merasa iba dan hendak melakukan protes kepada Syekh Abdul Qadir al-Jilani selaku pengasuh pesantren. Alangkah terkejutnya si ibu begitu menyaksikan Kanjeng Syekh sedang menikmati hidangan ayam goreng. Si ibu pun makin berang perasaannya. Para santri dipaksa menikmati kudapan tak bergizi, sementara pengasuhnya berlebih-lebihan. Si ibu mempertanyakan letak keadilan di sana.
Menanggapi hal itu, Kanjeng Syekh pun meletakkan tangannya di atas tumpukan tulang belulang ayam yang telah dimakannya. “Bangkitlah dengan izin Allah, Dzat yang mampu menghidupkan kembali tulang-tulang yang telah rusak” perintah Kanjeng Syekh. Maka tulang belulang yang sudah hancur itu pun menyatu kembali dan bermetamorfosis menjadi ayam jantan seutuhnya, dan bahkan mengeluarkan suara kokoknya: “Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, dan Syekh Abdul Qadir adalah wali Allah.”
Tak pelak jika kejadian ini turut membungkam ibu tersebut. Kanjeng Syekh pun berujar: “Jika putramu sudah mampu melakukan hal seperti ini, maka makanlah apapun yang dikehendakinya.”
Kisah Kanjeng Syekh di atas cukup menggugah kita bahwa sudah semestinya ‘pendidikan bukan hanya transfer ilmu pengetahuan’, melainkan mempelajari luasnya samudera cerita hidup. “Merasakan pahitnya kengoyoan dalam menuntut ilmu lebih aku sukai daripada penyesalan di hari nanti gegara menyia-yiakan waktu di masa muda.” Demikian ungkapan Imam Syafi’i.
Sekali lagi pesantren bukan berarti perbudakan model baru atau yang diistilahkan dengan neokolonialisme oleh Soekarno. Pesantren memberi kesempatan terbuka bagi santri mendapatkan hak dan kebebasannya. Si ibu dalam kisah di atas adalah potret masyarakat kebanyakan yang membiarkan geliat pertumbuhan persepsi melengkung akan realitas, sementara ayam jago adalah bukti keperkasaan yang diperoleh dengan upaya yang tidak mudah. Tidak mudah lho melatih ayam untuk berkokok indah, apalagi sampai mampu bertauhid dan menyaksikan kewalian Kanjeng Syekh.
Kemandirian hidup yang diajarkan di pesantren secara tidak langsung akan mampu mengekspresikan jiwa-jiwa kreatif santri. Mereka akan mengisi kesehariannya dengan sesuatu yang bermanfaat, setidaknya yang memerdekakan hatinya. Kelak ketika terjun di masyarakat juga tidak kaget menghadapi karakter masyarakatnya yang aneka ragam sifat dan sikapnya. Alhasil, kemandirian bukan semata tentang hasil, melainkan didahului proses perjuangan dan pengorbanan yang mutlak ada. ‘Man jadda wajada’.
Referensi:
Az-Zarnuji, Ta’limul Muta’alim
Abdul Karim Al-Barzanjy, Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilany