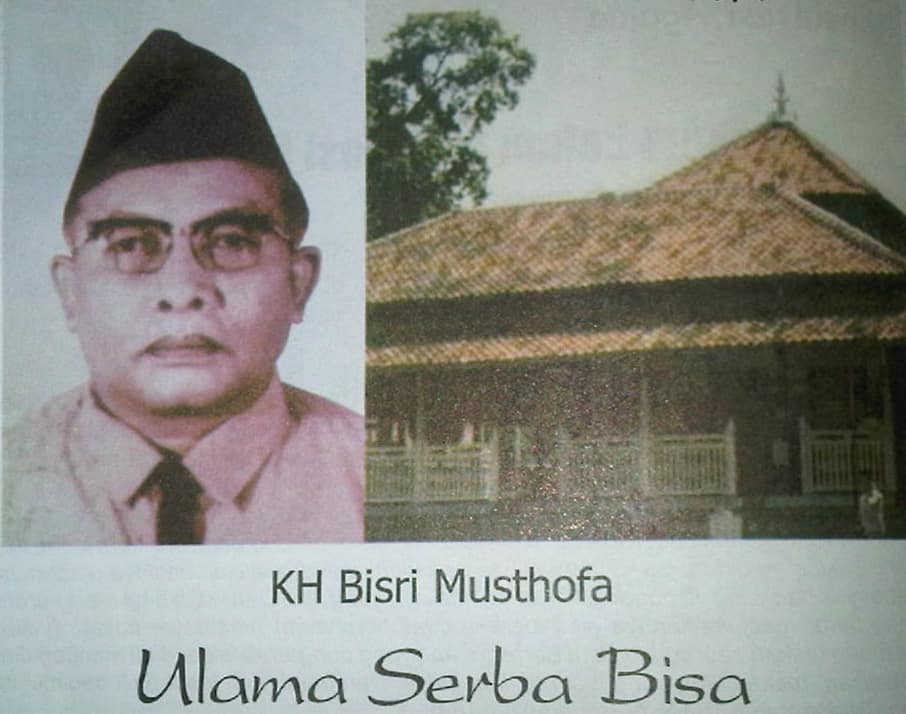Ketika Khalil al-Farahidi Ditanya Pendeta Tentang Iman pada yang Gaib

Imam Khalil al-Farahidi adalah salah satu ulama ahli bahasa Arab terkemuka. Salah satu jasa dan kontribusi terbesarnya dalam perkembangan keilmuan bahasa Arab adalah memberikan tanda baca (fathah, dhammah, kasrah, dan sukun). Bahkan, Gus Dur secara khusus pernah memuji tentangnya dalam sebuah tulisan berjudul “asal-usul tradisi keilmuan di pesantren” yang dimuat di jurnal Nuansa terbitan P3M.
Salah satu kisah tentang Imam Khalil Al-Farahidi ini juga dimuat oleh Abu Ali Muhsin At-Tanukhi (w. 384 H) dalam karya tebalnya berjudul Nisywar Al-Muhadharah wa Akhbar al-Muhadharah berikut ini:
At-Tanukhi berkata, Abul Husain bin Hisyam menceritakan dari Abul Hasan Zakariyya bin Yahya bahwa ia mendengar informasi dari Abul Abbas Al-Mubarrad yang sebelumnya diminta untuk menceritakan tentang Imam Khalil.
Dalam salah satu perjalanan saya berjumpa dengan seorang rahib atau pendeta di sebuah tempat khusus mereka: tempat pertapaan para rahib (sawma'ah).
Saat itu Aku mendapatkan sebuah ujian di mana hari yang kian sore membuatku sedikit khawatir karena berada di sebuah padang pasir. Aku pun bermaksud untuk meminta izin kepada sang rahib untuk ikut beristirahat di tempat ia bertapa.
Lalu ia berkata, "Siapa kamu?"
"Saya Khalil bin Ahmad," jawabku.
"Oh…..kamu yang mengklaim sebagai seorang pemimpin umat dan salah satu orang alim di kalangan bangsa Arab?" Sergah sang rahib.
Aku menjawab, "Memang orang-orang menyebutku demikian, padahal aku bukanlah seperti yang digambarkan orang-orang tentangku."
Sang rahib kembali berkata, "Baiklah. Jika engkau bisa menjawab tiga pertanyaan yang aku ajukan dengan jawaban yang tepat dan masuk akal, maka aku akan mempersilakan engkau beristirahat di sini dan aku akan memuliakan engkau sebagai salah satu tamu istimewaku. Namun, jangan gembira dulu. Sebab, jika tidak bisa menjawab pertanyaanku dengan baik maka tidak akan aku izinkan engkau berteduh di sini."
Aku berkata kepadanya, "Baiklah. Silakan sebutkan tiga pertanyaanmu."
"Bukankah kita bisa menunjukkan sesuatu yang tampak sebagai dalil bagi hal-hal yang bersifat gaib?" Ia memulai pertanyaannya.
"Ya", jawabku.
Ia melanjutkan, "Pertama, engkau berkata bahwa Allah Swt bukanlah dzat yang berupa "jisim", juga bukan "aradh", tidak ada satu pun makhluk yang menyerupai-Nya. Lalu bagaimana kita bisa yakin atas hal itu?"
"Kedua, engkau juga berkeyakinan bahwa manusia di surga kelak akan dapat menikmati makanan dan minuman, tapi mereka tidak membuang hajat. Bagaimana bisa orang yang makan dan minum tidak buang air kecil dan juga hajat besar?"
Terakhir, ketiga, "Engkau juga bilang bahwa kenikmatan di surga tidak akan terputus, sementara engkau lihat sendiri (di dunia ini) tidak ada sesuatu apa pun yang abadi?"
Lalu aku mencoba menjawab tiga pertanyaan yang ia ajukan.
"Mengenai sesuatu yang bisa kita saksikan "asy-Syahid" sebagai dalil atas keberadaan yang tidak tampak "al-Ghaib" kita bisa melihat bahwa misalnya tentang keberadaan Allah Swt, maka kita bisa melihat pada ketentuan-ketentuan-Nya. Misalnya, kita mengetahui bahwa di setiap makhluk yang dirimu termasuk di dalamnya terdapat ruh. Namun, bisakah kita tunjukkan di mana ia berada? Bagaimana wujudnya? sifatnya? bentuknya? Lalu kita saksikan bahwa setiap manusia akan mati dan ruh itu keluar darinya. Apakah bisa dilihat dengan mata? Jadi, untuk menentukan adanya ruh itu bisa dilihat dari perkara-perkara yang tampak darinya; pekerjaan dan gerakan-gerakannya bahwa ia ada di dalam tubuh kita.
Kedua, terkait dengan pertanyaanmu mengapa ahli surga tidak buang hajat meskipun mereka makan dan minum? Saya tunjukkan kembali dengan dalil yang bisa kita saksikan mengenai hal itu. Bukankah bayi yang ada di dalam kandungan itu mereka makan di dalam tubuh ibunya? Namun mereka tidak buang air kecil dan besar?
Sedangkan terkait pertanyaanmu yang ketiga tentang kenikmatan di surga kelak yang tidak terbatas oleh waktu, kita bisa menyaksikan bahwa sebuah hitungan diawali dengan angka satu. Jika kita ingin melakukan pembilangan yang tidak ada akhirnya, maka kita bisa mengulanginya dengan cara melipatgandakannya menjadi dua, empat, dan seterusnya."
"Mendengar jawaban-jawaban tersebut sang rahib terdiam sejenak, lalu ia membukakan pintu untukku dan memuliakanku sebagaimana layaknya seorang tamu," tutur Imam Khalil memungkasi kisahnya.