Kiai Sahal, Mendayung di antara Liberalisme dan Fundamentalisme (1)
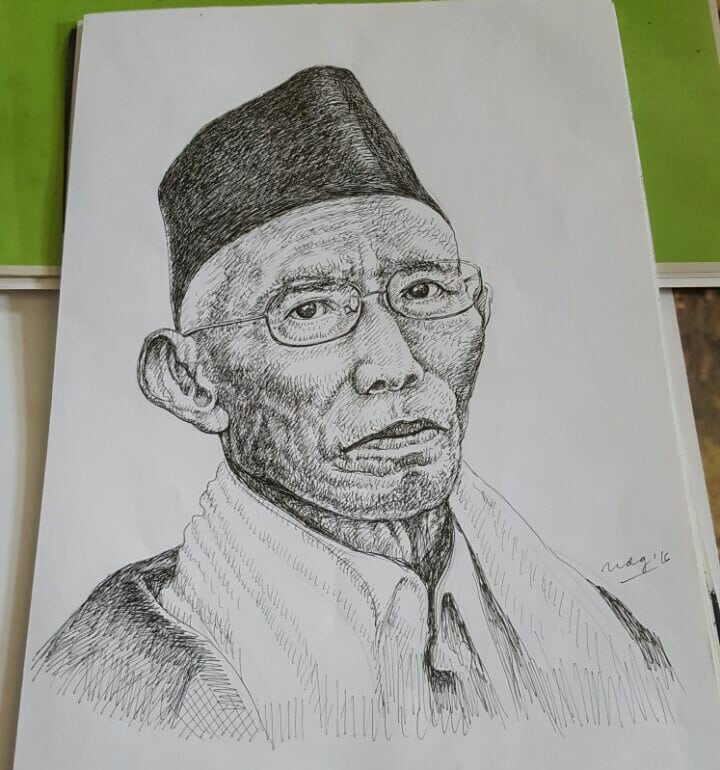
Ada problem krusial bagi fikih di negara yang mayoritas muslim dan bukan negara Islam seperti Indonesia. Fikih di satu sisi sebagai perangkat hukum dan nadi dalam beragama, tidak mengikat dan hanya menjadi semacam pelengkap.
Seringkali Islam sebagai agama mayoritas hanya "dimanfaatkan" oleh negara atau kelompok masyarakat pada saat-saat tertentu dan menjadi sangat politis. Hal ini dapat dilihat dalam kronik perjalanan kebangsaan kita, persoalan agama sampai saat ini masih menjadi semacam "problem" sosial yang masuk dalam istilah SARA, ini salah satu dari sekian bukti masih belum selesainya hubungan antara agama dan negara.
Perdebatan sengit soal dasar negara, akankah berasaskan agama (Islam) atau tidak telah terjadi sejak bangsa ini lahir dan senantiasa akan tetap berlangsung. Mulai dari pencabutan tujuh kata dalam sila pertama Pancasila, lalu dikeluarkannya dekrit Presiden Soekarno untuk menyudahi polemik sidang konstituante yang tidak rampung-rampung, sampai yang kekinian menguatnya Islam partisan baik di dalam maupun diluar parlemen.
Semua itu adalah upaya gigih kelompok Islam partisan dalam memperjuangkan Islam/syariat/fikih sebagai aturan resmi negara secara formal-konstitusional, gerakan ini semakin menguat dan "ngadar" akhir-akhir ini, baik melalui langkah politis biroktaris maupun gerakan sosial ekstra parlementer.
Di sisi lain fikih seakan stagnan, tak berkembang, jumud dan malah menjadi masalah daripada solusi kehidupan itu sendiri.
Fikih seringkali menjadi momok kemajuan dan peradaban, fikih pada "kenyataaannya" secara umum tak mampu memberikan jawaban atas tiap perubahan zaman.
Alquran satu-satunya sumber auntentik dan tidak ada keraguan di dalamnya sebagai rujukan utama dalam memahami Islam, dipakai bahan dan alat utama untuk "menyerang" fikih oleh kelompok liberal sekaligus kaum fundamental.
Bagi kelompok liberal jelas Alquran adalah sumber pokok yang utama di dalamnya tidak mengatur secara detail dan teknis soal aturan main kehidupan (malah masih bisa ditafsirkan). Jadi semua masih bisa dimaknai dan tafsirkan sesuai kebutuhan zaman, fikih dianggap sesuatu yang ketinggalan zaman.
Sedangkan fikih sebaliknya, seakan mempersempit dan menjadi bagian dari persoalan kehidupan, maka kalau ada produk fikih yang tidak atau kurang sesuai dengan tuntutan demokrasi dan kekinian akan menuai kritik dan evaluasi secara radikal.
Sementara menurut kelompok Islam fundamental malah sebaliknya, produk-produk fikih dianggap banyak yang tidak islami dan melenceng dari kemurnian Islam, bagi kelompok ini sumber utama dan pertama bahkan bisa jadi satu-satunya dalam Islam hanyalah Alquran maka ijtihad dan pendapat ulama tidak begitu diperhitungkan bahkan diabaikan.
Islam ala Indonesia adalah sebuah varian baru dalam ber-Islam
Islam Indonesia sangat khas, ada semacam adagium entah darimana, "Jawa" khususnya peradaban dan etikanya sesungguhnya tak pernah ditaklukkan, termasuk oleh Islam, sehingga sampai hari ini masih bisa kita lihat dan jumpai ajaran Islam yang seakan malah "terjawakan".
Dalam proses penyebaran Islam Jawa memiliki sejarah yang panjang dan kuat. Dua hal penting, Indonesia yang mayoritas rakyatnya muslim dan jawa yang memiliki peradaban serta nilai kehidupan yang endegeuneus, tua dan independen, saat ini yang mewarnai dan membingkai "Islam Arab", yaitu Jawa dan Indonesia, yang sering kita sebut Islam Nusantara
Perjumpaan Islam (tentu di dalamnya juga fikih) dengan Jawa menghasilkan pemahaman dan ritual yang unik dan khas, ini merupakan faktor utama yg memengaruhi. Sementara di sisi lain ke-Indonesiaan dengan NKRI dan Bineka Tunggal Ika sebagai semacam puncak kearifan masyarakat bangsa ini merupakan faktor penentu kedua yang sangat berpengaruh dalam penempatan agama-Islam-fikih di Indonesia, yaitu sebagai aliran Islam mainstream dan kelompok paling besar dan masih eksis sampai hari ini (katakanlah ahlussunah wal jama'ah), menempatkan fikih di luar negara meski masih berhubungan sesuai kebutuhan.
Walisongo dengan kearifan lokalnya dalam menyebarkan Islam yang rahmatan lil alamin, telah berhasil dengan baik mewariskan pola dan strategi dakwahnya kepada para sesepuh kiai-kiai besar Indonesia khususnya kiai NU.
Transformasi dan ideologisasi keilmuan dan karakter ke-Islaman yg rahmatan lil-alamin ala walisongo ini terbukti manjur membawa alur-nalar Islam khas Indonesia yang ramah dan menghargai nilai-nilai lokalitas sampai hari ini, yaitu keselarasan, perpaduan dan keharmonisan antara beragama-Islam dan berbangsa-Indonesia.
Genealogi dan akar nalar ini tentu tidak hadir dan eksis begitu saja, namun sejak dari awal sangat disadari dan menjadi pilihan para kiai dan pendiri bangsa sebagai pemahaman dan perilaku, aturan yang pas dan tepat untuk dan bagi bangsa ini, karena Indonesia sangat majemuk dan plural.
Islam pada hakikatnya sebagai agama Samawi, datang terakhir menjadi antitesa dan penyempurna ajaran-ajaran sebelumnya.
Islam yang memiliki sejarah panjang serta nilai-nilai dari agama-agama dan para Nabi sebelum Nabi Muhammad tentu sangat mengakomodir dan menghargai berbagai nilai dan budaya diluar dirinya, maka dari itu sudah sewajarnya Islam lebih arif dan bijak dalam memandang kehidupan karenanya ia adalah rahmatan lil-alamin.
Pandangan dan pemahaman semacam ini tentu tidak berjalan begitu saja dan tanpa tantangan, sejak dulu dan saat ini semakin menguat, kelompok fundamental yang ingin menjadikan Islam resmi sebagai dasar negara dan kelompok liberal yang menganggap fikih sebagai hambatan senantiasa mereduksi dan menempatkan fikih sebagai sebuah masalah.
Padahal sebenarnya fikihlah yang menjadikan Islam itu aplicated dan avialable serta membumi, dengan "alat takar" bernama maqashidusy syar'ah.
Dengan fikih, kita mampu menghitung dan menimbang-nimbang maslahah atau madorot perbuatan kita, kebijakan kita. Sebaliknya, tanpa fikih, Islam hanya bahasa langit dan sulit menjadi penerang dan pemandu kehidupan manusia, karena bagaimanapun juga, "nash" (Alquran dan hadis) telah berhenti, maka tidak lagi mungkin menanyakan setiap persoalan kehidupan langsung dari sumbernya. Di sinilah ulama sebagai warasatul anbiya' melalui fikih menjadi penerus para nabi penghubung antara umat dengan Islam dalam menghadapi kehidupan yang senantiasa berkembang dan berubah.
Di sini fikih menghadapi tantangan berat, karena memang dari awal Islam mainstream Indonesia yang rahmatan lil alamin tidak berniat menjadikan syariat-fikih sebagai hukum formal dasar negara, dengan demikian fikih akan dibiarkan sendiri hidup dan berjuang ditengah masyarakat untuk menjadi norma dan etika sosial.
Di sisi lain ketika fikih tidak menjadi hukum negara ia tentu tidak akan mengikat dan mudah ditinggalkan, sehingga fikih lambat laut tidak lagi menjadi penting dan dilaksanakan serta menjadi pegangan hanya bagi kelompok yang taat dan hanya menjadi bahan kajian di pesantren atau bangku kuliah.
Karenanya fikih akan sulit berkembang dan akhirnya mudah diserang oleh kelompok liberal atau dicibir dan dimaki oleh kelompok fundamental. Karena pada kenyataannya yang tampak fikih itu kuno jumud dan tidak solusif.





