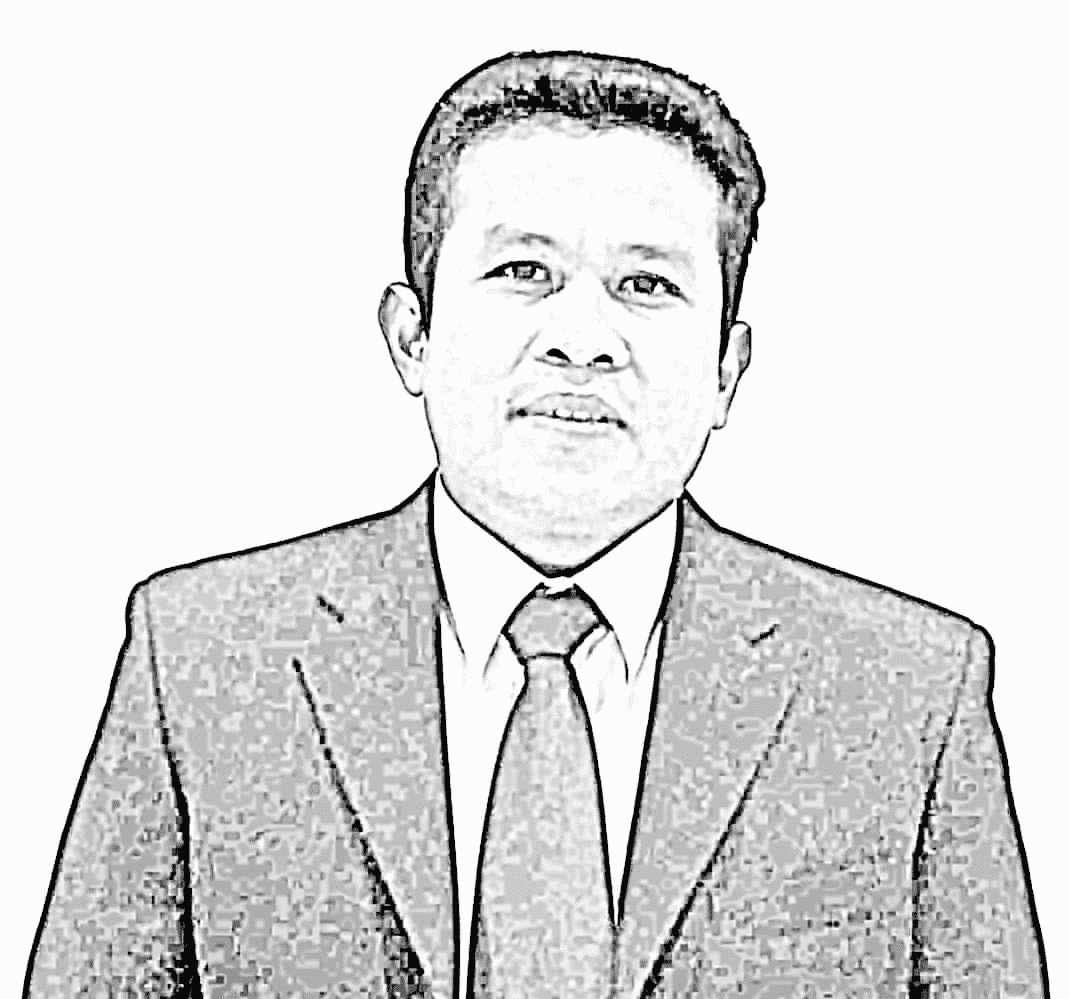Saya akan menjawab pertanyaan sahabat Ghozi Ahmad: apakah boleh hukum negara bertentangan dengan hukum agama?
Sebelum ke poin ini, saya perlu tegaskan titik tolak dan prinsipnya.
Pertama, Indonesia bukan negara Islam, meskipun bukan negara sekuler. Negara ini berdiri di atas sila Ketuhanan Yang Maha Esa, yang pernah mengalami fase sejarah dengan tambahan tujuh kata: ... ‘dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.’ Rumusan ini, yang dikenal dengan Piagam Jakarta, didrop pada 18 Agustus 1945 demi persatuan nasional. Jadilah Indonesia negara nasionalis-religius, bukan negara nasionalis sekuler. Negara membentuk Departemen/Kementerian Agama untuk memfasilitasi pelaksanaan ajaran agama bagi setiap pemeluknya.
Kedua, Kedualam konstruksi negara bukan-bukan ini (bukan negara agama dan bukan negara sekuler), doktrin-doktrin partikular agama tetap akan menjadi norma privat sampai dia diputuskan sebagai norma publik melalui undang-undang. Misalnya, ketentuan soal salat, zakat, puasa, dan haji tetap akan menjadi norma privat kaum Muslim sampai dia diundangkan sebagai norma publik. Jika, misalnya, ada undang-undang—setelah mengalami proses legislasi—mewajibkan orang Islam menjalankan rukun Islam, maka kewajiban salat, zakat, puasa, dan haji bukan sekadar kewajiban terhadap agama, tetapi kewajiban terhadap negara. Apa mungkin ini terjadi? Kalau pertanyaannya apa mungkin, jawabannya mungkin. Negara seperti Arab Saudi melakukannya. Kalau pertanyaannya apa perlu? Jawabannya tidak perlu. Tapi Islam jelas mengakui hak Ulil Amri untuk menetapkan kebijakan. Ayatnya jelas:
« ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » (النساء : ٥٩)
Kalau belajar ushul fiqh, ayat ini adalah contoh bagus tentang jenis ayat muthlaq (tanpa syarat) sekaligus muqayyad (bersyarat). Kepatuhan kepada Allah dan Rasulullah bersifat mutlak. Kepatuhan kepada Ulil Amri bersifat muqayyad. Qayyid-nya disampaikan oleh Nabi:
« السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بمعصية٠ فإذا امر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » (متفق عليه واللفظ للبخاري)
“Patuh dan taat wajib kepada pemimpin sejauh dia tidak menyuruh maksiat. Jika orang disuruh maksiat, tidak ada kewajiban mendengar dan menaati” (HR. Bukhari-Muslim).
Ayat dan hadis ini adalah dalil tentang kapasitas Ulil Amri untuk menetapkan kebijakan. Sebab, tidak semua hal tertuang secara jelas dalam Kitab Suci dan sunnah Nabi. Dalam hal kebijakannya baik dan sesuai dengan syariat, wajib ditaati. Bahkan, bobot wajibnya semakin kuat karena orang berarti menaati ajaran agama sekaligus aturan negara. Ini pernyataan Syeikh Sulaiman al-Bujairami dalam Hâsyihah al-Bujairamî ala –l Khatîb, Juz 2 h. 473:
« انه إذا أمر بواجب تأكد وجوبه ، وإن أمر بمندوب وجب ، وإن أمر بمباح فإن كان فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب ، بخلاف ما إذا أمربمحرم أو مكروه أو مباح لا مصلحة فيه عامة »
“Sesungguhnya Ulil Amri jika memerintahkan kepada sesuatu yang wajib, maka hukum wajibnya semakin kuat. Jika dia memerintahkan kepada barang sunnah, makanya status hukumnya menjadi wajib. Jika dia memerintahkan kepada mubah, jika di situ ada kemaslahatan umum seperti larangan MEROKOK, maka jadi wajib. Ini berbeda jika dia memerintahkan kepada barang haram, makruh atau mubah yang di situ tidak ada kemaslatan umum.”
Pernyataan ini diulang dan diperkuat oleh Syeikh Nawawi al-Bantani dalam Nihâyat al-Zayn Juz 1 h. 112. Ini artinya, Islam adalah agama yang mengakui kapasitas Ulil Amri untuk menetapkan kebijakan. Bahkan, kebijakan pemerintah bisa menambah bobot hukum syariat, dari sunnah jadi wajib, dari mubah jadi wajib. Terkecuali dalam hal maksiat, prinsip Islam mewajibkan Muslim untuk patuh kepada pemerintahnya. Jika diperintah kepada maksiat, orang Islam tidak wajib patuh dan mendengar. Tidak patuh apa berarti melawan? Tidak selalu. Bisa sekadar mengabaikan. Apa boleh melawan dengan kekuatan senjata? Kata Rasulullah, tidak boleh, kecuali dia melarang kamu untuk salat.
Ketiga, sekarang saya ingin menjawab poin pertanyaannya: apakah boleh hukum negara bertentangan dengan hukum agama? Boleh-boleh saja. Ini negara demokrasi. Bahkan, dalam hadis Nabi, beliau telah mengisyaratan kemungkinan kebijakan Ulil Amri bertentang dengan syariat. Dalam keadaan itu, kita berhak mengabaikan hukum negara yang bertentangan dengan hukum agama. Hukum agama di situ tentu saja sesuatu yang manshûsh bayyinan (dinyatakan secara eksplisit dalam Qur’an dan Sunnah) seperti miras, bukan perkara yang statusnya mukhtalaf atau diperselisihkan.
Keempat, dalam sejarah politik Islam, ada negara yang mengadopsi hukum Islam sebagai hukum negara. Ini terjadi di dawlah Islamiyah masa silam. Masa kini diterapkan oleh Arab Saudi. Hukum Islam bekerja di ranah state. Ada juga hukum Islam berjalan di ranah civil society. Orang Islam menjalankan syariatnya, asal tidak diganggu oleh negara. Di Indonesia, ini berlangsung sejak zaman kolonial. Meskipun kita dijajah, pemerintah Hindia Belanda tidak melarang umat Islam untuk salat, bahkan memfasilitasi pelaksanaan ibadah haji dengan menyediakan kapal. Format ini sudah memenuhi kualifikasi sebagai Darul Islam, sebagaimana putusan Muktamar NU di Banjarmasin tahun 1935. Bisa saja, dalam negara merdeka, syariat Islam atau prinsip-prinsip hukum Islam diadopsi sebagai hukum negara, asal telah melalui proses legislasi yang disepakati pembentuk undang-undang. Dalam hemat saya, pelaksanaan syariat Islam, yang bersifat fardhu ain, tetap dibiarkan berlangsung di ranah masyarakat tanpa campur tangan negara. Campur tangan negara bekerja di ranah publik, dalam mendukung kemaslahatan bersama, tanpa perlu membawa embel-embel syariat atau simbol-simbol agama lainnya yang bersifat partikular.