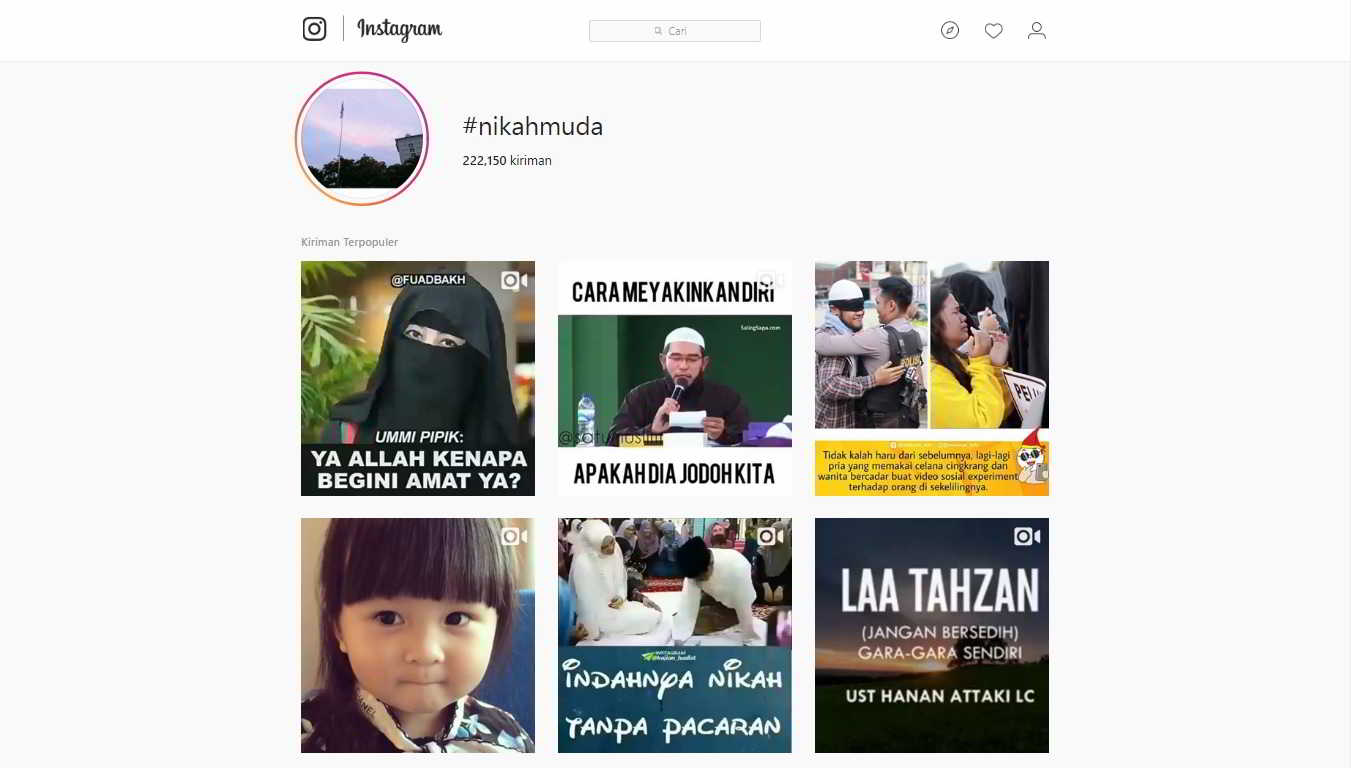Kenyataan yang mengindikasi bahwa perempuan masih dianggap warga kelas dua masih saja terlihat di berbagai belahan dunia. Hal ini terlihat pada aturan-aturan, kebiasaan, budaya, dan penafsiran agama, yang mengarah pada pengekangan dan perampasan hak-hak perempuan. Ada sebagian tradisi masyarakat Islam yang beranggapan bahwasannya suara perempuan adalah aurat, sehingga interpretasi ini dapat menghalangi kaum perempuan dalam mengaktualisasikan dirinya di ranah publik.
Istilah kesetaraan gender dalam tataran praksis memang hampir selalu diartikan sebagai kondisi “ketidaksetaraan” yang melahirkan diskriminasi, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil, dan semacamnya yang dialami oleh kaum perempuan. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika persoalan tentang perempuan dapat mengundang rasa simpati yang cukup besar dari masyarakat luas sehingga muncul upaya-upaya untuk memperbaiki kondisi kaum perempuan dengan penyadaran dan pemberdayaan.
Dalam tradisi Islam, apabila kita melihat reslasi antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif tasawuf, kita akan melihat adanya kesetaraan. Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan ini terekam dalam kitab Dzikru an-Niswah al-Muta’abidaat as-Shufiyaat yang menceritakan tentang daftar perempuan-perempuan yang memiliki tingkat spiritalisasi yang tinggi. Dalam kitab tersebut disebutkan 84 perempuan yang termasuk kedalam ahli sufi. kitab ini dikarang oleh Abdurrahman Muhammad ibn Al-Husein As-Sulami An-Naysaburi atau yang dikenal dengan As-Sulami pada abad ke-10 M. As-Sulami sendiri adalah ulama muslim pada awal abad ke-9 hingga 11 Masehi yang sering mengumpulkan anekdot para wali dan sufi. Namun, yang spesial dari beliau adalah perhatian besarnya terhadap perempuan-perempuan sufi.
Salah seorang filolog ketika mentahqiq atau menyuntng kitab Dzikru an-Niswah al-Muta’abidaat as-Shufiyaat yakni Rkia E. Cornell menyatakan bahwa As-Sulami adalah milik sekelompok kecil cendekiawan muslim laki-laki tetapi berkomentar bahwa “sufi perempuan melayani saudara laki-laki mereka, belajar dengan mereka, mendukung mereka secara finansial, dan bahkan para sufi perempuan ini melampaui laki-laki dalam hal pengetahuan.
Dalam kitab tersebut kita bisa melihat bahwa ketika beliau menjelaskan tentang Hukaimah guru dari Rabi’ah Al-Adawiyah beliau berkata :
(حكيمة الدمشقية): و كانت أستاذ رابعة وصاحبتها قال في ترجمة العابدة
As-Sulami berkata ketika menjelaskan seorang ahli ibadah yakni Hukaimah Ad-Dimasyqiyyah : Hukaimah adalah guru dari Rabi’ah dan sahabatnya.
Dalam bagian lain beliau juga menjelaskan tentang hikayat dari Dzu An-Nun Al-Mishri beliau berkata :
قال حاكيا عن ذي النون المصري, يصف العابدة (فاطمة النيسابورية ) : هي ولية من أولياء الله عز و جل, وهي أستاذي
As-Sulami berkata ada hikayat dari Dzu An-Nun Al-Mishri yang mensifati seorang ahli ibadah yakni Fatimah An-Naisaburiyah : Fatimah An-Naisaburiyah adalah salah seorang wali Allah, dan dia adalah guruku.
Dari kedua pernyataan As-Sulami di atas bisa kita perhatikan terdapat dua kata ustadz (أستاذ), kata ustadz ini biasanya digunakan untuk laki-laki, namun dalam pernyataan As-Sulami di atas kata ustadz dipakai untuk mensifati perempuan. Nah, menurut Rkia E. Cornell menjelaskan tentang konteks pernyataan As-Sulami di atas, bahwasannya dalam tradisi sufi perempuan itu sama dengan laki-laki. Karena ketika seorang perempuan sudah berada di jalan Allah, dia adalah insan kamil dan hamba Allah. Tidak ada perbedaan lagi antara laki-laki dan perempuan.
Demikianlah As-Sulami menjelaskan dalam kitabnya Dzikru an-Niswah al-Muta’abidaat as-Shufiyaat bahwa pada abad ke-10 terdapat perempuan-perempuan hebat yang berjasa dalam keilmuan Islam terutama Tasawuf. Tidak hanya itu, kitab ini juga menjelaskan bahwasannya dalam tradisi tasawuf eksistensi perempuan, kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan peran perempuan itu ada sejak abad ke-10 Masehi.