Istilah Kafir dalam Perdebatan Ushul Fikih
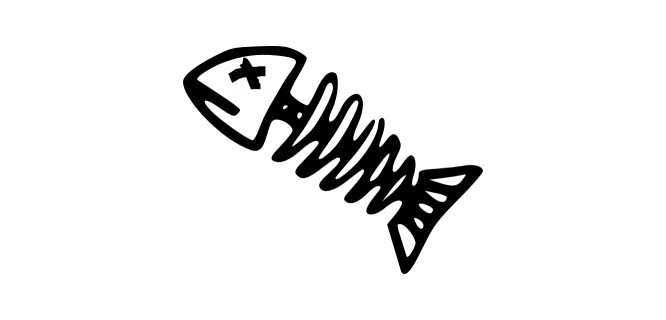
Sebagai seorang muslim, tentu kita meyakini adanya pencipta alam. Para ulama kalam menyepakati bahwa adanya Tuhan bukan hanya karena Alquran berkata demikian, namun juga karena akal manusia mengharuskannya.
Permisalan sederhana dibuat untuk justifikasi: Andai ada kopi di depan kita, dan ada orang berkata bahwa kopi itu tidak ada yang membuat namun ‘tiba-tiba ada’, maka tentu akal kita akan menolak hal ini mentah-mentah.
Nah, begitu juga alam, akal kita akan mentah-mentah menolak anggapan alam tidak ada yang menciptakan. Inilah yang dinamakan dalam ilmu kalam (disebut juga ilmu tauhid) dengan wajib aqli, yakni sesuatu yang diharuskan oleh akal.
Para ulama bersepakat bahwa mujtahid (orang yang mengerahkan daya dan upayanya dalam memikirkan sesuatu) mengenai masalah syariat adalah orang yang dinaungi kebenaran. Maka seluruh empat mazhab adalah benar menurut Allah Swt. Sedangkan untuk ijtihad masalah aqliyyat, para ulama berkata bahwa yang benar di sisi Allah Swt hanya satu, yakni Islam ahl sunnah wa al-jama’ah.
Namun literatur usul fikih mencatat ada dua ulama yang tidak sependapat soal terakhir ini. Beliau adalah al-‘Anbari (‘ain, bukan hamzah, wafat 168 H), dan al-Jahizh (wafat 255 H). Al-‘Anbari adalah hakim Basrah dan seorang ulama Sunni sementara Al-Jahizh adalah sastrawan dan teolog Muktazilah.
Kedua ulama tersebut berpendapat bahwa orang yang berpikir dalam hal aqliyyat tidak bisa divonis salah—seluruhnya adalah benar. Tentu yang dimaksud benar di sini bukanlah ‘sesuai dengan kenyataan’, karena tidak mungkin dua hal yang berbeda itu sesuai dengan kenyataan. Yang mereka maksud benar adalah mujtahid dalam aqliyyat tidak berdosa meskipun salah. Konsekuensi pendapat ini adalah Socrates, Descartes, Aquinas, bahkan Hawking sekalipun tidak bisa dihukumi salah. Karena pendapat mereka muncul dari proses pemikiran (ijtihad).
Mengenai referensi pendapat beliau berdua, penulis teringat sebuah nazam kitab Jam’ul Jawami’ bernama Kaukabus Sathi’ ketika penulis di pesantren dulu. Nazam bait 1276-1277 itu berbunyi:
مُخْطٍ أَثِيْمٌ كَافِرٌ لَمْ يُعْذَرِ # وَقَدْ رَأَى الْجَاحِظُ ثُمَّ العَنْبَرِي
لَا إِثْمَ فِي العَقْلِيِّ ثُمَّ المُنْتَقَى # إِنْ يَكُ مُسلِمًا وقِيْلَ مُطْلَقًا
“(Orang yang mengingkari Islam itu) keliru dan kafir serta tidak bisa dimaafkan. Namun al-Jahizh dan al-‘Anbari berpandangan bahwa tidak ada dosa bagi mujtahid dalam permasalahan aqli. Sebagian menafsiri “jika muslim”, namun sebagian berkata “mutlak muslim atau bukan”.”
Para ulama tentu bereaksi tentang hal ini. Banyak yang menafsiri ucapan beliau berdua. Al-Syahrastani (Al-Milal: 1/240) sendiri mengakui bahwa penafsiran para ulama tentang ucapan al-‘Anbari tampak jauh dari konteks. Karena kontroversi ini, tidak sedikit yang menyangkal pendapat al-‘Anbari dan al-Jahizh.
Salah satunya adalah al-Ghazali. Dalam Al-Mustashfa beliau menganggap banyak sekali kontradiksi dalam ucapan al-‘Anbari. Tidak mungkin, menurut al-Ghazali, dua hal yang berlawanan dalam satu waktu adalah benar dalam waktu yang sama. Tidak mungkin berhala adalah Tuhan dan bukan Tuhan dalam waktu yang sama. Maka kebenaran pasti hanya satu.
Namun seperti sudah penulis singgung di atas, bahwa yang dimaksud benar oleh Al-‘Anbari dan Jahizh bukan ‘sesuai kenyataan’ tapi ‘tidak berdosa meskipun salah’, demikian dijelaskan oleh ar+Razi (Al-Mahshul: 6/30). Maka sangkalan al-Ghazali dengan sendirinya gugur.
Namun meski menyangkal, al-Ghazali sebenarnya punya pandangan yang kurang lebih sama. Dalam karangannya berjudul Faishalut Tafriqah halaman 22 beliau pernah berkata bahwa non-muslim ada tiga macam. Yang pertama adalah orang yang tidak sempat didakwahi. Golongan ini sudah jelas tidak bisa dikatakan masuk neraka sebagaimana dalam ajaran teologis Asya’iroh bahwa mereka termasuk ahlul fatroh yang tidak diazab oleh Allah di akhirat.
Pembagian kedua adalah non-muslim yang ingkar kepada kebenaran Islam meskipun telah mengetahuinya. Yang terakhir adalah non-muslim yang mendengar Islam, tapi yang sampai ke telinganya adalah hal yang salah. Dia mendengar hal-hal buruk tentang Islam dan tidak mendengar sifat-sifat indah Nabi SAW. “Menurutku,” ujar beliau, “mereka ini sama seperti golongan pertama.” Yakni ahlul fatroh. Maka jika ada pendakwah yang menyebarkan Islam dengan keras dan orang-orang menolak, tentu saja jari telunjuk harus diacungkan ke arah pendakwah itu.
Al-Zarkasyi sendiri menolak jika dikatakan al-Ghazali cenderung setuju dengan al-‘Anbari dan al-Jahizh. Beliau berdalih dengan penolakan al-Ghazali dalam al-Mustashfa di atas. “Sedangkan yang ada di Kitab Tafriqah itu,” Al-Zarkasyi menulis dalam Bahrul Muhith (6/238), “Beliau hanya menjelaskan tentang orang yang tidak terkena dakwah.” Penolakan al-Zarkasyi ini tampak kurang tepat sasaran, karena sudah jelas al-Ghazali juga menjelaskan tentang orang yang terkena dakwah tapi yang didengar adalah kekeliruan tentang Islam.
Pandangan Al-Zarkasyi juga ditolak oleh Al-Syaukani yang mengakui posisi al-Ghazali mengenai persoalan ini. Dalam Irsyadul Fuhul (2/1064) beliau menulis, “Al-Ghazali sendiri cenderung condong ke pendapat ini (al-‘Anbari dan al-Jahizh) dalam Kitab Tafriqah.”
Lantas bagaimana dengan dalil-dalil naqli tenang kekafiran? Bukankah banyak ayat yang mengatakan orang kafir tidak masuk surga? Apakah pendapat al-‘Anbari dan al-Jahizh tidak bertentangan dengan ayat-ayat tersebut?
Ar-Razi dalam Al-Mahshul (6/30) sempat merekam jawaban Al-‘Anbari dan al-Jahizh. Beliau berdua mengatakan bahwa makna kafir adalah orang yang menutup diri dari sesuatu. Dan seseorang tidak bisa disebut menutup diri dari sesuatu kecuali dia mengingkarinya atau ‘dia taklid kepada leluhurnya’. Ar-Razi menulis jawaban mereka:
فَأَمَّا العَاجِزُ المُتَوَقِّفُ الذي بَالَغَ في الطَلَبِ فَلَمْ يَصِلْ فَهَذَا لايكونُ سَاتِرًا لشَيْءٍ ظَهَرَ عندَهُ فلا يكونُ كافِرًا
“Adapun orang (berpikir) yang sudah tidak sanggup—yang mana dia sudah berusaha mencari kebenaran namun tidak berhasil—maka orang seperti ini tidak bisa disebut sebagai orang yang menutup diri dari sesuatu yang sudah tampak. Maka dia bukanlah orang kafir.”
Dalam membaca analisa ar-Razi tentang hal ini penulis sendiri merasa bahwa diksi yang dipilih ar-Razi cenderung tidak menolak pendapat al-‘Anbari dan al-Jahizh—untuk tidak mengatakan setuju. Meskipun demikian, penulis tidak memiliki bukti kuat terhadap hal ini
Namun Ibnu Hajar Asqalan sendiri meriwayatkan dalam Tahdzibut Tahdzib (9/8) bahwa Al-‘Anbari sudah mencabut pendapat beliau ini. Wallahu a’lam.
Demikianlah, barangkali pendapat al-‘Anbari dan al-Jahizh terlalu berlebihan untuk aliran Islam mainstream—dan barangkali salah. Namun hal ini menunjukkan bahwa khazanah keilmuan sangatlah luas. Perlu kajian yang terus menerus untuk mengungkap dan menyingkap khazanah ini agar bisa diketahui khalayak. Apalagi beberapa hari terakhir kita dihebohkan dengan sekelompok orang yang sangat mudah sekali melemparkan vonis syirik. Naudzubillah.





