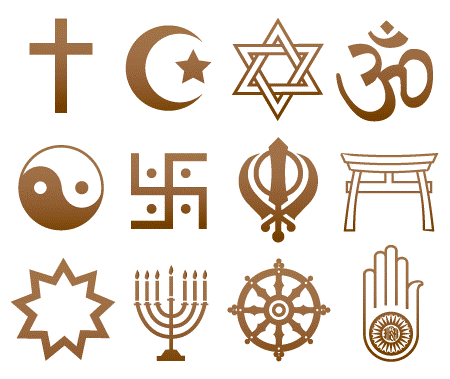Dunia seakan tidak pernah berhenti untuk terus berdinamika dalam berbagai hal, termasuk dalam dinamisasi behavioral (tingkah laku) dalam masyarakat. Perilaku masyarakat tentunya memiliki perbedaan dalam setiap daerah dan wilayah kebudayaannya, yang mana tergantung dari adat, tradisi ataupun kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat wilayah tersebut. Sehingga pada akhirnya, akan didapati kearifan lokal yang akan berbeda-beda dan beragam banyaknya, termasuk membicarakan teologis (konsep ketuhanan) dalam agama dari daerah tersebut,
Ada sebuah upaya terobosan untuk merumuskan “teologi muslim kontemporer tentang agama-agama dunia” yang tengah digiatkan sejumlah pemikir muslim antar-benua, yang umumnya bekerja sebagai guru besar di berbagai universitas dunia. Dalam Upaya itu, mereka menyelenggarakan konferensi pertama pada 27-30 Mei 2007 di Universitas al-Akhawayn, Ifrane, Maroko. Hasil-hasil pertemuan itu yang diakhir Januari 2008 lalu di release secara terbatas menampilkan sejumlah kerangka pemikiran menarik (Azra, 2020, pp. 78-79).
Konferensi Ifrane dalam konteks itu menawarkan kerangka yang disebut sebagai “religious vernacular”. Istilah ini dipinjam dari teori antropologi tentang “vernacular cultures” yang berdasarkan pada konsep sosio-lingusitik tentang Bahasa-bahasa vernacular (local) yang relatif berbeda dalam hal-hal tertentu dengan bahasa standar (Azra, 2020, p. 79).
Konsep Religous Vernacular tersebut memberikan sebuah gagasan yang sangat substantif dalam perkara untuk menangani permasalahan intoleransi dan eksklusifitas terhadap pemahaman ritual dan tradisi yang berlaku dalam sebuah agama tertentu. Tentunya, maksud dari pokok pikiran religious vernacular tersebut mengacu pada upaya agar masyarakat bisa memahami dan menghargai yang dilaksanakan setiap agama tertentu, baik tradisi tersebut berkorelasi dengan kebudayaan setempat atau dengan keagamaan (teologi) setempat.
Sejauh menyangkut teologi, seperti dikemukakan Seyyed Hossein Nasr, salah satu tantangan pemikir Muslim dewasa adalah bagaimana kita sebagai muslim dapat menjaga kebenaran Islam, ortodoksi Islam dan struktur dogmatis tradisi Islam, tetapi pada saat yang sama juga membuka diri kita pada tradisi-tradisi keagamaan lain. Stockholm bukan hanya orang tua, tapi juga banyak yang muda-muda, bahkan anak-anak (Azra, 2020, p. 79).
Tantangan seperti ini tidaklah unik, dan juga tidaklah baru, karena kaum muslim telah menghadapi tantangan seperti itu di masa silam. Dan para ulama dan pemikir muslim juga telah memberikan respons intelektual mereka terhadap tantangan tersebut. Tetapi pada akhir modernitas dan globalisasi sekarang, tantangan itu kelihatan kian sentral. Kini tantangan itu bahkan merupakan salah satu beberapa tantangan utama terhadap para pemuka dan pemikir agama, baik secara internal di dalam satu agama, maupun eksternal, antara satu agama dengan agama lain (Azra, 2020, p. 79).
Selain daripada keragaman konsep teologis, keragaman itu terlihat juga pada tingkat sosial-budaya yang kemudian mengalir ke dalam aspek-aspek kehidupan lain seperti politik. Keragaman ekspresi sosial-budaya banyak bersumber dari tradisi dan adat lokal, yang kemudian mengalami proses “islamisasi” dan menjadi apa yang disebut sejarawan Marshall Hodgson sebagai “Islamicate” yakni bidang kehidupan yang dipengaruhi Islam sehingga menjadi Islami (Azra, 2020, pp. 19-20).
Mengamati keragaman sosial-budaya “islamicate” itu, Azyumardi Azra menawarkan adanya delapan ranah budaya Islam (cultural Islamic spheres) yang berbeda satu sama lain dna memiliki karekter dan distingsinya masing-masing. Kedelapan ranah budaya Islam itu: Arab, Persia (Iran), Turki Anak Benua India, Nusantara, Sub-Sahara Afrika (Afrika Hitam), Sino-Islamic, dan belahan dunia Barat (Eropa, Amerika dan Australia).
Sering orang Islam sendiri tidak merasakan perbedaan-perbedaan itu, karena tidak melihat langsung ekspresi kehidupan sosio-kultural kaum muslimin yang beragam, atau juga sebab tidak bisa menggunakan perspektif perbandingan masyarakat-masyarakat Muslim (Azra, 2020, p. 20).
Bagaimana seharusnya menyikapi perbedaan-perbedaan itu? Tidak bisa lain adalah dengan memperkuat sikap tasamuh, toleransi, khususnya intra-Islam, di sini, tak bisa lain, jelas memerlukan penguatan dan revitalisasi Islam Washathiyah (moderasi Islam) dari waktu ke waktu (Azra, 2020, p. 20).
Dalam pandangan K.H Hasyim Muzadi, ummatan washatan adalah umat yang selalu bersikap tawashut (jalan tengah) dan i’tidal (bersikap adil-seimbang); menyeimbangkan di antara iman dan toleransi. Keimanan tanpa toleransi membawa kearah eksklusifisme dan eksterimisme; dan sebaliknya, toleransi tanpa keimanan berujung pada kebingungan dan kekacauan. Dengan toleransi, ummatan washatan berusaha hidup Bersama secara damai baik, intra maupun antar-agama (Azra, 2020, p. 19).
Dengan demikian, konsep religious vernacular memiliki relevansi dengan upaya harmonisasi dan menyatukan perbedaan di antara beragam tradisi keagamaan dan kebudayaan dalam masyarakat, dengan dan harus tetap memakai langkah moderasi (jalan tengah) agar masyarakat bisa memahami, menghargai dan menghormati kebiasaan-kebiasaan atau ritual-ritual yang berlaku dalam keagamaan dan kebudayaan yang lain, terkhususnya dalam konteks ini kita membicarakan kebhinnekaan yang sangat majemuk di Indonesia, agar terwujud Indonesia yang damai dan sejahtera.