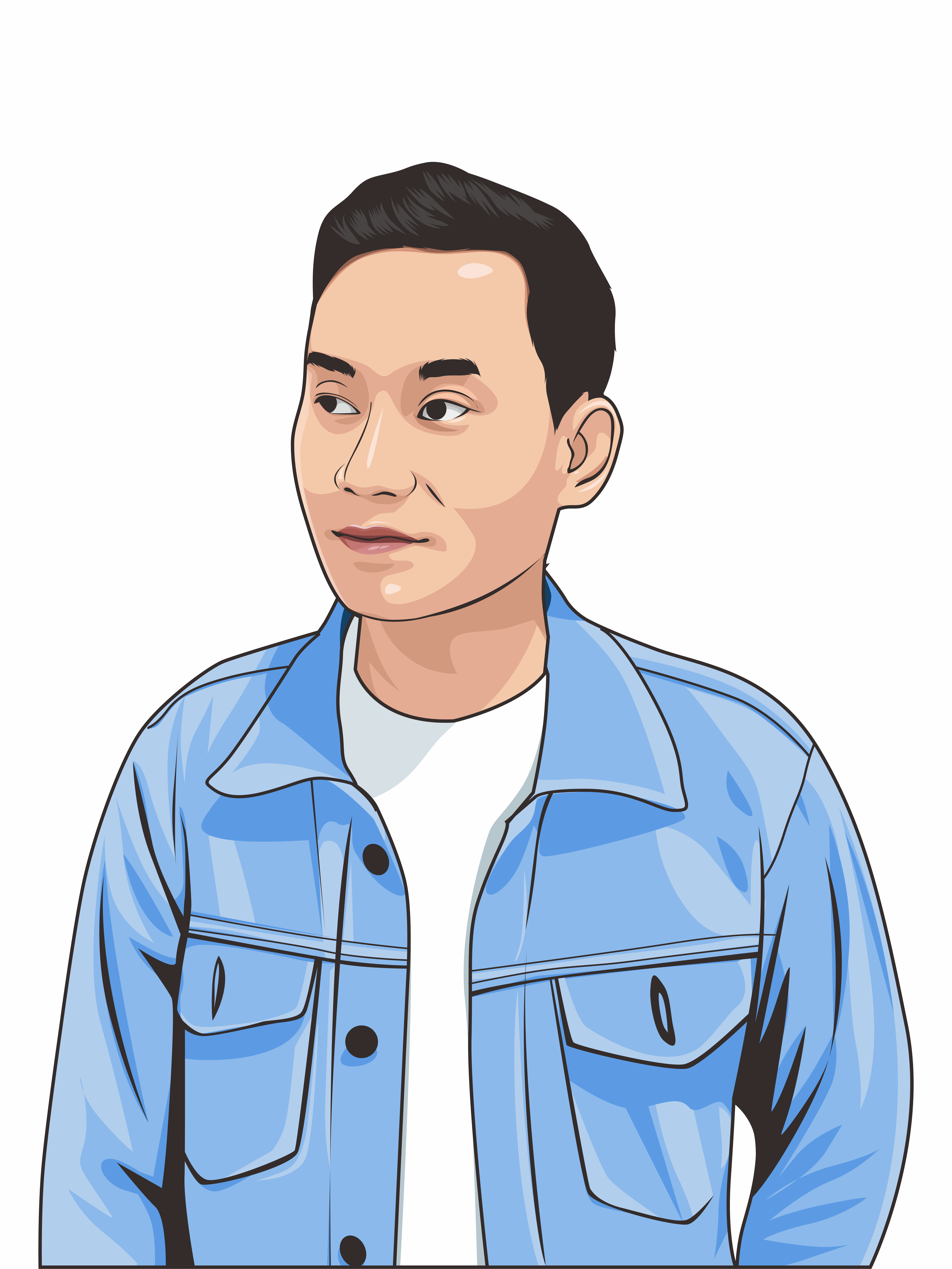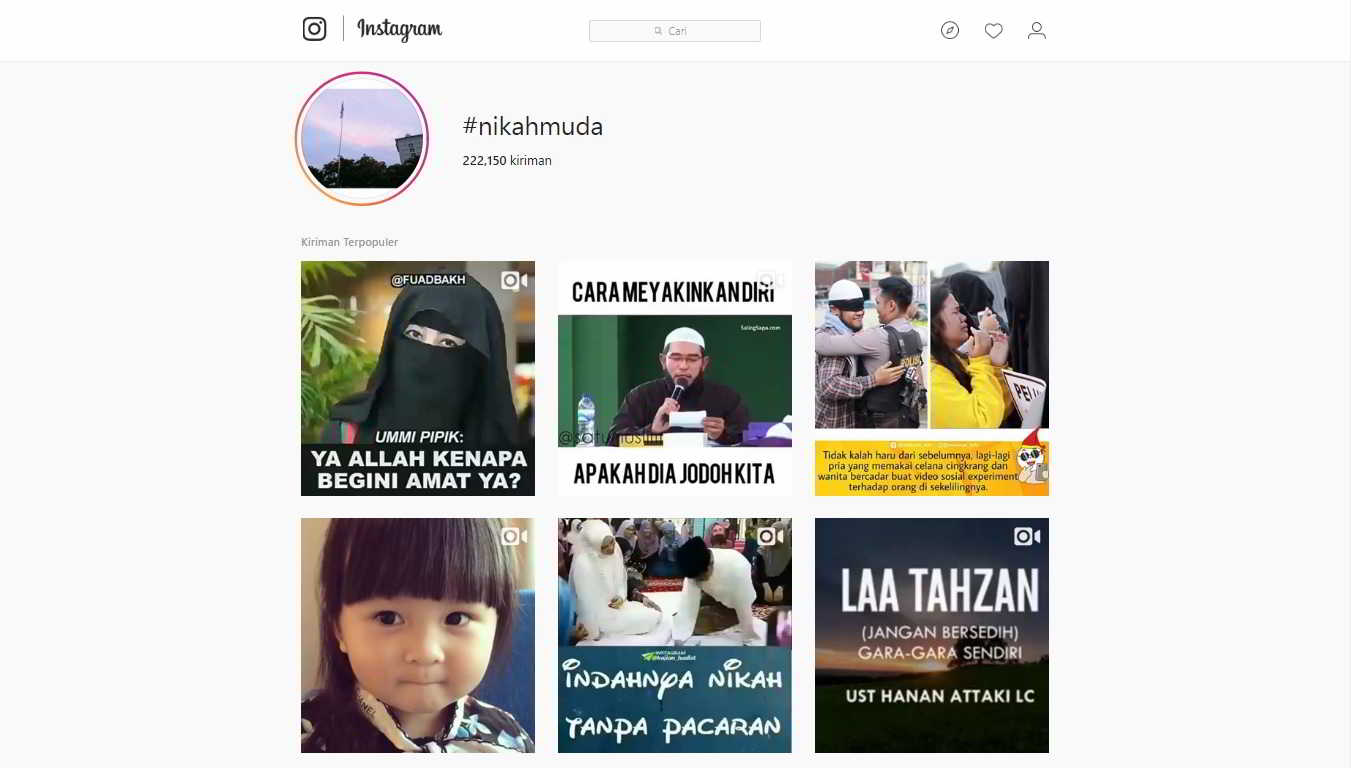Perempuan
|
Ulama Perempuan
Mursyid Perempuan Tarekat Naqsyabandiyah di Madura
Isqomar
Jumat, 9 April 2021 | 05:00 WIB

Secara historis, sedikit sekali dokumentasi tertulis tentang kiprah perempuan yang berkaitan dengan dakwah dan Islamisasi. Bisa dilihat misalnya, literatur yang menjelaskan tentang sepak terjang ulama perempuan dalam penyebaran Islam di Indonesia yang bisa dihitung jari. Tidak terkecuali dalam dunia tarekat, di mana mayoritas syekh, khalifah dan mursyid (pembimbing) tarekat didominasi oleh kaum laki-laki (patriarkis).
Sejak kemunculannya, tarekat telah menduduki posisi penting karena tidak bisa dipisahkan dari ritus sosial-religius orang-orang Madura. Bahkan, Martin van Bruinessen, menyebut dalam bukunya Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia, bahwa pandangan orang-orang Madura; “Islam sudah hampir sama artinya dengan tarekat Naqsyabandiyah”.
Di Madura, tarekat sudah ada sejak paruh baya abad ke sembilan belas, di mana tarekat-tarekat yang mendominasi Madura saat itu adalah; Naqsyabandiyah, Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dan Tijaniyah. Masifnya tarikat diikuti oleh orang-orang Madura, disebabkan oleh faktor kegemarannya pada kasaktean (spiritual-magis). Maka posisi kiai, pemimpin tarekat atau tokoh agama dan sejenisnya, memiliki otoritas yang tinggi, bahkan sampai mengesampingkan otoritas kebangsawanan tradisional.
Menariknya, eksistensi tarekat di Madura memiliki keunikannya tersendiri. Letak keunikan tersebut terletak pada mursyid-nya yang perempuan. Padahal bila dilacak dalam sejarah dunia tarekat, belum ditemukan mursyid, syaikh atau khalifah sebuah tarekat yang mursyid-nya seorang perempuan; tidak saja di Indonesia, tidak juga di Negara-negara lain.
Maka berbeda dengan tarekat Naqsyabandiyah di Madura, di mana mursyid-nya adalah perempuan bernama Nyai Thobibah. Sayangnya, biografi tentang Nyai Thobibah sendiri masih abu-abu. Meski begitu, diketahui bahwa Nyai Thobibah adalah saudara perempuan Kiai Abdul Wahid yang juga merupakan mursyid tarikat Naqsyabandiyah di Madura.
Martin van Bruinessen menyebut hal serupa, ia menulis bahwa selama dirinya melakukan penelitian secara historis, geografis, dan sosiologis tentang beberapa aliran tarikat di Dunia, Martin belum menemukan satupun aliran tarikat yang dipimpin oleh mursyid perempuan, kecuali tarekat Naqsyabandiyah di Madura, dengan mursyid-nya Nyai Thobibah. (Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia, (Bandung: MIZAN, 1992), 185.
Pada umumnya, peran perempuan atau istri syaikh hanya membantu memberikan pelajaran kepada murid perempuan suaminya. Tetapi, dalam kasus tarekat Naqsyabandiyah di Madura lain sama sekali. Dimana Nyai Thobibah berperan langsung sebagai mursyid yang memberikan pembelajaran penuh kepada murid-muridnya. Nyai Thobibah menerima ijazah dari seorang ulama yang cukup diakui kealiman dan ketawadhuannya di Madura, yaitu Kiai Ali Wafa Ambunten.
Menurut penulusuran Martin, Mursyid perempuan di Madura tidak hanya Nyai Thobibah. Nyai Syarifah Fathimah dari Sumenep juga pernah menjadi mursyid, di mana para pengikutnya kebanyakan dari kalangan perempuan; bahkan tidak hanya dari kalangan perempuan Sumenep, tetapi bahkan sampai ke daerah Kalimatan Barat dan Malang Selatan. Nyai Syarifah Fathimah adalah putri dari seoarang Habib bernama Habib Muhammad. Nyai Syarifah menjadi anggota tarekat dibaiat oleh Kiai Sirajuddin, dan menerima ijazah dari Kiai Syamsuddin (Sumberanyar). (Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia, (Bandung: MIZAN, 1992), 185.
Hal yang menarik lainnya adalah pola kepemimpinan tarekat di Madura. Pasalnya, kepemimpinan tarekat di Madura telah menerapkan semacam kepemimpinan bersama dalam tarekat. Artinya, para syaikh atau mursyid secara kolektif melayani pengikut tarekat yang sama.
Selain itu, para syaikh tarekat Naqsyabandiyah di Madura memiliki pertalian kekerabatan yang erat, sebab memiliki ikatan darah atau ikatan perkawinan. Bisa dilihat misalnya, beberapa syaikh tarekat Naqsyabandiyah di Madura; Kiai Zainal Abidin (yang dikenal KH. Zainal Arifin Terate) merupakan menantu dari Fathul Bari, sedangkan khalifahnya adalah menantunya, Kiai Zahid dan ipar laki-lakinya, Kiai Darwisy. Disisi yang lain, Habib Muhsin menikah dengan kakak perempuan Kiai Mahfudz, yang juga seorang mursyid. Sedangkan, pengganti Kiai Ali Wafa, dan Kiai Abdul Wahid Qudhaifah (Pamekasan) merupakan putra dari guru Kiai Ali Wafa sendiri.
Setidak-tidaknya, ada dua poin penting yang dapat kita petik di sini; pertama, prestise tarikat Naqsyabandiyah yang cukup gemilang di Madura, sampai menjadi tarekat dengan pengikut terbanyak, selain karena faktor para syaikhnya yang alim, lebih dari itu, karena syaikh-syaikhnya selalu mengedepankan persaudaraan; di mana pada masa itu tidak jarang ditemukan di antara para syaikh tarekat “bertengkar” untuk memperebutkan pengaruh atau pengikut.
Kedua, melalui silsilah yang jelas tersebut, dimaksudkan untuk menjaga orisinalitas ajaran tarekat sehinnga sanad keilmuannya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad saw. Untuk itu, dalam dunia terakat dikenal istilah; silsilah, baiat, ijazah dan khalifah yang fungsinya adalah melegitimasi anggota, syaikh dan ajarannya.
Tarekat Naqsyabandiyah sendiri merupakan perkumpulan spiritual yang mengenal sebelas asas sebagai pijakan hidup sehari-hari, di mana teknik meditasi dari tarekat ini banyak dipengaruhi oleh meditasi Hindu dan Budha. Adapun asas-asas tersebut, diantaranya; hush dar dam (sadar sewaktu bernapas), nazar bar qadam (menjaga langkah), safar dar watan (melakukan perjalanan di tanah kelahirannya), khalwat dar anjuman (sepi di tengah keramaian), yad kard (ingat, menyebut), baz gasyt (kembali, memperbarui), nigah dasyt (waspada), yad dasyt (mengingat kembali), wuquf-I zamani (memeriksa pengunaan waktu seseorang), wuqufi ‘adani (memeriksa hitungan zikir seseorang), dan wuquf-I qalbi (menjaga hati tetap terkontrol).
Di Madura sendiri, Terakat Naqsyabandiyah merupakan aliran tarekat yang pada akhir abad ke-19 menjadi tarekat yang paling banyak diikuti oleh orang-orang Madura. Lebih dari itu, orang-orang Madura mempercayai bahwa dengan mengikuti tarekat dapat menambah kekuatan spiritual yang akan membentengi diri melawan penjajah. Bisa dilihat misalnya, keterlibatan tarekat dalam perlawanan melawanan penjajah; tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah dalam pemberontakan anti kolonialisme petani di Banten tahun 1888, Sidoarjo tahun 1903 dan pemberontakan anti Bali di Lombok tahun 1991. (Martin van Bruinessen, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia, (Bandung: MIZAN, 1992), 108
Akhirnya, dengan kehadiran mursyid tarekat perempuan tersebut, memberikan penjelasan bahwa toleransi orang-orang Madura terhadap kepemimpinan perempuan amat besar, dibandingkan dengan beberapa daerah lain yang justru –pada masa itu–kepemimpinan perempuan masih dipermasalahkan.