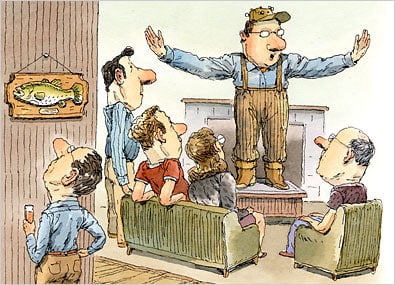Klambrangan. Sebagiam orang Jawa pasti masih memahaminya. Klambrangan terkait dengan kesan terhadap seseorang atau sesuatu yang dilebihkan/ditinggikan atau --sebaliknya-- dimerosotkan. Kesan itu tersiar secara gethok-tular (dari mulut ke mulut) sehingga diragukan objektifitasnya.
Klambrangan identik dengan kebiasaan kalangan akar rumput, utamanya di pedesaan, yang terbiasa untuk tak mengecek satu kesan atau kabar tertentu. Padahal, kesan itu bisa benar bisa salah.
Apakah klambrangan itu kebiasaan turun-temurun? Saya kira tidak. Klambrangan terkait erat dengan kolonialisme. Hal itu ditujukan untuk menguasai atau menjajah seseorang atau daerah yang terkait dengan orang itu.
Klambrangan membuat seseorang/sesuatu jadi membubung tinggi dan terbang, lalu terhembus angin entah ke mana ia terbawa dan jadi apa. Klambrangan merupakan hasil dari sesuatu yang diklambrangkan. Karena sesuatu itu diragukan kebenaran atau kekeliruannya, ia bisa berada di ruang ambang. Klambrangan biasanya hanya hidup di wilayah imajiner, tapi mdapat mempengaruhi kenyataan.
Kita tahu kasus dukun santet di Banyuwangi, atau jauh sebelumnya pada masa ’65. Banyak korban jatuh karena "budaya" klambrangan tersebut. Disebarkanlah desas-desus bahwa si Suto, misalnya, karena perilakunya yang suka membakar kemenyan atau dupa, pun karena faktor ketaksukaan belaka, adalah seorang dukun santet. Atau si Punto, hanya karena ia seorang loyalis Soekarno, di-klambrang-kanlah dirinya sebagai seorang PKI.
Klambrangan hanya akan hidup apabila, pertama, absennya negara dalam berbagai peristiwa yang menyangkut keselamatan orang banyak. Kedua, mindset yang memang sengaja digarap terlebih dahulu, seumpama budaya untuk bertanya yang dianggap sebagai sebentuk “kebodohan.”
Ada upaya-upaya untuk membuat dangkal segala sesuatu. Apabila budaya bertanya terlebih dahulu merupakan dasar dari tumbuh-kembangnya pengetahuan, yang berarti sebentuk tanda kepintaran, maka di era klambrangan semacam ini justru menjadi tanda dari sebentuk kebodohan.
Apa pasal? Sebab secara picik bahwa bertanya dimaknai sebagai tanda seorang yang tak tahu dan itu artinya bodoh atau masih dalam taraf belajar. Dapat kita bayangkan bagaimana nasib para wartawan yang mesti nyinyir penuh tanya di era klambrangan semacam ini?
Sudah menjadi tabiat era klambrangan bahwa bersikap literal menjadi keniscayaan, seperti kalangan Wahabi yang sering memaknai segala sesuatunya secara harfiah. Itulah kenapa di zaman ini orang-orang yang benar-benar menguasai persoalan (diupayakan) untuk didisfungsikan secara sosial.
Segala cara pun ditempuh, salah satunya adalah melalui klambrangan. Dicari-carilah alasan supaya orang-orang yang benar-benar menguasai persoalan itu terpuruk untuk kemudian diistirahatkan secara paksa, atau bahkan secara sosial dimatikan selamanya.
Seringkali alasan-alasan ad hominem menjadi bahan untuk pe-nglambrang-an demi tercukur tuntas karakternya. Pengakuan adalah senjata paling ampuh di era klambrangan seperti ini. Segetol apapun orang yang ditarget dalam era klambrangan ini mengaktualisasikan dirinya akan senantiasa berujung sia-sia.
Orang-orang yang membencinya akan selalu menutupinya. Atau dinisbahkanlah kemampuan-kemampuannya itu pada orang yang menurut para pe-nglambrang sesuai dengan standar mereka. Dan ternyata standar mereka tak muluk, dangkal-dangkal saja, cuma sekedar menuruti apa yang mereka mau—selaiknya bocah ingusan.
Analogi kehidupan di era klambrangan adalah sebuah hutan yang pepohonannya tak memiliki tinggi yang sejajar. Ada yang rendah, lebih tinggi, dan paling tinggi. Celakanya, egalitarianisme—karena juga menuntut adanya kesetaraan—yang diinginkan adalah egalitarianisme yang membunuh, bukannya menumbuhkan.
Pohon yang menjulang tinggi justru ditebang supaya sejajar atau bahkan lebih rendah dari lainnya. Orang atau sebuah daerah yang tumbuh dan berkembang pesat justru berupaya dirusak dengan segala cara untuk menjadi serendah orang atau daerah yang menghidupi budaya klambrangan.
Ada kesan bahwa budaya klambrangan identik dengan kalangan khawarij pada umumnya. Intelektualitas dan orang-orang yang benar-benar menguasai persoalan dianggap sebagai pepohonan yang menjulang tinggi tersebut. Dan memang, bagi orang-orang yang hidup dalam kungkungan budaya klambrangan memiliki pola pikir yang radikal dan mutlak-mutlakan: “Yes or nothing at all.”
Andaikata ada satu orang goblok, maka semuanya mesti goblok atau digoblokkan. Ada berbagai mekanisme untuk menggoblokkan tersebut.
Saya teringat Nietzsche di sini, tentang the herd instinct atau insting kawanan yang merupakan ciri dari moralitas budak. Budak dalam kategori Nietzschean bukanlah budak seperti di abad jahiliah, mereka adalah sekumpulan pecundang yang mengkambinghitamkan para pemenang atas kepecundangan mereka.
Alih-alih sadar diri untuk kemudian memperbaikinya, mereka justru mencari-cari alasan untuk menutupi ketakmampuannya dengan mengkambinghitamkan orang lain. Tentu, salah satunya juga melalui klambrangan.
Taruhlah perihal rekognisi di atas, sebenarnya yang berjuang mati-matian adalah si Suto, tapi karena banyak orang yang tak menyukainya, maka—melalui jaringan klambrangan—dinisbahkanlah hal itu pada si Punto. Lantas, ke manakah si Suto?
Tak usah tanya, ia telah dijadikan duplikat dan pelampiasan segala kesalahan dan ketakcakapan si Punto—selayaknya kesed bertuliskan “wellcome” di beranda sebuah rumah ningrat.
Ada satu lagi mekanisme jaringan klambrangan yang merusak orang untuk tak lagi berfungsi secara sosial: dengan merendahkan statusnya dan memperlakukannya laiknya orang yg lebih rendah status sosialnya. Taruhlah si Suto, meski ia seorang kyai atau sekaliber presiden sekali pun, ketika tak sesuai dengan selera mereka, maka melalui jaringan klambrangan ia akan diperlakukan seperti halnya si Punto, yang hanyalah seorang preman ataupun sekelas lurah—meski menurut akal sehat bersifat tak tersepadankan.
Jaringan klambrangan akan berkasak-kusuk di sekitarnya dan, secara tak langsung (melalui berbagai kode, bahasa tubuh, ataupun lontaran-lontaran verbal yang telah disepakati), memperlakukan si Suto selaiknya si Punto. Akibat terjauh, karena opini publik sudah terbentuk, ibarat stigma sudah melekat erat, maka bisa jadi si Suto pada akhirnya akan hidup seperti halnya si Punto yang celakanya tak pernah dikenalnya.
Dan di manakah si Suto, pada akhirnya? Tak usah telisik, secara sosial ia sudah “almarhum,” nama dan karakternya sudah klambrangan entah ke mana dan jadi apa.