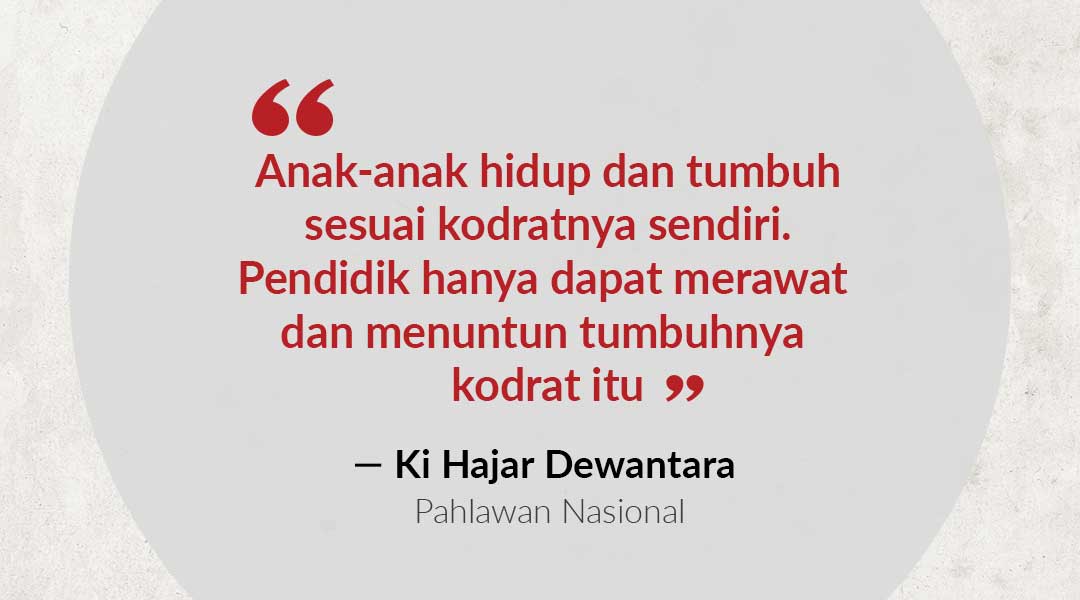Beberapa tahun lalu, majalah terkemuka Time pernah menampilkan laporan utama yang menjadi horor dan ditakuti pada orang tua sedunia, yakni bagaimana mendidik anak-anak di era milenial ini? Judulnya simpel dan lugas “Me Me Me Generation” mengenai perkembangan anak-anak muda masakini yang seakan hanya sibuk memikirkan dirinya sendiri. Mereka hanya mau terkoneksi dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya sendiri.
Sontak para psikolog dan budayawan merasa jengkel. Tidak kurang dari sahabat saya, sastrawati Leila S. Chudori merasa kesal dan ikut mengomentari pemberitaan yang cukup meresahkan tersebut. Bukankah generasi muda saat ini adalah calon-calon pemimpin bangsa, yang mestinya mempersiapkan diri sebagai pemimpin untuk menyongsong masadepan? Bagaimana nasib bangsa ini ke depan jika realitas sehari-hari pelajar kita, ternyata kurang terdidik dengan baik?
Di sisi lain, Leila Chudori tidak bisa menampik tentang kebenaran, serta akurasi data pada laporan utama di majalah internasional tersebut. Generasi baru masakini, begitu mudah memperoleh dan meraih segalanya: ilmu pengetahuan, rezeki, kebutuhan hidup dan sebagainya. Jika saja orang tua mampu membatasi rezeki dan ilmu bagi anak-anaknya, tentu hal ini tidak terlampau mengkhawatirkan. Tetapi faktanya, mereka begitu melesat melampaui zamannya. Bahkan, melampaui kecerdasan dan kekayaan orang tuanya dalam hitungan beberapa tahun saja. Pada majalah Time diungkap karakteristik mereka yang cenderung entitled, seakan merasa berhak meraih segalanya tanpa perlu berjuang keras, karena menurut mereka yang penting, “me, me, me”.
Kita juga pernah diperkenalkan dengan film berjudul “The Intern”, menggambarkan generasi orang tua berusia 70 tahun (dibintangi Robert De Niro) yang digolongkan sebagai generasi pendatang baru di abad milenial ini. Di dunia pendidikan kita, generasi pendatang baru justru didominasi para guru dan dosen, sementara para pelajar dan mahasiswa jauh lebih dulu melek teknologi ketimbang para pendidiknya.
Orang tua yang bijak akan paham belaka, bahwa segala aplikasi dan paparan teknologi digital membuat struktur otak anak-anak kian berubah (multitasking). Informasi mengalir dari mana-mana dan melimpah ruah. Tapi di sisi lain, ada etika dan nilai-nilai yang mesti dijaga dan dihargai, misalnya penghargaan kepada yang lebih tua dan sepuh. Penggambaran film “The Intern” menyibak adanya dekadensi pada generasi milenial, tentang kekeringan dan kegersangan sipiritual. Bahkan, sekadar mengucapkan “terimakasih” saja bisa dilupakan oleh mereka yang terlampau sibuk oleh hiruk-pikuh bisnis dan perdagangan.
Dampak lainnya dari pesatnya revolusi digital, seperti yang diutarakan psikolog dan ahli saraf otak manusia, Garry Small (University of California), “Anak-anak yang otaknya banyak menerima input dari teknologi digital, secara kognitif bisa menjadi superior.” Tetapi, bagi yang mental dan moralnya kurang terdidik dengan baik, mereka bisa saja menyerap informasi apapun dengan cepat, meskipun pada akhirnya memutuskan sesuatu secara keliru dan salah-kaprah.
Struktur otak mereka memang berubah menjadi multitasking, tetapi harus didukung dengan pendamping yang sanggup mengarahkan pola pikir untuk mengklasifikasi derasnya informasi yang diserap oleh otak dan pikiran mereka.
Orang tua selaku pendamping
Apapun yang terjadi, risiko menjadi orang tua bagi anak-anak yang harus berfungsi selaku pembimbing sekaligus guru yang ditiru, adalah keniscayaan bagi hidup kita. Di sisi lain, apakah kita yakin bahwa dunia sekolah sanggup mendidik anak-anak menjadi lebih cerdas dan kuat secara mental. Bagi anak-anak yang pintar secara kognitif, rapornya bagus dan ranking-nya selalu tinggi, apakah juga terjamin memiliki kualitas ketangguhan yang dapat diandalkan bagi pemenuhan kemandirian hidupnya di masadepan?
Untuk mengatasi sikap dan krakteristik generasi milenial yang cenderung hiper aktif, masabodoh dan semau gue, seorang pendidik dan psikolog Thomas R. Hoerr, tidak mau bersikap skeptis dan berpangku tangan, atau menjadi bagian dari kegagalan orang tua dalam mendidik anak-anak. Dengan kesungguhan dan ikhtiarnya, Hoerr mencari solusi untuk penerapan pola ajar dan pola asuh bagi anak-anak generasi milenial. Dalam bukunya “The Formative Five”, Hoerr memaparkan secara lugas, bagaimana seorang guru dan orang tua harus mempersiapkan diri selaku pembimbing bagi anak-anaknya, juga mempersiapkan kesiapan mentalitas anak-didik untuk menghadapi hari esok.
Analisis Thomas Hoerr bersifat ilmiah dan universal, tak terkecuali para pendidik di lingkungan pesantren juga perlu mendalami pemikirannya. Ada lima kecerdasan anak-anak didik yang perlu dikuasai oleh mereka untuk menjadi manusia dewasa di kemudian hari, yakni rasa empati, introspeksi-diri, integritas, memahami perbedaan, dan kekuatan mental. Empat kecerdasan pertama harus dikuasai anak-didik agar ia mampu berinteraksi dengan pihak lain, tanpa membeda-bedakan status maupun warganegaranya.
Tanpa rasa empati, manusia akan sulit memiliki kepekaan dan kepedulian pada nasib sesamanya. Tanpa introspeksi-diri, manusia akan sulit berdisiplin dan hanya sibuk mendahulukan kepentingan untuk dirinya sendiri. Tanpa integritas, hidup manusia hanya menjadi bunglon yang klamar-klemer, plintat-plintut, dan sulit mendapatkan kepercayaan dari pihak lain. Tanpa memahami perbedaan, manusia akan sulit mengakui realitas kemajemukan, serta menganggap bahwa setiap perbedaan adalah ancaman yang membahayakan.
Kekuatan mental adalah kecerdasan kelima yang harus dikuasai anak-didik agar tangguh menghadapi tantangan zaman. Di era milenial ini setiap negara sedang mengalami krisis anak-anak muda yang kuat dan tangguh. Ketika seseorang memiliki tujuan hidup, ia mesti akan menghadapi berbagai masalah yang harus diatasi, jika ingin berhasil mencapai tujuan itu dengan baik. Hanya mereka yang memiliki kualitas mental tangguh, tidak mudah putus asa, akan terus belajar dan mendalami sesuatu dalam situasi sesulit apapun. Mereka memiliki keuletan, tekad baja, dan ketekunan. Sementara orang-orang yang lemah dan skeptis, akan mudah frustasi dan menyerah, bahkan dalam proses-proses awal menghadapi kegagalan sekalipun.
Anak-anak masa depan
Lalu, siapa yang akan menjadi contoh pemula bagi anak-anak didik, kalau bukan orang tua dan gurunya sendiri? Apakah anak-anak kita cukup disuruh meneladani orang lain seperti Einstein, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Soekarno atau Thomas Alva Edison? Dalam persoalan yang lebih spesifik, mengenai anak-anak masadepan kita, apakah layak kita sebagai orang tua membentak-bentak mereka, “Ayo, tirulah orang lain, teladani Alexander Agung, Gandhi, Sokrates! Jangan contoh perilaku ibu dan bapakmu ini!”
Apapun yang kita risaukan sebagai orang tua, tak ada jalan lain bagi anak-anak yang sedang tumbuh, bahwa mereka menerima contoh dan teladan dari orang-orang yang terdekat dengannya. Di sinilah tanggungjawab kita sebagai orang tua, sekaligus diberi amanah dari Tuhan selaku pemimpin dan khalifah di muka bumi, dalam level dan tingkatan apapun kepemimpinan itu.
Anak-anak muda kita, jika mereka dibekali lima kecerdasan yang dicanangkan Thomas Hoerr di atas, niscaya memiliki ketangguhan dalam berpikir, serta keteguhan hati dalam menyikapi masalah, tanpa mudah frustasi dan putus asa. Bila kita berkaca pada perjalanan hidup Thomas Alva Edison, seorang ilmuwan dan penemu bohlam yang kemudian berhasil menerangi dunia, dengan tenang dan rendah-hati ia menjawab pertanyaan yang diajukan para wartawan, “Saya bukannya gagal seribu kali, tapi bohlam ini memang suatu penemuan yang memerlukan seribu tahapan. Ketika kita mengalami kegagalan, yang perlu kita lakukan hanya mencobanya lagi, sekali lagi, dan sekali lagi…”
Anak-anak muda yang tangguh semacam itu, yang akan tetap survive dan berhasil di masadepan nanti. Kelemahan banyak orang adalah mudah menyerah, tanpa mereka berpikir keras, betapa di balik kegagalan itu sudah menyambut tangan-tangan kesuksesan di depan mata. Tentu tidak banyak orang yang berani bersikap seperti itu. Misalnya jika kita menulis karya sastra, menggambarkan sifat dan karakteristik orang-orang di sekitar kita. Seringkali kita mudah tergoda oleh kepentingan-kepentingan lain yang – sebenarnya kita paham bahwa kepentingan itu – remeh-temeh dan sampingan belaka. Kadang-kadang tawaran proyek proposal dari instansi pemerintah atau perusahaan, menjadi godaan dan iming-iming yang sangat mengganggu kreativitas kita.
Ciri lain manusia tangguh adalah mereka yang memiliki tujuan hidup yang jelas demi kemaslahatan umat. Bahkan sanggup mengerjakan urusan yang ia tentukan sendiri sampai tuntas. Memang sangat jarang orang yang sanggup menentukan pilihan seperti itu. Karena pada umumnya, ketika mereka tengah mengerjakan sesuatu, kebanyakan mereka tidak kuat menghadapi berbagai gangguan, lalu mogok di tengah jalan karena merasa bosan, termasuk saya pribadi.
Setelah salah satu opini saya di harian Kompas mendapat banyak tanggapan (Membangun Akal Sehat, 24 April 2018), ingin sekali saya menulis karya sastra yang memberi kemaslahatan pada banyak orang. Khususnya mengenai watak dan karakteristik manusia Indonesia, supaya kita mampu bercermin diri, bermuhasabah, demi terciptanya generasi-generasi unggul yang sanggup mengidentifikasi diri, mencari solusi terbaik untuk menyongsong masadepan Indonesia yang gemilang. Insya Allah. (AU)