Tak Ada Mudik yang Berat, Kecuali Mudik ke Buku
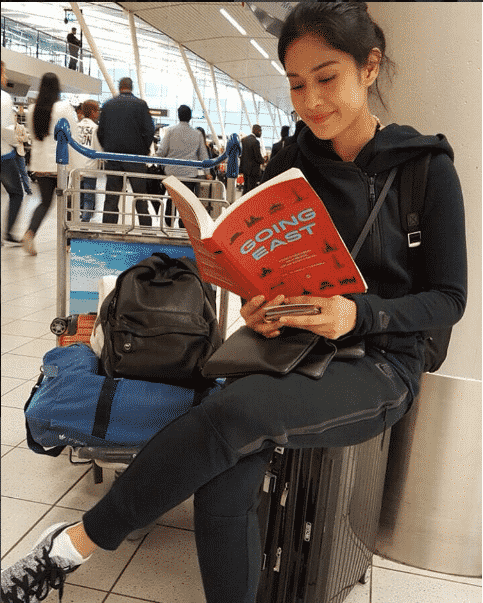
Orang mudik membawa pakaian, makanan, uang, dan benda-benda. Kita memandang peristiwa mudik memandang tas, kardus, karung, koper, atau tas plastik berisi segala benda diperlukan selama perjalanan dan ingin terbagikan di kampung halaman.
Mudik rutin mengartikan bawaan benda-benda ada di sepeda motor, mobil, bus, kereta api, kapal, dan pesawat terbang.
Buku mungkin bukan benda utama di mudik. Orang menempuh perjalanan sudah berisiko macet, lama, capek, dan membosankan. Pemudik memilih membawa benda-benda mungkin menghibur ketimbang buku. Kita jarang mendapat cerita ada pemudik membawa sekardus buku. Kardus itu naik bus atau kereta api, menempuhi perjalanan jauh melintasi kota-kota.
Buku tak cuma berdiam di dalam kardus. Sekian buku sengaja ditaruh di tas agar gampang diambil jika pemudik mau membaca. Kita menginginkan ada pemudik itu pembaca?
Pada kondisi berpuasa dan keramaian orang-orang, pemudik membuat peristiwa membaca tentu unik dan “menggemaskan”. Pemandangan paling khas adalah kaum mudik menikmati peristiwa perjalanan dan waktu-waktu senggang dengan menggerakkan jari dan mata ke gawai.
Anggapan-anggapan rutin dan baku agak “diganggu” oleh Kemendikbud, Ikapi, dan Perpustakaan Nasional. Mereka mengadakan program membagi buku gratis kepada para pemudik. Program dinamai “Mudik Asyik Baca Buku.” Pejabat di Kemdikbud memberi keterangan saat di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, 27 Mei 2019:
“Kami membagikan buku bacaan gratis di pusat atau titik keberangkatan para pemudik dengan harapan para pemudik mendapatkan hiburan dengan membaca buku selama perjalanan ke kampung halaman.”
Keterangan bermutu dengan penguatan buku sanggup memberi “hiburan” bagi pemudik sudah menanggungkan kangen pada keluarga dan kampung halaman. “Hiburan” di situasi pemudik lapar, haus, dan mengantuk. Pilihan diksi “hiburan” ingin menandingi pemberian hiburan di gawai milik pemudik.
Pembagian buku memilih lima lokasi, semua di Jakarta: Stasiun Gambir, Stasiun Senen, Terminal Bus Kampung Rambutan, Terminal Bus Kalideres, dan Terminal Bus Pulo Gebang (Suara Merdeka, 29 Mei 2019).
Para pemudik memilih perjalanan menggunakan pesawat terbang dan kapal diharapkan tak cemburu. Mereka tak mendapatkan buku gratis. Pemudik di bandara tentu dianggap adalah orang memiliki kemampuan membeli buku meski tak membelanjakan uang untuk buku.
Pada hari-hari menjelang Lebaran, uang cenderung digunakan untuk membeli pakaian, perhiasan, atau makanan. Buku jarang ada di daftar teratas belanjaan. Orang berduit belum tentu ingin mengartikan Ramadan dan Lebaran dengan buku.
Seribu buku dibagikan ke pemudik tanpa perlu seleksi ketat di masing-masing lokasi. Panitia pasti sulit unruk menebak atau mengadakan percakapan bermaksud pemberian buku sesuai sasaran. Kesibukan di tempat-tempat pemberangkatan jarang memberi kelonggaran waktu berdalih membaca buku. Kita tak mendapat keterangan jenis atau tema buku dibagikan ke para pemudik. Buku-buku dibagikan itu terbitan Gramedia, Intan Pariwara, Mizan, Erlangga, dan Amalia. Kita menduga saja selera bacaan itu melalui kekhasan para penerbit.
Konon, pemberian buku berfaedah bagi pemudik dan keluarga di kampung halaman. Faedah itu terbukti asal buku dibaca, bukan buku lekas dimasukkan dalam tas atau kardus: terdiamkan. Panitia tergesa menganggap acara itu sanggup mendukung Gerakan Literasi Nasional dan mengakibatkan buku-buku tersebar ke pelosok. Kita agak mufakat meski tetap memiliki ragu. Mudik dengan buku cenderung berita ketimbang peristiwa realis.
Di Solo dan pelbagai kota, ikhtiar mengartikan Ramadhan dan Lebaran itu buku rutin diadakan oleh toko buku “terbesar” di Indonesia. Toko itu sengaja mengadakan pameran buku obralan atau pesta diskon ratusan judul buku untuk dinikmati pembeli. Buku-buku sering memiliki harga, dari 10 ribu rupiah sampai 50 ribu rupiah. Harga “dimurahkan” ketimbang harga asli tercantum di buku.
Ribuan buku “lama” dijual agar memberi untung ke penerbit dan toko. “Keuntungan” pun diperoleh pembeli atau pembaca dengan mendapatkan buku-buku tak lagi berharga asli dari penerbit, sekian tahun lalu.
Belanja buku di pameran cap obralan memiliki “kekhasan” ketimbang berkerumun atau berdesakan demi belanja makanan dan pakaian di pasar atau pusat perbelanjaan modern. Buku teranggap berarti di hari-hari sakral. Belanja buku tak harus diumumkan mendukung Gerakan Literasi Nasional. Orang memilih belanja dan membaca buku mungkin berdalih “ibadah” atau memberi penguatan keaksaraan. Perbuatan terasa “melawan” kecenderungan orang menjalani hari-hari dengan godaan tidur, menonton televisi, dan menghibur diri di hadapan gawai.
Membaca buku bukan peristiwa biasa. Peristiwa itu sulit ditonjolkan dengan keseringan acara buka bersama. Orang-orang berselera buku mungkin mengandaikan ada acara “buka buku bersama” di sore hari, peristiwa setelah Ashar sampai menjelang Magrib. Membaca buku “menggantikan” obrolan omong kosong atau ceramah-ceramah mulai membosankan gara-gara repetitif.
Ramadan dan Lebaran mengingatkan buku. Ingatan bisa berjudul “mudik ke buku.” Peristiwa itu dialami oleh Dawam Rahardjo di pemaknaan mudik: kembali ke kampung halaman, kembali ke jati diri. Pada saat bocah dan remaja, ia menjalani hari-hari bersekolah di Solo. Ia mengingat memiliki “panggilan” ke buku-buku.
Dawam Rahardjo mengaku: “Mula-mula saya menekuni dan mempelajari buku-buku agama. Pada masa itu, saya memiliki koleksi yang lumayan banyak mencakup buku-buku agama klasik seperti dari Kiai Munawar Kholil, Abu Bakar Aceh, dan lain-lainnya. Saya belajar agama dari buku-buku.” Pengakuan tercancum di buku berjudulKembali ke Jati Diri: Ramadhan dan Tradisi Pulang Kampung dalam Masyarakat Muslim Urban (2013) dengan tim redaksi Lies Marcus, Roland Gunawan, dan Mukti Ali el Qum.
Peristiwa di masa kecil selalu teringat saat mudik Lebaran. Dawam Rahardjo sering berada di Jakarta dan pelbagai kita berurusan studi dan pekerjaan.
Di kejauhan, Solo dan Klaten menjadi kampung halaman selalu dirindukan setiap tahun. Ia memang pulang ke kampung halaman tapi memiliki imbuhan dengan “mudik ke buku”. Episode bocah dan remaja di masa lalu adalah hari-hari berbuku.

Pada liburan sekolah selama Ramadan, Dawam Rahardjo meninggalkan Solo menuju Klaten, “pulang” ke Klaten. Di rumah nenek, ia mengalami puasa tanpa “berpuasa” bacaan. Hari demi hari, ia adalah pembaca buku beragam tema. Kebiasaan itu berdampak saat dewasa:
“Di situlah saya mengalami akumulasi pengetahuan di segala bidang. Bidang kajian dan minat saya sangat luas, bukan hanya ekonomi, melainkan juga agama, politik, sosial, kebudayaan, dan sastra.”
Ramadan dan Lebaran mengingatkan diri adalah pembaca buku, bukan pencari hiburan atau penggemar kemalasan. Buku termaknai di hari-hari religius.
“Mudik ke buku” bukan pengalaman milik jutaan orang. Kesibukan mudik dan mengalami Lebaran justru membuat orang kesulitan “bermanja” membaca buku. Acara kumpul keluarga, pelesiran, belanja ke mal, atau menonton televisi sering “membatalkan” keinginan berwaktu bersama buku.
Di pinggiran Solo, kecenderungan itu mulai diralat oleh lelaki wagu dengan membiasakan belanja buku saat Lebaran di toko buku “terkenal” di Solo meski harus menunggu agak siang.
Toko mengubah jadwal buka saat Lebaran. Lelaki itu memilih belanja buku dan membaca buku di peringatan Lebaran, setelah berkumpul dengan dua keluarga besar. Peristiwa tambahan adalah mendekam di rumah: menulis berdalih ingin memberi makna diri, waktu, religiositas, dan keaksaraan. Ia tak berpikiran mengesahkan dan membesarkan Gerakan Literasi Nasional.
Di rumah, ia membaca buku itu peristiwa kecil dan biasa. Ia tak lupa berbagi buku sebelum Lebaran, berharap para penerima sengaja membaca buku di Lebaran tanpa mengganggu ibadah dan acara keluarga.
Berlebaran dengan buku itu seperti “mudik” ke makna-makna khas ketimbang capek pelesiran atau klenger gara-gara serakah makan. “Pemudik” ke buku justru ingin bersahaja, bukan di peristiwa membosankan atau “menghamburkan” waktu di hari suci.
Kita sejenak mengingat buku dengan Ramadan dan Lebaran berharap ada janji telat di tahun depan agar memberi pemaknaan buku mengimbuhi makna makanan, busana, pelesiran, dan hiburan. Buku itu penting dan perlu. Begitu.





