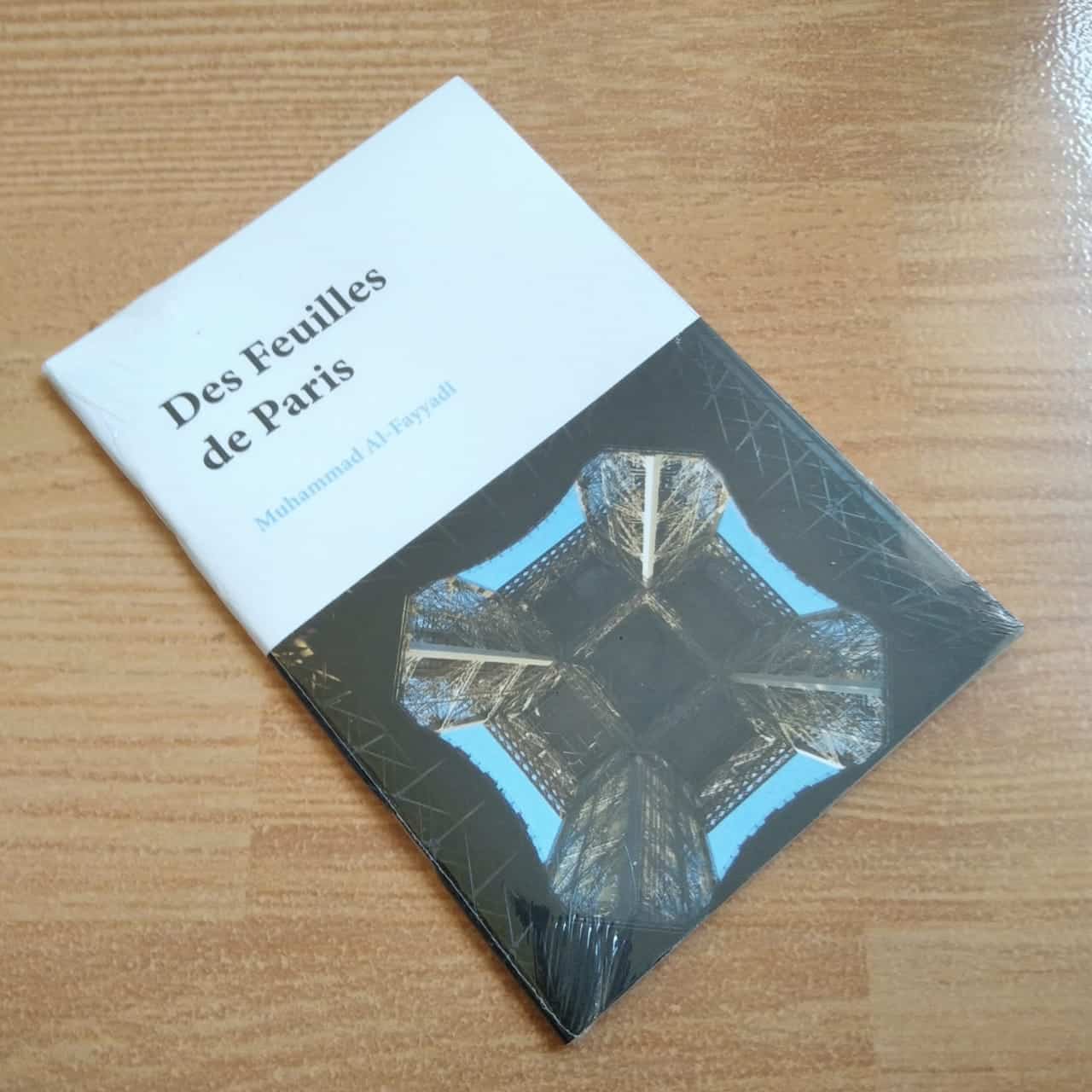Buku itu biru. Buku berukuran kecil dan tipis. Foto di sampul mengesankan intelektual garang. Ia bernama Arief Budiman. Dulu, buku itu cuma dijual dengan harga 500 rupiah. Buku berwarna biru tak bermaksud mengikuti seruan rezim Orde Baru tentang biru dan keluarga. Biru mungkin “iseng” ketimbang hitam-putih. Foto sang intelektual tetap hitam-putih seperti berasal dari masa lalu saat tak mudah mencetak foto.
Judul sederhana saja: Pengalaman Belajar di Amerika Serikat. Buku terbitan Leppenas mungkin tak lagi menjanjikan cetak ulang agar terbaca orang-orang masih bershasrat melanjutkan studi ke Amerika Serikat. Abad telah berganti, gairah studi tak lagi sama. “Saya sadar betul bahwa kesempatan yang saya peroleh untuk belajar di Amerika hanya dimungkinkan oleh pengurbanan, langsung atau tak langsung, dari sebagian besar bangsa Indonesia,” pengakuan Arief Budiman.
Pada masa berbeda, lelaki ceking membuat penjelasan: “Tapi ini detik-detik terakhir di Indonesia. Bertemu teman-teman di Pesantren Ciganjur dan pamitan. Saat itu aku berpikir, ‘Sejauh-jauhnya aku belajar ke luar negeri, aku toh tetap santri.’ Rasanya tak sopan bila pergi tanpa pamitan dulu ke pesantren almamater tempatku belajar.” Lelaki itu bernama Muhammad Al-Fayyadl. Kalimat-kalimat kita temukan dalam buku kecil berjudul Des Feuilles de Paris (2023).
Pada saat mau ke Amerika Serikat, Arief Budiman itu momok atau musuh bagi rezim Orde Baru. Ia dianggap melawan “tertib-politik” dan bikin onar keintelektualan. Pergi dari Indonesia itu kejutan dan pengharapan. Arief Budiman tak langsung ke Amerika Serikat. Ia mengingat: “… saya berangkat ke Paris pada bulan September 1972. Sebuah lembaran baru dalam sejarah kehidupan pribadi saya dimulai.” Di Paris, ia bekerja sambil mencari kepastian studi di Amerika Serikat. Paris untuk persinggahan sejenak. Pada 1973, ia sudah berada di Amerika Serikat tapi tak lekas gembira. Ia masih bingung dan ragu atas nasib diri dan keluarga. Arief Budiman memiliki tempat untuk reda dan tenang sambil merancang masa depan: “Supaya saya tidak sesat, maka saya terpaksa menjadi penghuni perpustakaan, dari pagi sampai pukul 9 malam setiap hari, untuk membaca buku-buku dasar ditambah bacaan-bacaan yang diwajibkan.”
Zaman telah berubah. Pada 2 September 2012, Muhammad Al Fayyadl berada di Paris. Ia melihat dan mencatat: “Jalanan aspal dengan pohon-pohon hijau yang tampak muram dan berdebu. Ini akhir musim panas, banyak pohon meranggas. Aku melewati jalan menuju kampusku, melihat sudut-sudut banlieue Paris dari jauh: pasar murah St Ouen, tenda-tenda tunawisma di pinggir jalan. Paris bukan hanya kota bagi yang berpunya. Di sini banyak juga orang melarat.”
Kita mengenal dua sosok belajar di Amerika Serikat dan Prancis. Mereka gandrung filsafat dan paham kiri. Pilihan tempat studi berbeda tapi gairah pengetahuan sama-sama meluap. Pada masa berbeda, mereka pergi sejenak dari Indonesia. Mereka tak berperan sebagai turis. Mereka pulang ke Indonesia, memberi tulisan dan buku untuk mendapat perhatian serius.
Pengalaman mengesankan bagi Muhammad Al-Fayyadl masa awal di Paris, 5 September 2012: “Beli buku pertama di Prancis, buku profesorku, Jacques Ranciere, Aux bords du politique. Berkenalan dengan pemilik toko buku, Mme Silvie. Dia menunjukkan toko buku murah di mana aku bisa mendapatkan buku-buku bekas…” Di negara jauh, berjumpa buku itu kebahagiaan dan ketagihan.
Kita selingi dulu dengan mengenali tokoh-tokoh pernah belajar di Prancis. Mereka menuliskan pengalaman, terbit menjadi buku berjudul Rantau dan Renungan (1992) dengan editor Ramadhan KH, Marcel Bonneff, dan Ilen Surianegara. Buku bersifat dokumentasi dan godaan bagi orang-orang berhasrat sampai ke Prancis.
Pada 1950, Ilen Surianegara tiba di Paris, menempuh perjalanan dengan kereta api dari Amsterdam. Ia mengaku takjub, wajar tebar pujian: “Sebab Paris memang dibenahi untuk manusia. Biarpun jalan-jalan rayanya lebar-lebar dan lurus-lurus, pejalan kaki tetap merasa sebagai tuan rumah di negeri sendiri… Dan untuk melepaskan lelah tinggal mampir di kedai kopi. Dengan memesan secangkir kopi, ia bisa duduk berjam-jam sambil membaca dan berkisah, maupun menikmati lalu lintas orang yang pamer mode busana paling mutakhir.” Kita berimajinasi situasi tak lagi sama saat Muhammad Al-Fayyadl tiba di sana.
Sosok tiba di Prancis masa 1950-an bernama Winarsih Arifin. Kita mengenali sebagai penerjemah dan pembuat kamus. Pengalaman unik dan penuh keberanian. Ia mengisahkan: “Di Prancis, aku memakai kain kebaya… Aku memang senang berpakaian Jawa. Dan ternyata tidak mengganggu biarpun harus naik turun tangga, berjalan cepat, kadang-kadang mengejar metro.” Ia tiba di Perancis melalu jalur laut.
Ia memiliki alamat terpenting, berbeda dari alamat ingin dikunjungi Muhammad Al Fayyadl pada hari-hari awal. “Yang segera kucari setibaku di Paris ialah Museum Rodin. Rodin karena di sekolah dahulu guru gambarku orang Belanda pernah memperlihatkan album dari Rodin dan Toulouse-Lautrec,” kenang Winarsih Arifin. Ia datang ke museum satat Minggu pagi. Kunjungan dengan perut kelaparan.
Kita kembali ke buku kecil dibuat Muhammad Al-Fayyadl. Di Paris, ia senang belajar dan kaget mengamati tipe para profesor bila dibandingkan kaum profesor di Indonesia. Muhammad Al-Fayyadl menulis: “Dari luar dan secara lahir, tak tampak wajah-wajah militansi pada profesor-profesor yang kutemui; mereka mengajarkan dan mendiskusikan filsafat dan teori-teori ‘perlawanan’ dengan dingin dan santai – kata-kata ‘revolusi’ berseliweran nyaris tanpa ekspresi, seakan-akan itu istilah yang tidak istimewa atau biasa-biasa saja. Tak tampak pretensi pada penampilan mereka sebagai pemikir yang harus disegani dan dihormati karena mengajarkan sesuatu yang ‘wah’, yang bisa mengguncang dunia.” Sosok dan situasi itu membuat ia betah meski direpotkan dingin.
Kita membaca buku tipis cuma 48 halaman. Kita mengerti Muhammad Al-Fayyadl itu santri. Ia bergerak ke Prancis. Ia mengalami hari-hari untuk khatam buku-buku, percakapan, menikmati omongan filosof, dan memandang kota. Ia tak mau hari-hari itu sia-sia. Tulisan atau album kenangan masih mungkin tersajikan tanpa janji lengkap. Begitu.
Judul : Des Feuilles de Paris
Penulis : Muhammad Al-Fayyadl
Penerbit : Mori
Cetak : 2023
Tebal : 48 halaman