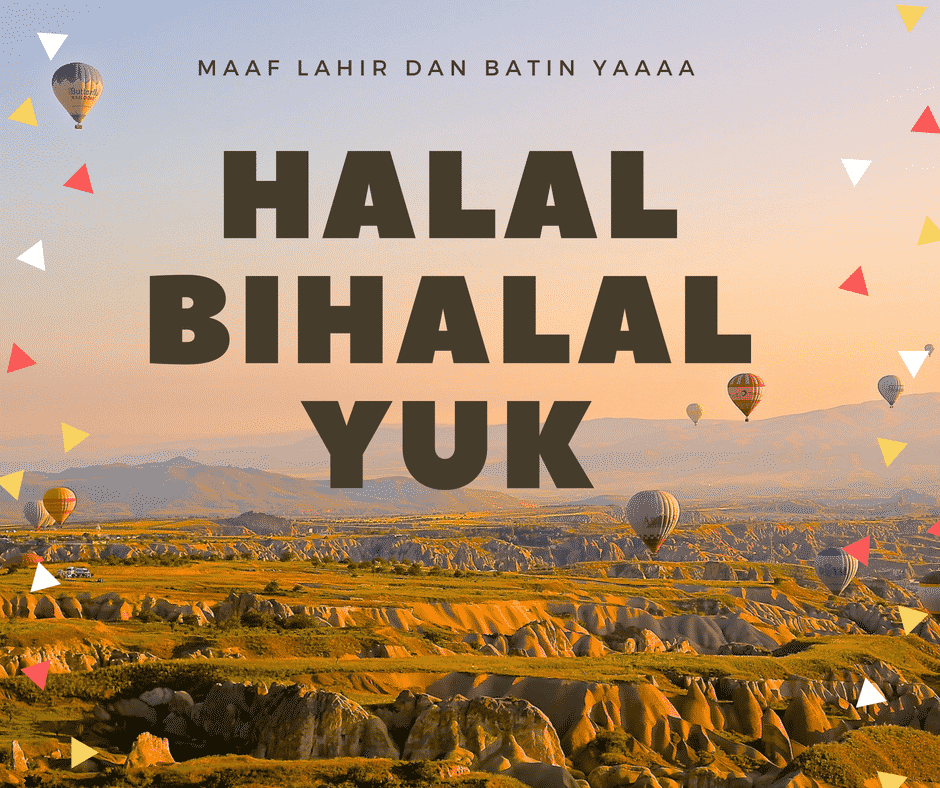Ada banyak hal yang merekatkan seseorang dengan identitas yang melekat pada dirinya. Seperti misalnya warga Nahdliyyin, faktor biologis dan ideologis jamak dijadikan alasan. Banyak yang NU karena orangtuanya, karena belajar di pesantren NU, atau sebab ikut organisasi NU di bangku sekolah dan kuliah. Demikian halnya dengan saya, pertautan dengan organisasi islam terbesar di Indonesia ini manakala mengikuti kaderisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Namun lebih jauh dari itu, bahkan terkesan sepele, saya ikut NU karena makanan.
Saya bukannya ingin bercerita kalau hanya numpang makan di Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) – kaderisasi tingkat pertama PMII, itu soal lain. Jangan bilang-bilang ya, sssttt! Heheheh. Tetapi, bagaimana indoktrinasi pemahaman tentang Nahdlatul Ulama, menyerobot ke kepala saya lewat makanan. Ketika memperoleh materi Aswaja di MAPABA, saya diceramahi tentang tradisi Nahdlatul Ulama yang selaras dengan apa yang dipraktikkan masyarakat di Bugis-Makassar – sekalipun secara kuantitatif, mayoritas jarang yang mengenal Nahdlatul Ulama. Sedikit trivia, terkhusus di kampung saya, masyarakat lebih mengenal Muhammadiyah secara organisasi yang kerap dikontraskan dengan pemerintah dalam urusan keagamaan seperti penetapan waktu awal puasa dan lebaran.
Pikiran saya menjelajah ke kampung halaman. Semua tradisi itu dipertemukan oleh satu hal: makanan. Begini, ada banyak kudapan yang hanya bisa dinikmati ketika beragam tradisi tersebut diselenggarakan. Khusus acara mabbaca doang (selamatan), misalnya saat masuk rumah baru, menjelang Ramadhan, atau maulidan, akan dihidangkan berbagai kudapan seperti songkolo’ (olahan nasi dari beras ketan), gami’ jangang (ayam gulai kelapa), dan roko’-roko’ unti (sejenis kue dari tepung dan pisang yang dibungkus daun pisang) – beberapa sajian tersebut tentu berbeda di berbagai wilayah di Sulawesi Selatan.
Dalam acara mabbaca doang, tuan rumah mengundang tetangga sekitar. Penyelenggaraan mabbaca doang dipilih menjelang magrib. Seusai pak imam membaca doa syukur kepada Allah SWT, acara makan-makan dimulai. Selepasnya, dilanjutkan dengan shalat magrib berjamaah. Fadly Rahman dalam Rijsttafek, Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870 - 1942 (2016) mengungkapkan bahwa tradisi makan menjadi ciri khas aspek religi dalam tradisi selamatan. Bahkan, makanan memiliki aspek simbolik yang berkaitan dengan fungsi sosial.
Di titik inilah, saya memahami tentang arti penting makanan di setiap penyelenggaraan tradisi islam dalam masyarakat Bugis-Makassar. Selain sebagai sarana mengungkapkan rasa syukur atas rezeki yang senantiasa dilimpahkan oleh sang pencipta, makanan merupakan fenomena kebudayaan untuk memperkuat kohesi sosial. Menikmati kudapan bersama mampu merekatkan kebersamaan antar anggota masyarakat, tanpa memandang kelas dan status sosial. Di meja makan, segala perbedaan bisa melebur dalam nikmatnya songkolo’ dan gami’ jangang.
Ibarat “Meja Makan”
Seringkalinya, perbedaan pandangan di antara sesama Nahdliyyin dalam menanggapi sebuah isu, dianggap oleh publik sebagai perpecahan, pertengkaran, bahkan ketidaksamaan visi. Banyak yang mengira, kaum Nahdliyyin selalu satu suara di setiap hal. Sejatinya, pergulatan ide, gagasan, hingga metode gerakan adalah sesuatu yang jamak ditemui di tubuh Nahdlatul Ulama.
Kisah perbedaan visi di antara Gus Dur dengan KHR. As’ad Syamsul Arifin bisa dijadikan contoh bagaimana keluwesan kaum Nahdliyyin menghadapi beragamnya cara pandang di tubuh Nahdlatul Ulama. Diceritakan bahwa sejak Muktamar Nahdlatul Ulama di Situbondo tahun 1985, friksi antara Kiai As’ad dengan Gus Dur mulai mengemuka. Rentetan perbedaan pandangan terus terjadi setelah itu di antara keduanya. Namun, kedua tokoh NU tersebut tetap menjalin silaturahmi yang hangat, antara santri dengan kiai, antara sahabat dengan sahabat. Kisah sejenis banyak diceritakan dan disaksikan, sejak Nahdlatul Ulama berdiri hingga hari ini.
Nahdlatul Ulama barangkali bisa diibaratkan sebagai meja makan. Ide, gagasan, dan gerakan seperti makanan yang dihidangkan. Mereka yang duduk melingkar punya selera masing-masing dalam memilih makanan mana yang ingin dinikmati. Sekalipun harus berdebat tentang selera makan, toh semuanya tetap menyelami kebersamaan di sekeliling meja makan. Bahkan, mereka yang menyiapkan makanan di dapur, pun memiliki resep berbeda untuk mengolah satu jenis kudapan. Tak perlu sama metodenya, asal bisa dimakan dan enak rasanya.
Realitas kaum Nahdliyyin memang begitulah adanya. Makanan adalah penyambung kehangatan di antara ratusan ide, gagasan, dan metode gerakan yang saling berkelindan satu sama lain. Makanan pulalah yang tak boleh alfa hadir di setiap tradisi islam yang mereka rawat turun temurun.
Perbedaan di antara kaum Nahdliyyin bahkan sudah menjadi makanan sehari-hari. Kudapan yang menyuplai nutrisi untuk membakar semangat dalam membela “yang liyan”. Panganan yang didapat dari dapur dan meja makan bernama Indonesia. Sederhana saja bukan?
Selamat Harlah ke-95 Nahdlatul Ulama!