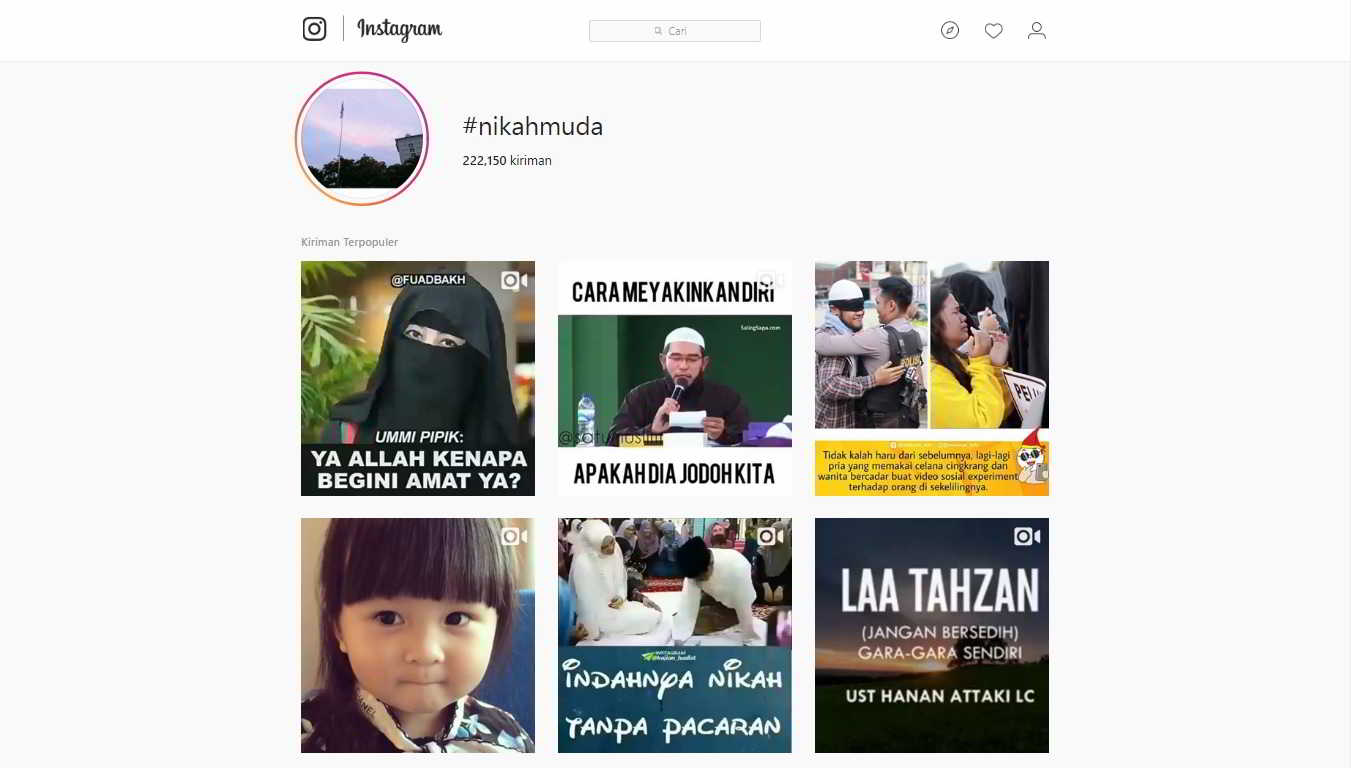Obituari Hanna Rambe: Perempuan, Kolonialisme, dan Luka Banda
Rambe adalah penulis yang menolak menulis “sejarah besar”, dan lebih tertarik menuliskan sejarah kecil berupa kisah manusia biasa yang hidup di sela-sela peristiwa dunia yang besar.

Ada sebuah pulau kecil di Laut Banda. Langitnya seperti kaca yang retak, lautnya biru dan dalam, seakan menyimpan gema dari berabad-abad silam. Pohon pala tumbuh di sana. Di bawah rindangnya, ombak datang dan pergi membawa rahasia, menjadi saksi bisu atas dosa-dosa yang pernah dilakukan manusia atas nama rempah, agama, dan kejayaan.
Banda, yang dulu dijuluki The Bride of the Moluccas, pernah menjadi jantung dunia. Di pulau mungil itu, bangsa-bangsa besar pernah berlayar, berperang, dan saling menumpahkan darah demi aroma dari biji pala yang menguar seperti keabadian. Kiwari, pulau itu diam. Ia seperti seorang perempuan tua yang duduk di beranda rumah, menatap laut sambil menunggu anak-anaknya yang tak akan pernah pulang.
Dalam novel Mirah dari Banda (2010), Hanna Rambe mengisahkan Banda bukan sebagai pemandangan tropis untuk brosur wisata, tetapi sebagai tanah yang mengingat. Ia menulis tentang tempat di mana sejarah, kolonialisme, dan pencarian jati diri manusia bertaut seperti akar tua di dasar laut.
Johanna (Hanna) Rambe lahir di Jakarta titimangsa 23 November 1940. Ia masyhur sebagai salah satu novelis perempuan Indonesia paling berpengaruh dalam mengangkat sejarah kolonial dan kisah perempuan dalam bingkai sosial-budaya Nusantara. Sebelum menjadi penulis penuh waktu, ia adalah jurnalis dan editor di harian pagi Indonesia Raya dan di majalah mingguan Mutiara. Karya-karyanya, antara lain Seorang Lelaki di Waimital: Riwayat Hidup Pelopor Petani (1986), Mencari Makna Hidupku, Riwayat Hidup Pejuang Emansipasi Wanita (1974), dan Mirah dari Banda (pertama kali terbit 1983, kemudian direvisi 2010), Pertarungan (1988), memperlihatkan kepiawaiannya menggabungkan riset sejarah, sensitivitas antropologis, dan empati feminis.
Rambe adalah penulis yang menolak menulis “sejarah besar”, dan lebih tertarik menuliskan sejarah kecil berupa kisah manusia biasa yang hidup di sela-sela peristiwa dunia yang besar. Hanna Rambe berpulang di RS Sumber Waras Jakarta, pada Rabu, titimangsa15 Oktober 2025, pukul 18.40 WIB, di usia delapan puluh empat tahun.
Dalam Mirah dari Banda, ia menghadirkan sejarah yang hidup dan bernafas. Bukan lewat dokumen kolonial atau arsip pemerintah, tetapi melalui suara laut, aroma pala, dan tubuh perempuan yang mencari asal-usulnya. Tokoh utama, Wendy, seorang perempuan Indo-Eropa, anak perang yang kehilangan ibu dan tak mengenal ayah menjadi penjelmaan dari luka kolonial itu sendiri. Ia datang ke Banda dengan kamera dan rasa ingin tahu, tanpa tahu bahwa setiap langkahnya di atas tanah itu adalah langkah di atas tulang-tulang manusia yang dibunuh oleh sejarah.
Cerita dimulai dari perjalanan sepasang suami istri Eropa, Wendy dan Mat Morgan, yang datang ke Banda untuk membuat film dokumenter. Awalnya mereka ingin mengabadikan keindahan, tetapi perjalanan itu perlahan berubah menjadi ziarah batin. Sebuah penelusuran ke masa lalu yang terluka dan ke dalam diri yang kehilangan.
Perempuan yang Datang dari Dua Dunia
Wendy adalah perempuan Indo-Eropa, anak dari perang yang kehilangan ibu dan tidak mengenal ayah. Ia membawa dua darah (Eropa dan Jepang) yang saling menolak. Dua bangsa yang sama-sama menjajah, dua luka yang terjalin dalam tubuh yang sama.
Sejak awal, Rambe melukiskan Wendy dengan keindahan yang tak sepenuhnya damai: kulitnya putih kemerahan, matanya abu-abu, rambutnya berwarna madu. Ia seperti berdiri di antara dua dunia yang tak pernah berdamai. Namun di balik parasnya yang lembut, bersemayam sesuatu yang rapuh. Kerinduan untuk mengetahui siapa dirinya dan dari mana ia berasal. “Menurut petugas Palang Merah Sekutu, ibu kandungnya berpesan sebelum meninggal dunia: bayi ini tidak bersalah. Serahkanlah ia pada keluarga yang mencintai anak-anak, tak peduli bangsa apa pun.”
(Rambe, 2010, hlm. 19).
Kalimat itu seperti getar pelan di dada pembaca. Di balik kelembutan pesannya, tersimpan kenyataan yang getir: Wendy adalah anak dari kekuasaan, lahir dari tubuh perempuan yang menjadi korban perang. Ia tumbuh tanpa bahasa untuk menyebut kata ibu, tanpa tanah yang bisa ia sebut asal.
Dalam perjalanan ke Banda, Wendy membawa kamera, seolah berusaha menangkap dunia yang terus menjauh darinya. Walakin sesungguhnya, ia tengah mencari sesuatu yang jauh lebih dalam: dirinya sendiri. Ia datang bukan untuk merekam Banda, melainkan untuk belajar mendengar suaranya.
Pulau yang Dihapus dari Peta
Nama Banda terdengar seperti nyanyian yang terlupakan. Ia hanya noktah kecil di tengah samudra di peta dunia modern. Namun dalam sejarah umat manusia, Banda pernah menjadi pusat gravitasi kekuasaan, tempat dunia berputar demi rempah.
Hanna Rambe menulis Banda dengan kepekaan seorang penyelam. Ia tidak hanya menyelam ke laut, tetapi ke dalam waktu. Ia mengangkat serpihan ingatan yang tenggelam dan menatanya menjadi narasi yang hidup. Bukan tentang pahlawan, melainkan ihwal orang-orang biasa yang namanya tidak pernah masuk dalam buku sejarah. “Orang Banda asli sudah punah, dibantai habis oleh Jan Pieterzoon Coen tahun 1621. Setelah penduduk Banda habis mereka mengimpor manusia untuk memulai usaha kebun pala.” (Rambe, 2010, hlm. 37).
Sejarah itu sering disebut sepintas di pelajaran sekolah, namun dalam novel ini, Rambe membuatnya bernafas. Ia menulisnya dengan garam dan darah. Ia tahu bahwa pembantaian bukan hanya tragedi masa lalu, tetapi trauma yang diwariskan ke tanah, pohon, dan laut.
Melalui karakter Jack Zakaria, seorang pengusaha lokal dan keturunan orang Banda, Rambe memperlihatkan bagaimana ingatan bisa hidup di tubuh manusia. Jack bukan pahlawan, melainkan penjaga kenangan. “Beta ini bukang pahlawan eee!” katanya dengan tawa getir, dan dalam tawa itu ada kejujuran: bahwa menjadi manusia yang ingat jauh lebih sulit daripada menjadi pahlawan.
Kamera, Kolonialisme, Pandangan
Wendy datang ke Banda dengan kamera, bersama suaminya Mat dan sahabat mereka, Ratna dan Jack. Mereka hendak membuat film dokumenter tentang laut dan taman karang. Sebuah proyek kecil yang kelak membuka tabir besar.
Dalam tangan Hanna Rambe, kamera menjadi simbol kolonialisme modern. Ia bukan lagi meriam atau kapal perang, tetapi cara memandang. Kamera Wendy adalah mata Barat: netral di permukaan, tapi sesungguhnya memilih, memilah, dan menundukkan dunia. “Ia memotret Mat yang sedang membuat film para turis wanita. Mereka tertawa-tawa saling memotret dan memasang gaya aksi.”
(Rambe, 2010, hlm. 4). Adegan ini tampak ringan, namun di baliknya ada kritik yang halus. Kamera tidak hanya merekam; ia juga menyingkirkan. Ia memotong kenyataan menjadi bingkai-bingkai indah yang dapat dijual.
Bagi Rambe, kamera adalah wujud baru kolonialisme: kolonialisme optik. Turis datang ke Banda bukan untuk mengingat, melainkan untuk mengkonsumsi pemandangan. Mereka memotret luka dan menyebutnya eksotisme.
Tetapi Wendy, perlahan, mulai resah. Ia merasa laut yang ia rekam tampak terlalu tenang, terlalu jernih. Dalam setiap foto yang ia hasilkan, ia melihat bayangan dirinya sendiri—indah tapi kosong. “Laut Banda diketahui sangat dalam, namun laut di sekitar pulau-pulau mungil itu sangat jernih bagai kaca,” tulis Rambe (hlm. 10).
Kejernihan itu, dalam pandangan Rambe, adalah cara laut menyembunyikan luka. Keindahan menjadi bentuk penyangkalan. Mungkin karena itulah Wendy mulai berhenti memotret. Ia tahu bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditangkap kamera. Pelbagai hal yang hanya bisa didengarkan oleh hati yang berani menatap masa lalu.
Tubuh Perempuan sebagai Arsip
Dalam novel ini, tubuh perempuan bukan sekadar simbol; ia adalah arsip sejarah. Hanna Rambe mengubah tubuh Wendy menjadi peta yang retak. Setiap garisnya adalah batas antara penjajah dan terjajah, antara cinta dan kekerasan, antara pengakuan dan penghapusan.
Tatkala Wendy berdiri di tepi pantai Banda, pasir di bawah kakinya seperti berbisik. Ia merasakan sejarah yang mengalir di tubuhnya sendiri. Ia mulai memahami bahwa dirinya adalah perpanjangan dari tanah ini: sama-sama indah, sama-sama kehilangan.
Wendy menatap laut dan melihat bayangannya memantul. Dalam pantulan itu, ia melihat wajah-wajah yang tak dikenalnya: ibu yang hilang, ayah yang entah di mana, dan barangkali wajah-wajah perempuan Banda yang dibunuh karena aroma pala. Ia sadar bahwa ingatan bukan sekadar sesuatu yang disimpan di kepala, tetapi sesuatu yang hidup di tubuh. “Ia tahu, pengharapannya hanya setengah dibanding seratus. Semua tali yang mungkin menghubungkannya dengan tanah kelahiran atau asal usulnya telah putus dibawa ibunya ke dalam kematian.” (Rambe, 2010, hlm. 20).
Kalimat itu seperti air asin yang menggenang di dada. Ia tidak berteriak, tetapi menyesakkan. Rambe menulis dengan suara yang tenang namun menyayat, seolah mengatakan bahwa kadang kesedihan yang paling dalam tidak butuh air mata.
Tanah, Pasir, dan Luka yang Tak Pernah Hilang
Tanah Banda tidak pernah diam. Ia menyimpan segalanya: jejak langkah, darah, bahkan keheningan. “Pohon pala berbuah emas,” kata Jack, “tetapi emas itu dari darah manusia.” (Rambe, 2010, hlm. 38). Hanna Rambe tahu bahwa setiap kekayaan lahir dari penderitaan. Ia menulis Banda dengan kesadaran ekologis yang mendalam, jauh sebelum istilah ekosastra populer. Tanah baginya adalah makhluk hidup yang melahirkan, tapi juga menanggung dosa.
Ketika Wendy berjalan di pesisir dan menggenggam pasir, ia merasa butiran halus itu berbicara padanya. Setiap butir adalah serpihan dari sejarah yang tak sempat ditulis. Ia belajar bahwa sejarah bukan hanya masa lampau, melainkan sesuatu yang terus hadir di bawah telapak kaki. “Tanah ini tak bisa melupakan, karena di dalamnya terkubur nama-nama yang tak sempat ditulis.” (Rambe, 2010, hlm. 42). Dalam kalimat itu, Rambe menyatukan puisi dan kebenaran. Ia menulis dengan keheningan seorang penyair dan ketegasan seorang saksi. Banda, dalam pandangannya, bukanlah objek wisata, melainkan tubuh yang hidup, yang terus bernafas di antara ingatan dan kelupaan.
Laut yang Mengingat
Tatkala pagi tiba, laut Banda tampak tenang seperti kaca. Namun Hanna Rambe tahu: laut tidak pernah benar-benar tenang. Ia hanya pandai menyembunyikan rahasia.
Di bawah permukaan biru itu, sejarah berbaring dengan tenang. Nama-nama yang dihapus dari buku pelajaran masih bergetar di arus bawah laut. Dalam setiap gelombang, kita bisa mendengar bisikan masa lalu: suara perahu yang karam, tangis perempuan yang ditinggalkan, doa anak yang tak pernah sampai.
Mirah dari Banda berakhir dengan kesadaran bahwa sejarah tak pernah mati; ia hanya berganti bentuk menjadi air, udara, dan tubuh manusia. Wendy tidak menemukan ibu kandungnya, tetapi ia menemukan sesuatu yang lebih penting: akar yang tak terlihat, ingatan yang menolak mati.
Rambe menutup novel ini tanpa heroisme. Tidak ada penebusan, tidak ada akhir yang damai. Karena bagi Rambe, sejarah bangsa bukan dongeng yang bisa diselesaikan, melainkan laut yang tak bertepi. Kita hidup di atasnya, kita tenggelam di dalamnya, tapi kita tak bisa keluar darinya. “Laut Banda yang biru dan kelam, yang menyimpan begitu banyak rahasia peperangan karena pala dan cengkeh.” (Rambe, 2010, hlm. 21). Di kalimat itu, laut menjadi simbol keabadian sekaligus luka. Ia adalah ibu bagi semua yang hilang, sekaligus kuburan bagi mereka yang tak sempat pulang.
Arkian, Hanna Rambe menulis bukan untuk menyembuhkan luka, tetapi agar luka itu tetap diingat. Ia percaya bahwa bangsa yang melupakan akan kehilangan arah. Dalam dunia yang sibuk memotret, membangun, dan melupakan, menulis adalah bentuk paling sunyi dari perlawanan. Melalui Mirah dari Banda, ia mengajarkan bahwa mengingat adalah tindakan politik, dan bahwa cinta sejati kepada tanah air bukanlah bangga tanpa luka, melainkan keberanian untuk menatap luka itu tanpa berpaling.
Laut Banda akan terus bergemuruh, entah oleh ombak atau oleh kenangan. Dan mungkin, sebagaimana Wendy, kita semua hanyalah peziarah yang sedang belajar berenang di dalam ingatan yang tak pernah tenang. Tanah ini tidak bisa melupakan, karena di dalamnya terkubur nama-nama yang tak sempat ditulis.