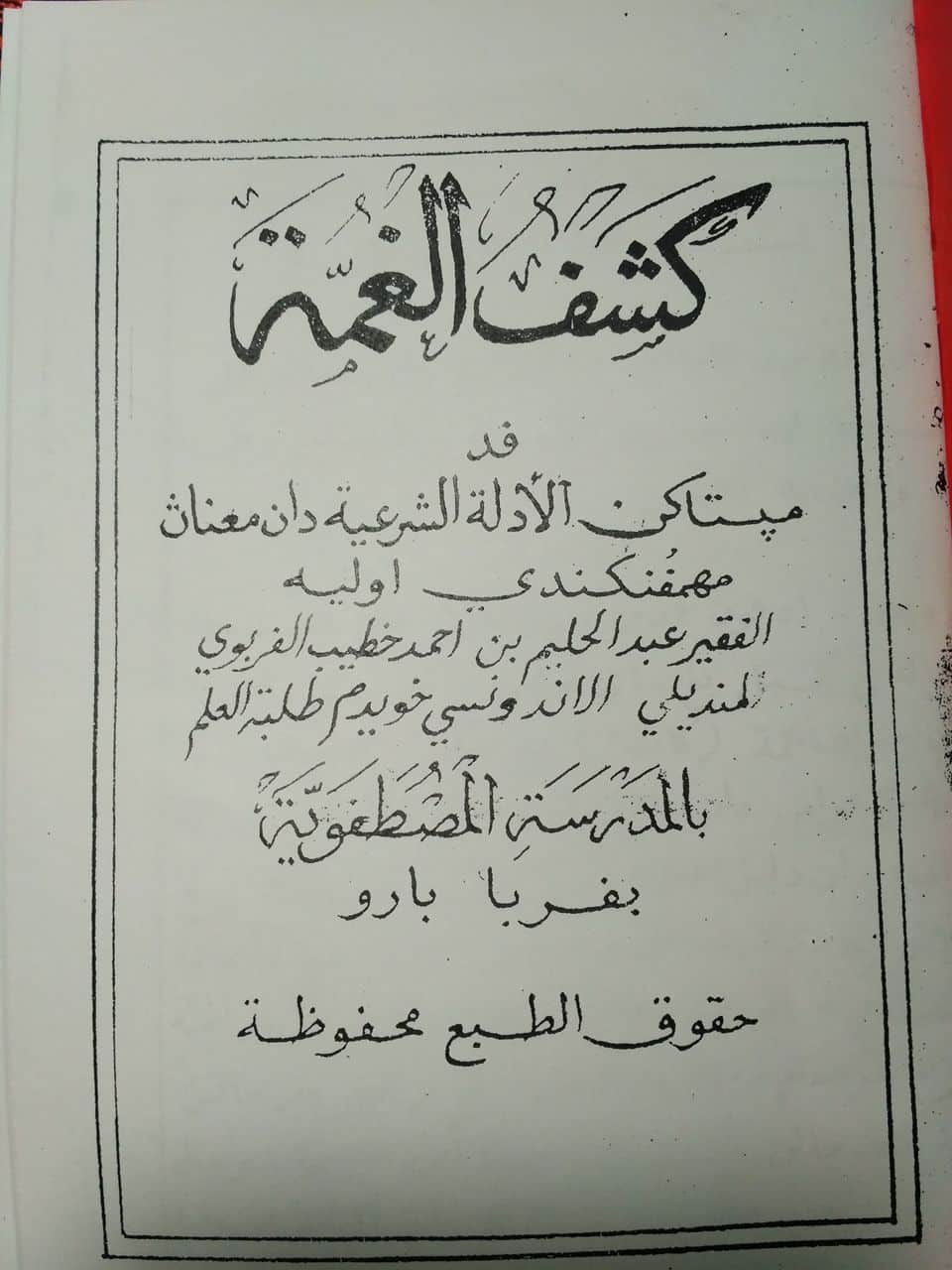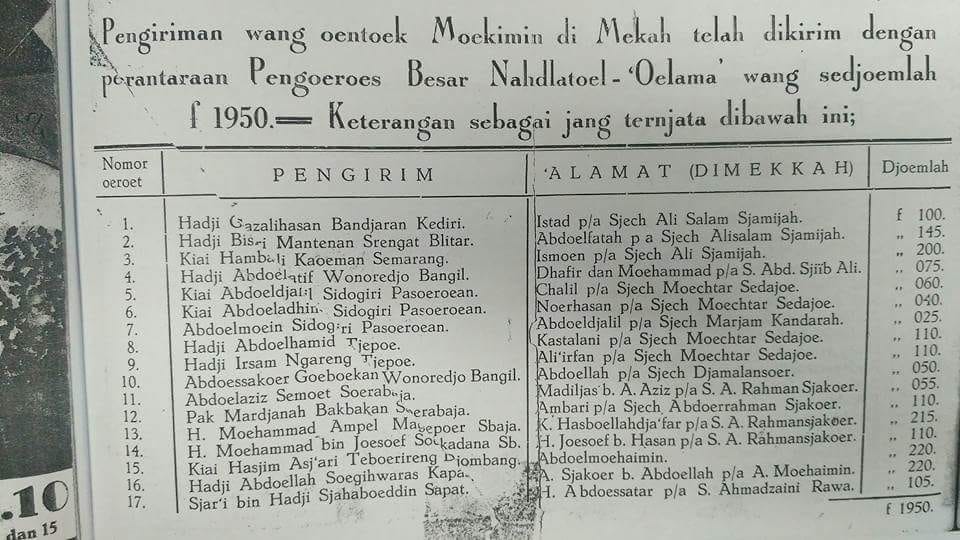Beberapa hari terakhir, kita dibikin terhenyak oleh sebuah berita sedih. Seorang anak umur 10 tahun kelas IV SD di Ngada, Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya dengan menggantung diri. Ia meninggalkan surat untuk ibunya, dengan kalimat pendek-pendek dan sederhana, khas anak-anak. Isinya begitu menyentuh – permintaan maaf dan harapan agar ibunya tidak sedih.
Orang mengenalnya sebagai anak periang dan cerdas. Tapi ia tinggal bersama neneknya karena ibunya menjadi orang tua tunggal bagi kelima anak, termasuk dirinya. Pagi sebelum meninggal, anak itu minta dibelikan buku dan pena tapi tidak bisa dipenuhi karena ibunya tak punya uang (Harian Kompas, 2/2/2026)
Saya jadi teringat film Jude (1996) karya Michael Winterbottom. Film adaptasi novel Jude the Obscure (1895) karya Thomas Hardy ini dibintangi Kate Winslet sebagai Sue Bridehead dan Christoper Ecclestone sebagai Jude Fawley.
Film ini menceritakan kehidupan keluarga miskin di Inggris abad XIX yang hidup serba kekurangan. Orang tua bekerja tanpa henti, berpindah-pindah untuk bertahan dengan segala cara. Anak-anak hidup, mendengar, mengalami dan menjadi bagian keadaan.
Tapi Jude tidak menampilkan kekerasan fisik atau verbal terhadap anak. Yang ada hanya percakapan-percakapan – tentang uang yang tidak cukup, rumah yang terlalu sempit, pekerjaan yang tidak pasti dan anak-anak yang “terlalu banyak”. Semua itu diucapkan sebagai keluhan sehari-hari, tanpa niat jahat. Tapi ternyata, justru di situlah masalahnya.
Anak sulung, yang dijuluki “Little Father Time”, menyerap semua itu dalam benaknya. Ketika tekanan hidup makin sempit dan mereka kembali terusir dari tempat tinggal, ia bertanya “is it because of me we have to leave?”. “No”, jawab ibunya. “Because we are too many”.
Maka, anak itu lalu mengambil keputusan, yang masuk akal di pikirannya. Ketika kedua orangtuanya bekerja, ia menggantung diri bersama adik-adiknya, dengan meninggalkan sepucuk pesan (dengan ejaan yang belum sempurna): “Done because we are too menny”.
“Sudah dilakukan, karena kami terlalu banyak.” Kalimat ini bukan penanda kemarahan. Ia adalah kesimpulan sederhana dari seorang anak tentang dunia orang dewasa yang ia amati. Dan di situlah ironisnya.
Membaca Dunia Orang Dewasa
Lebih dari seratus tahun setelah novel itu ditulis, dan sekitar tiga puluh tahun setelah filmnya dirilis, logika yang sama muncul dalam sebuah peristiwa di Indonesia. Kesamaan itu bukan pada latar, waktu atau konteks sosialnya, tapi fakta yang lebih menyentuh, yaitu bagaimana seorang anak membaca dunia orang dewasa lalu menarik kesimpulan yang terlalu berat untuk usianya.
Dalam Jude, kalimat “because we are too many” bukan sekedar pernyataan tentang jumlah. Ia adalah kesimpulan “sederhana” tentang dunia yang terasa penuh, sesak dan tidak lagi menyediakan ruang.
Peristiwa di NTT bekerja dengan logika serupa. Dalam surat terakhir untuk ibunya itu, kata-katanya sederhana, bahkan terdengar dewasa. Terlalu dewasa bahkan, bagi seorang anak yang sudah belajar membaca hidup dengan ukuran-ukuran yang seharusnya belum menjadi bebannya.
Selama ini, kita tahu, anak bukan sekedar individu dengan psikologi personal, tapi subjek yang hidup di antara dunia orang dewasa. Anak tidak sepenuhnya dilibatkan dalam pengambilan keputusan, tapi juga tidak sepenuhnya dilindungi dari dampaknya.
Ia mendengar percakapan tentang biaya hidup, bayar sekolah, kesulitan ekonomi, dan beban keluarga lainnya. Ia mungkin tidak paham sepenuhnya, tapi cukup untuk menangkap satu pesan berulang, bahwa hidup ini berat.
Di sinilah masalahnya. Dunia kita penuh kebisingan kesibukan. Orang dewasa sibuk menyelesaikan urusan untuk bertahan dan menjaga hidup agar bisa dilalui. Dalam ritme seperti itu, kegelisahan anak kerap dianggap sebagai gangguan. Bukan karena orang tua jahat, tapi karena terlalu banyak yang harus diselesaikan.
Selama ini, kita meyakinkan diri bahwa anak akan menyesuaikan diri. Seiring bertambahnya usia, ia akan kuat dengan sendirinya dan “mengerti keadaan”. Padahal ketika seorang anak diminta mengerti keadaan, sesungguhnya ia diminta menanggung logika orang dewasa tanpa kesiapan yang memadai.
Film Jude menunjukkan hal ini dengan jelas. Orang dewasa di film ini tidak kejam. Mereka hanya lelah karena mereka sibuk bertahan hidup. Dan justru di sinilah tragedi bekerja.
Anak melihat dunia sebagai ruang yang terus penuh oleh urusan, kerja dan kesulitan. Ia tidak melihat ruang untuk dirinya. Bukan karena ia tidak dicintai, lebih karena cinta dan perhatian tidak pernah hadir sebagai kenyataan yang tenang.
Kalimat “because we are too many” lahir dari pembacaan semacam itu. Anak itu tidak berkata “aku tidak dicintai, tapi ia berkata “kita terlalu banyak”. Dalam hal ini, ia menempatkan dirinya sebagai bagian dari masalah, bukan korban. Ini jadi penting karena anak itu tidak menuduh siapapun, tapi ia menyimpulkan.
Surat anak di NTT juga bekerja dengan logika yang sama. Ia tidak menuduh orang tuanya, tapi justru menenangkan ibunya. Ia memastikan bahwa kepergiannya tidak menyulitkan. Surat itu menjadi bentuk terakhir percakapan yang tidak tersedia karena tekanan hidup yang dialami ibunya.
Dalam perspektif ini, bunuh diri ini bukan ledakan emosi, tapi hasil dari internalisasi panjang. Anak menyerap bahasa orang dewasa tentang beban, kekurangan dan kesulitan hidup, lalu menerjemahkan ke dalam dirinya.
Tapi ia belum punya kesadaran untuk berjarak dari itu semua dan berkata pada dirinya bahwa itu masalah orang dewasa, bukan tentang dirinya. Akibatnya, kesimpulannya mengarah ke dirinya sendiri.
Tanggung Jawab
Maka sepertinya kita perlu bertanya kondisi sosial budaya macam apa yang menyusun cara kita berbicara tentang hidup yang membuat seorang anak merasa keberadaannya perlu ditiadakan? Di situlah letak tanggung jawab orang dewasa, masyarakat dan negara.
Dalam hal ini negara tidak mampu mewujudkan kesejahteraan dengan menyediakan ruang kehidupan yang layak bagi warganya. Banyak keluarga kebutuhan dasarnya belum terpenuhi secara utuh.
Tidak hanya kebutuhan material seperti pangan, pekerjaan dan akses pendidikan. Tapi juga kebutuhan immaterial seperti rasa aman, komunikasi intens dan perhatian utuh. Tekanan hidup orang dewasa sering tumpah ke dalam rumah dan anak ikut menanggungnya tanpa pernah benar-benar mengerti atau dimintai persetujuan.
Masyarakat juga memperlakukan anak sebagai “beban” yang harus cepat patuh, membantu dan tidak merepotkan. Keluhan atau kesedihan dianggap kerewelan yang merepotkan, kelemahan dan tidak perlu. Tidak ada ruang untuk mendengar anak sebagai subjek yang punya kecemasan sendiri.
Tanda-tanda beban psikologis pun kerap disalahartikan sebagai kenakalan atau kebiasaan. Solidaritas baru muncul setelah tragedi, sehingga anak tumbuh dalam lingkungan yang menormalisasi kesulitan sebagai nasib, bukan sebagai masalah bersama, dan akhirnya tidak melihat masyarakat sebagai tempat meminta tolong.
Untuk itu kita perlu menata ulang cara kita menyusun kehidupan bersama, cara orang dewasa mengatur hidup bersama sehari-hari. Dari rumah yang tidak menjadikan anak sebagai tempat mengalihkan kecemasan, dari lingkungan yang awas, peduli dan bersedia mendengar tanpa menghakimi dan dari negara yang hadir sebelum tekanan hidup berubah menjadi tragedi keputusasaan.
Ketika ruang hidup dibangun dan disusun dengan lebih manusiawi, anak tidak perlu membayangkan kematian sebagai jalan keluar. Ia belajar, melalui pengalaman konkret, bahwa hidupnya tidak diukur dari seberapa besar ia berguna, tapi dari kenyataan bahwa ia memang berhak ada.