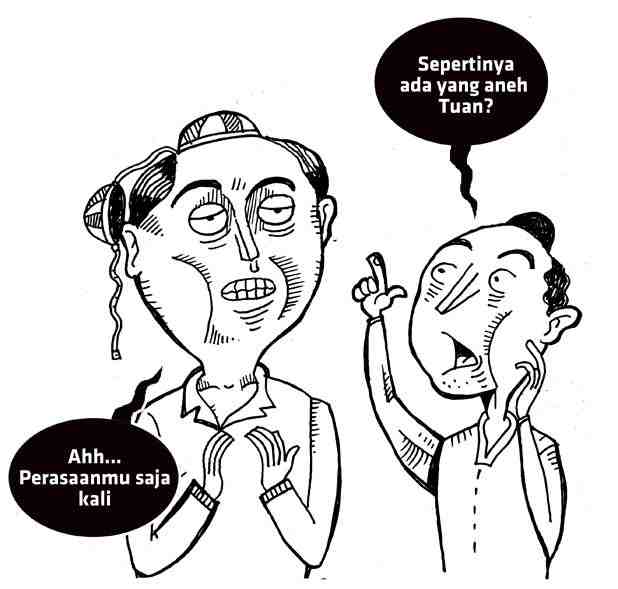Spiritualitas Air di Zaman Plastik
Air kehidupan adalah segalanya. Apabila ia telah ternoda, maka yang harus dimurnikan bukan sekadar sungai atau udara, tetapi cara kita hidup, berpikir, dan beriman.

Beberapa waktu lalu, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mempublikasikan hasil penelitian yang mengguncang kesadaran kita. Sejak 2022, tim menemukan bahwa setiap sampel air hujan di Jakarta mengandung mikroplastik. Partikel-partikel plastik mikroskopis itu terbentuk dari degradasi limbah plastik yang melayang di udara akibat aktivitas manusia: serat sintetis pakaian, debu kendaraan dan ban, sisa pembakaran sampah plastik, serta degradasi plastik di ruang terbuka (Kompas.id, 18/10/2025). Hujan yang selama ini kita anggap romantis itu, ternyata membawa jejak paling ironis dari gaya hidup kita sendiri.
Hujan yang turun kini bukan lagi air murni, melainkan cairan yang mengandung residu dari sistem sosial dan ekonomi modern. Setiap tetes air yang menyentuh bumi adalah cermin kehidupan urban—yang berpakaian cepat ganti, bertransportasi berbasis fosil, dan membuang sisa tanpa tanggung jawab.
Dalam setiap butir hujan yang jatuh di Jakarta, ada serpihan plastik dari jaket olahraga, debu ban mobil, dan sisa pembakaran sampah. Krisis ini bukan sekadar masalah lingkungan, melainkan juga krisis spiritual. Air, yang dahulu menjadi lambang kesucian, kini telah kehilangan maknanya.
Kosmologi Nusantara
Dalam kosmologi Nusantara, air (toya, banyu, cai, wai) adalah unsur sakral. Ia bukan hanya elemen alam, tetapi simbol kehidupan, kesuburan, dan keterhubungan kosmos. Air hujan diyakini sebagai berkah dari langit—rahmat, bukan sekadar sumber daya.
Dalam ritual agraris, air menjadi medium pemurnian. Di Bali, umat Hindu melakukan melasti untuk menyucikan diri dan alam dari kotoran duniawi. Di Jawa, air menjadi bagian tak terpisahkan dari ruwatan atau sedekah bumi. Dalam tradisi itu, air bukanlah benda, melainkan roh kehidupan yang menyambungkan manusia, bumi, dan langit. Maka ketika air hujan kini tercemar mikroplastik, sesungguhnya yang tercemar bukan hanya unsur alam, tetapi relasi spiritual manusia dengan semesta.
Filsuf Prancis Michel Serres dalam Le Contrat Naturel (1990) menulis bahwa manusia modern telah melanggar “kontrak alami” dengan bumi—perjanjian tak tertulis untuk hidup selaras dengan lingkungan. Alam yang dulu dianggap mitra kini diposisikan sebagai objek eksploitasi.
Dalam konteks hujan plastik, alam tampak “berbicara” dalam bahasa partikel dan polusi. Ia tidak lagi menegur lewat banjir atau gempa, melainkan lewat butiran halus mikroplastik yang turun bersama air hujan—pesan lembut namun tegas dari bumi tentang cara kita hidup.
Kita hidup dalam paradoks besar: di satu sisi, manusia modern begitu terobsesi pada kebersihan; di sisi lain, ia dikelilingi polusi yang diciptakannya sendiri. Kita mensterilkan tangan dengan cairan antiseptik, mencuci pakaian dengan deterjen wangi, namun tak sadar bahwa semua itu melepaskan serat mikroplastik ke udara dan air.
Jean Baudrillard dalam Simulacra and Simulation (1981) menulis bahwa modernitas hidup dalam simulasi—tanda-tanda kebersihan yang menutupi realitas kotor di baliknya. Sabun, plastik, dan kemasan bersih hanyalah estetika steril dari peradaban yang sebenarnya sedang membusuk secara ekologis. Kebersihan menjadi citra, bukan kesadaran; menjadi konsumsi visual, bukan etika spiritual.
Dalam pandangan Vandana Shiva, aktivis ekofeminisme India, keadilan ekologis menuntut pembagian beban dan tanggung jawab yang setara, sebab lingkungan bukanlah latar, melainkan ruang hidup bersama (Earth Democracy, 2005). Mikroplastik di udara mungkin jatuh merata, tetapi dampaknya tidak merata.
Warga miskin yang tinggal dekat jalan raya, pabrik, atau tempat pembakaran terbuka akan menghirup lebih banyak polusi dibanding mereka yang tinggal di kawasan hijau. Krisis ekologis dengan demikian juga krisis keadilan sosial: yang menikmati kenyamanan konsumsi belum tentu menanggung beban pencemarannya.
Spiritual – Epistemologis
Namun, di balik dimensi politik dan sosialnya, sebenarnya ada krisis yang lebih dalam lagi, yaitu krisis spiritual dan epistemologis. Modernitas memutus relasi sakral antara manusia dan alam. Kita menatap alam dengan mata teknologi, bukan dengan rasa hormat. Air dianggap sebagai “sumber daya” yang harus diatur, bukan “roh kehidupan” yang harus disyukuri.
Antropolog Niels Bubandt dalam The Empty Seashell (2014) menulis tentang hilangnya “agen non-manusia” dalam kosmologi modern. Kita tak lagi percaya bahwa air, tanah, dan udara memiliki kesadaran. Dengannya, polusi bukan hanya pencemaran fisik, tapi juga pencemaran cara pandang. Kita telah menyingkirkan dimensi ruhani dari dunia, lalu bertanya-tanya ada apa dengan dunia ini.
Dalam konteks spiritualitas Nusantara, air adalah penanda keseimbangan (pancer) antara jagat kecil (mikrokosmos) dan jagat besar (makrokosmos). Maka ketika air kehilangan kesuciannya, itu berarti keseimbangan kosmos terganggu.
Mikroplastik bukan sekadar partikel kimia, tetapi simbol “sampah batin” manusia modern berupa keserakahan, kecepatan, dan ketakpedulian. Dalam bahasa Jawa, “banyu panguripan”—air kehidupan—telah menjelma “banyu plastik,” tanda bahwa kita tidak hanya mengotori bumi, tetapi juga mengeruhkan kesadaran sendiri.
Kita membutuhkan cara pandang baru, atau mungkin cara lama yang dihidupkan kembali yaitu paradigma spiritualitas ekologis. Dalam banyak tradisi lokal, air dihormati dengan doa, tidak dikomersialkan. Kesadaran seperti itu dapat menjadi dasar bagi etika ekologis baru yang bukan sekadar kampanye daur ulang, melainkan perubahan sikap batin terhadap dunia.
Kesadaran ini bisa berwujud sederhana, yaitu dengan menahan diri dari konsumsi berlebihan, memilih bahan alami, atau sekadar menghargai air hujan yang turun tanpa segera menutup jendela. Dalam kebijaksanaan Nusantara, menyatu dengan alam bukan romantisme atau nostalgia belaka, melainkan sikap politik spiritual untuk zaman krisis ini.
Hujan yang turun di Jakarta hari ini membawa pesan yang tak terucap. Bahwa air kehidupan kini telah menjadi air limbah yang kita ciptakan sendiri. Ia menetes di atap, di pohon, di tanah, membawa partikel plastik yang berasal dari baju, ban, dan kemasan yang kita buang.
Namun barangkali di situlah letak peringatan sekaligus harapan. Alam sedang mengingatkan bahwa hubungan spiritual kita dengannya belum sepenuhnya putus, karena ia masih berusaha berbicara, meski lewat mikroplastik.
Mungkin sudah saatnya kita berhenti memandang hujan hanya sebagai fenomena cuaca. Hujan adalah cermin. Ia memantulkan cara kita memperlakukan dunia, tubuh, dan batin sendiri.
Bila air kehidupan saja telah ternoda, maka yang harus dimurnikan bukan sekadar sungai atau udara, tetapi cara kita hidup, berpikir, dan beriman. Sebab spiritualitas sejati tidak berhenti di altar atau tempat ibadah, tetapi menetes dalam setiap hujan yang jatuh di bumi dan di hati kita sendiri.