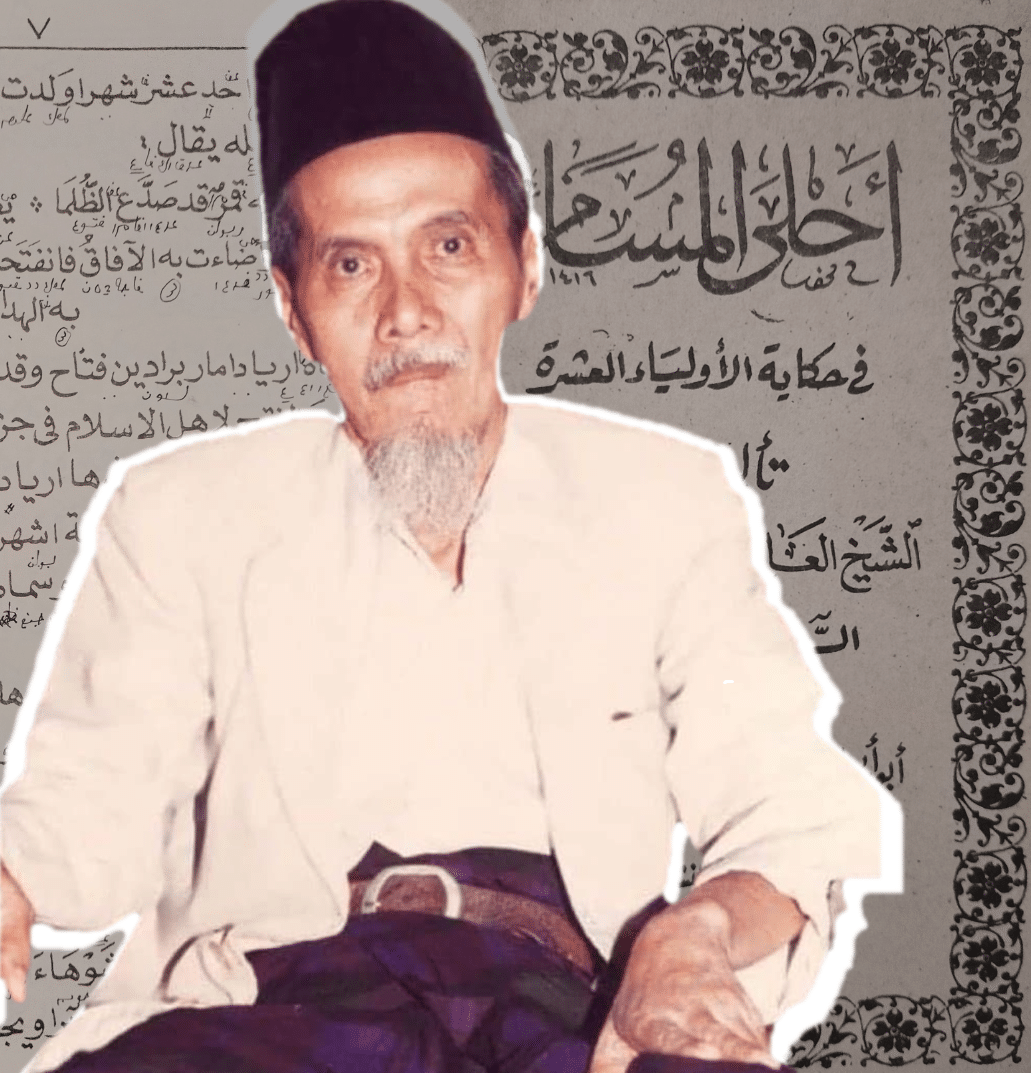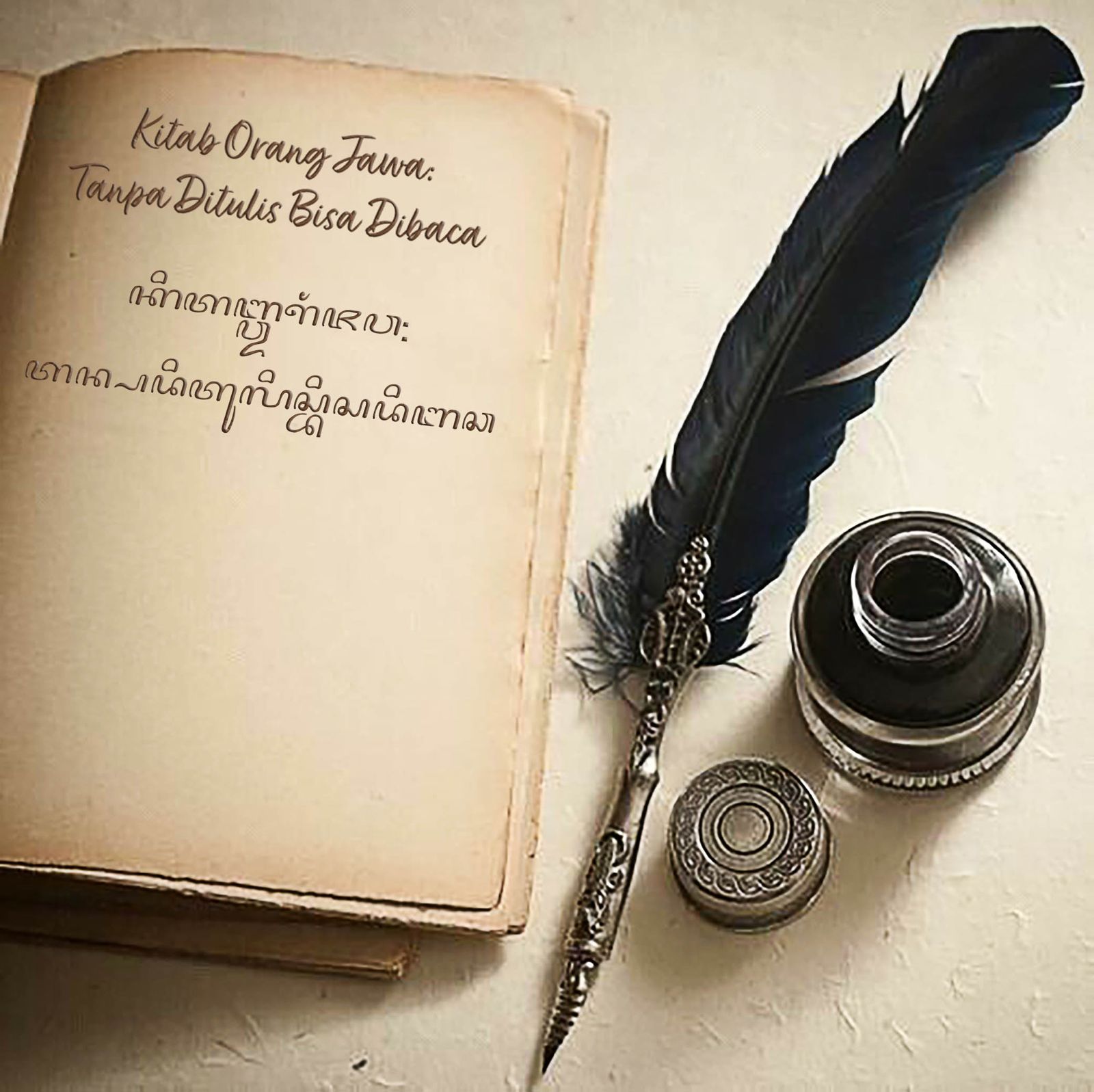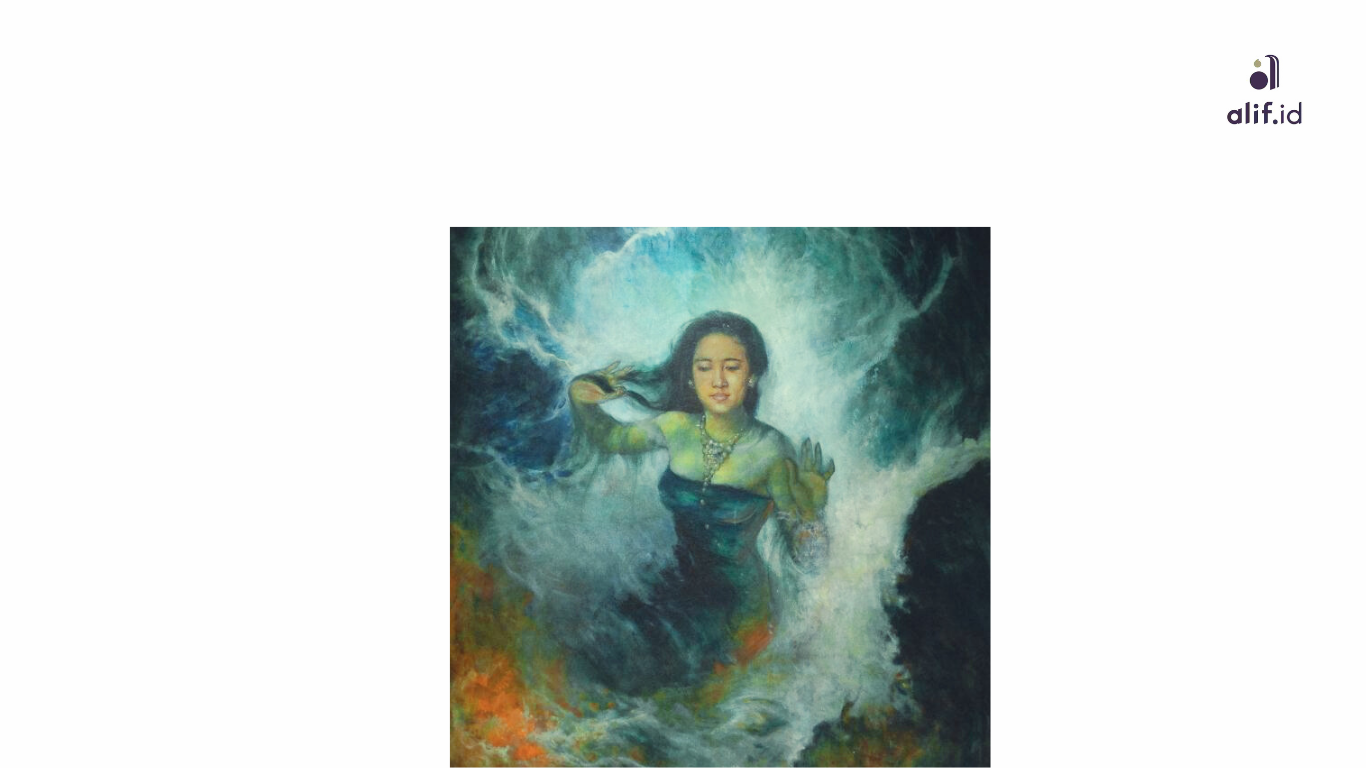Mengapa kita khawatir bahwa tradisi akan dilupakan oleh generasi muda? Dunia kini bergerak dalam ritme yang makin cepat. Teknologi bukan lagi sekadar alat bantu, tetapi telah mengubah cara kita berpikir, berkomunikasi, dan membentuk identitas. Di tengah derasnya arus globalisasi dan budaya populer global yang mendominasi, kekhawatiran akan lunturnya seni dan budaya Nusantara terasa semakin nyata.
Di tengah laju peradaban yang semakin dinamis dan teknologi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan dunia, generasi muda saat ini, terutama Generasi Z, memegang peranan yang sangat penting dalam pelestarian seni dan budaya Nusantara. Seperti sungai yang mengalir melalui pegunungan, seni dan budaya adalah arus tak terlihat yang mengaliri kehidupan kita, membentuk cara berpikir, berbicara, dan bersikap terhadap dunia.
Namun, dalam gemuruh dunia yang serba digital ini, seringkali kita terlena oleh kemajuan teknologi yang menggeser tradisi. Data Jakpat (2023) menunjukkan bahwa 71% responden muda Indonesia lebih mengenal budaya pop global daripada tradisi lokal. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat penurunan 15% partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya komunitas dalam sepuluh tahun terakhir.
Apakah ini pertanda generasi muda meninggalkan akar budayanya? Tidak sesederhana itu.
Generasi Z bukan hanya penerus, melainkan agen perubahan yang mampu menggali, memelihara, dan menyebarkan seni dan budaya Nusantara dengan cara yang relevan di zamannya. Seni dan budaya adalah cermin jati diri bangsa. Menjaganya berarti menjaga identitas kolektif agar tetap hidup di tengah perubahan.
Di sinilah urgnesi—daya cipta kreatif yang lahir dari pergulatan zaman—muncul sebagai kekuatan Generasi Z.
Di Yogyakarta, komunitas Jogja Hip Hop Foundation memadukan puisi Jawa dan musik hip hop. Di Bandung, kelompok Sundanika menciptakan gamelan elektronik. Di media sosial, akun Indonesia Traditional Dance Community menjangkau puluhan ribu anak muda yang belajar tari tradisional. Nadya Karima Melati, peneliti kuliner sekaligus kreator media sosial, mempopulerkan kekayaan kuliner tradisional kepada generasi digital.
Tak kalah penting, Swargaloka—sebuah kelompok seni yang berdedikasi pada pengembangan seni berbasis tradisi—aktif dalam kegiatan edukasi melalui pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang berlokasi di Taman Mini “Indonesia Indah” (TMII). PKBM ini menyediakan pelatihan dan pendidikan seni bagi masyarakat umum, khususnya generasi muda, untuk menanamkan nilai-nilai tradisional dan memperkuat identitas budaya. Swargaloka telah tampil di berbagai panggung bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Salah satu pencapaian penting adalah kemenangan grup tari Ksatria—yang merupakan bagian dari Swargaloka—dalam ajang Indonesia Mencari Bakat (IMB) pada tahun 2021. Kesuksesan ini menginspirasi penyelenggaraan Festival Ksatria Tari Indonesia (KTI), sebuah kompetisi tari kreasi kelompok berbasis tradisi yang telah diikuti oleh ratusan peserta dari berbagai provinsi.
Di ranah seni rupa, banyak seniman muda seperti Aditya Novali atau Arkiv Vilmansa membawa elemen budaya lokal ke dalam karya-karya kontemporer yang dipamerkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga di kancah internasional. Para kreator muda ini memadukan warisan leluhur dengan bahasa visual yang dipahami oleh generasi global. Mereka membuktikan bahwa pelestarian budaya bukan sekadar romantisme masa lalu, melainkan proses kreatif yang dinamis.
UNESCO dalam laporan 2022 menegaskan bahwa masa depan warisan budaya sangat bergantung pada pelibatan generasi muda, bukan sekadar sebagai penjaga pasif tetapi sebagai inovator yang mentransformasikan tradisi agar relevan dengan zaman.
Generasi Z memiliki keunggulan unik: hidup dalam jejaring global, mahir teknologi, dan terbiasa beradaptasi. Di tangan mereka, cerita rakyat bisa menjadi serial web, batik tampil di panggung mode dunia, dan musik tradisional bersanding dengan teknologi augmented reality. Korea Selatan menjadi contoh sukses bagaimana K-pop dan K-drama—yang menyisipkan unsur budaya tradisional—menguasai panggung global. Indonesia dapat belajar bahwa budaya bukan hanya dipertahankan, tetapi ditawarkan sebagai kekuatan lunak.
Di Indonesia, budaya Nusantara tidak hanya dilestarikan tetapi juga dijadikan alat perekat sosial. Di era yang memicu polarisasi, seni dan tradisi menjadi jembatan pemersatu. Generasi Z dikenal sebagai generasi paling inklusif. Mereka terbuka terhadap keberagaman etnis, agama, gender, dan perspektif hidup. Festival Indonesia Menari, yang melibatkan ribuan penari muda dari berbagai latar belakang, menjadi bukti budaya adalah ruang membangun kebersamaan.
Seni dan budaya Nusantara mengandung filosofi yang dalam. Dari tarian, musik, batik, hingga upacara adat, semua mengajarkan nilai spiritual dan sosial. Bagi generasi muda, pelestarian budaya bukan beban, melainkan peluang menggali potensi diri dan bangsa. Budaya yang hidup adalah budaya yang terus berkembang. Mengutip gagasan bijak, “Segala sesuatu yang hidup selalu berubah.” Pelestarian budaya berarti menjaga esensi dan nilai di dalamnya, bukan terpaku pada bentuk lama.
Perubahan zaman memang tidak bisa dihindari. Namun nilai-nilai budaya bisa tetap dijaga dan bahkan tumbuh bersama perubahan itu. Pelestarian budaya bukan tugas segelintir orang, tetapi gerakan kolektif. Pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta perlu membangun ekosistem yang mendukung kreativitas budaya anak muda. Kurikulum harus membuka ruang bagi ekspresi budaya lokal. Platform digital harus memberi tempat bagi konten budaya. Dana abadi kebudayaan yang sudah ada perlu dioptimalkan agar komunitas muda tidak hanya bertahan, tetapi berkembang.
Pada akhirnya, Generasi Z tidak hanya bisa menjadi penjaga warisan. Mereka adalah nahkoda yang membawa budaya Nusantara melintasi zaman—dihidupi sebagai identitas modern yang bermakna. Seperti seniman yang melukis dengan kuasnya, Generasi Z adalah generasi yang bisa menciptakan kanvas besar yang memadukan masa lalu, kini, dan masa depan.
“Budaya adalah api yang tak akan padam, selama ada generasi yang berani meniupkan napas kehidupan ke dalamnya.”