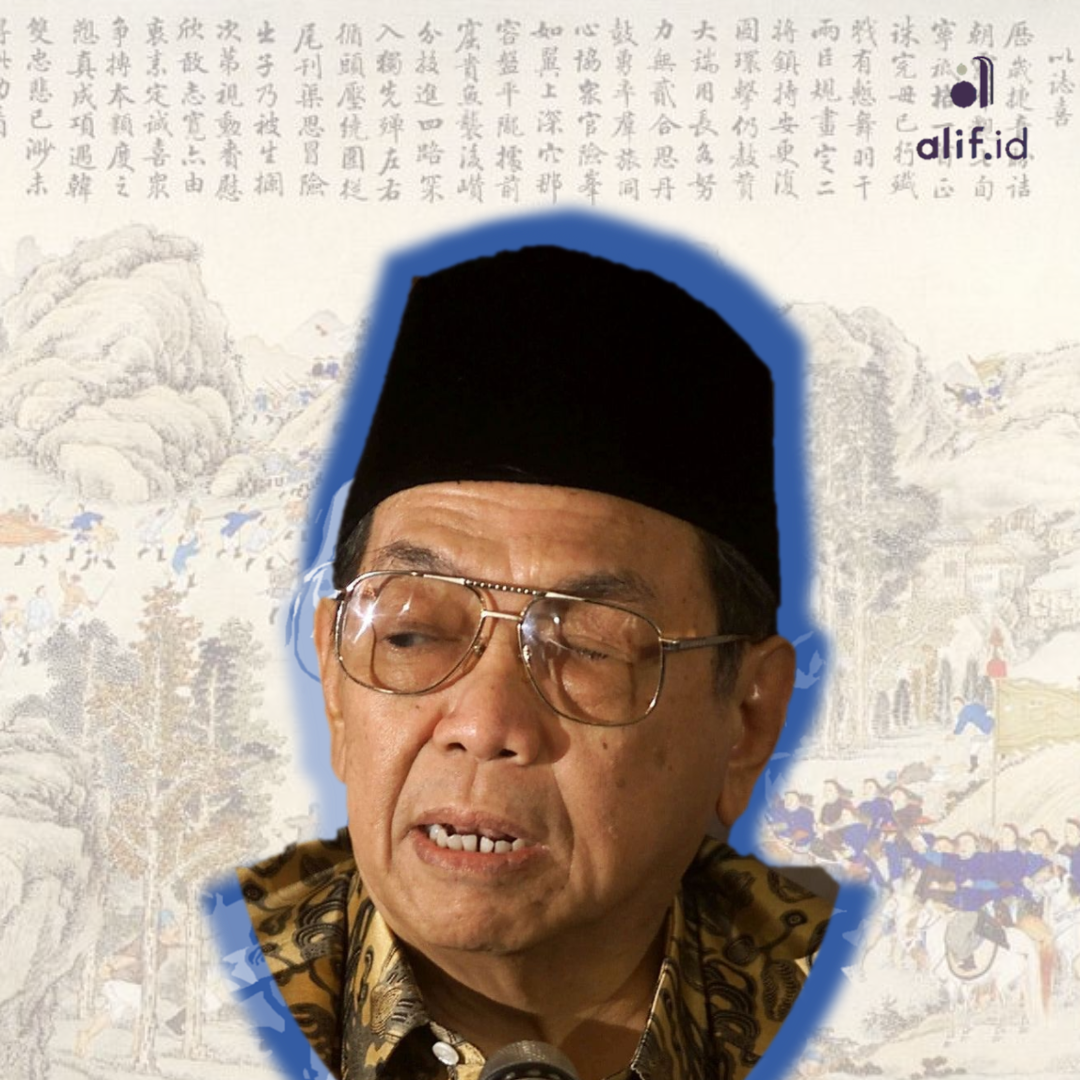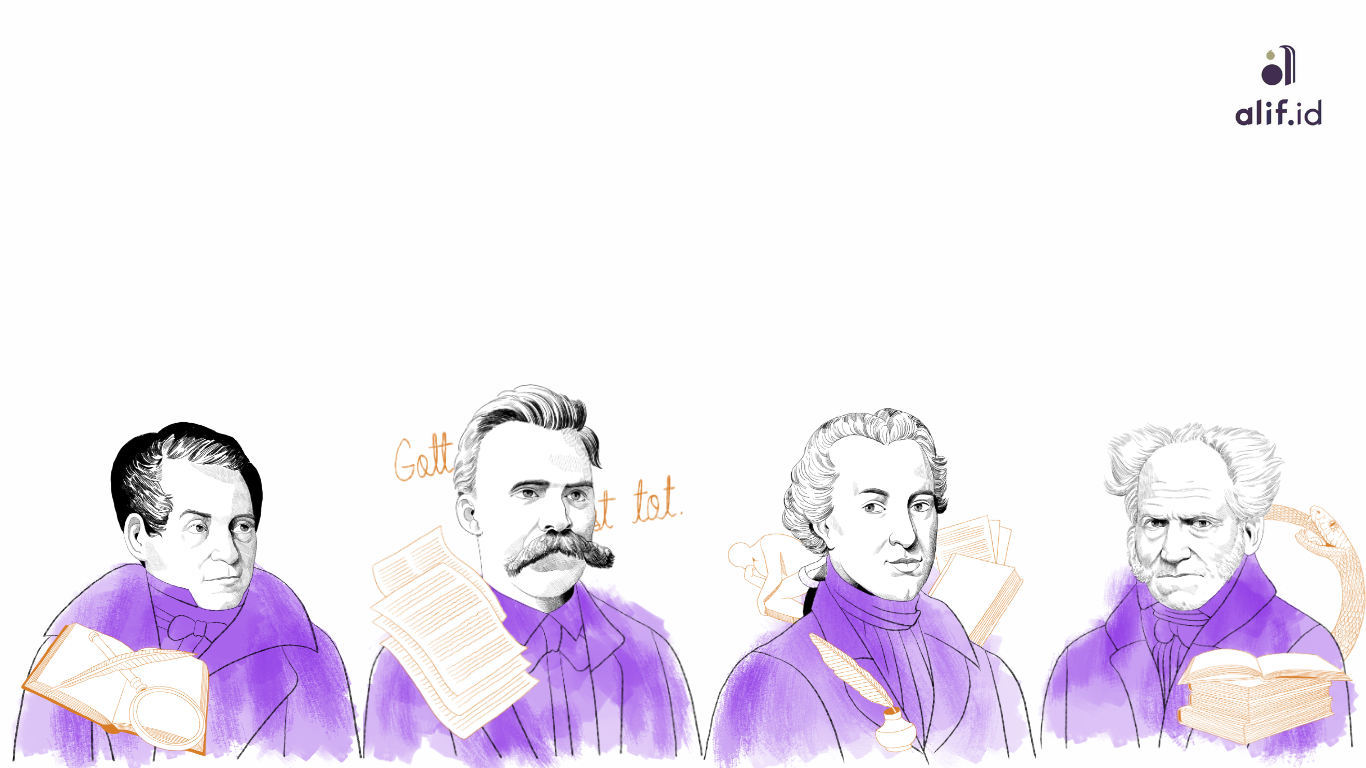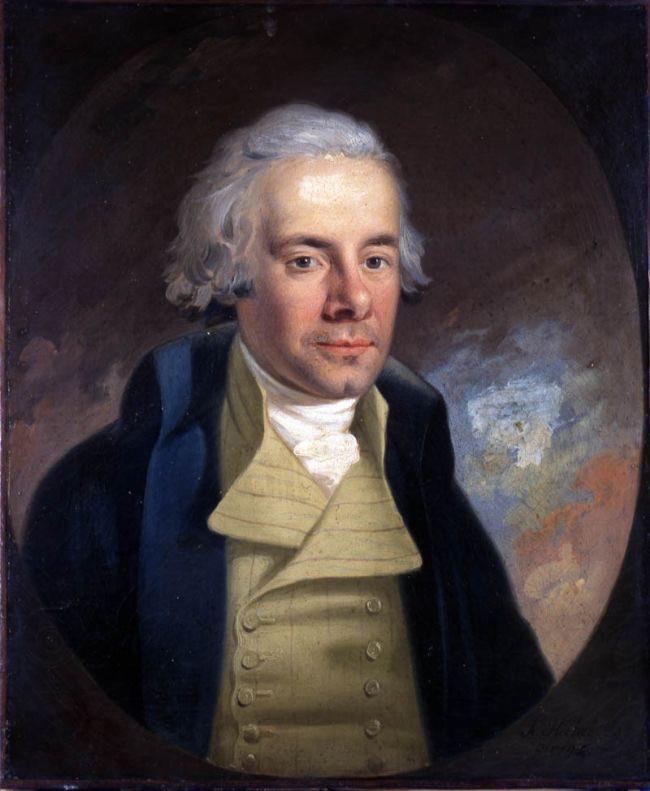Di sebuah desa pada abad keenam belas di lereng Gunung Cakrabuana, menjelang matahari terbit, seorang kakek tua bernama Kai Raga, duduk bersila menghadap timur. Wajahnya bening oleh usia dan ketenangan, jemarinya menghitung biji tasbih dari kayu gaharu tua—warisan leluhurnya. Di hadapannya, tergelar sebuah serat beraksara Jawa kuna: ꦱꦁꦲꦾꦁꦲꦪꦸ—Sang Hyang Hayu.
Serat ini terdiri dari Serat Catur Bumi, Serat Buwana Pitu, Serat Sewaka Darma, dan Serat Dewa Buda. Pengarangnya seorang warga di Tatar Sunda, yang buah karyanya ternyata menjadi perantara dua dunia. Tak banyak yang tahu, terkandung di dalamnya warisan paling halus dari kebudayaan spiritual Nusantara: keseimbangan antara langit-bumi, manusia-semesta, dan Ilahi.
Dalam bahasa Sunda, kata ‘hayu’ bukan sekadar ajakan (mari), melainkan gema dari konsep rahayu—keselamatan dan harmoni. Dalam Kropak 630, naskah kuno Sunda dari abad ke-16 yang kini tersimpan di Perpustakaan Nasional, konsep hayu muncul dalam petikan doa: “Mugia rahayu salamet ti sanghyang manon“, yang berarti “semoga keselamatan dan kebaikan datang dari Hyang Maha Melihat.”
Lebih dari sekadar kata, hayu adalah cara hidup. Ia semarak dalam adat kasepuhan; dalam larangan merusak hutan (leuweung larangan); dalam cara menyadap nira tanpa menyakiti pohon aren; dalam cara berbicara penuh unggah-ungguh. Ia mewujud sebagai tata rasa, tata laku, dan tata diri. Tiga prinsip utama (tri tangtu di buwana) dalam kebijaksanaan Sunda yang mementingkan keselarasan antara niat dan tindakan.
Dalam Serat Catur Bumi, unsur lemah atau tanah adalah lambang keteguhan batin, kesabaran yang mengakar, dan rasa lapang yang menerima segala proses kehidupan. Tanah tak pernah berkeluh kesah saat diinjak, dicangkul, atau kita abaikan. Ia tetap menumbuhkan, tetap menyimpan, tetap menopang.
Manusia tanpa unsur tanah dalam jiwanya akan mudah tercerabut—oleh sifat ahangkara. Ia kehilangan akar. Maka tak heran jika hidupnya limbung, kehilangan tempat berpijak. “Lemah kang dipiji, lemah kang dadi sejatining awak: Tanah yang kau injak adalah tanah yang menjadi dirimu sendiri.” Melalui geguritan di atas, kita diajak untuk menjadi tanah bagi diri sendiri dan orang lain: bersedia menopang, menumbuhkan, dan menyerap luka menjadi laku. Jiwa yang matang bukan yang keras, tetapi yang rela menjadi pesanggrahan semesta.
Banyu dalam Serat Catur Bumi adalah lambang rasa: empati, cinta, kasih, dan kesedihan yang tak terucap. Air tidak menolak bentuk. Ia meresap ke pori-pori tanah, menampung langit dalam riaknya, dan bahkan bisa menyimpan rahasia lautan. Namun, air juga bisa meluap. Maka ajarannya bukan hanya merasakan, tapi mengolah rasa—agar tak menenggelamkan akal dan cahaya dalam jiwa.
“Banyu kang bening, kang nyumurupi wujudé jagad lan rasa: Air yang bening adalah yang mampu memantulkan wujud dunia dan rasa dalam jiwa.” Menyelami pesan itu, kita seolah diingatkan: jangan takut menangis, tapi jangan larut. Jangan kering dari rasa, tapi jangan juga hanyut tanpa bentuk. Belajarlah dari air: mengalir, tapi tetap mencari lautan.
Dalam Serat Catur Bumi, unsur geni adalah lambang dari karsa—daya kehendak dan semangat hidup. Api adalah kehendak. Ia membakar, menggerakkan, membentuk tekad. Tapi api yang berkobaran akan melalap bukan hanya lawan, tapi juga diri sendiri. “Geni kang kawelasan, geni kang nyepetaké lakon: Api yang sarat welas asih adalah api yang mempercepat takdir berjalan.” Pesannya sederhana saja: jangan padam, tapi jangan membakar tanpa arah. Api dalam dirimu harus menjadi suluh, bukan sekadar obor yang membakar habis “hutan batin.” Semangat perlu disulut oleh cinta, bukan oleh dendam.
Angin atau maruta dalam Serat Catur Bumi adalah simbol dari cipta dan atma—pikiran dan jiwa yang mencari. Angin tidak pernah tinggal menetap. Ia hanya melintas. Tapi justru karena itulah ia membawa berita, membawa suara, membawa nafas. “Maruta iku suwara ing urip, suwara kang ora katon nanging nyurung: Angin adalah suara hidup: tak tampak, tapi mendorong segalanya bergerak.”
Kali ini kita diajak mendengar angin (udara) dalam diri sendiri. Pikiran yang jernih adalah angin yang membawa kabar, bukan yang berisik memecah hening. Nafas adalah zikir yang paling awal. Maka setiap helaan nafas adalah kesempatan untuk kembali kepada sumber: Sang Peniup ruh itu.
Serat Catur Bumi bukan sekadar ajaran tentang anasir, melainkan tentang tata letak jiwa. Empat unsur itu bukan beroperasi sendiri, tapi saling menata dan dinata. Bila tanah tak mengikat air, maka air akan hanyut. Bila api tak dijaga angin, ia jadi badai. Bila angin tak tahu arah, ia hanya riuh yang melukai daun. “Catur kang selaras, kang dadi gapuraning urip sejati: Empat yang selaras adalah gerbang menuju hidup yang sejati.”
Di era yang serba terburu-buru ini, Serat Catur Bumi datang seperti secarik peta dari langit yang terjatuh di telapak tangan kita. Ia mengajak kita membaca diri—bukan melalui cermin, tapi angin, tanah, air, dan api. Ia mengajarkan bahwa kesadaran tidak dilahirkan oleh kecepatan, tapi oleh keseimbangan. Jika empat unsur itu kau tata dalam dirimu, maka segala hal di luar tak akan membuatmu guncang. Sebab di dadamu sendiri, telah bersemayam bumi kecil, yang memutar hari dan malam tanpa kehilangan arah.
Serat Sewaka Darma
Dalam Sewaka Darma, dunia digambarkan sebagai sesuatu yang fana dan sarat penderitaan. Kesadaran akan kefanaan itu meliputi sikap menerima suka-dukanya hidup (lapar-kenyang, sehat-sakit, muda-tua, dan akhirnya mati). Meski demikian, realitas dunia yang dipenuhi duka tidak dianggap tanpa tujuan. Serat ini memperkenalkan konsep mhoksa (kesempurnaan hidup spiritual) sebagai tujuan akhir perjalanan manusia—bahwa “hidup mengarah pada kesempurnaan hidup”, dan untuk mencapainya diperlukan tekad dan kegigihan jiwa.
Sewaka Darma menggambarkan perjalanan hidup sebagai ujian untuk memperkuat tekad (misalnya menyatakan janji dan perjuangan dengan sepenuh hati). Dengan kata lain, teks ini mengajarkan agar setiap individu menyadari batas-batas duniawi dan terus memperbaiki diri, karena dunia hanyalah sementara. Sedangkan keberhasilan sejati adalah penyatuan dengan dharma (mhoksa). Secara keseluruhan, Serat Sewaka Darma menyajikan nilai-nilai moral tradisional Jawa-Sunda yang mendalam. Ajaran yang termaktub di dalamnya, pernah dijadikan pedoman kehidupan masyarakat tradisional di negeri kita, dan masih relevan sebagai nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat kiwari.
Bersambung..