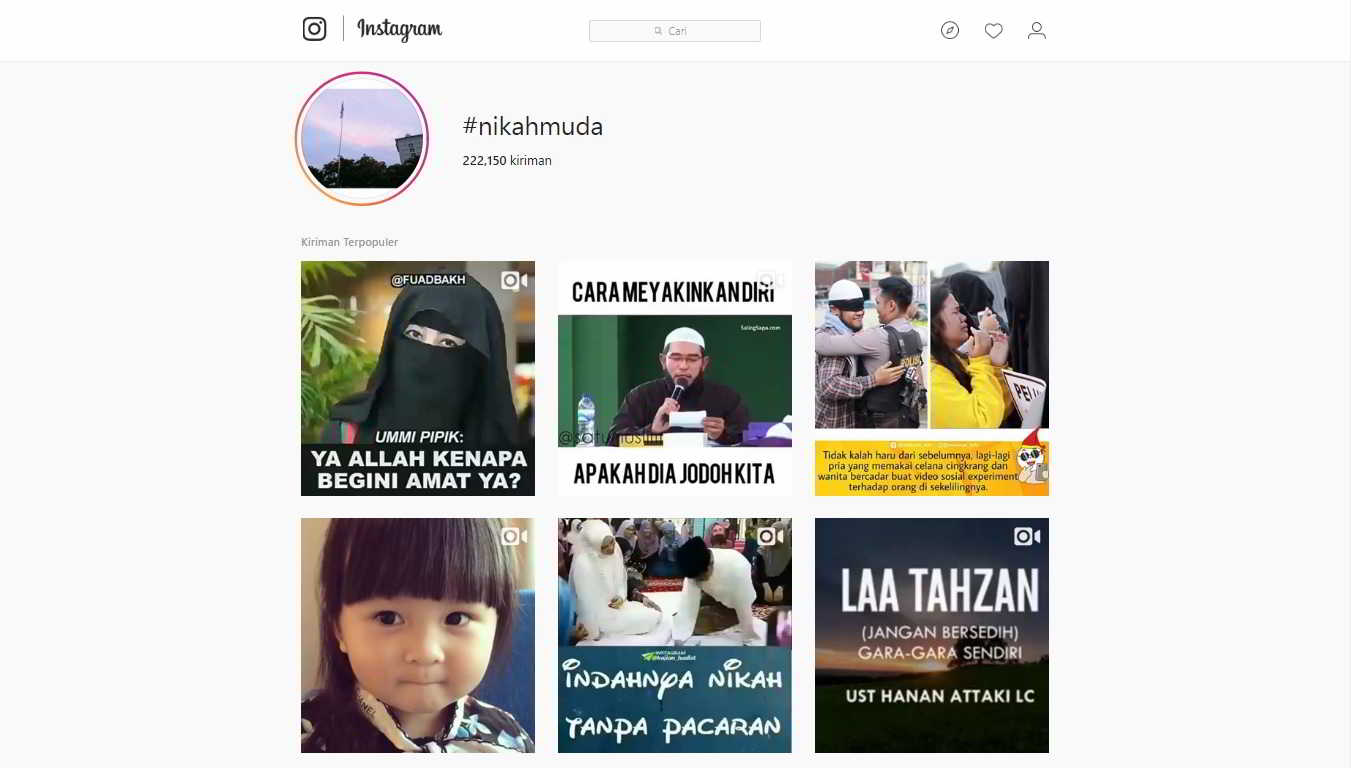Ibuku, Hj Husnul Khotimah, menghadap Sang Khaliq dalam usia 85 tahun pada Senin pagi, 6 April 2020. Semoga Allah telah mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima semua amal baiknya. Semoga beliau beristirahat dengan tenang di alam barzakh. Setiap untaian doa bagi beliau sungguh sangat berharga bagi kami yang ditinggalkannya.
Dalam situasi apapun, kehilangan seorang Ibu hampir seperti kehilangan segalanya. Waktu dan kenyataan membeku. Semua berubah bisu, tak bergerak dan menjelma menjadi duka yang amat pekat. Kepergian seorang Ibu meninggalkan lubang hitam yang menghisap segalanya menjadi kesedihan. Doa dan kepasrahan membantu mengurangi beban teramat berat itu secara perlahan-lahan. Juga doa dan simpati dari para tetangga dan teman-teman.
Ibuku meninggal dengan status sebagai PDP (pasien dalam pengawasan). Sejak awal, dengan usia beliau yang sudah sangat lanjut dan riwayat penyakit jantung serta paru-paru yang sudah dideritanya sejak 2,5 tahun terakhir, aku sendiri sebetulnya yakin bahwa Ibu meninggal secara alamiah karena fisiknya yang amat renta. Tapi dalam situasi wabah seperti saat itu, siapa saja yang masuk Rumah Sakit (RS) dengan gangguan pernafasan akan otomatis masuk kategori PDP. Aku sudah menjelaskan ini kepada tim medis begitu kami masuk RS Panti Rapih. Tapi lebih-lebih karena dalam waktu dua minggu itu aku baru pergi keluar Jogja—yaitu ke Jombang untuk menjemput kedua anakku di pesantren—pihak RS tetap memasukkan Ibu sebagai PDP. Semua demi kehati-hatian, untuk mengantisipasi segala kemungkinan, termasuk untuk melindungi kesehatan keluarga. Kalau akhirnya memang hasil tesnya negatif tidak apa, tapi jika positif, RS sudah melakukan tindakan semestinya, sehingga penularan penyakit bisa dicegah sebaik-baiknya. Ibuku pun segera menerima swab test pada hari pertama dan kedua masuk RS.
Aku hanya pasrah. Terasa berat memang, tapi aku juga sangat memaklumi betapa para petugas medis berusaha melakukan yang terbaik untuk setiap pasien dan anggota keluarganya. Alhamdulillah, Ibuku pelanggan asuransi kesehatan BPJS, sehingga semua biaya, kecuali ongkos ambulans, ditanggung oleh BPJS.
Ketika pertama kali dibawa ke RS Panti Nugroho hari Sabtu siang, Ibuku memang sudah kritis. Dokter menyatakan bahwa Ibu mengalami stroke ringan. Sewaktu dalam perjalanan kami masih bisa komunikasi biasa. Tapi begitu masuk RS beliau kejang-kejang lagi. Hari itu di rumah beliau sudah kejang-kejang beberapa kali. Dalam dua bulan terakhir memang beliau sempat terjatuh dua kali. Pertama di teras rumah, sewaktu bangun dari duduk setelah berjemur pagi hari. Yang kedua, ketika sudah mulai kembali bisa jalan dengan bantuan tongkat setengah lingkaran, beliau terjatuh lagi di kamar mandi. Di rumah Cilacap dua bulan sebelumnya beliau juga sempat tidak bisa bangun selagi buang hajat di kamar mandi dan memaksanya untuk dilarikan ke RS.
Sejak saat itulah kujemput beliau dan kuminta tinggal di Jogja. Sudah sejak hampir tujuh tahun terakhir, ketika kesehatan fisiknya makin menurun, sebetulnya kami sudah meminta beliau tinggal bersama kami di Jogja. Tapi kalau sudah sebulan di Jogja, asal merasa sehat, selalu ada saja alasan yang membuat Ibuku meminta pulang dan kami tak bisa menolaknya. Dulu sempat setengah kupaksa beliau tak boleh pulang, tapi akhirnya malah sakit. Dari banyak cerita saudara dan teman-teman, akhirnya aku sadar dan hanya bisa menuruti apa kemauan beliau saja. Kalau lagi mau di Jogja, beliau kami jemput. Tapi kalau sudah meminta pulang ke Cilacap, kami antar.
Terutama sejak terjatuh yang terakhir di kamar mandi di rumah kami di Jogja, Ibu lebih sering terbaring di kasur. Tapi baru pada hari ketika akhirnya kami bawa ke RS Panti Nugroho itu Ibuku kejang-kejang. Awalnya hanya gerak-gerak kecil tak terkontrol di kaki, tapi lama-lama gerakan itu makin keras dan berubah menjadi kejang-kejang di sekujur tubuh. Aku baru tahu kemudian, rupanya itulah gejala stroke.
Di Panti Nugroho dokter memberi tahu bahwa kondisi Ibu sudah sangat buruk. Konsumsi obat jantung yang dijalaninya selama 2,5 tahun terakhir rupanya harus dibayar dengan kerusakan ginjal. Ginjal yang rusak membuat tubuhnya keracunan. Kejang-kejang itu berasal dari sana. Stroke adalah urutan berikutnya. Paru-parunya pun kini setengah terendam. Hari itu HB darahnya juga sangat rendah. Secara fisik beliau sudah sangat lemah. Itulah yang membuatku sangat yakin, meski ada gangguan pernafasan, itu pasti bukan karena Covid-19. Tapi pihak RS yang harus menangani begitu banyak orang memang tetap harus hati- hati. Kami maklum saja dan mematuhi prosedur yang harus dilewati dengan sikap yang pasrah.
Peralatan di RS Panti Nugroho tidak memadai untuk perawatan Ibu. Maka hari itu juga, lewat tengah malam Ibu dirujuk ke RS Panti Rapih, setelah menunggu untuk mendapatkan kamar pasien berjam-jam. Situasi darurat Covid membuat mayoritas RS di Jogja penuh. Malam itu juga Ibu masuk ruang ICU, sebagai PDP, seperti kutulis di depan. Tak boleh ada anggota keluarga yang menemani dari dekat. Di Panti Rapih mestinya Ibu segera mendapat transfusi darah, supaya kemudian bisa dilakukan cuci darah untuk membersihkan racun-racun yang membuat tubuhnya kejang-kejang. Transfusi pertama berhasil dilakukan pada siang harinya. Karena HB darah Ibuku masih sangat rendah, cuci darah pun belum bisa dilakukan. Pagi berikutnya, ketika cuci darah itu tetap belum bisa dilakukan, rupanya kondisi Ibu semakin drop. Beliau kritis.
Aku sudah seperti mendapat firasat. Itulah saat-saat terakhir Ibuku sebelum mangkat. Meski tadinya tim medis melarang keras aku untuk masuk ruangan, aku tak menyerah. Aku harus mendampingi Ibu pada saat-saat terakhir.
Siapapun tak bisa menghalangiku, dengan alasan apa pun.
“Mungkin ini adalah saat-saat terakhir Ibu saya di dunia. Saya sangat yakin, Ibu saya tidak kena virus Corona. Saya harus mendampinginya untuk berdoa. Ijinkan saya masuk. Saya harus berada di sampingnya. Jika Ibu Anda dalam keadaan kritis seperti Ibu saya sekarang tapi tak bisa mendampinginya, padahal hanya berjarak beberapa meter saja, seperti apa perasaan Anda?!”
Akhirnya tim medis mengijinkan saya masuk. Begitu berada di dalam, kupeluk dan kuciumi wajah Ibuku. Kubisikkan di telinganya bahwa aku ada di sampingnya. Aku meminta beliau supaya tawakkal, pasrah kepada Allah.
Kuusap-usap rambut dan keningnya. Nafasnya terlihat sangat berat. Tapi pandangannya berubah lebih tenang ketika berkali-kali lagi kubisikkan kalimah thoyyibah di telinganya. Sambil tak kuasa menahan tangis, aku terus memeluk tubuhnya. Kubacakan al Qur’an dan dzikir di telinganya tanpa henti. Kalau saja aku bisa menggantikan dirinya untuk menanggung rasa sakit yang dideritanya, ingin rasanya biar aku saja yang merasakan semua yang menimpanya. Aku terus membaca Qur’an dengan air mata yang makin deras.
Hampir dua puluh tahun lalu, adikku satu-satunya, Bariroh Baroroh, juga menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit ini. Ia meninggal dalam pelukanku dan Ibu, orang-orang yang paling mencintainya. Tiba-tiba aku teringat dialog terakhir antara Ibu dan adikku dua puluh tahun lalu itu. Secara begitu saja, aku pun seperti mengulang apa yang dikatakan Ibu pada adikku. Kali ini kalimat itu kuucapkan di telinga Ibu: “Aku sudah ikhlas. Kamu juga yang ikhlas ya. Serahkan semuanya kepada Allah. Besok insya Allah kita ketemu lagi di sana. Besok tolong jemput aku. Yang ikhlas ya, Bu. Allah, Allah, Allah…..”
Istriku tak diijinkan masuk. Dia hanya menyaksikan kami dari balik kaca jendela kamar ICU. Entah berapa lama, mungkin 1,5 jam lebih, aku terus memeluk tubuh Ibuku sambil tak henti tadarrus, dzikir dan menangis secara bergantian. Ketika bacaanku sampai pada ayat “Salamun qaulan min rabbir rahiiiiiim……” yang kuulang berkali-kali, kudengar suara mesin monitor berbunyi panjang. Tak lama kemudian dua orang dokter datang untuk memeriksa. Mereka seperti ingin menyampaikan sesuatu padaku, tapi aku tak peduli dan terus khusyuk membaca Qur’an. Lalu, mereka mulai melepasi peralatan di sekitar Ibuku. Apa yang mereka lakukan membuatku makin erat memeluk tubuh Ibu dan tak henti melanjutkan bacaan Qur’an di telinganya.
Entah berapa lama setelah itu, para dokter itu akhirnya memberitahuku bahwa Ibu sudah wafat. Meski berita itu bukan tidak terduga, bumi tempat kakiku berpijak seperti runtuh berantakan. Ibu yang sepanjang hidupnya telah menjadi penopang keberadaanku kini telah pergi untuk selama-lamanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji’uuuun….
Aku seperti tak lagi bisa melihat apa-apa, tak ada kalimat yang bisa kuucapkan. Entah berapa lama lagi masih kupeluk Ibuku, kuusap-usap wajahnya yang mulai terasa dingin. Aku hanya bertanya, bagaimana harus kutebus semua kebaikan yang tak henti mengalir untukku sejak hari pertama aku terlahir ke dunia ini?
Tim dokter kemudian menjelaskan, karena status Ibu sebagai PDP, dengan permohonan maaf, mereka memberitahu bahwa proses pemakaman Ibu harus mengikuti prosedur standar Covid. Tidak ada pemandian seperti biasa, juga tidak boleh singgah dulu di rumah. Jenazah Ibu yang dibalut beberapa lapis,
dimasukkan ke dalam peti yang juga dibungkus plastik untuk diantar mobil jenazah ke makam di kampung tempat kami tinggal. Dari Panti Rapih, dalam waktu tidak lebih dari 4 jam, Ibu sudah harus dimakamkan. Aku hanya bisa menurut dengan hati pasrah. Sepanjang jalan, kupeluk peti jenazah Ibu dan kembali tak henti tadarrus. Istriku yang sibuk mengurus semua keperluan administrasi dan mendengar informasi dari tim medis.
Aku seperti tak bisa merasakan apa-apa lagi. Semua terasa begitu berat, tapi semuanya juga seperti melayang. Ketika turun dari mobil, di makam ketiga anak-anakku sudah menunggu. Puluhan tetangga juga hadir membantu kami. Satu-satu anak-anakku kupeluk dan kami lama bertangisan. “Embah sudah tak ada. Doain Embah ya. Jadi cucu yang shaleh dan shalehah….” Mereka menitikkan air mata dalam pelukanku.
Karena tak sempat shalat jenazah secara langsung, kami shalat ghaib untuk Ibu setelah pemakaman selesai. Tentu saja kami diliputi rasa kecewa yang tak terkira, karena Ibu dimakamkan tidak menurut tata cara ketentuan agama dalam situasi normal. Tapi dengan menyadari bahwa situasi ini memang darurat dan ada ketentuan lain yang membolehkannya, kami hanya pasrah dengan sepenuh doa. Malamnya, sampai malam ketujuh, kami mengadakan doa tahlil dengan belasan tetangga sekitar. Banyak anggota keluarga, teman-teman dan kolega kami juga turut memanjatkan doa lewat zoom dari jauh.
Dua minggu setelah Ibu dimakamkan, baru kami mendapat informasi dari RS bahwa hasil swab test Ibu adalah negatif, seperti yang kuyakini sejak awal.
Ibu sudah pergi hampir dua bulan, tapi rasanya semua seperti baru kemarin. Tiap kali terbersit wajahnya, air mataku kembali menitik begitu saja bersama doa yang tak henti kupanjatkan. Sejak kepergian Ibuku, aku memandang hidup dan mati dengan nilai yang hampir sama. Ayah dan Ibuku, adikku, kedua kakakku telah menghadap Sang Khaliq. Jika kelak aku mati, semoga aku bisa kembali dipertemukan dengan orang-orang yang sangat kucintai. Jika aku berumur panjang, semoga aku juga terus hidup bersama orang-orang yang amat kucintai, istri dan anak-anakku. Hidup atau mati, apa yang lebih bermakna ketimbang disatukan bersama orang-orang yang kita cintai? Yang harus dilakukan adalah, bagaimana supaya makna itu bisa kita rengkuh lebih utuh dengan menggoreskan tindakan-tindakan berharga sehingga hidup dan mati kita ada yang patut untuk dikenang.
Ibu, semoga Engkau telah kembali kepada sang Pemilik Hidup secara husnul khatimah, seperti namamu. Dengan mengenang seluruh kebaikan dan perjuanganmu, kini kakiku bisa kembali berpijak. Ibu adalah pondasi bagi setiap anak-anaknya. Lahal fatihah….