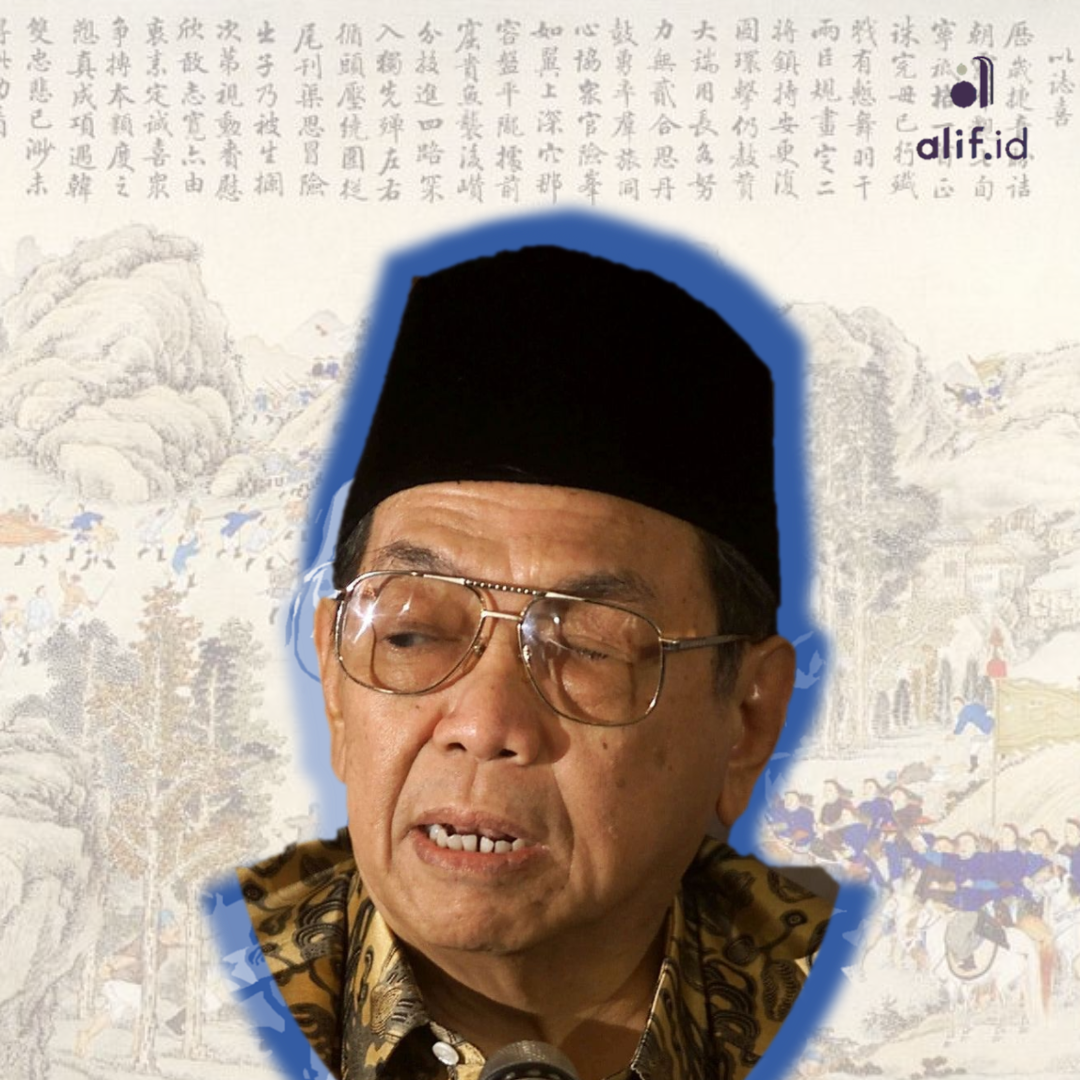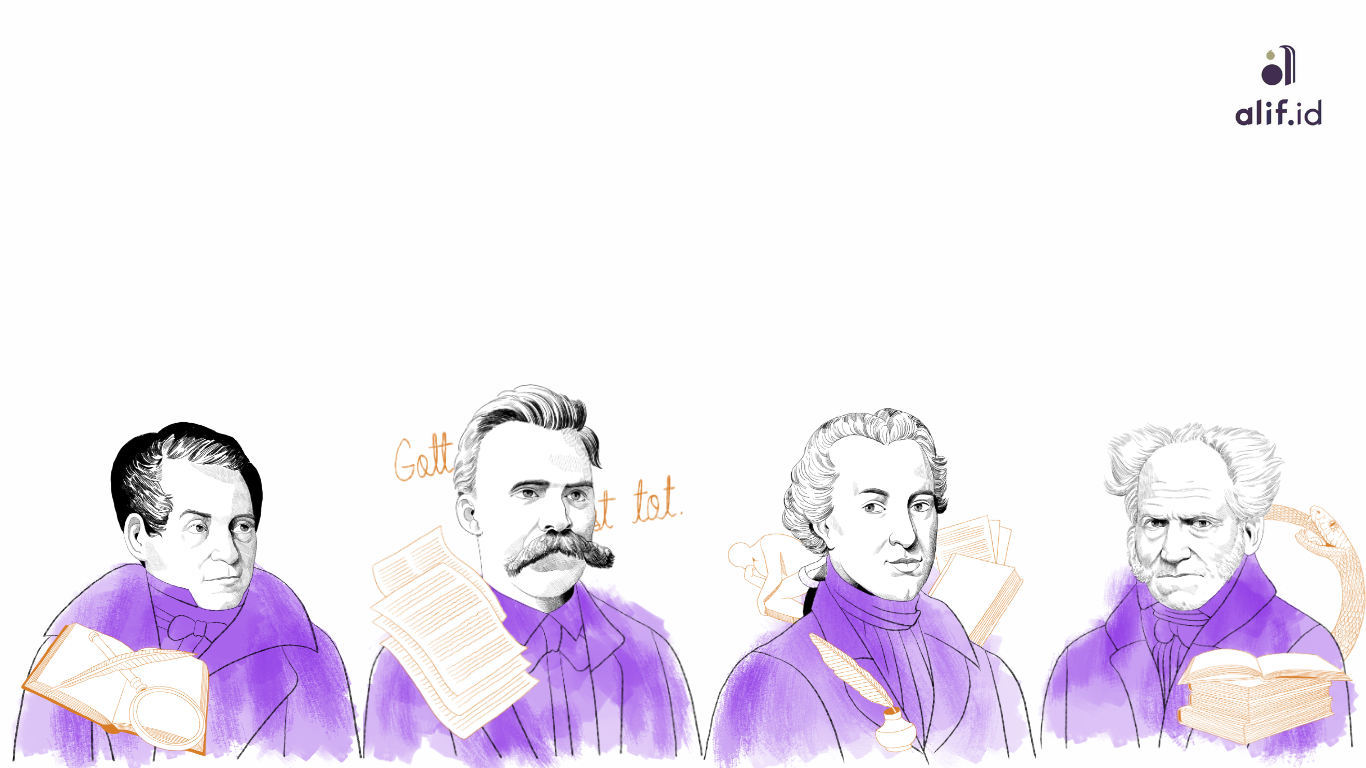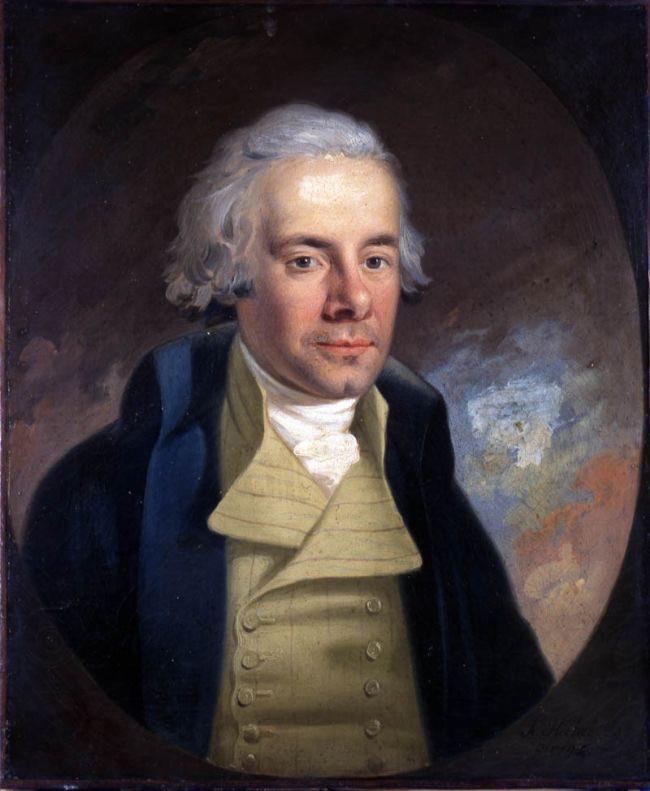Perayaan Hari Kartini adalah warisan orang-orang Belanda, ketokohan dari sosok ini merupakan produk dari pengetahuan kolonial. Festivalisasi Kartini bahkan berusia lebih tua dari republik kita. Pada tahun 1918, untuk pertama kalinya Kartinidag atau Hari Kartini diperingati di Semarang. Sampai akhir masa penjajahan di Hindia Belanda, Yayasan Kartini yang didirikan oleh para bule yang bersimpati pada Putri Jawa dari Jepara ini rutin mengadakan peringatan yang mengenang riwayat hidupnya (Harnawan, 2021).
Sampai sekarang, tanggal 21 April dirayakan oleh masyarakat Indonesia sebagai hari untuk mengenang seorang perempuan cerdas yang melenting lewat gagasan dari surat-suratnya yang pertama kali dipublikasikan tahun 1911, setelah dikumpulkan oleh Jacques Henrij Abendanon. Hari Kartini dianggap sebagai sebuah kelaziman dan menjadi rutinitas tahunan oleh banyak orang, jarang orang mempertanyakan mengapa mesti Kartini? Apa bedanya tokoh tersebut dengan perempuan terdidik sezamannya?
Hari Kartini pertama kali diperingati di era Indonesia merdeka pada tahun 1946, dan Kartini sendiri kemudian diangkat sebagai pahlawan nasional pada 1964. Tradisi ini kemudian diteruskan oleh Orde Baru, diperingati setiap tahun di seluruh penjuru Nusantara, terutama oleh anak-anak sekolah dan di lingkungan instansi pemerintahan. Cepatnya pemerintah republik untuk menetapkan peringatan Hari Kartini, kemungkinan berkaitan dengan kebutuhan pragmatis akan sosok yang perlu ditokohkan dan sudah dikenal luas oleh publik pada masa itu.
Hal ini serupa dengan strategi kelompok nasionalis sekuler semacam M. Yamin yang mencari pijakan kejayaan masa lalu dengan memunculkan Majapahit dengan segala klaim-klaim kebesaran historisnya. Cara yang sama nampaknya dilakukan dalam kasus peringatan Hari Kartini, mungkin pada masa itu perempuan Indonesia membutuhkan simbol yang bisa dengan cepat diterima oleh masyarakat. Karena pada saat Indonesia merdeka, perempuan yang paling populer di wilayah bekas Hindia Belanda adalah Kartini.
Menurut Muhammad Yuanda Zara (2024), peringatan Hari Kartini pada awal masa kemerdekaan adalah salah satu cara untuk menumbuhkan nasionalisme di kalangan perempuan Indonesia saat negara-bangsa yang baru lahir ini masih membentuk idenitas nasionalnya. Selain itu, promosi Hari Kartini yang dilakukan melalui media secara masif di periode revolusi (1946-1949) juga menjadi ajakan untuk kaum perempuan agar mau ikut dalam perjuangan membangun negara di momentum kritis saat berkonflik dengan negara bekas penjajahnya.
Posisi Kartini sebagai media darling membuat sosok ini menjadi solusi instan bagi kebutuhan kampanye politik persatuan di awal kemerdekaan. Dalam dokumentasi media, peringatan Hari Kartini pertama kali muncul di koran De Locomotief pada tahun 1929 (Mahy, 2012). Sebuah media yang berkantor di Semarang, kota yang menjadi tempat peringatan Hari Kartini pertama sebelas tahun sebelumnya. Popularitas Kartini mulanya terbangun karena kumpulan suratnya menjadi buku laris lalu diterjemahkan ke dalam banyak bahasa dan menjangkau pembaca luas.
Setelah terbit pertama kali dalam bahasa Belanda pada 1911, Door Duisternis Tot Licht lalu diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul Letters of a Javanese Princess pada tahun 1920. Penerjemahan inilah yang kemudian menjadi populer hingga kemudian bermunculan terjemahan dalam bahasa Prancis, Rusia, Jepang, dan Arab. Untuk pembaca di tanah air, surat-surat Kartini diterjemahkan ke bahasa Melayu dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang, lalu bahasa Sunda dengan judul Tina Poek Ka Noe Tjaang dan juga bahasa Jawa pada zaman kolonial (Bijl dan Chin, 2020; Harnawan, 2021).
Nama Kartini di zaman penjajahan semakin populer karena liputan media tentangnya terbilang tinggi. Menurut Paul Bijl (2015), sampai dengan 1945, terdapat kurang lebih 1600 tulisan tentang Kartini yang tersebar di berbagai surat kabar berbahasa Belanda. Dengan sorotan yang begitu banyak, tidak terlalu mengherankan jika pada awal kemerdekaan para pimpinan pemerintahan memilihnya sebagai simbol perempuan teladan dari bangsa sendiri. Namun dipilihnya Kartini sebagai tokoh nasionalis perempuan untuk menentang kolonialisme adalah sebuah ironi, karena popularitasnya justru dirancang oleh pengetahuan kolonial.
Narasi ketokohan Kartini terkesan menjadi wacana tunggal yang dominan tentang citra perempuan Indonesia, secara perlahan hal tersebut mereduksi pluralitas wajah perempuan Indonesia dan juga menyamarkan berbagai sosok perempuan penting lain karena terpinggirkan oleh kampanye Kartini sejak awal Indonesia berdiri. Identitas Kartini yang selalu ditonjolkan ke permukaan, membuat identitas perempuan Indonesia dari golongan sosial, kelas, atau perangkat identitas lainnya yang berbeda tidak mendapat tempat memadai dalam pengetahuan publik.
Dengan hanya adanya Kartini di puncak kesadaran masyarakat tentang sosok ideal perempuan Indonesia, berbagai kelompok di luar lingkaran sosial tempat Kartini berasal ikut berkontestasi memperebutkan Kartini. Salah satu yang menghebohkan adalah hasil editan foto Kartini yang mengenakan kerudung beberapa waktu lalu. Fenomena ini menjadi tanda bahwa ada sebagian kelompok yang merasa terpinggirkan, tidak memiliki perwakilan dalam wacana publik. Sehingga mereka merasa perlu merebut simbol dengan sebuah rekayasa dan membuat kelompoknya mendapat pengakuan luas.
Dominasi ketokohan Kartni juga menjadi wajah Indonesia yang sentralistik. Seperti wajah kekuasaan negeri ini. Paradoks bagi sebuah negara yang punya identitas sangat beragam. Karena sudah menjadi kebiasaan, bukan berarti orang-orang dari wilayah selain Jawa tidak pernah merasa ganjil untuk mengenakan kebaya setiap 21 April.
Pekerjaan yang mungkin perlu dilakukan saat ini adalah mengangkat nama-nama perempuan dari banyak kelompok lain ke permukaan agar setiap kelompok punya teladannya. Sehingga nasionalisme perempuan Indonesia bisa benar-benar menjadi persatuan, bukan persatean. Sayangnya, produksi pengetahuan tentang tokoh perempuan lain masih relatif minim. Kalangan santri misalnya, selalu tergopoh-gopoh menyebut Kartini sebagai santri (dalam artian yang paling luas) hanya karena pernah menimba ilmu kepada Kiai Soleh Darat. Padalah ia berasal dari kultur abangan yang telah mengalami pembaratan.
Kalangan santri nampak kurang percaya diri untuk mengangkat tokoh perempuan yang lahir dari tradisi pesantren dengan intonasi sekuat kalangan abangan-sekuler mengangkat nama Kartini. Mungkin mentalitas ini pula yang menyebabkan kalangan santri tidak bisa tahan lama berada dalam kepemimpinan nasional jika dibandingkan dengan para pimpinan dengan wajah abangan.
Untuk menampakkan sosok-sosok perempuan hebat lain dalam panggung sejarah yang layak, mungkin bisa meminjam pendekatan Sheila Rowbotham (1976) tentang cara penulisan sejarah perempuan agar bisa “terlihat.” Pertama, menyingkap fakta tokoh-tokoh perempuan di masa lalu. Kemudian melakukan interpretasi ulang terhadap narasi sejarah tentang peristiwa-peristiwa penting yang menafikan kehadiran para tokoh perempuan, yang telah membuat mereka “tersembunyi.” Lalu mengungkap aktivitas tokoh perempuan dalam proses perjuangan untuk untuk mencapai keadilan bagi banyak orang.
Dengan dibukanya tabir sejarah tokoh-tokoh perempuan selain Kartini, maka pluralitas wajah perempuan akan bersinar terang dan keluar dari kesunyian lorong sejarah. Sejarah tokoh-tokoh perempuan yang lain perlu ditulis dan dipopulerkan agar tidak terjadi mistifikasi sosok Kartini, membuat wacana tentang perempuan Indonesia lebih berimbang.
Menulis sejarah tokoh perempuan dari kelompok masing-masing dan dengan sudut pandang yang beragam mungkin akan menjadi proses dekolonisasi dalam wacana ketokohan perempuan. Karena bagaimanapun, perlu diingat bahwa popularitas Kartini adalah produk pengetahuan kolonial. Sosoknya dibuat berdasarkan kepentingan rezim kolonial yang pada masa itu tengah gencar mengampanyekan keberhasilan politik etis.
Tokoh-tokoh perempuan lain juga perlu ikut dirayakan. Meskipun demikian, penghormatan pada sosok Kartini tentu masih perlu dipertahankan, tapi bukan sebagai satu-satunya simbol yang paling utama dari kepahlawanan seorang perempuan Indonesia, melainkan sebagai salah satu dari banyak sosok perempuan lain yang berjasa besar bagi masyarakat.