Dengan membincangkan kembali tema peradaban Islam, saya membuka diri untuk dikata-katai muluk-muluk. Apa pentingnya bicara peradaban Islam pada masa sekarang, di era post truth, meningkatnya populisme, di tengah siapa pun bisa mewakili agama Islam? Bukannya lebih bermanfaat bicara tentang problem politik atau yang kita hadapi sehari-hari?
Begitu pertanyaan yang mungkin muncul di benak sebagian kita, dan sebenarnya juga di hati saya. Tapi tidak apa-apa. Saya malah merasa tema ini perlu digaung-gaungkan kembali agar “menghantui” pikiran kita. Dengan begitu akan muncul ide-ide dan upaya-upaya membangun kembali peradaban Islam “secara abad ke-21”, yang menyumbang pada peradaban kemanusiaan global.
Yang perlu disadari adalah bahwa peradaban kemanusiaan itu tidaklah tunggal, dan merupakan tenunan berbagai peradaban: Timur, Barat, Selatan, Utara. Dalam konteks ini, sumbangan peradaban Islam kontemporer nyaris tak terlihat.
Pertanyaan tentang peradaban ini muncul dalam dan ‘menghantui’ pikiran saya sejak lama, sejak belajar sejarah Islam di madrasah dan belajar di IAIN. Namun peristiwa yang agak menohok kesadaran saya adalah saat mengikuti "the first International Convention of Asia Scholar" (ICAS), sebuah konferensi besar yang dihadiri ahli-ahli Asia dari 140 negara, dan ada 130 panel, yang diselenggarakan di Leiden, tapi bertempat di Noordwijkerhout, Belanda, pada 1998. Penyelenggaranya adalah International Institute of Asian Studies (IIAS), sebuah lembaga riset tentang Asia yang berpusat di Leiden. Ya, saat itu saya mahasiswa magister di Leiden University.
[caption id="attachment_218814" align="alignnone" width="198"]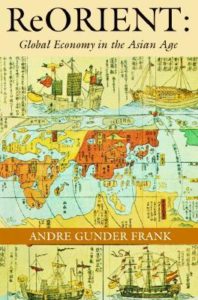 Apa yang terjadi setelah 21 tahun buku ini terbit?[/caption]
Apa yang terjadi setelah 21 tahun buku ini terbit?[/caption]
Saat di bus menuju lokasi, saya penasaran dengan Andre Gunder Frank, yang saat itu akan meluncurkan bukunya yang baru saja terbit, Re-ORIENT: Global Economy in the Asian Age (1998). Frank adalah sejarawan dan sosiolog ekonomi global yang mempromosikan world-system theory.
Frank menerapkan beberapa konsep Marxian, tetapi menolak tahapan-tahapan sejarah dan sejarah ekonomi Marx secara umum. Dia mengutip juga konsep ekonomi Ibn Khaldun tentang “wealth of nations” (kekayaan bangsa-bangsa), empat abad sebelum Adam Smith.
Saat menghadiri peluncuran bukunya saya duduk di samping Goenawan Mohamad yang saat itu didapuk memberikan keynote speech (saat itulah saya tahu kalau kaos kaki GM bolong di jempol kaki. Haha). Pidato GM saat itu menarik The Last Temptation of the West, terasa senafas dengan buku Frank itu.
Sebagaimana judul bukunya “Re-ORIENT” (di sampul buku ditulis: ReORIENT), dia mendekonstruksi pandangan-pandangan "Eurosentrik" tentang peradaban dunia, dan mengatakan bahwa dominasi Barat sebenarnya baru dimulai pada abad ke-19. Sebelum Barat, peta ekonomi global dikuasai Cina, India, Jepang, dibantu oleh Rusia, Persia dan Imperium Ottoman. Dan yang menghantui saya itu adalah pernyataannya bahwa peradaban itu bergeser dari suatu tempat ke tempat lainnya. Dari Timur ke Barat, lalu akan kembali ke Timur.
Ya, judul buku dia “Re-Orient” memprediksikan bahwa peradaban akan kembali ke Timur! Jauh sebelum Kishore Mahbubani menuliskan prediksi lebih-kurang serupa dalam bukunya The New Asian Hemisphere: The Irresistible Shift of Global Power to the East (2008).
Saat mendengar pernyataan Frank, saya mulai bertanya-tanya dalam hati, “Apakah Timur itu Islam, negara-negara Islam?” Sebagaimana yang saya duga dia mengatakan, peradaban akan kembali ke Asia, dan itu adalah Cina, India, Jepang! Hadhehh…
Saat itu saya lihat buku manual konferensi yang bergambar "Burak" (atau Buraq), kuda bersayap dengan kepala gadis cantik berambut panjang. Walau itu gambaran populer tentang Buraq yang banyak kita temui di Indonesia, tapi itu digambar oleh orang Asia Selatan.
[caption id="attachment_208338" align="alignnone" width="300"] Imajinasi seniman Indonesia, Nasirun tentang Burak (2015)[/caption]
Imajinasi seniman Indonesia, Nasirun tentang Burak (2015)[/caption]
Memang image Burak seperti itu jamak di Asia. Gambaran dalam hadis tidak seperti itu. Bahkan digambarkan seperti bighal (keledai). Imajinasi liar saya mengatakan itu seperti unicorn yang melesat melalui black hole.
Burak adalah tunggangan Nabi Muhammad saat Isra‘ dan Mi‘raj, yang mengantarkan beliau ke Masjid al-Aqsha dan ke Sidrah al-Muntaha (Pohon Lote di Batas Terjauh) di langit tertinggi, di mana beliau bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah shalat lima waktu. Mengapa setelah Barat itu bukan, yang disiratkan oleh gambar ini, negara-negara Muslim Asia? Tetapi secara objektif haruslah saya akui bahwa di bandingkan ketiga negara tersebut, negara-negara Muslim masih jauh.
Tulisan terkait:
Setelah pulang dari Belanda, saya mulai mengajar di UIN Sunan Kalijaga. Di antara mata kuliah yang saya ajar, di samping yang bernuansa studi Islam, adalah Filsafat Ilmu dan, belakangan, Agama dan Teori-teori Sosial.
Di tengah ruang kuliah itu, saya selalu dihadapkan pada kenyataan tentang absennya filosof dan ilmuwan sosial muslim di sana. Satu sisi ini memang disebabkan karena ilmu pengetahuan yang berkembang saat ini, termasuk di negara kita, bersifat "Euro-sentris", berpusat pada Eropa. Ada jejak kolonialisme dan politik pengetahuan di sana.
Pada sisi yang lain, sejak runtuhnya Andalusia pada abad ke-14, memang peradaban Islam tidak sepenuhnya ikut runtuh. Masih ada Dinasti Mogul di India (abad ke-16 s.d. ke-19), dan Ottoman (Usmani) di Turki (abad ke-13 s.d. ke-20).
Namun, harus diakui bahwa tidak lagi muncul filosof-filosof dan ilmuwan-ilmuwan muslim yang mumpuni dalam bidang filsafat dan ilmu sosial sekelas Ibnu Sina, Ibnu Rusyd dan Ibnu Khaldun, untuk menyebut sebagian (mohon koreksi jika salah).
Saya merasa absennya nama-nama ilmuwan sosial muslim itu wajar, karena memang tidak ada. Kecuali Ibnu Khaldun, yang hadir 400-an tahun lebih awal dari ilmuwan-ilmuwan sosial Barat yang rata-rata muncul pada abad ke-18, ke-19, dan ke-20. Itu pun, tak semua textbook teori sosial menyebut Ibnu Khaldun.
Sejak tiga tahun lalu, iseng-iseng saya, di sela-sela kesibukan akademis dan sosial di kampung, mulai membaca kembali “ide-ide” terserak ulama dan intelektual Muslim tentang peradaban. Sebagiannya sudah pernah saya pelajari di IAIN dan Leiden.
Saya mulai dengan membaca Jalaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridha, dan Syakib Arslan--para pembaru jaringan Mesir. Saya posting di Facebook saya saat itu. Terima kasih kepada alif.id yang "meng-Alif-kan" tulisan-tulisan ringan itu. Saya merasa gagasan-gagasan mereka menarik dan masih relevan.
Ide-ide itu rencananya akan saya sanding-bandingkan dengan ide-ide peradaban yang muncul di kalangan pemikir Muslim di belahan Dunia Islam, termasuk Indonesia, dan Barat. Yang akah mengkhawatirkan adalah rupanya energi saya untuk membaca dan menulis seringkali byar pet. Muncul-tenggelam. Banyak tenggelamnya, malah. Klelep. Tetapi mudah-mudahan ada energi untuk menuliskannya.
Penekanan pada sejarah ide atau sejarah intelektual ini bukan berarti saya mengabaikan peran orang-orang biasa dalam membentuk sebuah peradaban.
Saya termasuk yang berpendapat bahwa peradaban itu dibentuk oleh bukan hanya oleh aktor-aktor besar (nabi, raja, ilmuwan), tetapi juga petani, pedagang, difabel, dan sub-altern lainnya. Mereka juga aktor-aktor peradaban dalam dunia Islam.
Namun, karena keterbatasan, perkenankan saya memfokuskan diri dulu pada ide-ide peradaban. Itu semua dalam rangka upaya memikirkan kembali bangunan peradaban Islam. Bukan demi masa lalu, tapi masa kini dan mendatang. In urīdu illa l-islāh ma-stata‘tu.
Yogyakarta, 1 Ramadan 1440/6 Mei 2019




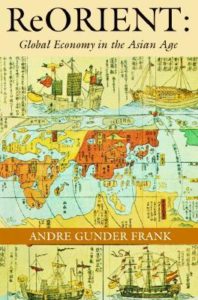 Apa yang terjadi setelah 21 tahun buku ini terbit?[/caption]
Apa yang terjadi setelah 21 tahun buku ini terbit?[/caption]
 Imajinasi seniman Indonesia, Nasirun tentang Burak (2015)[/caption]
Imajinasi seniman Indonesia, Nasirun tentang Burak (2015)[/caption]


