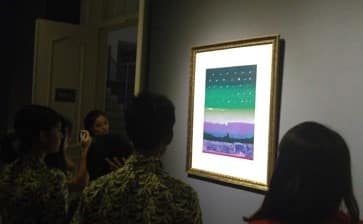Slametan: Jantung Spiritualitas Orang Jawa
Slametan bagi orang Jawa adalah wujud rasa syukur, kebersamaan, dan doa yang tidak pernah putus.

Di tengah arus modernisasi, banyak tradisi lokal mulai tergerus oleh gaya hidup praktis dan serba instan. Namun, di Jawa, masih ada satu tradisi yang tetap hidup dan dijaga hingga kini, yakni slametan. Sebuah ritual sederhana yang mengintegrasikan doa, kebersamaan, dan jamuan makan. Saya kira, ini bukan hanya sekadar peristiwa budaya belaka, melainkan justru sebagai jantung spiritual masyarakat Jawa. Clifford Geertz, seorang antropolog asal Amerika, bahkan menyebut slametan sebagai inti kehidupan keagamaan orang Jawa.
Klaim Geertz di atas, saya kira juga cukup menunjukkan resiliensi tradisi slametan, betapa tradisi itu memiliki daya tahan luar biasa yang mampu bertahan di berbagai wilayah, baik itu di pedesaan maupun di perkotaan, serta di komunitas agraris maupun maritim (Hakim & Yoesoef, 2023). Saya kira, juga bukan hanya itu saja, bahkan dalam dinamika sosial yang terus berubah pun, slametan tetap berfungsi, tetap hidup sebagai ruang kebersamaan, sebagai sarana perekat sosial, bahkan sekaligus sebagai simbol harmoni antara manusia, alam, dan dunia gaib.
Simbol Kesetaraan
Slametan adalah sebuah aktivitas individu sekaligus kolektif, berupa upacara sederhana yang biasanya digelar di rumah. Tuan rumah menyiapkan hidangan, para tetangga, saudara, dan kerabat diundang untuk duduk bersama. Ada doa yang dibacakan, lalu makanan dibagikan. Tidak ada pesta meriah, tidak ada pula musik atau tari-tarian, tapi justru kesederhanaannya itulah yang kemudian mencipta dan penuh dengan makna.
Menurut Arif Budiman (2022), ia memaknai slametan sebagai sebuah ritual, merepresentasikan wujud ekspresi syukur dan permohonan keselamatan yang diwujudkan melalui serangkaian doa dan penyajian sesaji atau ubarampe, yang memiliki makna filosofis mendalam dalam kosmologi Jawa.
Dalam slametan, semua makhluk dianggap sama sebagai ciptaan Tuhan. Antara si kaya dan si miskin, tua dan muda, bahkan roh leluhur dan makhluk halus dipercaya ikut hadir. Di sinilah letak uniknya, slametan merangkul dunia nyata sekaligus dunia gaib.
Seperti apa yang disampaikan oleh Eka & Sinduwiatmo (2024) bahwa, slametan, adalah sebuah ritual komunal yang tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk memohon perlindungan dari gangguan makhluk kasat mata maupun yang nyata, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat ikatan sosial dan komunitas antar warga.
Dengan demikian, saya kira, kesetaraan yang lahir dalam ritual slametan itu, sejatinya mencerminkan falsafah hidup orang Jawa, dengan selalu menjunjung tinggi sebuah prinsip “rukun”. Dalam suasana itu, tercipta simbol konstruktif, bahwa setiap orang merasa memiliki kedudukan yang sama, baik di hadapan Tuhan maupun di tengah masyarakat. Tidak ada jarak sosial yang membedakan derajat seseorang, sebab semua duduk melingkar dalam posisi yang setara. Karena itulah slametan menjadi ruang penting untuk merawat harmoni sosial, sekaligus sarana kultural yang mampu mengelola perbedaan secara damai di tengah kehidupan masyarakat.
Lebih dalam lagi, bahwa slametan juga menjadi sebuah bentuk komunikasi simbolik antara manusia dengan dimensi transendental. Sesaji, doa, dan kebersamaan bukan hanya sekadar formalitas ritual, melainkan itu semua menjadi cara konkret untuk terus meneguhkan relasi spiritual yang menyatukan unsur mikrokosmos (individu dan masyarakat) dengan makrokosmos (alam semesta dan kekuatan gaib). Dengan demikian, artinya bahwa, slametan hadir bukan hanya sebagai ekspresi religius, tetapi juga sebagai jembatan filosofis yang menjaga keseimbangan antara kehidupan sosial, spiritual, dan kosmis.
Detak Rukun dalam Denyut Sosial
Di balik doa yang lirih dan hidangan sederhana yang tersaji tersebut, tersimpan pesan mendalam tentang betapa pentingnya hidup berdampingan secara damai, menjadi sebuah denyut rukun yang menjaga harmoni dalam kehidupan masyarakat Jawa, status sosial melebur dan yang tersisa hanyalah rasa kebersamaan.
Inilah wajah rukun ala Jawa. Sebuah kesadaran kolektif yang saya kira harus terus dijaga, bahwa kesadaran atas ketenteraman hidup tidak hanya dibangun terbatas oleh individu, melainkan juga lahir dari solidaritas bersama, sehingga memiliki rasa kesalingan, saling peduli, saling menolong, dan saling menghormati.
Namun, harus diingat dengan penuh kesadaran bahwa ini bukan sekadar ritual, tetapi lebih dari itu, ini adalah sebuah denyut sosial yang akan terus menjaga jalinan antarwarga tetap hidup dan berdetak seirama.
Ibarat sebuah benang, ritual ini saya kira menjadi sebuah benang halus yang menjahit perjalanan hidup orang Jawa, dari awal kelahiran hingga akhir kematian. Setiap tahap kehidupan tidak pernah dilewati begitu saja, melainkan ditandai dengan ritual yang mengikat masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu lingkar doa. Mulai dari tingkeban, pitonan, pernikahan, hingga slametan kematian. Semuanya adalah simpul-simpul waktu yang terajut oleh tradisi ini.
Sebagai pungkasan, melalui slametan, orang Jawa tidak sekadar merayakan peristiwa, melainkan meneguhkan keterhubungan mereka dengan leluhur, sesama, dan generasi yang akan datang. Ia menjadi semacam jembatan spiritual yang memastikan bahwa nilai-nilai kebersamaan, syukur, dan doa tidak putus oleh perubahan zaman. Dalam kesederhanaannya, slametan merupakan cara orang Jawa merawat kesinambungan hidup, menjaganya agar waktu tidak hanya berjalan, lewat begitu saja, tetapi juga harus bermakna.