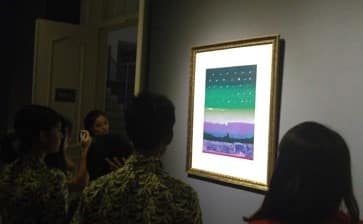Kritik Pesantren: Antara Ilusi Kebangkitan Kiri dan Bayangan Ekstrem Kanan
Kritik terhadap pesantren belakangan ini bukanlah dorongan dari ideologi kiri, melainkan aktor yang lebih dominan justru berasal dari kanan ekstrem—Salafi takfiri, dan sejenisnya.

Beberapa hari terakhir muncul analisis yang cukup ramai diperbincangkan di kalangan intelektual muda: bahwa kritik terhadap pesantren, baik pada kasus Ponpes Al-Khoziny maupun dalam riuh tayangan Trans7, merupakan bagian dari “kebangkitan ideologi kiri” yang mulai mendapat tempat di kalangan Gen Z.
Sekilas pandangan itu tampak menarik, karena memang belakangan ini wacana kiri, buku Tan Malaka, hingga narasi anti-feodalisme mulai mencuat kembali. Sebagian influencer sosial media juga terlihat membawa semangat kritik ala sosialisme terhadap negara dan struktur sosial. Namun setelah saya renungkan secara lebih jernih, tesis bahwa kaum kiri adalah aktor utama serangan terhadap pesantren justru terasa tergesa-gesa, bahkan keliru dalam membaca peta zamannya.
Kritik kaum kiri pada dasarnya bergerak di ranah struktur sosial, ekonomi, kelas, dan kesadaran material. Ketika ideologi kiri menyerang agama, ia biasanya menyoal “agama sebagai ideologi penindas”, “opium”, “alat legitimasi kelas atas”, atau “mitos yang harus dibongkar melalui rasionalisme materialis.” Di titik inilah sebagian orang mengira bahwa istilah seperti “feodalisme pesantren”, “kelas santri tertindas”, atau “logika mistik” adalah bukti bahwa ideologi kiri sedang menyerang pesantren. Padahal istilah-istilah itu tidak otomatis menandakan gerakan kiri yang hidup dan sistematis. Kata-kata itu lebih sering dipungut secara random oleh para pembenci agama, aktivis sekuler, buzzer digital, bahkan oleh kelompok kanan ekstrem yang membungkus serangannya dengan istilah modern.
Kalau kita telusuri dengan jernih, siapa sebenarnya yang paling keras, paling agresif, dan paling konsisten menyerang tradisi pesantren selama ini? Bukan Marxis. Bukan sosialis. Juga bukan pengusung Tan Malaka. Yang paling keras dan paling hidup serangannya justru datang dari kelompok kanan ekstrem: Salafi takfiri, HTI, Wahabi garis keras, dan varian-variannya.
Mereka ini muncul dari rahim gerakan yang mengklaim kemurnian tauhid, menolak tradisi keagamaan lokal, mengharamkan takzim kepada guru, dan memvonis amaliyah pesantren sebagai bid’ah, syirik, khurafat, dan ahlul hawa. Mereka tidak berbicara tentang kelas sosial, tapi tentang neraka dan tauhid. Mereka tidak menyerang dari wilayah ideologi materialis, tapi dari tafsir tekstual yang ketat dan eksklusif.
Lihat saja narasi yang bertebaran di media sosial saat kasus Ponpes Al-Khoziny mencuat. Istilah “kultus”, “sesat”, “kyai dianggap wali”, “santri memperbudak diri”, dan “ngalap berkah sebagai kesyirikan” bukan kosa kata khas kiri, melainkan narasi kanan takfiri. Begitu pula ketika tayangan Trans7 menggambarkan pesantren seolah tempat penindasan, kekerasan, dan praktik mistik, narasi yang bersorak bukan kelompok kiri, tapi akun-akun Salafi radikal dan eks HTI. Mereka menyambutnya sebagai “momentum terbongkarnya kesesatan tradisi pesantren.”
Kelompok kiri mungkin sesekali ikut menyindir agama, tetapi mereka tidak punya jaringan dakwah, tidak punya basis massa keummatan, tidak punya agenda memurnikan akidah, dan tidak punya gairah membongkar kitab kuning. Yang punya gairah itu adalah kanan ekstrem yang dalam dua dekade terakhir aktif menggerogoti fondasi ajaran Islam tradisional. Mereka yang menyalahkan tawassul, mencurigai amalan tahlil, dan memperolok ijazah sanad. Mereka yang menuduh hormat kepada guru sebagai pengkultusan. Mereka pula yang men-delegitimasi peran kyai dalam kehidupan sosial dengan dalih “kemurnian”.
Lalu mengapa sebagian orang mengira kritik ini berasal dari kiri? Karena narasi liberal-sekuler yang oportunis sering memungut istilah kiri seperti “feodalisme” untuk menyerang agama atau institusi tradisional. Namun mereka bukan bagian dari gerakan kiri ideologis yang jelas. Sekadar memungut diksi kiri tidak menjadikan seseorang sosialis atau Marxis. Bahkan kelompok kanan ekstrem pun kadang meminjam retorika sosial bila diperlukan untuk memukul lawan.
Kita perlu membedakan antara “pengaruh wacana kiri” dan “gerakan kiri yang hidup.” Buku Madilog bisa laris, tapi tidak berarti komunisme sedang bangkit. Influencer bisa bicara anti-feodalisme, tapi tidak berarti mereka kader kiri. Bahkan istilah “logika mistik” bisa dipakai siapa saja yang anti agama. Yang berbahaya bukan istilahnya, tapi siapa yang memegang megafon dan kemana serangan diarahkan.
Dalam konteks inilah pesantren tidak boleh salah membaca arah angin. Jika kita mengira sedang diserang dari kiri, maka kita sibuk membuat argumen materialisme lawan spiritualitas. Padahal yang menyerang akidah kita justru kanan ekstrem yang anti tradisi. Kalau kita salah membaca musuh, kita akan salah menyiapkan benteng.
Serangan terhadap pesantren hari ini bukan semata persoalan konten media, tetapi kelanjutan dari proyek panjang untuk memutus mata rantai otoritas keilmuan Islam tradisional. Ada tangan ideologi takfiri yang ingin menjatuhkan martabat kyai agar umat kehilangan marja’. Ada jaringan dakwah transnasional yang sejak lama membidik pesantren sebagai benteng terakhir Ahlussunnah wal Jamaah. Dan anehnya, sebagian dari kita malah sibuk membayangkan sosok Marxis yang tidak pernah turun ke gelanggang.
Apakah wacana kiri tidak berbahaya? Tentu tetap menjadi tantangan di ranah diskursus dan intelektual. Tapi jika ditanya siapa lawan utama pesantren hari ini, jawabannya bukan kiri, melainkan kanan ekstrem yang berkamuflase dalam bahasa kesalihan.
Pesantren harus cerdas membaca peta ideologi agar tidak terjebak pada ilusi. Kita butuh narasi tandingan yang memperkuat tradisi, menegaskan akidah, dan merawat hubungan kyai-santri secara bermartabat. Tantangan kita bukan hanya mengoreksi stigma, tapi meneguhkan kembali bahwa pesantren bukan feodal, bukan mistik buta, melainkan institusi peradaban yang telah melahirkan ulama, pejuang, dan pendidik bangsa sejak sebelum republik ini lahir.
Jika ada ideologi kiri yang bangkit, hadapilah dengan dialektika dan argumentasi. Tetapi jangan buta terhadap ideologi kanan ekstrem yang sejak lama menusuk dari jantung umat sendiri. Di sinilah kewaspadaan kita diuji.