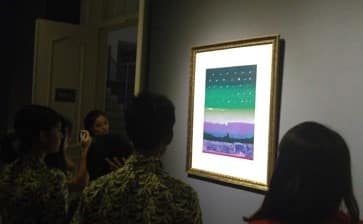Bukan Feodal, Adab Santri yang Sering Disalahpahami
Banyak tradisi atau kultur pesantren yang disalahpahami oleh kebanyakan awam. Seperti cara mereka berjalan, membungkukkan tubuh, dan mencium tangan.

Di tengah derasnya arus modernitas, tradisi santri yang mencium tangan kiai, menundukkan tubuh ketika lewat di hadapannya, atau berjalan merunduk di ruang-ruang pesantren sering kali menimbulkan perdebatan publik, bahkan ramai diperbincangkan di media sosial seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Di satu sisi, ada kelompok masyarakat yang memandang tradisi ini sebagai sisa feodalisme Jawa.
Di sisi lain, para santri justru melihat tindakan itu sebagai wujud cinta, penghormatan, pendidikan moral atau akhlak. Perbedaan tafsir ini menunjukkan bahwa takdhim atau etika bukan sekadar gerak tubuh, tetapi nilai dan norma sosial yang maknanya dibentuk oleh sudut pandang dan pengalaman sosial, spiritual, dan historis yang berbeda-beda.
Untuk memahami fenomena ini secara objektif, saya ingin mengombinasikan tiga pendekatan, yakni khazanah keilmuan Islam melalui beberapa kitab atau literatur ilmiah Islam seperti kitab Ta’lim al-Muta’allim, Adab al-Alim wa al-Muta’allim karya KH. Hasyim Asy’ari, dan Ihya’ ‘Ulum al-Din yang di dalamnya mengkaji tentang etika murid dan guru atau dalam tradisi pesantren disebut dengan santri dan kiai.
Saya juga ingin menggunakan kacamata sosiologi klasik yakni teori fakta sosial dan tindakan sosial Durkheim dan Weber. Pendekatan ini diharapkan memberi gambaran lebih utuh bahwa takdhim tidak bisa dinilai dari satu perspektif tunggal, sebab ia lahir dari tradisi yang kaya dan keberagaman interpretasi budaya dalam kehidupan masyarakat.
Membaca fenomena yang disebut sebagai “feodalisme” di pesantren harus menggunakan kacamata ilmu pengetahuan yang relevan dengan sifat persoalannya, karena isu ini merupakan fenomena sosial-budaya, bukan persoalan angka atau reaksi kimia, maka disiplin seperti sosiologi, antropologi, filsafat sosial, etika Islam menjadi pendekatan yang tepat untuk memahami nilai dan norma di pesantren, relasi kiai dan santri, makna adab atau etika, serta bagaimana struktur sosial dan nilai bekerja di dalam tradisi pesantren.
Sosiologi dapat mengkaji interaksi sosial dan struktur sosial, antropologi memahami makna budaya dan tradisi sebagai ekspresi identitas kolektif, filsafat menggali secara kritis dan rasional makna adab atau etika tersebut, sementara etika Islam memberi kerangka teoritis perspektif islam mengenai takdhim dan adab yang tidak dapat dipahami oleh ilmu sosial Barat semata.
Dengan demikian, analisis feodalisme di pesantren valid jika menggunakan ilmu yang memang dirancang untuk memahami manusia sebagai makhluk sosial dan kultural.
Takdhim sebagai Adab: Perspektif Keilmuan Islam
Islam menempatkan ilmu pengetahuan pada kedudukan yang sangat mulia bagi manusia. Hal ini ditegaskan dalam al-Qur’an, salah satunya melalui Surah Al-Mujādilah ayat 11:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْۚ وَاِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ
Ayat ini menyebut bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Ayat ini juga menjadi landasan teologis mengapa tradisi menghormati guru dan majelis ilmu begitu dijunjung tinggi dalam Islam. Penghormatan kepada orang yang berilmu bukan sekadar budaya, tetapi bagian dari etos keilmuan yang menempatkan ilmu dan para ahli ilmu pada derajat tinggi di hadapan Allah SWT.
Dalam tradisi keilmuan pesantren, takdhim bermakna mengagungkan, kata ini berasal dari kosakata bahasa arab yang bermakna mengagungkan atau menganggap besar sesuatu. Kemudian takdhim dalam pendidikan pesantren terkhusus bagi pencari ilmu, murid, santri, atau pelajar tidak hanya dimaknai kewajiban formal semata, tetapi takdhim juga dimaknai sebagai nilai (value) yang diwariskan turun-temurun yang mengandung kedekatan emosional, spiritual, dan sosial dengan kiai, ustadz, atau guru.
KH. Hasyim Asy’ari, Adab al-Alim wa al-Muta’allim, dalam Bab 2 yang berbunyi Fi Adabil Muta’alim Fi Nafsihi dan di Bab 3 yang berbunyi Adabul Muta’alim Ma’a Syaikhihi, menjelaskan tentang langkah dan etika seorang murid, santri, atau pelajar bagi dirinya sendiri saat belajar atau menggali ilmu pengetahuan, serta etika atau adab santri atau pelajar terhadap gurunya.
Kitab ini menekankan bahwa adab adalah kunci keberkahan ilmu. Adab mendahului ilmu, dan salah satu bentuk adab yang paling ditekankan adalah adab terhadap guru. Adab santri kepada kiai tidak dimaknai sebagai relasi politis sebagaimana dalam sistem feodalisme yang ada di Eropa pada abad pertengahan, akan tetapi sebagai relasi spiritual dan emosional dalam konteks keilmuan. Karena tidak ada motif kiai untuk menguasai santri, kiai yang dalam budaya Islam Jawa adalah tokoh yang memiliki pemahaman agama Islam yang mendalam tentang syariat dan akidah, serta memiliki karakter mulia yang dapat dijadikan contoh kebaikan bagi santri dan masyarakat Islam di Jawa pada dasarnya dalam rangka menyebarkan ajaran Islam dan ilmu pengetahuan Islam kepada santri.
Perbedaan motif inilah yang harus dikaji dan dipahami secara jeli, ilmiah, dan objektif agar tidak ada kesalahan dalam memaknai arti dan maksud feodalisme itu sendiri.
Sementara itu, Ta’lim al-Muta’allim karya Imam Burhanuddin al-Zarnuji dalam fasal keempat yang berbunyi Fasl fi Takdhimil Ilmi wa Ahlihi, dalam paragraf pertama berbunyi;
اعلم أن طالب العلم لا ينال العلم ولا ينتفع به إلا بتعظيم العلم وأهله، وتعظيم الأستاذ وتوقيره
Penting diketahui, seorang pelajar tidak akan memperoleh kesuksesan ilmu dan tidak pula ilmunya dapat bermanfaat, selain jika mau mengagungkan ilmu itu sendiri, ahli ilmu, dan menghormati keagungan gurunya.
Imam al-Ghazali dalam Ihya’ Ulum al-Din juga menekankan bahwa hubungan murid–guru adalah relasi mendidik jiwa. Guru bukan hanya penyampai pengetahuan, tetapi teladan moral. Karena itu, adab bersamanya dipandang sebagai bagian dari pendidikan karakter. Dalam perspektif ini, takdhim tidak bisa dilepaskan dari tujuan spiritual: membersihkan hati dari kesombongan, sebuah penyakit batin yang seringkali menghalangi seseorang menerima ilmu.
Dengan demikian, dari perspektif keilmuan Islam, takdhim bukan alat penundukan, melainkan alat pendidikan. Takdhim bukan sekadar aksi tubuh, tetapi upaya pembentukan karakter.
Bagi santri, jika mengacu pada kitab Ihya’ Ulum al-Din, takdhim adalah proses tazkiyah (pensucian diri) dari kemaksiatan dan kotoran batin seperti kesombongan dan kerakusan. Al-Ghazali memberi sentuhan sufistik dalam kitabnya agar aktivitas seseorang memiliki makna esensial, bukan sekadar rutinitas sosial, tetapi juga terdapat makna kausalitas antara makhluk dengan Tuhannya; ada ruh spiritual yang menghubungkan manusia dengan Allah SWT.
Takdhim Sebagai Fakta Sosial: Membaca Durkheim
Emile Durkheim memandang bahwa norma sosial baik berupa ritual, kebiasaan, maupun simbol bekerja sebagai fakta sosial yang eksis di luar individu dan bersifat memaksa. Namun pemaksaan di sini bukan selalu dalam arti kekerasan, melainkan dalam bentuk tekanan moral yang membuat masyarakat mematuhi suatu norma karena ia dianggap sakral.
Jika memakai lensa Durkheim, takdhim santri dapat dilihat sebagai norma kolektif yang mengukuhkan kohesi sosial. Pesantren selain sebagai institusi Pendidikan islam juga adalah komunitas moral yang di dalamnya terdapat nilai-nilai bersama yang menjadi fondasi solidaritas. Ketika santri menundukkan tubuh atau mencium tangan guru, tindakan itu memperkuat kesadaran bahwa mereka berada dalam komunitas yang memiliki aturan tertentu-aturan yang mereka sepakati dan hargai.
Durkheim juga mengatakan bahwa masyarakat cenderung membedakan antara yang sakral dan profan. Dalam konteks pesantren, guru, ilmu, dan adab terkait keduanya berada di ranah sakral. Takdhim menjadi cara untuk menjaga kesakralan tersebut. Tanpa adanya ritual penghormatan, nilai sakral ini bisa memudar dan pesantren kehilangan identitasnya sebagai institusi moral.
Dengan demikian, takdhim sebagai fakta sosial bukanlah feodalisme, tetapi simbol solidaritas moral dan kesadaran kolektif.
Takdhim sebagai Tindakan Sosial: Membaca Weber
Jika Durkheim melihat norma secara struktural, Weber melihatnya secara individual. Weber membagi tindakan sosial ke dalam empat kategori: rasional instrumental, rasional nilai, afektif, dan tradisional. Fenomena takdhim santri dapat dianalisis sebagai berikut: Pertama, tindakan rasional nilai. Santri meyakini bahwa menghormati guru membawa keberkahan dan keberhasilan ilmu. Tindakan mereka digerakkan oleh nilai, bukan keuntungan material. Kedua, tindakan afektif. Banyak santri merasa sangat mencintai dan menghormati gurunya. Ikatan emosional ini membuat takdhim dilakukan dengan tulus, bukan keterpaksaan.
Ketiga, tindakan tradisional. Pesantren memiliki tradisi yang panjang. Santri melakukan takdhim karena melihat senior mereka melakukannya, dan itu menjadi bagian dari habitus atau kebiasaan yang diwariskan. Keempat, tindakan rasional instrumental. Ada sebagian kecil santri yang mungkin berpikir bahwa menghormati guru mempermudah komunikasi atau mendapatkan perhatian. Namun ini bukan motif dominan dan tidak merepresentasikan makna takdhim secara keseluruhan.
Melalui Weber, kita memahami bahwa takdhim adalah tindakan yang sarat makna subjektif, bukan semata-mata tekanan struktural. Ia lahir dari nilai, cinta, dan tradisi, bukan paksaan.
Antropologi mengajarkan bahwa budaya tidak bisa dinilai untuk menggunakan standar budaya lain. Apa yang dianggap ekstrem di satu budaya bisa dianggap wajar, indah, atau penuh makna di budaya lain. Relativisme budaya ini penting dalam memahami mengapa masyarakat luar pesantren memiliki penafsiran yang berbeda tentang etika, adab, dan juga takdhim.
Dalam budaya Jepang, membungkuk adalah simbol hormat yang sangat tinggi. Di Korea, memanggil orang tua tanpa gelar tertentu dianggap kasar. Di India, siswa masih menyentuh kaki gurunya sebagai simbol penghormatan spiritual. Di sebagian wilayah Afrika, posisi tubuh saat menyapa orang tua menunjukkan status moral. Jadi, mengapa ketika santri menundukkan tubuh ia dianggap feodal?
Di sinilah pentingnya perspektif antropologis, semua budaya memiliki cara masing-masing untuk mengekspresikan hormat. Tidak ada budaya yang lebih “maju” dalam hal ini, yang ada hanyalah perbedaan orientasi nilai. Analogi dialog di film Hell on Wheels sangat tepat menurut saya dalam melihat fenomena ini. Ketika Senator Crane berkata, “I’m offering you a better way of life,” Chief of Horses menjawab, “Better than what? I like what I have.”
Percakapan ini menggambarkan bahwa “kemajuan” selalu relatif dan ditentukan oleh nilai yang dianut suatu kelompok. Bagi sebagian masyarakat kota yang modern, bentuk hormat ala santri dianggap ketinggalan zaman. Namun bagi santri, itulah cara terbaik untuk memuliakan ilmu dan menyucikan hati. Tidak ada standar universal untuk menentukan mana yang lebih baik.
Modernitas dan Perdebatan tentang Kemajuan: Apakah Semua Harus Meniru Barat?
Dalam perdebatan sosial kontemporer, ada kecenderungan mengukur kemajuan berdasarkan model Barat atau negara industri. Modernitas selalu diasosiasikan dengan model atau pendekatan pendidikan STEM, Sains (Science), Teknologi (Technology), Teknik (Engineering), dan Matematika (Mathematics) sehingga hal-hal yang tidak sesuai dengan kerangka ini dianggap “tradisional” atau “terbelakang”.
Namun masyarakat Indonesia tidak hidup dalam ruang hampa. Kita memiliki tradisi, agama, spiritualitas, dan budaya lokal yang kuat. Banyak kelompok masyarakat Indonesia tidak menginginkan modernitas yang semata-mata materialistik.
Misalnya dalam wacana nation-state dan pembangunan nasional oleh kalangan Islam kultural di Indonesia disebut “baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur” atau dalam falsafah Jawa disebut dengan istilah “Toto Titi Tentrem Kerto Raharjo” sebuah kehidupan yang harmonis, aman, adil, dan bermakna.
Pesantren bukan anti-modernitas, tetapi modernitas yang mereka inginkan adalah modernitas yang berpijak pada adab, bukan hedonisme atau sekularisme total. Mereka tidak menolak pendidikan sains, tetapi menolak jika sains dijadikan standar tunggal kemajuan dan menegasikan nilai spiritual.
Dalam antropologi klasik, Edward B. Tylor, yang dikenal sebagai bapak antropologi budaya mendefinisikan kebudayaan sebagai berikut
“Culture is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities acquired by man as a member of society.”
Dalam pandangannya, budaya adalah keseluruhan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, moral, adat, hukum, seni, dan kemampuan manusia lain yang diperoleh melalui proses belajar, bukan warisan biologis. Tradisi, dalam konteks itu, merupakan bagian dari budaya yang diwariskan antar generasi sebagai pola kebiasaan yang bertahan lama dan berfungsi menjaga kesinambungan sosial.
Di Indonesia, Koentjaraningrat menjelaskan kebudayaan sebagai sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang diperoleh melalui proses belajar, dengan tiga wujud utama, yakni gagasan (nilai, norma, konsep), aktivitas (tindakan dan ritus), serta artefak (benda hasil karya). Menurutnya, budaya muncul karena manusia memiliki kemampuan berpikir abstrak, kebutuhan hidup bersama, dan kreativitas dalam memecahkan masalah kehidupan sehari-hari.
Fungsi budaya pada dasarnya mencakup memberi pedoman hidup, menciptakan keteraturan sosial, membangun identitas kelompok, serta menjadi mekanisme adaptasi manusia terhadap lingkungannya.
Dengan demikian, budaya hadir secara ilmiah sebagai hasil pembelajaran kolektif yang memungkinkan manusia bertahan, bermakna, dan berkembang dalam kehidupan sosialnya.
Maka, kita sebagai satu bangsa yang multikultural dan plural ini tidak bisa hidup tanpa perbedaan. Keberagaman adalah keniscayaan bagi bangsa dan negara Indonesia, perbedaan yang tetap bersatu dalam Republik Indonesia. Perbedaan nilai dan cara pandang jangan dijadikan standar untuk mengatakan baik atau buruk dalam kehidupan sosial; ini tidaklah relevan. Maka saya sebagai penulis menekankan pentingnya berpikir ilmiah agar segala fenomena yang terjadi dalam masyarakat tidak disikapi secara kekerasan dan memicu konflik yang pada akhirnya merugikan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri.