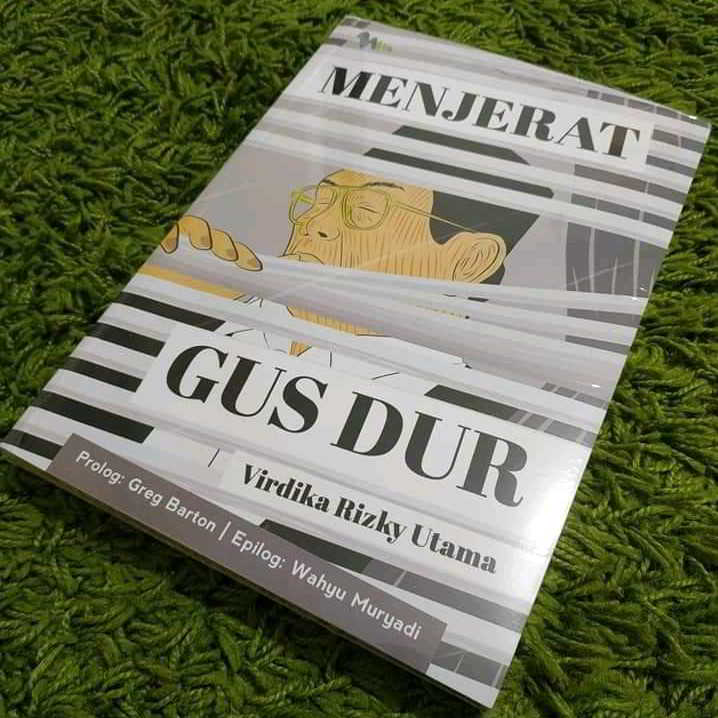Hampir tiga bulan menjalani diskusi buku Menjerat Gus Dur di 50 kota (dari 80 kota yang direncanakan) di Jawa, Bali, dan Sumatera tentu sebuah hal yang sangat penting dalam hidup saya. Tak hanya itu, dari beberapa tempat membuat saya semakin mengukuhkan bahwa Gus Dur tidak pernah pergi. Ia selalu hidup bersama orang-orang yang berjuang dan terpinggirkan. Gus Dur lebih dari sekadar tokoh Nahdlatul Ulama (NU), ia adalah pejuang kemanusiaan yang nyata.
Oleh sebab itu, selama bulan ramadan ini saya akan menulis kembali beberapa episodik tentang isi buku Menjerat Gus Dur. Akan tetapi, pada tulisan pertama ini, saya akan menuliskan tentang pengalaman saya selama mendiskusikan buku Menjerat Gus Dur. Saya ingin membagi pengalaman diskusi saya menjadi tiga garis besar.
Pertama, seperti yang saya tulis di paragraf pertama, bahwa Gus Dur bukan hanya tokoh NU, melainkan milik semua. Saya merasakan hal itu langsung setiap melakukan diskusi. Meski banyak berdiskusi di kalangan NU seperti pesantren, kantor-kantor NU—sampai anak cabang—, dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), diskusi selalu dihadiri oleh kelompok-kelompok minoritas.
Tak hanya hadir, mereka juga membagikan pengalamannya. Contoh, ketika diskusi di salah satu tempat di Surabaya, seorang bapak yang sudah terlihat sepuh yang berjalan dengan menggunakan tongkat dan dibantu anaknya mengatakan, “Saya sangat berterima kasih dengan Gus Dur, sebagai penganut agama Konghucu yang tidak diakui saat Orde Baru. Gus Dur siap pasang badan untuk kami merayakan imlek pada 1990-an.”
Tak cukup sampai disitu, sambungnya, Gus Dur juga ikut turut serta saat dirinya harus diperiksa di kantor kodim. “Saya masih ingat, Gus Dur bilang, “Kalau sampai keluarga bapak ini dan seluruh warga tionghoa lainnya mendapat teror, kalian akan berhadapan dengan saya dan NU.”katanya sambil menangis.
Ada banyak cerita serupa yang saya dengar langsung dan itu merasa ‘bergetar’ karena mendengarkan langsung dari orang yang dibantu oleh Gus Dur. Selama ini, saya hanya mengetahui cerita itu dari buku dan murid-murid Gus Dur, yang mungkin tidak melibatkan emosinya.
Kedua, pengalaman berinteraksi dengan warga NU dan pesantren. Sebagai anak yang lahir dan besar di Jakarta, saya tak terlalu tahu banyak tentang NU dan pesantren. Bahkan, di tempat tinggal saya, terkesan bahwa pesantren hanya sebatas pelepasan tanggung jawab orang tua yang sudah tidak sanggup mendidik anaknya yang nakal. “Kalau susah dinasehati dan enggak mau menuruti orang tua, nanti kamu akan dimasukkan ke pesantren,” kata beberapa tetangga saya kepada anaknya.
Namun, ketika saya beberapa kali melakukan diskusi dan bahkan harus bermalam di pesantren, kesan pesantren hanya sekadar tempat pelarian atau “buangan” itu terbantahkan. Justru, pesantren mengajarkan hidup yang sangat asketis, sederhana, secukupnya, atau orang-orang kota besar seperti Jakarta menyebutnya hidup minimalis.
Tentu kalau sikap dan mentalitas asketisme ini dikelola dengan baik dan visioner, maka akan menghasilkan manusia-manusia yang unggul. Sebab, mereka yang di pesantren hidup bersama masyarakat. Ia tidak seperti lembaga pendidikan lain yang terpisah dari kehidupan masyarakatnya—tidak di menara gading. Para santri tahu dan merasakan sendiri masalah-masalah yang terjadi masyarakat.
Pun demikian dengan warga NU, mayoritas mereka hidup dengan sederhana dan gotong-royongnya pun masih kuat. Ketika saya berdiskusi di Madura, ada salah satu kelakar untuk membuktikan warga NU itu sangat teruji gotong-royongnya.
“Vir, NU di Madura itu mayoritas. Hampir setiap 200-300 meter pasti ada yang minta sumbangan untuk pembangunan masjid. Itu membuktikan, warga NU itu suka bersedekah dan gotong-royong,” ujarnya sambil tertawa.
Pengalaman lain di pesantren yang tak akan mungkin bisa dilupakan adalah panggilan “Gus” dan banyak salim kepada saya. Saya berkali-kali menolak panggilan dan salim kepada saya, tetapi tidak bisa. Bukan apa-apa, menurut saya, panggilan Gus itu terhormat dan juga suci yang sama sekali tidak mencerminkan diri saya. “Duuh, saya itu kasihan kalau mereka tahu kelakuan saya itu seperti apa,” ujar saya dalam hati.
Ketiga, antusiasme untuk membeli buku. Saya dan penerbit (Mas Savic Ali), tidak akan pernah menyangka buku ini akan begitu laku dan banyak dibeli oleh warga NU.“Ini luar biasa, Vir. Biasanya orang NU itu hanya beli buku satu. Setelah dia baca, dia akan bercerita kesepuluh temannya,” kata Mas Savic, Manajer Tim Merah di Liga Futsal Khatulistiwa.
Sebagai bukti, ketika bedah buku di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, ada seorang ibu-ibu yang sudah agak tua mendatangi saya setelah acara diskusi. Dia meminta tanda tangan dan berfoto dengan saya. Lalu, ia berkata kepada saya, “Mas Virdi, ini pertama kali dalam hidup saya membeli buku dan itu buku Menjerat Gus Dur ini.”
“Kenapa ibu beli buku ini?” tanya saya.
“Saya suka dengan Gus Dur, saya mungkin tidak baca sampai habis. Tapi buku ini akan saya warisi ke anak saya supaya dia tahu Gus Dur itu orang baik dan tahu juga siapa Mas Virdi,” ujarnya. Percakapan berhenti, karena saya tidak sanggup harus merespons apa. Saya hanya terharu.
Pengalaman lainnya saat diskusi buku di daerah Pantura, ada seorang remaja laki-laki menggunakan jaket Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dengan agak malu menghampiri saya. Dia bilang bahwa dirinya ingin sekali punya buku itu, tetapi dirinya tidak punya uang. “Saya enggak mau beli bajakan. Saya takut kuwalat sama Gus Dur dan Mas Virdi. Apa boleh saya minta bukunya ke mas Virdi saja? Nanti bukunya itu bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk teman-teman,” ucapnya sambil sesekali menunduk.
Saya lalu mengajaknya ke panitia untuk memberikannya buku.
Terakhir, sebelum wabah virus corona menyebar luas. Ada pertanyaan tak terduga dari seorang mahasiswa di salah satu kampus PTN di Jawa Timur. Dia bertanya tentang kemungkinan buku Menjerat Gus Dur akan diangkat ke layar lebar. “Bukankah itu juga bisa meluaskan pengetahuan ke anak muda? Mas Virdi ‘kan alumni Pendidikan Sejarah, pasti belajar media pembelajaran. Bukannya, saat ini film itu media pembelajaran yang paling efektif untuk murid?” tanyanya.
Saya tidak bisa menjawab banyak selain, “Itu tergantung kepada sineasnya, berani atau tidak? Lalu, yang paling utama, ia harus izin kepada keluarga Gus Dur.”
Sebenarnya, masih ada banyak hal lain selama saya berdiskusi keliling daerah yang ada dalam catatan harian saya. Akan tetapi, saya tidak berniat menceritakan semuanya. Biar banyak cerita itu tersimpan dengan baik dalam memori saya.
Tulisan selanjutnya, saya akan menuliskan beberapa bagian dari isi buku Menjerat Gus Dur.