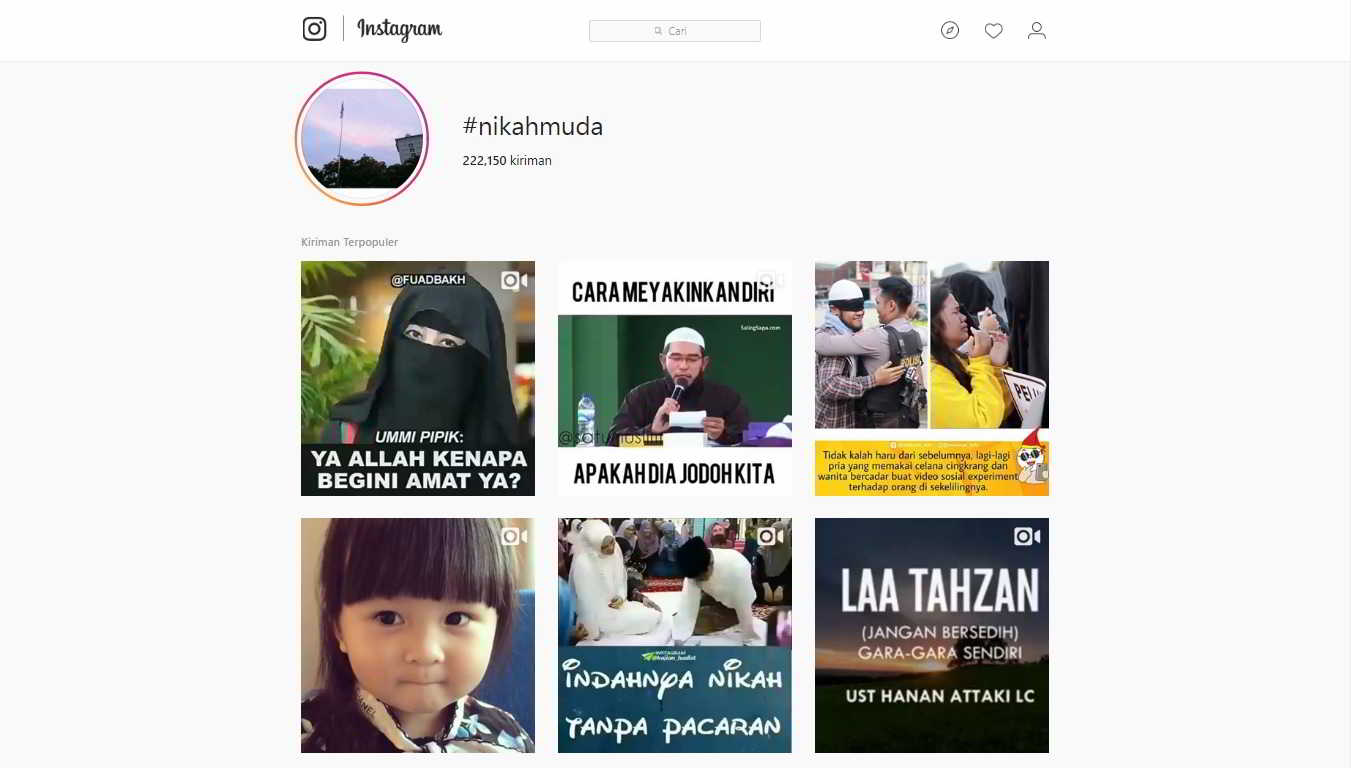Saya tidak tahu lagi bagaimana cara mengekspresikan diri ketika mendengar kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Pendidikan. Bagaimana cara mengekspresikan rasa shock, marah, kesal dan kasihan sekaligus dalam satu waktu? Saya yakin anda pun juga merasakan hal yang sama.
Kita terhenyak, terkejut dan marah. Bagaimana bisa di lingkungan yang kita percayakan pendidikan anak-anak kita kepadanya dengan harapan mereka menjadi anak-anak yang cemerlang masa depannya, justru malah menjatuhkan mereka dalam jurang trauma yang terdalam.
Masih segar di ingatan kita kasus kekerasan seksual di SMA Selamat Pagi Indonesia (SPI) Malang dan Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang Jawa Timur yang kasusnya muncul ke publik baru-baru ini di waktu yang hampir bersamaan.
Kedua Lembaga Pendidikan ini awalnya sama-sama mempunyai citra yang baik. Pendiri SMA SPI adalah salah satu motivator yang cukup terkenal karena kedermawanannya menyekolahkan anak-anak kurang mampu di sekolah yang didirikannya. Pondok pesantren yang juga punya citra baik karena dianggap tempat yang paling religious dan bermoral. Siapa sangka justru seperti sarang iblis berkulit manusia bagi anak-anak.
Ada kesamaan dalam proses hukum kedua kasus ini terkait penahanan pelaku yang terlihat sulit untuk dilakukan. Dalam kasus di SMA SPI misalnya, meskipun sudah dilaporkan sejak 29 Mei 2021, berkas perkara Julianto Eka Saputra (JE) baru disidangkan pada 16 Februari 2022. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya sebagai terdakwa, JE masih juga tidak ditahan. Pun ketika sudah memasuki sidang lanjutan pada 13 April 2022, JE masih berkeliaran bebas.
Hal serupa juga terjadi pada Bechi, pelaku kekerasan seksual di Pondok Pesantren Shiddiqiyah Jombang. Upaya penangkapan Bechi bahkan sempat trending di twitter karena memang prosesnya yang sangat alot melibatkan pimpinan pondok sekaligus ayah dari pelaku. Video pertemuan antara kyai pimpinan dan kapolres Jombang saat itu juga sempat viral, di mana sang ayah menolak menyerahkan anaknya untuk ditahan karena menurutnya kasus anaknya adalah fitnah dan rekayasa saja.
Padahal, setelah tiga tahun proses hukum dan berulangkali mangkir dari penggilan pemeriksaan, berkas Bechi sudah P21 yang artinya berkas sudah lengkap. Polisi pun berusaha menangkap Bechi bahkan dengan menangkap paksa dan melakukan pengepungan di pesantren. Herannya ada saja massa yang menghalangi upaya penangkapan anak pimpinan pondok tersebut.
Walaupun akhirnya pelaku ditahan dan menjalani persidangan, namun dapat kita lihat bahwa proses penangkapan atau penahanan dalam kasus serupa selalu saja mengalami hambatan. Biasanya argumen yang diajukan pelaku untuk ngeles adalah belum cukupnya bukti dan alasan bahwa korban hanya merekayasa bukti untuk menfitnah pelaku.
Inilah kemudian yang menjadi penting untuk menjadi pengetahuan kita bersama semua setelah disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) tepatnya di pasal 25 UU TPKS menyebutkan bahwa keterangan saksi dan/korban korban tindak pidana kekerasan seksual dengan satu alat bukti sah sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah.Hal tersebut menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap korban dalam proses penyelesaian hukum kasus kekerasan seksual.
Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwa ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban adalah akar dari kekerasan seksual. Ketimpangan diperparah ketika satu pihak memiliki kendali lebih terhadap korban seperti kendali ekonomi, sumber daya, pengetahuan, ataupun status sosial. Dalam konteks kekerasan seksual yang terjadi di Lembaga Pendidikan, pelaku biasanya adalah pengajar, guru atau pengasuh dari peserta didik.
Kekerasan seksual dengan relasi kuasa, selain menempatkan korban dalam posisi yang tidak berdaya karena posisinya yang subordinat, biasanya juga disertai dengan ancaman. Dalam kasus SPI misalnya, korban diancam akses pendidikan dan ekonominya akan diputus jika melapor, dan berbagai intimidasi lain yang membuat korban semakin tidak berdaya.
Dalam kontek ini UU TPKS hadir sebagai alternatif terbaik untuk melindungi korban kekerasan seksual. Dia berperan sebagai Lex Spesialis dari KUHP yang menjadi Lex Generalis. Banyak sekali poin-poin penting dalam UU TPKS yang belum diatur dalam KUHP dan kesemuanya mempunyai perspektif korban.
Salah satu tujuannya adalah untuk menembus penegakan hukum yang dulunya sangat sulit bagi korban, menjadi dipermudah. Terutama kasus yang melibatkan relasi kuasa di Lembaga Pendidikan. Undang-Undangnya sebenarnya sudah bagus, Namun yang menjadi tugas kita selanjutnya adalah bagaimana semua ketentuan dalam UU TPKS ini dapat terimplementasikan dalam berbagai lini kehidupan termasuk dalam dunia Pendidikan.
Sebagai tempat dan rumah kedua bagi anak untuk bertumbuh dan berkembang, sekolah harus menjadi aktor utama dalam pemberantasan kekerasan seksual. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut agar para aktor di dunia Pendidikan seperti guru, pengajar, dan pimpinan sekolah lebih peka dan lebih mempunyai perspektif korban
Ke depannya mungkin diperlukan kebijakan khusus yang disusun sendiri oleh sekolah sebagai upaya penanganan Tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekolah. Hal ini penting untuk diperhatikan oleh semua pemangku kepentingan di Lembaga Pendidikan tersebut, selain agar kebijakan itu sesuai dengan kondisi lingkungan di sekitar sekolah, juga agar lebih mendorong penyusun untuk bertanggungjawab dalam melaksanakannya.
Selain itu, Kebijakan anti kekerasan seksual tersebut juga dapat menyadarkan adanya relasi kuasa antara guru dan murid yang rentan disalahgunakan. Harapannya, dengan memahami dinamika relasi kuasa dan gender tersebut, guru maupun peserta didik dapat memahami dan memiliki kesadaran sosial yang lebih baik dan yang lebih berkeadilan sehingga kekerasan seksual di sekolah dapat dihapuskan.