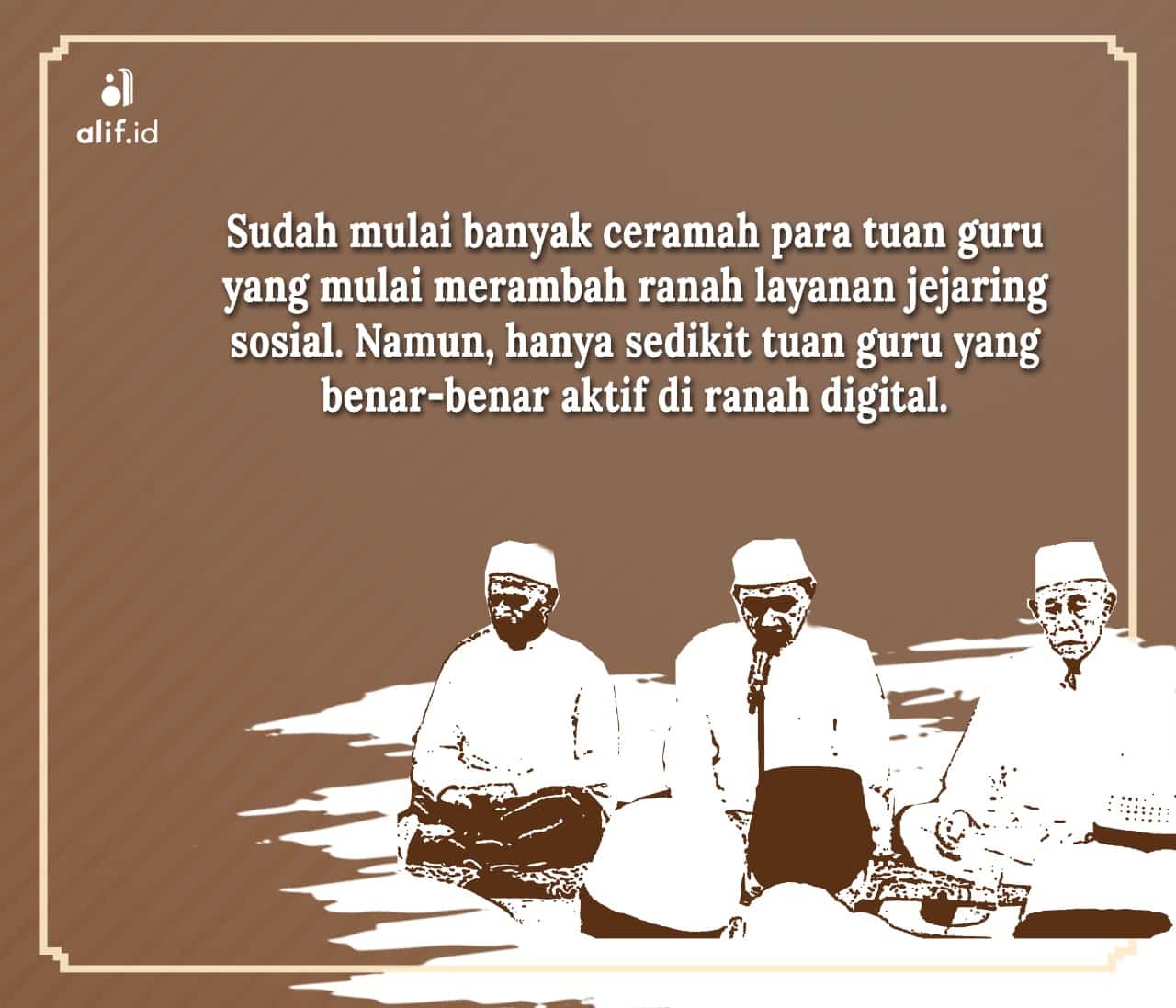15 tahun lalu, kita masih berpikir bahwa menyiarkan secara langsung sebuah event perlu peralatan yang mahal dan banyak. Kemajuan teknologi mementahkan perkiraan kita semua. Ya, saya yakin tidak banyak di antara kita yang pernah terpikir pengajian di sebuah desa bisa dinikmati orang yang berada di tempat lain.
Sebuah gawai pintar, tentu di dalamnya ada kamera kecil, sudah menggantikan seluruh perangkat kamera dan lain-lain yang dulu harus dimiliki untuk bisa menyiarkan kegiatan kecil sekalipun. Dus, dengan hanya beberapa kali klik di layar gawai, kita juga bisa memproduksi konten atau menyiarkan kegiatan sendiri.
Kita sekarang juga bisa menikmati even-even yang sebelumnya tidak mungkin karena batas atau sekat tempat atau daerah yang berjauhan, tanpa harus menggunakan teknologi yang banyak dan rumit. Terlihat kehadiran internet memang menjanjikan dunia tanpa batas.
Shira Ovide, Kolomnis di New York Times, di salah satu kolomnya menuliskan:
“Kita sudah terbiasa menganggap internet sebagai bahasa yang mempersatukan di seluruh dunia”.
Jika dunia dipersatukan dalam satu wilayah baru bernama “dunia maya”, bagaimana segregasi yang terjadi pergumulan atau perjumpaan paham keagamaan di ranah tersebut?
Pertanyaan serupa juga ditanyakan oleh Shira dalam kolomnya berjudul Tech is global Right?. “Akankah internet menjadi satu dunia, atau akankah ia berbatasan?” tulis Shira. Memang, dinamika pergumulan paham keagamaan di ranah internet memang sudah sering dibahas di dunia maya, namun berangkat dari poin yang sama kita akan lebih berfokus pada konsumsi sekaligus produksi konten di media sosial sebagai bagian identitas keislaman masyarakat Banjar.
Di esai lainnya, digambarkan sedikit tentang polemik yang terjadi saat viralnya video potongan ceramah dari Firanda Andirja dan Subhan Bawazier. Bagi masyarakat Banjar, ceramah mereka berdua dianggap tidak cocok dengan keberislaman mereka.
Misalnya, saat Subhan Bawazier dianggap menghina KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau Guru Sekumpul, yang notabene panutan masyarakat Kalsel. Adapun Firanda Andirja, pernah menghina orang tua Nabi Muhammad SAW karena dia mengatakan orang tua Nabi masuk neraka.
Niat kedatangan Firanda ke tanah Banjar di tahun 2018 sontak mendapatkan penolakan keras. Bahkan GP Ansor Kalsel menganggap penolakan tersebut untuk menjaga marwah tradisi Ahlussunah wal Jamaah (ASWAJA) yang menjadi karakteristik keagamaan di Kalimantan Selatan dan demi menyelamatkan akidah seluruh generasi agar terhindar dari paham salafi wahabi takfiri.
Selain dua kasus di atas, dinamika di media sosial yang pernah menyedot perhatian publik masyarakat Banjar adalah kasus Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada waktu dia dituduh melakukan tindak pidana melakukan penodaan agama. Memang, kasus ini menyedot perhatian secara nasional, termasuk masyarakat Banjar. Di Banjarmasin, terjadi juga demo kasus Ahok bahkan sebagian besar dimobilisasi di media sosial.
Ketiga kasus ini di atas adalah bukti bahwa dinamika identitas keberagamaan masyarakat Banjar mulai bersentuhan dengan dinamika media sosial. Sudah mulai banyak ceramah para tuan guru yang mulai merambah ranah layanan jejaring sosial. Namun, hanya sedikit tuan guru yang benar-benar aktif di ranah digital.
Memang, mencari tuan guru yang aktif bermedia-sosial bagai mencari jarum dalam tumpukan jerami. Namun, kehadiran para tuan guru di media sosial tidak menjamin ranah digital akan lepas dari problematika khas, seperti hoaks dan ujaran kebencian.
Saya pernah mendengar salah seorang anak tuan guru di Banjarmasin, yang melarang ayahnya untuk memiliki akun Whatsapp. Saat saya tanya alasannya, dia hanya jawab singkat, “Saya hanya tidak ingin ayah mengonsumsi pesan-pesan berantai yang tidak jelas asal-usulnya”.
Ketakutan sang anak, yang juga seorang tuan guru, didasari pada asumsinya bahwa tidak semua orang memiliki daya tahan dan daya saring yang kuat atas informasi di dunia maya, bahkan sekelas tuan guru sekalipun.
Di tengah belantara media sosial, perjumpaan dan pergumulan terkait paham keagamaan memang tidak bisa dibendung. Semuanya tersedia dan siap dikonsumsi dengan bebas. Adaptasi masyarakat, tidak saja Banjar, dalam menerima dan mengonsumsi informasi keagamaan di media sosial masih terlihat mengandalkan perasaan, dalam menilai informasi tersebut negatif atau positif.
Adapun masyarakat Banjar yang sangat mempertahankan model interaksi komunal, maka posisi patron seperti tuan guru sangatlah penting. Andai tuan guru terpapar dengan informasi hoaks atau ujaran kebencian, maka umat atau jemaahnya sangat rentan terinfeksi juga. Arkian, imunitas tuan guru atas hoaks dan ujaran kebencian poin yang harus dipertanyakan kalau ada dari mereka yang mulai aktif di media sosial.