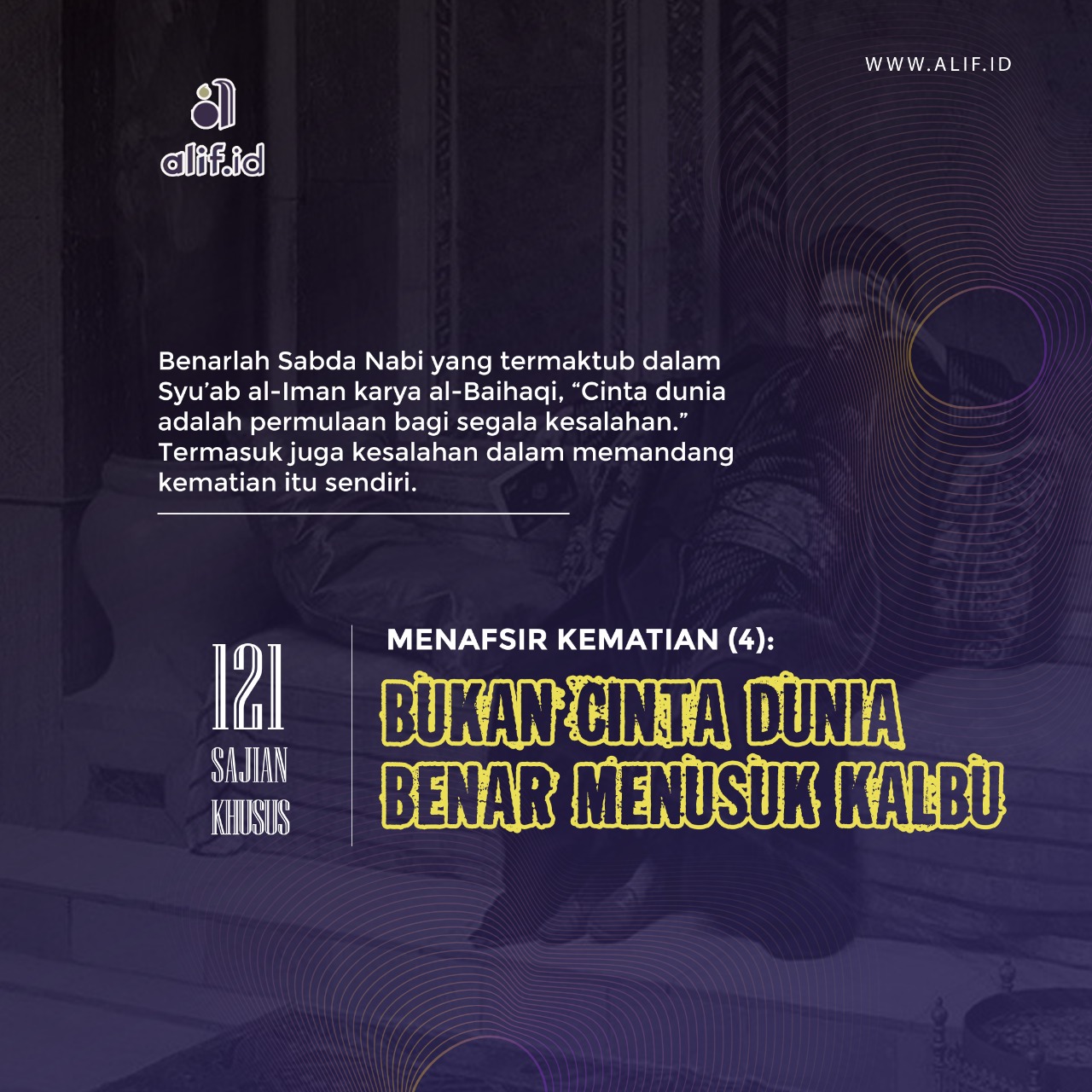Dalam banyak telaah eskatologi atau al-sam’iyat dalam bahasa Teologi Islam, tersebut bahwa salah satu sebab manusia parno atau sekurang-kurangnya benci dengan kematian adalah cinta dunia. Orang yang hatinya kadung terpaut dengan dunia, sulit mencerap rahasia-rahasia indah di balik kematian. Sabda Nabi Musa yang dikutip al-Ghazali dalam Ihya ‘Ulum al-Din, menyatakan bahwa di hati seorang Mukmin cinta duniawi tak kan pernah selaras dengan cinta ukhrawi, persis seperti air dan minyak, kendatipun dapat disatukan dalam wadah namun tak mungkin bersenyawa. Bohong, kata al-Syafi’i, sesiapa yang mendaku telah menghimpun cinta dunia dan cinta akhirat dalam satu hati.
Tak hanya itu, cinta dunia acapkali menjadi mindset atau awal mula tindakan-tindakan destruktif sepanjang sejarah manusia. Penjajahan, korupsi, perusakan alam, adalah di antara ekses-ekses orentasi duniawi yang kita jumpai. Benarlah Sabda Nabi yang termaktub dalam Syu’ab al-Iman karya al-Baihaqi, “Cinta dunia adalah permulaan bagi segala kesalahan.” Termasuk juga kesalahan dalam memandang kematian itu sendiri.
Tetapi, jawaban bahwa manusia takut mati karena cinta dunia belum cukup menohok. Jawaban itu belum secara eksplisit menunjuk ke diri kita. Kita masih bisa berkilah semisal, “Itu semua terjadi karena karakter dasar dunia yang menipu!” Pendek kata, jawaban ini rentan membuat kita bermental “korban”, lantas mendakwa dunia tak ubahnya pelaku kriminal. Pun jawaban ini adalah buah dari pertanyaan yang relatif dangkal, belum cukup radikal alias masih pada tataran permukaan. Pertanyaan pokoknya adalah mengapa manusia begitu mencintai dunia? Inilah yang hendak dijawab dalam tulisan ini.
Dalam telaah al-Ghazali, cinta didefinisikan sebagai kecenderungan tempramen kepada sesuatu menyenangkan. Kecenderungan itu timbul setelah adanya pengetahuan (ma’rifah) dan konsepsi (idrak) terhadap suatu objek. Tak salah jika dibilang bahwa cinta tak bisa dilepaskan dari indra sebagai salah satu sumber beroleh pengetahuan yang paling sering didayagunakan. Barangkali ini adalah penjelasan dari pepatah lama, “Tak kenal, maka tak sayang!”
Selaras dengan hal ini, manusia secara tabiat cenderung menyukai hal-hal yang selaras, cocok atau klop dengan dirinya. Sementara itu, tak ada entitas yang lebih cocok, lebih selaras, dengan diri manusia selain dirinya sendiri. Pada aras ini, timbullah kecenderungan manusia mencintai dirinya sendiri atau benih-benih narsisme, medahului kecintaannya terhadap yang lain. Oleh karenanya al-Ghazali menyimpulkan, “Cinta pertama semua makhluk hidup adalah dirinya, eksistensinya”.
Adapun maksud narsisme atau cinta kepada diri sendiri adalah bahwa manusia selalu ingin mendawamkan esksistensinya sembari terus memunggungkan kebinasaan. Dan kita tahu bahwa hanya Tuhan yang benar-benar “Independen”. Sedang makhluk seluruhnya, termasuk manusia adalah tempatnya kelemahan. Bahkan manusia tak sanggup menopang eksistensinya sehingga ia senantiasa membutuhkan hal-hal lain di luar dirinya.
Sepintas manusia memang mencintai hal-hal di luar dirinya. Sebut saja keluarga, harta, jabatan dan seterusnya. Tetapi jika ditilik lebih mendalam, itu semua tak lain adalah sebentuk upaya manusia untuk mendawamkan dan mengukuhkan eksistensi dirinya. Misal, saat manusia mencintai harta, itu karena harta adalah medium pendukung kelestarian dan kesempurnaan eksistensinya. Demikian pula cinta kepada anak, kolega, jabatan, dan seterusnya. Sehingga dengan tegas al-Ghazali menyatakan, “Manusia mencintai hal-hal tersebut bukan semata karena hal-hal itu sendiri, melainkan karena berhubungan dengan suatu keuntungan dalam menopang kelanggengan dan kesempurnaan eksistensinya.” Semakin manusia mencintai dirinya, semakin menguat keinginannya untuk eksis. Semakin menguat keinginannya untuk eksis, semakin meningkat pula kecintaannya pada referen-referen dunia yang menopang eksistensinya.
Selanjutya, kulminasi kecintaan terhadap diri sendiri ini mau tak mau berakibat pada pandangan manusia kematian. Al-Ghazali mengatakan bahwa manusia membenci maut dan kebinasaan bukan semata karena takut terhadap hal ihwal setelahnya. Bukan juga karena menghindar dari pedihnya sakratul maut. “Bahkan, seandainya manusia direnggut nyawanya tanpa rasa sakit, tanpa perhitungan dosa dan pahala, ia tetap tak ‘kan rela.” Demikian pengandaian ekstremnya. Kalaupun pada akhirnya manusia mencintai kematian dan kebinasaan, itu bukanlah cinta yang tulus. Melainkan karena sudah tak tahan menanggung sakit dalam hidupnya.
Namun demikian, al-Hasan al-Bashri menangkap sebuah keganjilan. “Bagaimana mungkin seorang insan begitu mencintai dirinya tapi tidak mencintai Tuhan yang menopang eksistensi dirinya?”, tanyanya, heran. Toh, kalau memang manusia cinta pada hal yang mendunkung eksistensi dirinya, maka Allah-lah Dzat yang paling berhak dicintainya. Sementara itu, cinta Ilahi membakar kerinduan atau bahkan memantik keinginan untuk menyegerakan perjumpaan agung. Sebab itu, Abu al-‘Ustman menyatakan bahwa mencintai kematian adalah tanda kecintaan pada Tuhan. Lantas, bagaimana mungkin membenci kematian?
Tetapi tenang, dari tadi yang kita perbincangkan adalah konsep ideal dengan standar yang melangit. Mengutip K.H. Dr. (Hc) Afifuddin Muhajir, pakar Fikih dan Ushul-Fikih yang didapuk sebagai Rais Suriyah PBNU dan Ketua Dewan Fatwa MUI, “Sesekali kita perlu turun dari langit ideal menuju bumi realita.”. Demikian, al-Ghazali sendiri memberi semacam pemakluman dengan mempertimbangkan realita bahwa tak semua manusia mampu mencintai Tuhan secara sempurna, dengan tulus nan sepenuh hati. Tak jarang kesempurnaan cinta Ilahi yang semestinya tak menyisakan ruang bagi cinta yang lain terciderai oleh kecintaan kepada sanak famili. Dan bisa dibilang itu wajar adanya. “Karena manusia,” kata al-Ghazali, “dalam urusan cinta memang berbeda-beda.”