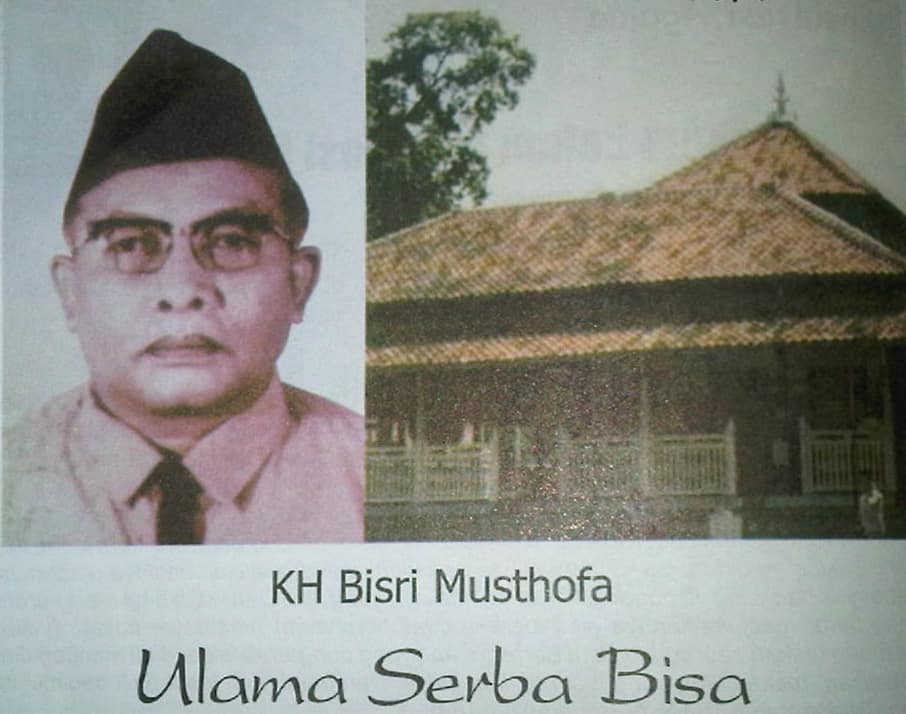Semenjak diumumkannya pandemi covid-19 di Indonesia dan pemerintah memberlakukan PSBB, maka sejak itu pulalah pemerintah membatasi setiap kegiatan sosial yang dapat menyebabkan kerumunan massa. Segala aktivitas pun menjadi terhambat, mulai dari ekonomi, politik, hingga ritual keagamaan. Berbagai penganut agama terkena dampak dari pandemi. Mulai dari masjid, gereja, pura, wihara, klenteng, ditutup untuk sementara.
Ya, dan tampaknya bagi umat Islam, idul fitri kali ini tentu akan jauh berbeda dengan Idul Ffitri sebelumnya, Apalagi pemerintah melarang masyarakat untuk mudik—tradisi tahunan yang telah menjadi kultur menjelang Idul Fitri. Tentu bagi para perantau hal ini akan sedikit berat, karena hari raya yang seharusnya menjadi momentum untuk berkumpul bersama keluarga setahun sekali harus terelakkan.
Terlepas dari itu semua, kita tahu Idul Fitri adalah salah satu dari dua hari raya umat islam yang dianggap sakral. Idul Fitri, atau dalam bahasa lokal yang sering kita sebut Lebaran, bahkan bisa dibilang bukan hanya sebatas ritual, namun juga mengandung nilai-nilai sosial. Dianggap sebagai ritual karena mengandung unsur-unsur nilai ibadah dan sosial karena mengartikulasikan semangat kemanusiaan.
Dalam situasi dan kondisi seperti sekarang, mungkin kita bisa bercermin dari lebaran ala Sayidina Ali. Lebaran yang sederhana, namun tentu tanpa mengurangi makna spiritualitas.
Alkisah pada hari raya Idul Fitri seseorang berkunjung ke rumah Sayidina Ali. Lantas ia mendapati Sayidina Ali sedang memakan roti yang keras. Ia pun berkata, “Dalam suasana hari raya kenapa engkau mememakan roti yang keras ini?”
“Sesungguhnya hari ini adalah Id (lebaran) orang yang diterima puasanya, yang bersyukur atas usahanya, dan diampuni dosa-dosanya. Hari ini adalah lebaran bagi kami, demikian juga esok. Bahkan setiap hari pun engkau juga bisa lebaran seperti ini,” ucap Sayidina Ali.
“Bagaimana bisa aku lebaran setiap hari?”
“Jika seorang hamba tidak bermaksiat sedikitpun kepada Allah di hari itu, maka sesungguhnya ia sedang berlebaran.”
Di lain kesempatan Sayidina Ali juga pernah berkata: Laisal-id liman labisa-l-jadid, innama-l-id liman tho’atuhu tazid. Wa-laisal-id liman tajammala bil-libas wal-markub, innama-l-id liman ghufirot lahu-d-dzunub; hari raya bukanlah diperuntukkan bagi orang yang mempunyai pakaian baru, namun bagi orang yang ketaatannya bertambah. Hari Raya bukan pula diperuntukkan bagi orang yang bersolek dengan pakaian maupun kendaraan, akan tetapi bagi orang yang dosa-dosanya diampuni.
Demikianlah semangat Lebaran yang diajarkan Sayidina Ali. Lantas pertanyaannya, apakah Sayidina Ali tidak mampu menghidangkan berbagai makanan dan membeli baju baru untuk lebaran?
Bukan begitu. Beliau tidak hanya melihat realitas lebaran secara eksplisit, namun juga implisit. Seakan memberitahu kita tentang hidup untuk lebih memahami isi dari pada kulit. Sayangnya masyarakat kita sering luput akan hal ini dan menganggap Lebaran sebatas euforia belaka. Sehingga jadilah kita sebagai masyarakat materialistik yang lebih suka melihat lahiriyah yang ada pada Lebaran: THR, baju baru, hidangan lezat, mudik, dan sebagainya.
Tidak, tidak sepenuhnya salah memaknai Lebaran dengan hal itu semua. Namun, marilah kita melihat hal yang lebih substansial dan prinsipil dari Lebaran, apalagi dalam situasi dan kondisi seperti ini, seharusnya kita tidak usah berlebihan dalam merayakan lebaran. Bukan semata-mata karena kita tidak bergembira, namun sebagai bentuk simpati dan empati kita terhadap masyarakat yang tidak bisa ikut merayakan hari raya sesuai rencana karena banyak faktor.
Idul fitri seharusnya menjadi perjalanan transendental bagi kita sebagai ghirah atau gairah semangat umat islam dalam menjalani kehidupannya. Karena makna Idul Fitri itu sendiri yang berarti kembali ke fitri, suci. Nabi pun menganalogikannya seperti bayi yang terlahir kembali dari rahim ibunya. Karenanya Idul Fitri bukanlah akhir dari sebuah perjalanan, tapi justru sebagai tolak ukur awal menuju perjalanan selanjutnya.
Jika selama Ramadan kita ditempa, dididik, dilatih, serta dibimbing menjadi pribadi yang mulia, untuk menjadi manusia paripurna, insan kamil, maka kemudian liburan (lebaran) adalah kompensasi agar kita rehat sejenak dan bersiap kembali meneruskan perjalanan.
Sekali lagi, mari kita bercermin kepada sosok Sayidina Ali untuk menjalani kehidupan yang sederhana dan memandang kehidupan lebih bijaksana. Karena hidup memang sebetulnya sederhana, yang membuatnya rumit adalah gengsi, gaya hidup.