Selayang Pandang Gerakan Sumatera Thawalib
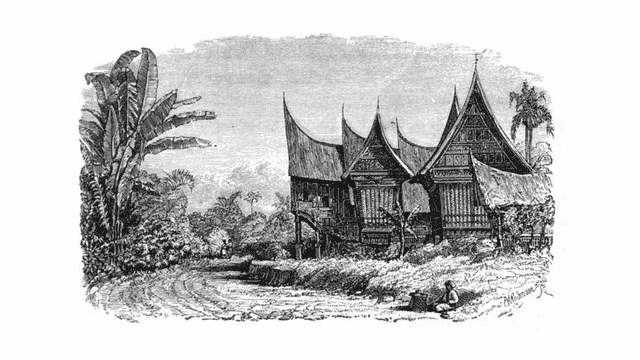
Politik dan agama, dua ranah yang berbeda. Terbukti dari sebutannya saja sudah berlainan. Ada tiga relasi yang diyakini oleh tiga kelompok terkait dua entitas ini. Kelompok pertama, memercayai bahwa dua ranah ini sejatinya berbeda, namun keduanya memiliki zona yang beririsan. Masing-masing ranah, memiliki otonomi relatifnya sendiri.
Kelompok kedua memandang bahwa baik agama maupun politik merupakan ranah yang sama sekali terpisah. Keduanya tak punya irisan sama sekali. Memisah laiknya minyak dan air. Kelompok ketiga mengaburkan batasan antara keduanya. Politik ya agama, agama ya politik. Politik dibaca satu tarikan napas dengan agama. Kalangan ini meyakini: politik sama dengan agama.
Menarik bila kita menyibak lembaran-lembaran sejarah lalu yang menggambarkan dinamika dua ranah ini dalam perjalanan gerakan-gerakan Islam era kolonial. Salah satunya yang akan kita bahas adalah Sumatera Thawalib. Bisa dibilang perkumpulan Thawalib termasuk mengambil pandangan kelompok yang ketiga dari kategori relasi di atas.
Titimangsa 1918, di Sumatra Barat, Padang Panjang, berdiri perkumpulan keagamaan bernama Sumatera Thuwailib.
Cikal-bakal organisasi ini sebelumnya hanya dikenal dengan sebutan perkumpulan sabun. Pasalnya, perkumpulan ini berusaha memenuhi keperluan sehari-hari para anggotanya, para pelajar, yakni keperluan berupa sabun, pensil, tinta, kertas dan sebagainya.
Dua tahun kemudian, nama persekutuan ini bersulih menjadi Sumatera Thawalib.
Sumatera Thawalib mengintrodusir cara-cara mengajar yang dianggap modern di lembaga yang dicakupnya. Yakni sistem berkelas, pemakaian bangku-bangku dan meja, kurikulum yang lebih diperbaiki dan juga kewajiban pelajar membayar uang sekolah. Perhatian Sumatera Thawalib pada ihwal agama Islam pada dasarnya berhaluan pembaharu. Kitab-kitab karangan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, dan Ibn Taimiyyah merupakan bacaan utama. Perhatian pada soal-soal adat tentu ada, dan yang paling menyorot perhatian adalah soal-soal politik.
Soal-soal politik memasuki Sumatera Thawalib seiring menguatnya paham Komunisme. Penting dicatat bahwa komunisme ini lebih merupakan sikap radikal terhadap Belanda dan bukan merupakan suatu ideologi yang berdasar pada materialisme historis. Diperkenalkan oleh seorang dari guru-guru Thawalib sendiri, Datuk Batuah, yang kembali dari Jawa.
Tergiring oleh arus politik yang cukup sengit, lambat laun Sumatera Thawalib menggeser perhatiannya dari soal-soal Islam kepada partisipasi kegiatan politik. Bacaan-bacaan koran dan majalah yang bersifat politik turut meminyaki tren ini.
Kehadiran Abdul Muis, wakil presiden partai Sarekat Islam , yang banyak memberikan penerangan-penerangan dan mengurus kepentingan-kepentingan rakyat banyak terkait tanah terhadap pemerintah juga berperan besar menggugah kesadaran politik para pelajar dan guru-guru Thawalib.
Masa-masa ini, para ulama pembaharu bersaing sengit dengan pemimpin-pemimpin komunis dalam memengaruhi massa. Uniknya, tanpa direncanakan para ulama pembaharu mendapat sokongan dari para ulama tradisi. Perlawanan atas komunisme dari para ulama pembaharu maupun tradisi didasarkan atas pandangan komunis yang relatif kontra terhadap ajaran-ajaran agama.
Pemberontakan Silungkang (1926) menimbulkan dampak yang signifikan bagi organisasi ini. Pasca-pemberontakan Silungkang banyak guru-guru Thawalib Padang Panjang dilarang mengajar oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Gempa bumi yang melanda pada tahun yang sama juga di lain pihak membawa pada perhatian kembali lembaga pendidikan ini atas persoalan-persoalan pendidikan.
Titimangsa 1930, organisasi Thawalib bersulih lagi menjadi Persatuan Muslimin Indonesia (PMI atau Permi). Perubahan ini terjadi setelah di tahun sebelumnya Thawalib memperluas cakupan keanggotaannya pada semua bekas pelajar dan guru-guru yang tak lagi memiliki hubungan langsung dengannya.
Dua tahun pertamanya, PMI hanya menjadi wadah silaturahmi. Titimangsa 1932 ia menjadi partai politik. Seiring perubahannya menjadi berorientasi politik, secara simbolik ia menjadi lebih dikenal dengan sebutan Permi, pemerintah kolonial melancarkan tekanan-tekanan yang membuat organisasi ini menderita. Pemimpin-pemimpinnya dibuang dan sejumlah guru-guru Thawalib yang berperan serta di dalam Permi dilarang mengajar. Tak terkecuali, para pelajarnya juga mendapat tekanan dan intimidasi dari pejabat-pejabat pemerintah untuk meninggalkan sekolahnya.
Thawalib sebagai organisasi atau pun lembaga pembaharu berbeda dengan yang lainnya. Meskipun pada dasarnya ia sama sependapat dengan lembaga-lembaga lainnya ihwal masalah agama, tentang sistem pendidikan, prinsip bahwa kegiatan seorang muslim hendaklah didasarkan pada ajaran Islam, kontra cara-cara tradisional, akan tetapi, hanya Thawalib-lah yang aktif dalam kegiatan politik.
Perkawinan antara agama dan politik dalam Islam sangat mewarnai kehidupan sehari-hari para pelajar Thawalib. Nuansa politik ini rupanya secara perlahan namun pasti menggerogoti tubuh Thawalib.
Sedini 1934 dan seterusnya sekolah ini mundur baik secara kualitas maupun prestasi. Pengetahuan pelajar-pelajarnya dalam agama tak dapat bersaing lagi dengan pengetahuan kawan-kawan mereka dari sekolah lainnya. Padahal, di masa-masa jayanya sebelum bertungkus-lumus dalam bidang politik, Thawalib memiliki pelajar-pelajar dari luar daerah seperti Malaya, Kalimantan dan Sulawesi.
Arkian, menggabungkan antara agama dan politik mungkin berefek yang menggairahkan karena dampaknya adalah adrenalin jiwa politik yang meletup-letup. Namun demikian, tak bisa dimungkiri, pada akhirnya ia akan bersifat destruktif bagi lembaga atau organisasi pendidikan. Mengapa? Karena di dasarnya, yakni pelajaran agama yang menjadi dasar iman, cenderung terkaburkan oleh hingar-bingar dan centang-perenangnya ranah politik. Ada kecenderungan psikologis manik-depresif terkait ihwal ranah politik. Di satu saat, ia bisa hiper-bersemangat, namun di kali lain ia bisa hiper-tertekan.
Di lain sisi, mungkin saja tumbuh rasa optimisme politik bagi yang bersangkutan, namun bukan tidak mungkin psikologi paranoia bersemayam tanpa terasa. Lantas, apakah kemudian pilihan bagi agama menjauhi politik dan memisahkan keduanya sepenuhnya? Rasanya tidak. Akan selalu ada irisan antara ranah politik dan agama, namun, seyogianya keduanya ditempatkan secara proporsional, kritis, dan bijaksana. Wallahu a’lam.





