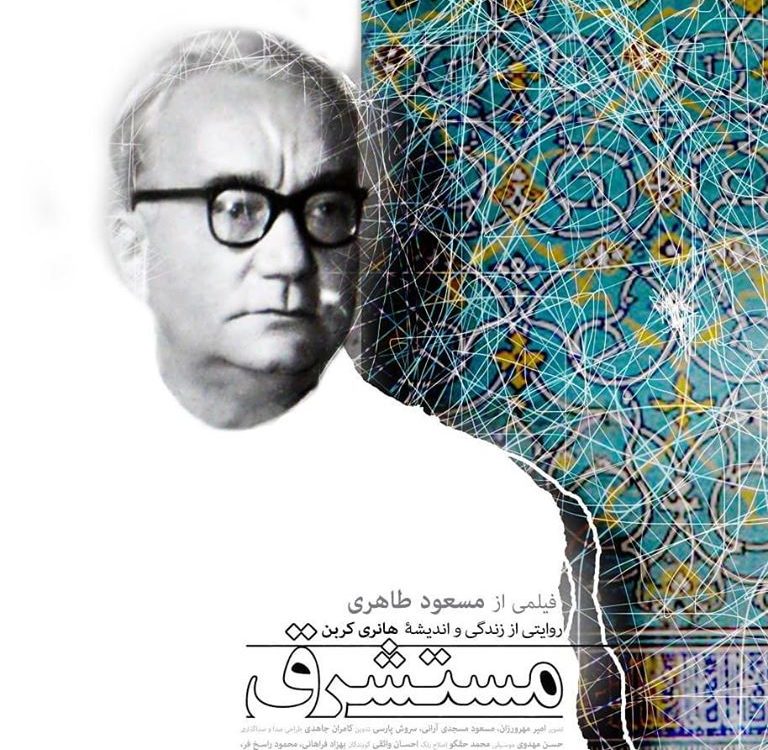Henry Corbin adalah satu dari sedikit filsuf yang memahami lahir-batin tradisi Islam Iran umumnya dan gnosis Syiah khususnya. Terkait dengan filsfafat Islam, buku besutan Corbin Histoire de la philosophie islamique (Sejarah Filsafat Islam) adalah buku penting yang perannya tidak kecil dalam mengubah arah kemudi kajian filsafat Islam secara keseluruhan. Buku ini dilansir Henry Corbin pertama kali pada 1964 (Bagian I) dan menyusul kemudian 1974 (Bagian II).
Bila di Bagian I dia bicara tentang filsafat Islam dari masa permulaan hingga kematian Ibn Rusyd (Averroes), di bagian II Corbin membincangkan tentang masa setelah Ibn Rusyd hingga kiwari. Ada jarak satu dekade antara bagian pertama dan kedua. Versi bahasa Inggris buku ini terbit hampir dua dekade kemudian. Ia diterjemahkan dengan apik oleh Liadain Sherrard dan diterbitkan oleh Kegan Paul International bersama Islamic Publications untuk Institute for Ismaili Studies pada 1993.
Buku Histoire merekam tantangan Corbin pada pandangan umum di kalangan sejawatnya di Barat bahwa filsafat telah kehilangan nyawa di dunia Islam bersama wafatnya Ibn Rusyd. Ya, karya filsuf Kordoba itu memang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin sehingga melahirkan Averroisme yang lantas menggusur ‘Avicennisme Latin’. Tapi, di Timur, khususnya di Iran, Corbin menyebut bahwa sejatinya Averroisme tak mendapat perhatian, dan kritik filsafat al-Ghazali pun tak pernah dianggap mengakhiri tradisi filsafat yang dimulai oleh Avicenna (Ibn Sina) di sana. Iran terus menghasilkan filsuf seperti Mir Damad (abad ketujuhbelas) dan Hadi Sabzavari (abad kesembilanbelas).
Buku Corbin, saya rasa melengkapi karya Annemarie Schimmel tentang sufisme. Bila daya magis kata-kata yang disusun Annemarie Schimmel dalam buku Mystical Dimension in Islam (terbit pertama 1975 dalam bahasa Inggris, sementara dalam bahasa Indonesia diterbitkan oleh Pustaka Firdaus menjadi Dimensi Mistik dalam Islam) membuat kita terlena, maka daya sihir prosa Corbin tak kalah membuai. Karya Schimmell itu terasa menyihir mungkin karena terjemahannya dieditori mendiang Sapardi Djoko Damono, salah satu pujangga terkemuka Indonesia. Nah, membaca karya Schimmell ihwal mistik di dunia Sunni dan Corbin perihal filsafat dan mistik Islam Iran (Syi’ah), kita akan mendapatkan wawasan kesejarahan nan hampir utuh dan berimbang bagi intelektualitas dan spiritualitas kita.
Dalam bukunya Histoire itu, pertama dan terutama, Corbin menegaskan tentang pengertian filsafat Islam yang dia maksud. Dia menolak pemakaian istilah filsafat Arab yang dipakai para sejawatnya di Barat. Corbin berargumen, sebutan filsafat Arab itu problematik karena bila Descartes, Spinoza, Kant dan Hegel menulis beberapa risalahnya dalam bahasa Latin, toh mereka tidak lantas diklasifikasi sebagai penulis ‘Latin’ atau ‘Roma’. Ya, kebingungan untuk menyebut apakah filsafat Arab atau filsafat Islam ini, hemat saya, rupanya bahkan menghinggapi Bertrand Russell, filsuf Inggris.
Dalam bukunya History of Western Philosophy (pertama terbit 1946) Russell terombang-ambing dalam menyebut antara filsafat Mohammedan, filsafat Arab, dan filsafat Muslim. Secara meremehkan, Russell menganggap bahwa tidak ada orisinalitas dalam pemikiran filosofis budaya Mohammedan. Ia hanya menyebut Islam sebagai budaya Mohammedan nan baginya hanya berperan mentransmisikan pengetahuan dari Yunani dan India yang baginya orisinal. Pandangan semacam inilah yang ditolak oleh Corbin.
Corbin memilih penggunaan istilah ‘filsafat Islam’ dengan alasan bahwa frase ini merupakan penunjukan yang cukup luas nan mewadahi ekumenisme (dakwah) spiritual konsep ‘Islam’ itu sendiri dan di saat sama mempertahankan konsep ‘Arab’-nya pada level inspirasi kenabian nan membuat penampakannya dalam sejarah bersama Wahyu Quranik. Menurutnya, filsafat Islam sangat terkait dengan fakta religius dan spiritual Islam nan luas yang tak bisa dikerdilkan pada ihwal fiqh (hukum/yurisprudensi) semata. Menganggap Islam semata hanya persoalan fiqh jelas merupakan ekspresi yang sempit dan persepsi nan picik.
Corbin membagi tiga periode dalam sejarah filsafat Islam. Periode pertama dimulai sampai wafatnya Ibn Rusyd (595/1198). Dalam beberapa hal, periode ini bersitahan pada tahun yang tergurat tersebut. Bersama meninggalnya sang filsuf besar Kordoba itu, sesuatu tiba di ujungnya di Islam Barat. Tetapi, pada saat nan sama, bersama al-Suhrawardi dan Ibn ‘Arabi, sesuatu sedang mulai bahkan tetap berlanjut hingga kini di Islam Timur. Periode kedua merentang lebih dari tiga abad sebelum Renaissance Safawi di Iran.
Periode kedua ini dicirikan terutama dengan apa nan layak disebut ‘metafisika Sufi’: pertumbuhan mazhab Ibn ‘Arabi dan mazhab yang diturunkan dari Najm al-Din al-Kubra, penggabungan antara Sufisme dengan Syi’isme Dua Belas di satu pihak dan dengan reformasi Ismailisme di pihak lain. Penggabungan yang terjadi setelah pembangsaian Alamut oleh Mongol pada 1256. Periode ketiga ditandai dengan penyelidikan filosofis nan berkurang hingga senyap, tetapi Renaissance Safawi (1501-1736) pada abad keenambelas menghasilkan pertumbuhan luar biasa bagi pemikiran dan para pemikir di Iran, nan efeknya meluas sampai periode Qajar (1789-1925) hingga masa kiwari.
Henry Corbin memiliki premis menarik tentang relasi filsafat dan spiritualitas dalam Islam. Baginya sejarah filsafat dan sejarah spiritualitas dalam Islam sama sekali tak bisa dipisahkan. Ia berpendirian bahwa pencarian filosofis (tahqiq) dalam Islam menjadikan fakta fundamental kenabian dan Wahyu kenabian sebagai obyek perenungannya. Itu sebabnya, filsafat baginya niscaya mengambil bentuk ‘filsafat kenabian’.
Simpatinya pada tradisi intelektual dan spiritual Syi'ah tanpa tedeng-tedeng aling. Cukup banyak istilah-istilah teknis yang diciptakan Corbin dalam buku Histoire. Misalnya historiosophy, hierohistory, Imamology, prophetology, prophetic philosophy, gnosiology, arithmosophy, dst. Pada dasarnya, dengan menciptakan istilah-istilah teknis tersebut, Corbin memiliki prinsip yang bernisbah dengan visinya tentang kesadaran sejarah dalam Islam.
Filsuf kelahiran Perancis ini membandingkan antara kesadaran Islam dan Kristiani. Dia memandang bahwa kelahiran dan penyebaran kesadaran Kristiani sejatinya menandai kebangkitan dan pertumbuhan suatu kesadaran sejarah. Pemikiran Kristiani berpusat pada peristiwa yang terjadi pada tahun pertama era Kristiani: Inkarnasi ilahi nan menandai masuknya Tuhan ke dalam sejarah. Akibatnya, kesadaran sejarah terfokus terus-menerus pada makna kesejarahan nan diidentifikasi dengan makna harfiah, makna sejati Kitab Suci. Ia mencatat hal penting nan harus diperhatikan, yakni tiadanya fenomena Gereja dalam Islam.
Karena tak punya lembaga kependetaan yang memiliki ‘sarana berkah’ formal, Islam menurut Corbin tak memiliki dogmatic magisterium, tak ada otoritas kepausan, tanpa Konsili yang bertanggungjawab menentukan dogma. Istilah-istilah yang dipakai Corbin ini khas Katolik, dan Corbin memang mendapatkan gelar kesarjanaannya pertama dari institusi pendidikan Katolik, yakni Catholic Institute of Paris. Meski mendapatkan pendidikan dari institusi Katolik, pria kelahiran Paris ini berlatarbelakang keluarga Protestan.
Corbin membandingkan kesadaran Kristiani dengan kesadaran religius Islam. Dia menganggap kesadaran Islam bukan berpusat pada fakta historis, tapi fakta yang meta-historis, bukan pasca-historis, tapi trans-historis. Fakta paling dasar ini nyatanya mendahului semua sejarah empiris kita. Fakta tersebut, menurut Corbin, diekspresikan melalui pertanyaan ilahi pada Ruh-ruh manusia yang meminta jawaban sebelum mereka ditempatkan di dunia bumi: ‘Apakah Aku Tuhanmu?’ (QS. 7:172). Sahutan gembira atas pertanyaan ilahi ini menyimpulkan adanya perjanjian keimanan abadi. Dari masa ke masa, perjanjian ini diingatkan dengan berulangnya para nabi yang datang sehingga membentuk ‘siklus kenabian’.
Dari aturan-aturan para nabi inilah muncul apa yang disebut huruf agama positif: Hukum ilahi atau syariah. Pertanyaannya kemudian: apakah kita hanya bersitahan pada tingkat hal-ihwal literal ini?Jika demikian, menurut Corbin, para filsuf tak punya bagian lebih jauh untuk dijalankan. Bila agama habis pada tingkat hal-ihwal literal semata betapa gersang dan terkungkungnya ia. Tidakkah kita seharusnya bergerak lebih jauh, berupaya mencerap makna sejati, makna spiritual, nan hakikat?
Tapi muncul fakta keyakinan Islam tentang Nabi Terakhir. Pertanyaan lantas muncul, bagaimana sejarah religius kemanusiaan berlanjut dengan adanya Nabi Terakhir? Corbin menyoroti bahwa pertanyaan ini dan jawaban atasnya-lah nan pada dasarnya membentuk fenomena religius Islam Syi’ah nan dibangun pada prophetology (perspektif tertentu tentang ilmu-kenabian) yang diperkuat menjadi Imamology (ilmu keimaman). Aspek atau ‘dimensi’ ganda (prophetology dan Imamology) ini berpijak pada filosofi kenabian yang seiring dengan ditutupnya siklus kenabian diteruskan oleh siklus walayah.
Salah satu premis dasar dari filosofi kenabian ini adalah polaritas syariat dan hakikat yang tujuannya adalah keberlanjutan dan perlindungan atas makna spiritual Wahyu ilahi, yakni makna tersembunyi, nan esoterik. Eksistensi suatu Islam nan spiritual bergantung pada perlindungan atas makna spiritual ini. Tanpanya, Islam akan kalah seperti proses yang dialami Kristiani nan sistem teologisnya telah tersekularisasi menjadi ideologi sosial dan politis menjadi mesianisme teologis tersekularisasi seperti mesianisme sosial.
Corbin menyatakan karena tak perlu menghadapi masalah macam ‘kesadaran sejarah’, pemikiran filosofis dalam Islam Iran pun bergerak dalam dua arah yang berlawanan tapi saling melengkapi: berangkat dari Asal-Mula (mabda’) dan kembali (ma’ad) ke Asal-Mula. Berangkat dan kembali ini berlangsung dalam dimensi vertikal. Bentuk-bentuk (forms) dipikirkan sebagai wujud dalam ruang ketimbang dalam waktu.
Para filsuf Islam Iran menilik dunia bukan sebagai ‘berkembang’ dalam arah horizontal dan lurus, melainkan menanjak. Masa lalu bukanlah berada di belakang, akan tetapi ‘di bawah kaki kita’. Dari sumbu inilah kemudian muncul percabangan makna-makna Wahyu ilahi. Masing-masing makna ini bernisbah dengan hierarki spiritual, dengan suatu tingkat semesta yang muncul dari ambang metahistori. Pemikiran pun lantas bisa bergerak dengan bebas, tak terhalang oleh larangan-larangan otoritas dogmatik.
Di lain pihak, ia juga harus berhadapan dengan syariah, andaikata syariah kapan pun menolak hakikat. Kaum literalis yang hanya menyokong syariah acap menganggap hakikat sebagai akal-akalan. Pada dasarnya, mereka itu tak menganut perspektif menanjak. Penolakan perspektif menanjak ini merupakan ciri khas kaum literalis agama legalistik.
Arkian, Corbin memiliki pandangan yang agak suram ihwal relasi Islam legalistik dengan filsafat. Menurutnya keduanya ini memiliki relasi oposisi yang tak dapat didamaikan. Relasi mendasarnya adalah tergantung pada pandangan terkait Islam esoterik (batin) dan eksoterik, agama literalis. Orang akan menilai nasib dan peran filsafat dalam Islam menurut penilaiannya secara a priori dalam menegaskan/mengafirmasi atau menolak aspek esoteriknya. [ ]