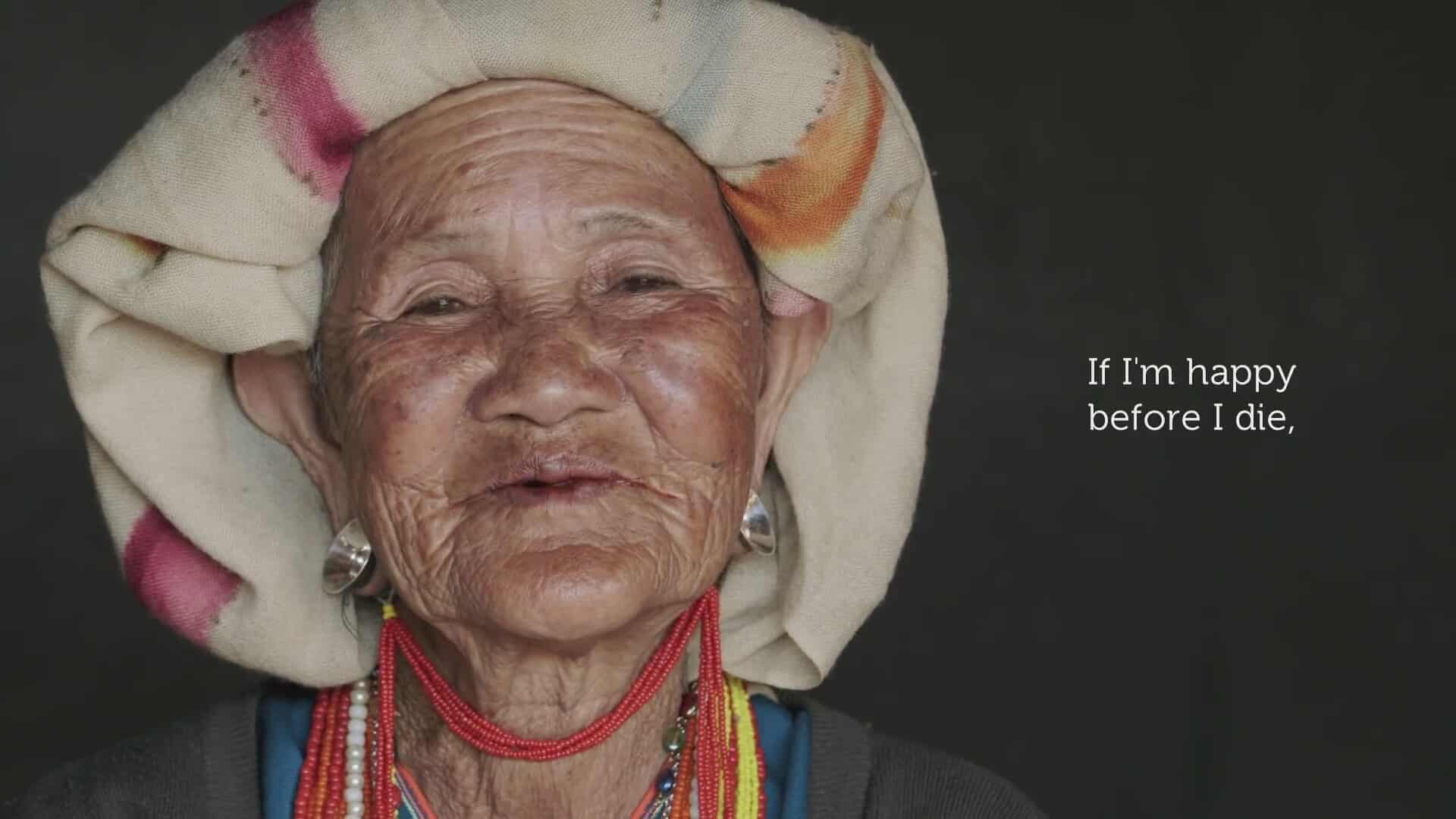Sudah sejak dari semula muncul ke dunia, anak turunan manusia adalah misteri terbesar jagat raya kita. Makhluk yang satu ini, menggumuli hidupnya dari satu pertanyaan ke jawaban berikutnya. Dari rasa penasaran berlanjut pencarian yang tiada sudah.
Berbekal akalnya semata, manusia bisa memikirkan diri sendiri yang berpikir tentang pikiran, yang memikirkan. Berdasar cara semudah ini sejatinya kita sudah beroleh sebuah ilmu. Bukan pengetahuan, bukan sekadar wawacan.
Masa depan yang dulu pernah kita nantikan, ternyata sudah dijalani hari ini. Masa lalu yang telah kita lintasi, padahal adalah hari ini yang menyatu bersama penantian sarat misteri. Pada dasarnya, kita semua memulai langkah pertama hidup seturut rasa ketidaktahuan. Apakah itu berupa keyakinan, pilihan, atau tindakan. Meski kita tahu tabir rahasia menyelubungi, namun dengan tekun kita menyibaknya helai demi helai. Kendati tak mengerti apa-apa, namun kita kerap berupaya memafhumi apa saja.
Kali ini mari kita menyelam ke dalam pikiran terdalam, dengan menembusi batas-batas yang menyekat akal sehat. Dunia kita, sampai kapan pun adanya, melulu hanya berisi kesimpang siuran tiada tara. Muspra. Purnasia. Lalu tinggalah kita yang tak pernah mau berpikir dan merenung, tentang segala rahasia kehidupan yang disimpan tuhan dalam hati mereka yang memiliki-Nya. Sementara hati orang yang demikian, adalah kuburan bagi pelbagai rahasia kecil dan yang terbesar.
Sebagian manusia awam, hanya sibuk menghabiskan waktu hidupnya untuk terus menilai orang lain. Mereka yang kaya dianggap pongah oleh si miskin. Sementara si miskin hanya sekelompok pemalas bagi yang kaya—bukan apa-apa.
Para pemberani dianggap dewa di mata pengecut. Ia yang pengecut jadi hina bagi pemberani. Si dungu terkesan mengiba pada yang bijak. Mereka yang bijaksana tercitra angkuh di mata si dungu. Pencinta Tuhan ditahbis gila oleh mereka yang kecanduan doktrin dan dogma.
Sementara sebagian kecil dari yang terkecil golongan manusia, memilih jalan sebaliknya. Mereka merasa lebih miskin dari yang termiskin. Lebih dungu dari yang paling pandir. Lebih tak tahu apa-apa tinimbang mereka yang mengetahui segalanya. Lebih nista dari pendosa. Lebih menyukai difitnah daripada sanjungan manusia. Lebih sepi dari yang ramai. Lebih ramai ketika sepi. Mereka tak pernah alpa mengintimi diri sendiri. Intinya, mereka menyenangi semua kekurangan dan lebihnya, demi menggali ketiadaan di dalam diri dan menemukan Dia Hyang Maha Ada.
Ketika mengawali hari perdana di bumi, kita juga tak tahu harus bagaimana dengan dunia seisinya—kecuali bahwa kita terpaksa harus mengajari diri sendiri agar terus bersabar dalam menjalani detik per detik keniscayaan. Toh pada ghalibnya, bumi itu tidak sama dengan ruang-waktu dunia yang adalah sarana belajar-mengajar. Jadi di mana saja kita berada, jika dua hal itu terjadi, maka sesungguhnya kita sedang melibatkan diri dalam belajar mengerti hidup.
Semua kita yang pernah terlibat dalam sejarah besar manusia sejak masih berusia nol, sejatinya telah mendidik diri sendiri untuk percaya pada keindahan hidup yang bertitik tolak dari ketiadaan. Pada ranah inilah kita berjibaku membangun kebudayaan. Menggali ilmu dalam segala kemisteriusan hidup masing-masing.
Tak ada yang lebih menggairahkan tinimbang melakukan temuan baru sepanjang karier kemanusiaan. Meski senyatanya tak ada yang baru di bawah matahari, tapi bagi anak-anak manusia, perjalanan rasa hidupnya adalah kata kunci dari pintu-pintu rahasia yang siap ia sibak dengan kesadaran baru.
Jangankan memahami sebuah agama dengan rentetan panjang sejarahnya, mengerti diri sendiri saja sudah jadi perkara besar. Padahal bangsa manusia hanya dua jenis sahaja. Maskulin-feminin.
Lucunya, sesama penyandang maskulinitas-femininitas pun masih bertengkar. Berbilang sudah kita banyaknya, namun tiada sudah kita saling berbalahan. Masing-masing bertahan dengan cara dan pola berpikirnya semata.
Jika untuk memahami sebuah hal ikhwal dibutuhkan seorang guru, mengapa kita tak jua pintar selaku murid? Siapakah yang salah? Haruskah ada yang benar di antara kedua posisi itu? Mungkin, tak perlu kita sematkan kata benar-salah pada keduanya? Begitukah?
Guru terbaik itu, tak pernah mengajar—kecuali terus menerus belajar. Murid paling teladan itu, ialah mereka yang sadar bahwa dirinya pembelajar sejati kehidupan. Murid seorang guru, ya dirinya sendiri. Guru seorang murid, ya diri sendiri.
Murid yang menyadari kebodohannya, sama dengan guru yang pintar. Guru yang sadar pada kekurangannya, adalah murid yang cerdas bagi dirinya pribadi. Jika hidup dilakoni dengan kesadaran, maka indahlah kisah yang kan tersusun di atas kanvas sejarah manusia.
Mengajari diri sendiri tentang betapa indahnya belajar dalam hidup, kelak dapat menciptakan hidup yang selalu dalam kondisi belajar. Hamba yang dhaif ini memang telah sedari kecil bersusah payah menandai huruf demi huruf Hijaiyah, namun sampai detik ini, baru satu huruf saja yang bisa dimafhumi, diamalkan. Itu pun dengan susah payah. Lebih tepatnya, menyedihkan.
Ilmu terkait menuntun diri ini sudah merupakan riwayat langka di zaman kita. Orang-orang sibuk menilai, mengoreksi yang lain di luar dirinya, lalu abai pada kepandiran sendiri.
Banyak orang yang begitu cepat menguliti salah siapa saja, lantas tak pernah mau dan bisa menemukan salah dalam dirinya. Ilmu sedemikian tampak sederhana. Ya... Tapi bila mau dikaji, niscaya sampailah kita pada satu samudera di mana diri sejati menanti dalam balutan rindu purbani.
Pembelajar terbaik dalam hidup, bukanlah mereka yang punya sederet gelar lan segudang prestasi, melainkan ia yang tahu diri, berikut dengan segala batas, potensi, daya, cipta, & karsanya.
Selemah apa pun kita, masih ada lebihnya. Jika sudah tahu punya kelebihan apa, maka tutupilah kekurangan itu. Hidup nan indah tak melulu soal manfaat & perenungan, namun yang setiap detiknya adalah kesabaran mengeja huruf tanpa aksara.
Huruf yang takkan pernah ditulis, tapi bisa dibaca. Huruf yang hanya bisa tercetak pada kedalaman samudera hati & pikiran yang nirwana. []
Banjarmasin, 26 November 1927 Saka