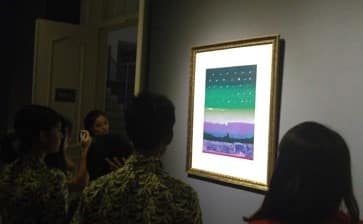Menurut penanggalan Hijriyah, Sya’ban adalah bulan sebelum Ramadan. Orang Jawa menyebutnya sebagai bulan Ruwah. Di bulan ini umat Islam melakukan ritual nyadran berupa pertemuan keluarga, kenduri (makan dan doa bersama), lalu dilanjutkan berziarah ke makam leluhur. Di hari terakhir bulan Sya’ban atau Ruwah, kaum Muslim (di Jawa khususnya) melaksanakan tradisi padusan yaitu melakukan adus/mandi, sebagai persiapan fisik, mental dan spiritual untuk membersihkan dan menyucikan pikiran dari nafsu dasar sebelum menjalankan ibadah suci puasa.
Agenda Ruwahan menjadi ekspresi Islam Nusantara yang mengisahkan sebuah bentuk formasi kultural masyarakat dalam memahami esensi Islam. Tidak hanya menjadi sarana pembersihan spiritual, tetapi sebuah praktik transisi yang mengkontraskan dinamika modernitas dengan kekuatan tradisi yang terus hidup sekaligus menciptakan sebuah identitas keagamaan yang unik dan kontekstual di Indonesia.
Transisi – Resistensi
Secara filosofis, konsep ritual transisi yang dikemukakan oleh Victor Turner tentang "liminalitas" menjelaskan bahwa masa transisi merupakan fase di mana struktur sosial yang mapan berhenti sementara, membuka peluang bagi terbentuknya identitas baru dan hubungan sosial yang lebih egaliter.
Dalam konteks Ruwahan, kegiatan seperti nyadran dan ziarah makam berfungsi sebagai momen liminal—yaitu waktu di mana masyarakat melepaskan beban konflik dan keterikatan sosial masa lalu, lalu berkumpul untuk berdoa, memaafkan, dan memperbaharui ikatan mereka. Ritual Ruwahan menjadi ruang transisi yang memungkinkan terjadinya pembaruan spiritual dan sosial, menghubungkan tradisi masa lalu dengan harapan masa depan yang lebih inklusif dan harmonis. Ritual-ritual ini menjadi titik temu antara masa lalu yang penuh tradisi dan masa depan yang ditandai dengan harapan serta perbaikan diri.
Dari perspektif kajian budaya, formasi kultural Ruwahan dapat dilihat sebagai wujud resistensi terhadap modernitas yang homogen dan sekuler. Di tengah arus globalisasi yang sering mengikis nilai-nilai lokal, praktik-praktik seperti nyadran muncul sebagai penegasan identitas kultural yang otentik.
Kegiatan-kegiatan ini memungkinkan masyarakat untuk mengenang kembali diri mereka dengan akar sejarah dan nilai-nilai moral yang telah teruji oleh waktu. Ritual ini tidak hanya mempertahankan tradisi lisan dan simbolik, tetapi juga menggabungkan unsur estetika, keagamaan, dan sosial yang memberikan warna pada identitas kolektif.
Dalam kondisi masyarakat kontemporer, yang ditandai oleh dinamika urbanisasi, digitalisasi, dan individualisme yang semakin kuat, formasi kultural Ruwahan menawarkan alternatif bagi nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Di era di mana interaksi sosial banyak terjadi secara virtual dan hubungan antarpribadi kerap diwarnai oleh transaksi ekonomi, ritual-ritual Ruwahan menghadirkan kembali nuansa keintiman dan kehangatan yang sulit didapat dari dunia digital. Formasi kultural Ruwahan berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat untuk “merefresh” diri secara spiritual dan sosial, serta menolak homogenisasi yang dihadirkan oleh modernitas yang serba instrumental.
Pada saat yang sama, kondisi ekonomi-politik saat ini menghadirkan tantangan yang signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat. Ketimpangan ekonomi, korupsi, dan dinamika politik yang tidak stabil telah menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara. Dalam situasi seperti ini, praktik-praktik kultural tradisional memiliki peran penting sebagai alat resistensi dan penyeimbang nilai.
Ritual Ruwahan misalnya, bukan sekadar seremonial agama, melainkan juga momen di mana masyarakat berkumpul, berbagi pengalaman, dan saling menguatkan dalam menghadapi kenyataan yang keras. Kegiatan ini mengingatkan bahwa kesehatan sosial dan kesejahteraan bersama tidak hanya bergantung pada kebijakan ekonomi semata, tetapi juga pada kekuatan relasional dan solidaritas yang tumbuh dari budaya bersama.
Dalam kerangka filsafat kontemporer, teori “Masyarakat Risiko” (risk society) yang dikemukakan oleh sosiolog Jerman Ulrich Beck, dapat memberikan perspektif baru. Dalam karyanya, Risk Society: Towards a New Modernity (1992), Beck menyebut modernitas menghadirkan risiko yang tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif, yang harus dikelola melalui mekanisme sosial yang adaptif. Krisis ekonomi dan politik yang sering melanda Indonesia merupakan bagian dari risiko modern yang harus dihadapi bersama.
Dalam konteks ini, praktik keagamaan seperti Ruwahan tidak hanya berfungsi sebagai ritual penyembuhan, tetapi juga sebagai strategi kolektif untuk menghadapi dan mengelola risiko tersebut. Masyarakat diingatkan bahwa kekayaan sejati terletak pada kebersamaan dan hubungan yang harmonis, bukan hanya pada akumulasi harta. Melalui ritual ini, masyarakat membangun jaringan solidaritas yang berperan sebagai sistem pendukung emosional dan sosial, yang dapat mengurangi dampak negatif dari komunikasi ekonomi dan politik.
Paradigma Alternatif
Dalam menghadapi berbagai permasalahan ekonomi-politik saat ini, pemahaman terhadap Islam Nusantara dan formasi kultural Ruwahan menawarkan sebuah paradigma alternatif. Daripada sekedar mengandalkan solusi teknokratis atau struktural yang seringkali bersifat kosmetik, masyarakat dapat mengintegrasikan nilai-nilai tradisional yang telah teruji dengan pendekatan inovatif untuk membangun sistem sosial yang lebih inklusif.
Secara visioner, transformasi budaya melalui revitalisasi tradisi keagamaan seperti Ruwahan memiliki potensi untuk membentuk identitas nasional yang lebih memperhitungkan nilai-nilai lokal dan pluralitas. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi dan serba cepat, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya warisan budaya menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang tidak hanya cerdas secara ekonomi, tetapi juga kuat secara spiritual dan sosial. Islam Nusantara, dengan segala kekayaan tradisi dan praktiknya, menyuguhkan sebuah model integratif yang dapat merespon tantangan zaman dengan cara yang lebih humanis dan berkeadaban.
Dengan demikian, pembentukan formasi kultural Ruwahan dalam konteks Islam Nusantara bukan sekadar ritual keagamaan, namun juga merupakan wujud perjuangan kolektif melawan homogenisasi dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi-politik modern. Dalam masyarakat yang semakin terdigitalisasi dan terfragmentasi, Ruwahan menawarkan ruang bagi peremajaan identitas dan penguatan nilai-nilai kemanusiaan, yang pada akhirnya dapat menjadi landasan bagi masa depan yang lebih inklusif dan beradab.