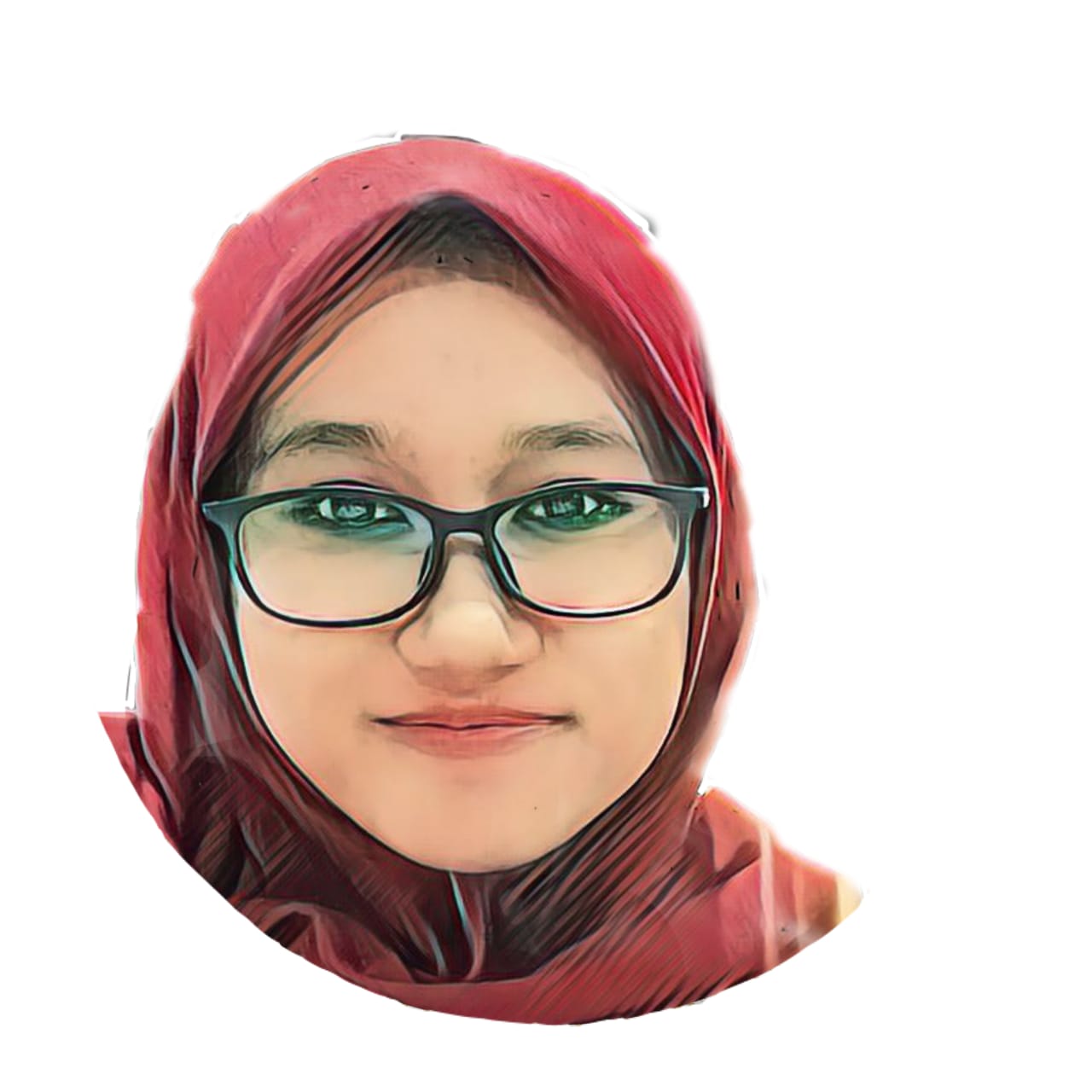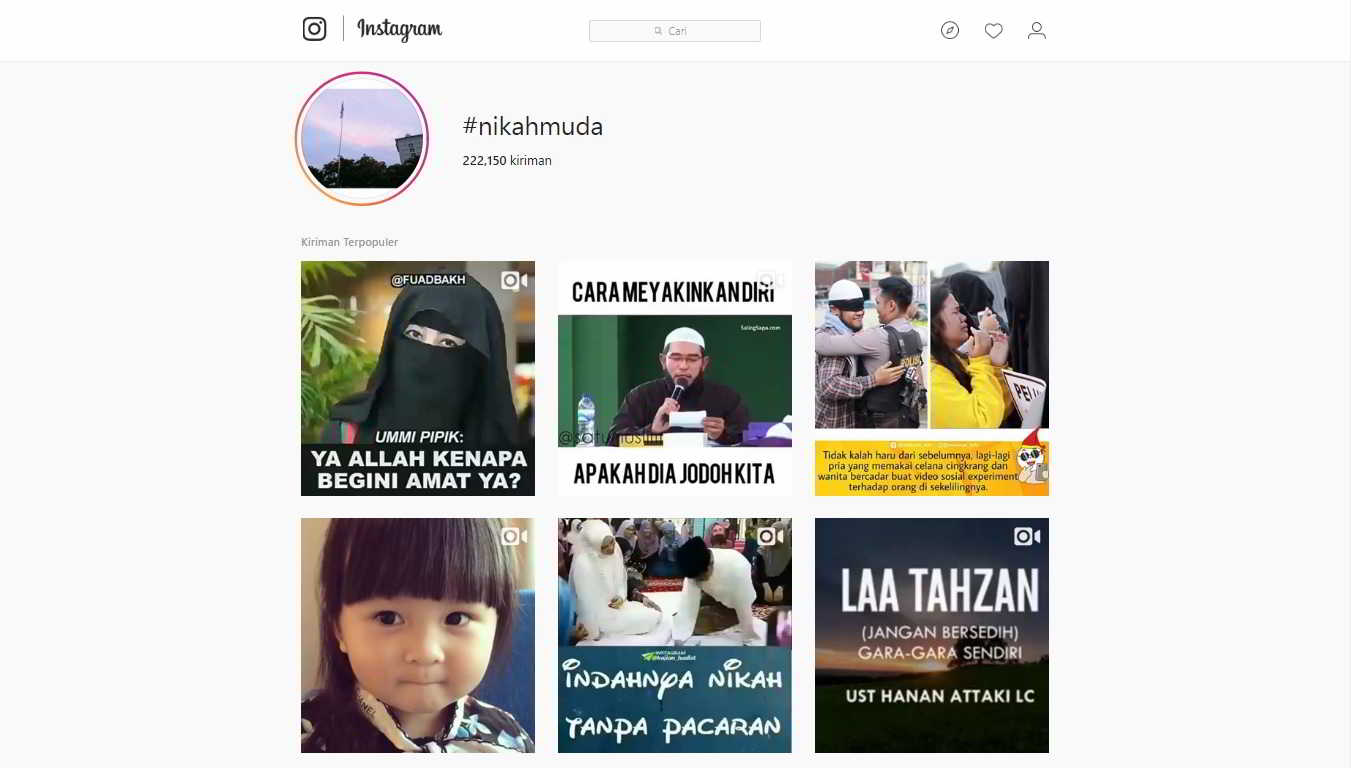Saba Mahmood, seorang profesor, ahli teori dan penulis dari Pakistan yang karyanya berfokus pada persimpangan antara Islam dan teori feminis, meninggal pada 10 Maret di rumahnya di Berkeley, California. Dia berusia 57 tahun. Penyebabnya adalah kanker pankreas, kata suaminya, Charles Hirschkind.
Dalam studinya, Profesor Mahmood, seorang sarjana Mesir modern yang berspesialisasi dalam antropologi sosiokultural di Universitas California di Berkeley, juga menantang gagasan yang mengakar tentang sekularisme dan agama, khususnya dalam masyarakat Muslim. Dia dibesarkan sebagai seorang Muslim.
Dalam bukunya "Politik Kesalehan: Kebangkitan Islam dan Subjek Feminis" (2004), Profesor Mahmood mengeksplorasi gerakan perempuan akar rumput yang berfokus pada reformasi moral di Kairo pada 1990-an.
Gerakan satu wajah dari upaya Timur Tengah yang lebih luas untuk menghidupkan kembali praktik etika Muslim unik karena para wanita ini "memahami bahwa pembangunan kembali komunitas Islam yang saleh tidak dapat dibiarkan hanya oleh pria," kata Profesor Hirschkind, seorang rekan sarjana antropologi sosiokultural di Berkeley yang kadang-kadang bekerja sama dengan istrinya.
Dalam kata pengantar bukunya edisi 2012, Profesor Mahmood menggambarkan pujian dan kritik yang dia terima dari para feminis. Para pengagumnya melihatnya sebagai upaya mengatasi "kegagalan feminisme untuk menerima sudut pandang dan kehidupan wanita religius, kecuali sebagai objek yang perlu direformasi," tulis suaminya dalam email.
“Karya Saba menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi agen di dalam, dan tidak hanya melawan, tradisi agama patriarkal,” tambahnya. Para pengkritiknya, katanya, melihat undangan Profesor Mahmood untuk memahami perspektif wanita religius ini sebagai "pengabaian mandat emansipatoris feminisme."
Profesor Mahmood menulis bahwa kedua perspektif ini “mengabaikan fakta bahwa saya tidak tertarik untuk memberikan penilaian tentang apa yang dianggap sebagai praktik feminis versus anti-feminis.” Dia berputar kembali ke intinya pada tahun 2016 pada sebuah konferensi di Universitas Ilmu Manajemen Lahore di Pakistan. "Jika saya mengutuk gerakan-gerakan itu, tidak berarti ada yang lebih memahami mereka," katanya. “Tugas saya sebagai seorang sarjana bukan hanya untuk mencela, tetapi mencoba memahami apa yang memotivasi orang untuk terlibat dalam gerakan semacam itu.”
Dalam bukunya tahun 2015, "Perbedaan Agama dalam Zaman Sekuler: Laporan Minoritas", Profesor Mahmood menghadapi gagasan konvensional bahwa sekularisme yang umumnya dipahami sebagai ketiadaan agama atau pemisahan agama dari negara akan membantu mengurangi ketidaksetaraan sosial dan politik dan agama. ketegangan di negara-negara Islam. Penemuannya didasarkan pada pekerjaannya yang melelahkan di Mesir, mengamati minoritas agama seperti Kristen Ortodoks Koptik dan Bahais.
Ia mengatakan, pada konferensi 2016, sering diperdebatkan bahwa solusi untuk ekstremisme agama adalah lebih sekularisme, dan bahwa negara-negara seperti Pakistan menderita fundamentalisme karena negara dan rakyatnya tidak cukup sekuler. Tetapi gagasan bahwa sekularisme berarti pemisahan gereja dan negara "adalah gagasan lama" yang telah ditentang oleh para sarjana selama sekitar 20 tahun terakhir, katanya.
Para ulama kini berargumen bahwa kondisi sekularisme sebenarnya adalah di mana negara “semakin banyak terlibat dalam pengaturan kehidupan beragama dan institusi keagamaan,” katanya. Jadi, ketika gerakan Islam berjuang untuk menjadikan negara sebagai sarana mereka untuk mengislamkan masyarakat, mereka sejalan dengan konsepsi modern tentang sekularisme, Profesor Mahmood menegaskan. “Bahkan di Amerika, Protestantisme adalah aspek yang sangat penting yang menginformasikan hampir semua hukum dan praktik,” katanya.
Karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, Prancis, Persia, Portugis, Spanyol, Turki, dan Polandia. Saba Mahmood lahir pada 3 Februari 1961, di Quetta, Pakistan, dari pasangan Mahmood Hussein, seorang polisi, dan Latif Begum, seorang ibu rumah tangga.
Ms. Mahmood pindah ke Amerika Serikat pada tahun 1981 untuk belajar arsitektur dan perencanaan kota di University of Washington di Seattle. Dia menerima gelar doktor dalam bidang antropologi dari Universitas Stanford pada tahun 1998 dan mengajar di Universitas Chicago sebelum bergabung dengan fakultas Berkeley pada tahun 2004. Dia telah mengajar selama semester musim gugur terakhir.
Profesor Mahmood adalah tokoh sentral dalam pembentukan Berkeley Pakistan Studies Initiative, yang disebut sebagai program akademik pertama di Amerika Serikat yang didedikasikan untuk studi sejarah, politik, dan budaya Pakistan.
Dia juga berafiliasi dengan Pusat Studi Timur Tengah, Program Teori Kritis, dan Institut Studi Asia Selatan. Selain suaminya, yang dinikahinya pada tahun 2003, ia meninggalkan seorang putra, Nameer Hirschkind, dan dua saudara laki-laki, Tariq dan Khalid.
Profesor Mahmood menerima banyak penghargaan dan penghargaan, di antaranya Axel Springer Fellowship di American Academy di Berlin dan fellowship di Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences di Stanford University dan University of California Humanities Research Institute. “Jelas Saba Mahmood selalu menjadi kekuatan yang terlalu kuat di dunia untuk 'pergi',” Laurie A. Wilkie, ketua departemen antropologi Berkeley, menulis di situs web universitas. “Dia bertahan dalam banyak kontribusinya yang penting di dalam dan di luar antropologi. Dia bertahan dalam kehidupan dan karier banyak mahasiswa sarjana dan pascasarjana. "
Teori Feminis dalam Islam
Dalam teori feminis, Mahmood menantang pembaca untuk memahami bahwa wanita Muslim saleh yang dia pelajari di Kairo bukanlah subjek yang patuh tanpa berpikir, tetapi terlibat dalam pendekatan hermeneutis yang berbeda untuk membaca Alquran di sekolah mereka sendiri, menumbuhkan praktik keagamaan sebagai bentuk etika. Mengadakan, Menantang pandangan kebebasan subyektif yang diwariskan oleh filosofi moral Barat, dia membuat argumen yang berani dan menantang, untuk memahami wanita saleh dalam Islam seseorang harus memahami subjek yang didefinisikan dalam hubungannya dengan representasi tekstual dan imajistik dari ketuhanan.
Wanita yang terlibat dalam praktik keagamaan semacam ini, menurutnya, harus dipahami sebagai terlibat dalam praktik kultivasi diri yang etis. Namun, dalam kasus ini, subjek etika bukanlah kesukarelaan, sebuah gagasan yang akan memisahkan 'kehendak bebas' dari norma sosial dan agama formatif; sebaliknya, dalam Islam, subjek etika mewujudkan hubungan yang hidup dan dipraktikkan dengan yang ilahi, dan membutuhkan pengertian yang berbeda tentang pembentukan subjek.
Salah satu konsekuensi dari pandangan ini diperjelas dalam intervensinya dalam debat tahun 2006 tentang kartun Denmark yang membuat karikatur Muhammad. Mereka yang mengklaim bahwa gambar seperti itu hanya menyinggung merindukan sifat dari cederanya itu sendiri. Dalam Islam, menurutnya, serangan terhadap citra ketuhanan sama dengan serangan terhadap diri yang hidup, karena diri itu berada dalam hubungan itu sendiri.