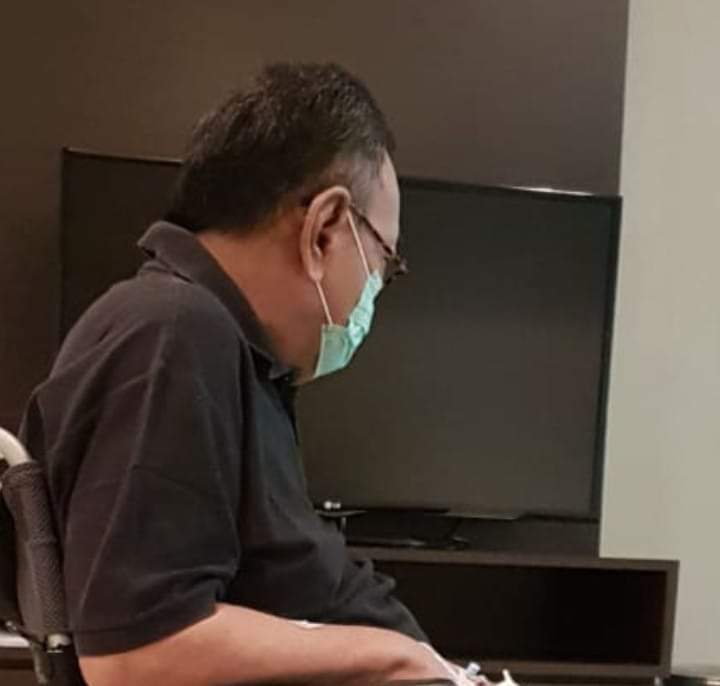Dini hari, permulaan bulan Agustus, seperti berlalu dengan cepat. Perasaan campur baur antara kuawatir, takut, sedih, dan juga takjub. Sedih karena melihat kondisi Gus Im semakin berat, sudah tak bisa diajak berinteraksi lagi. Takjub lantaran sebuah perasaan aneh yang beberapa hari belakangan menggelayuti benak: hari Arofah.
Ya, ingatan akan hari atau waktu para jamaah haji melaksanakan wukuf di Padang Arafah tersebut, muncul setelah Gus Im sempat drop tak sadarkan diri seminggu sebelumnya, pada sekitar pukul 5 pagi, sabtu (25/7).
Ketika itu, di tengah kepanikan dan kuwatir menunggu kabar dari dalam ruang rawat, saya jadi teringat saat-saat beliau sering menyebut tentang hari Arafah beberapa tahun lalu sewaktu beliau masih bugar. Gus Im selalu antusias tentang hari Arafah, entah sekedar bercerita ataupun bertanya tanggal masehinya jatuh kapan. Dari situ saya tahu bahwa hari Arafah merupakan salah satu "hari khusus" beliau.
Pada hari tersebut Gus Im biasa menggeber "ngajinya". Dan untuk tahun ini, hari Arafah itu sudah akan segera tiba, 30 juli nanti. Disusul esoknya adalah hari raya Idul Adha.
Ingatan itu terus saja mengiang seolah menempel terus di kepala. Saya pun berdoa semoga saja hari itu akan menjadi momentum kebangkitan beliau kembali setelah sekian lama berjuang melawan sakit, bukan sebaliknya. Tanpa memberi embel-embel apapun saya menuliskan "Yaumul Arofah" di timeline FB saya pada 26 Juli.
Jumat malam (31/7). Di ruang tunggu lantai tiga rumah sakit Mayapada sedikit pun saya tak dapat memicingkan mata. Savic sudah keluar duluan untuk suatu pertemuan, disusul Fuko yang juga harus pulang ke Ciganjur. Hari itu memang giliran saya menunggu menggantikan mereka.
Sekitar pukul 21 malam saya minta izin masuk ke ruang HCU untuk melihat kondisi Gus Im sekaligus hendak mengoleskan air zamzam ke bibir beliau sebagaimana pesan mbak Asti, sang istri. Tapi masih belum diperbolehkan saat itu sehingga saya pun kembali lagi ke ruang tunggu.
Namun beberapa saat kemudian saya diberitahu bahwa dokter ingin bertemu. Segera saya menyambar botol zamzam dan berlari menuju pintu ruang perawatan, di mana dr. Rofi, dokter spesialis bedah digestif yang sekaligus sahabat Gus Im sendiri, sudah memunggu.
Dokter menyampaikan kondisi terakhir Gus Im yang disebutnya makin mengalami penurunan. "Bisa jenguk, Dok?" pinta saya. "Ayok tak kancani mlebu, Ji," jawab dokter yang memang sudah saya kenal baik sejak Gus Im pernah dirawat sebelumnya di RS. Fatmawati beberapa tahun lalu.
Semua kamar di ruangan HCU tersebut berdinding kaca, termasuk pintunya. Gus Im sudah berpindah kamar sebanyak tiga kali selama dirawat di tempat itu. Yang pertama jaraknya sedikit jauh dari nurse station, lalu dipindahkan tepat di belakangnya agar pantauan dapat dilakukan lebih intensif. Selanjutnya beliau dipindahkan lagi di kamar 3503 untuk proses resusitas HD sehari pasca drop.
Saya berjalan di belakang dokter Rofi. Kami memasuki ruangan tempat Gus Im terbaring dengan selang oksigen yang masih menopang pernafasan beliau. Saya lihat dokter mendekatkan mulutnya ke telinga Gus Im dan bicara sedikit agak keras, "Kuat ya Gus. Iki Loji nok kene, Gus," katanya dalam bahasa Jawa Timuran. Dokter Rofi beringsut keluar untuk memberi saya kesempatan. Saya pun segera mendekat dan menyapanya dengan cara yang sama seperti dilakukan pak dokter. Saya bicara dengan jarak sangat dekat, "Gus, niki Loji. Tetap berjuang nggih Gus, seperti Dersu Uzala." Dersu Uzala adalah sebuah film karya Akira Kurosawa yang dirilis tahun 1975 di Uni Soviet. Gus Im sangat menyukai sosok Derzu dalam film kontemplatif tersebut.
Tak ada tanda-tanda respon. Mata Gus Im masih terkatup rapat. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan saat terakhir kali saya lihat tiga hari sebelumnya. Ketika itu masih banyak gerakan. Artikulasi kalimat beliau juga terdengar cukup jelas serta dapat ngobrol secara interaktif. Bahkan waktu itu saya sempat dibuat kaget ketika tiba-tiba beliau menatap saya sembari berkata, "Kenapa sih, Ji... dalam beberapa pertemuan terakhir awakmu koyok adoh?" Beliau bertanya begitu dengan tiba-tiba, dengan nada seperti menuntut.
Saya pun gelagapan dan segera memegang tangan kanan beliau, "Mboten, Gus. Saya selalu di sini bersama mbak Asti, Savic, Mas Farid, Mbak Iim, Mas Yayi, Mas Budi, dan lain-lain. Kami gantian menjaga Sampean, Gus."
"Aku gak seneng Ji, uwong dadi repot perkoro awakku," keluh beliau sembari menggerakkan kepala ke kiri.
Buru-buru saya menyergah, "Enggak, Gus. Kabeh kami di sini seneng iso nunggoki Sampean. Sing penting saiki sampean ndang cepet pulih. Ojo dipikir ya Gus. Sampean sing penting istirahat."
"Iyo, maturnuwun Ji.." jawab belau sembari menarik nafas lemah, namun segera terasa ada yang membetot ujung tenggorokan saya. Mata saya berkaca-kaca.
Kembali ke ruang HD. Saya hanya menatap beliau sembari berdoa untuk kesembuhan dan membacakan wirid yang pernah beliau ijazahkan. Saya bacakan pula beberapa teks doa yang dikirim sahabat2 beliau di Malang melalui Gus Din. Setelah itu saya oleskan beberapa tetes air zamzam ke bibir beliau sembari berucap di dekat telinga beliau, "ma'u zamzam 'ala niyah, bismillahir-rohmanir-rahim".
Saya melangkah keluar dan melihat dr. Rofi sedang memberi instruksi kepada beberapa suster jaga untuk melaporkan setiap perkembangan. Lalu kami melangkah keluar bersama dari ruangan itu. "Bagaimana menurut dokter terkait kondisi Gus Im?" saya coba meminta informasi termutakhir.
"Dokter-dokter ini juga heran semua. Gus Im bisa bertahan sejauh ini. Dia terus melawan," jelas dokter kalem, namun dengan penekanan serius.
Sesampai di pintu keluar dekat resepsionis HCU kami berhenti sejenak dan membersihkan tangan menggunakan sanitizer. Saat hendak berpisah saya memberanikan diri bertanya lagi, "Jadi menurut dokter, seberapa besar peluangnya?"
Dr. Rofi terlihat menarik napas pendek dan membenahi letak maskernya dan sejurus kemudian berkata lirih.