Fatimah, Perempuan Pengarang Kitab Kuning dari Banjar
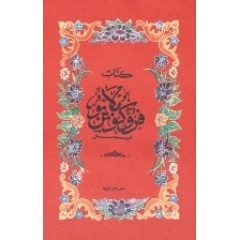
Di antara banyak kitab kuning di Indonesia, yang menjadi rujukan di pondok pesantren maupun madrasah, yang jumlahnya menurut Antropolog Martin van Bruinessen (2015) sekitar 900-an teks, rata-rata ditulis oleh pengarang laki-laki. Mungkin belum banyak orang tahu, ada satu kitab karangan ulama perempuan Melayu. Ia adalah Fatimah binti Abdul Wahab Bugis bin Syekh Arsyad al-Banjari.
Alkisah sekembalinya Syekh Arsyad dari mengaji di Makkah selama puluhan tahun (1772), konon disambut dengan antusias oleh pihak sultan, pembesar kerajaan dan para warga ibu kota. Sultan yang memerintah pada waktu itu, Sultan Tahmidillah I (1745-78), sangat menghormatinya, dan mengawinkannya dengan salah seorang kerabat dekatnya, Ratu Aminah, anak pertama Pangeran Thaha, saudara sepupu sultan.
Sultan juga menghadiahkan sebidang tanah sekitar lima kilometer dari Martapura, tempat kedudukan keraton pada waktu itu. Di atas tanah ini kemudian dibangun oleh Syekh Arsyad menjadi tempat permukiman baginya dan keluarganya, dan sebagai tempat pengajian guna mencurahkan ilmu-ilmu keislaman yang dipelajarinya selama di tanah haram.
Pengajian tersebut mengahasilkan banyak tokoh-tokoh ulama yang kemudian tersebar ke seluruh pelosok Banjar dan tempat-tempat lain di Kalimantan, dan bahkan ke Sumatera. Murid-murid ini pada gilirannya membuka pula pengajian sendiri di tempat tinggalnya masing-masing. Di antara murid-muridnya terdapat keturunannya sendiri, yang kemudian menjadi ulama terkemuka pula.
Kitab Parukunan
Konon Syekh Arsyad, di samping membuka pengajian agama yang diikuti oleh kaum pria, juga membuka pengajian untuk kaum perempuan. Di antara murid perempuannya yang paling cerdas adalah cucunya sendiri, Fatimah, yang dengan rapi mencatat pelajaran-pelajaran yang ia terima. Catatan itu, seperti yang dituturkan oleh Alfani Daud dalam Islam dan Masyarakat Banjar (1997), kemudian disalin turun-temurun dan belakangan dicetak dengan nama Kitab Parukunan.
Jangan-jangan tidak banyak pembaca Kitab Parukunan menyadari bahwa penulisnya perempuan. Sebab, kitab itu belakangan diatasnamakan seorang lelaki, yakni paman Fatimah yang bernama Jamaluddin, anak Syekh Arsyad dari istrinya yang bernama Ratu Aminah. Karena itulah kitab ini lebih dekenal dengan nama Kitab Parukunan Jamaluddin.
Kurang jelas mengapa kitab itu diatasnamakan Jamaluddin. Dalam dunia kitab kuning, menurut Martin van Bruinessen (2015) memang tidak ada hak cipta, dan menyalin tulisan orang lain tanpa kreditasi sudah menjadi kebiasaan. Mungkin saja identitas pengarangnya dengan sengaja disembunyikan–sesuai dengan anggapan yang sudah mapan bahwa mengarang kitab merupakan pekerjaan laki-laki. Kalau kita menggali lebih dalam sejarah, tidak menutup kemungkinan kita akan menemukan perempuan-perempuan lain yang menguasai ilmu-ilmu agama dan telah menulis kitab.
Menurut Ahmad Juhaidi (2009) dalam tulisannya yang berjudul “Untuk Kartini di Tanah Banjar”, paling tidak ada dua kemungkinan mengapa karya itu diatasnamakan Mufti Jamaluddin. Pertama, pihak kerajaan hanya mengakui otoritas ilmu agama Islam hanya dipegang oleh mufti kerajaan yang dijabat oleh Jamaluddin. Fatwa keagamaan yang tidak dikeluarkan mufti tidak diakui dalam struktur kerajaan banjar ketika itu. Bisa jadi, jika parukunan itu diklaim sebagai tulisan Fatimah, bukan mufti kerajaan, beragam hukum fiqih dalam Parukunan tidak diakui kebenarnnya.
Kedua, Fatimah melihat kepentingan yang lebih besar dengan tidak ditulisnya namanya sebagai pengarang Parukunan tersebut. Dengan mencantumkan nama Jamaluddin, kitab itu akan cepat diakui kerajaan dan masyarakat luas, dan Fatimah, barangkali sebagai keponakan merasa berkewajiban menghormati pamannya yang notabene pemegang otoritas Islam tertinggi di Kerajaan Banjar.
Kitab serderhana
Kitab ini sederhanan saja, sesuai dengan namanya parukunan, berarti uraian dasar mengenai rukun Islam dan iman, dalam istilah Banjar disebut dengan rukun-marukun. Walaupun sederhana, kitab ini merupakan salah satu yang paling popular diantara kitab-kitab yang sejenis, dan sering dicetak kembali. Belakangan beredar kita sejenis yang diberi nama Kitab Parukunan Besar, disusun oleh Haji Abdurrasyid Banjar. Menurut Alfani Daud (1997), kemungkinan dari kitab yang dikarang Fatimah inilah yang kemudian ditambah dan diadakan perubahan sekedarnya.
Salah satu dari kedua Kitab Parukunan ini, sejak sangat lama senantiasa terdapat di hampir setiap rumah tangga muslim di Kalimantan Selatan, dijejerkan dengan Alquran. Kitab Parukunan yang lain, yang bernama Rasam Parukunan, dikarang oleh Haji Abdurrahman dari Sungai Banar, Amuntai (wafat pafa 1965). Kitab yang usai ditulis pada 1938 itu kurang popular dibanding kedua kitab di atas.
Kalau dilihat dari segi isi, kitab Parukunan Jamaluddin tak jauh berbeda dengan kitab sejenis lainnya. Namun yang menarik, kitab ini tidak menyinggung sisi-sisi fikih klasik yang kini dianggap diskriminatif terhadap perempuan. Penulisnya tidak menyebut mandi usai haid sebagai bersuci (yang secara implisit menganggap haid adalah kotor), tetapi hanya menyebutnya sebagai mandi wajib (Mujiburrahman, 2013: 30).
Pengarang tidak meletakkan perempuan pada posisi lebih rendah atau kurang suci daripada laki-laki. Ia menghindari dari perkara yang sangat membedakan antara kedua jenis kelamin, seperti aqiqah, warisan, dan kesaksian. Akan tetapi sayangnya, kita tidak mengetahui secara rinci peran apa yang dilakukan Fatimah sebagi ahli agama di masyarakat, lantaran ketiadaan sumber-sumber historis.
Keberadaan Fatimah sebagai penulis Kitab Parukunan menunjukkan bahwa sejak abad ke-19, penguasaan ilmu-ilmu agama tidak hanya terbatas di kalangan laki-laki saja, tetapi juga perempuan, khususnya di masyarakat Banjar. Sekarang ini, Kitab Parukunan masih beredar luas dan tetap dipergunakan oleh masyarakat terutama di kalangan muslim tradisional.
Fatimah binti Abdul Wahab Bugis diperkirakan wafat pada 1828 dalam usia 53 tahun. Jenazahnya kemudian dimakamkan di komplek pemakaman Desa Karang Tengah, Kecamatan Martapura, satu komplek dengan makam ayah dan ibunya.





