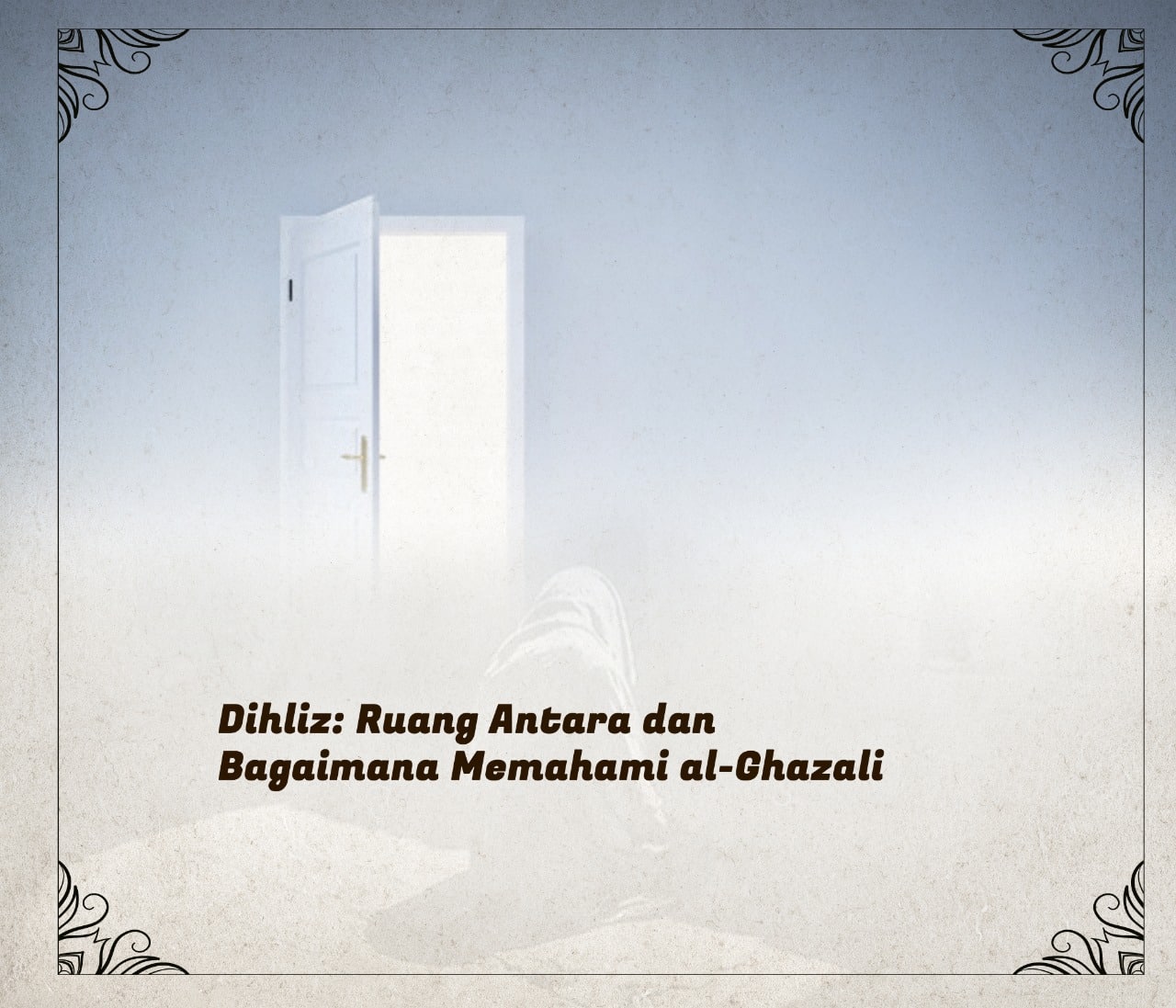Dihliz. Kata ini hanya muncul beberapa kali dalam keseluruhan karya al-Ghazali; tidak lebih banyak dari kata salik, jawahir atau a’rad (‘arad). Kata dihliz muncul dalam salah satu pernyataan al-Ghazali yang paling menonjol dalam al-Munqiz min al-Dalal: Wa ma qabla dzalika ka al-dihliz li al-salik ilaihi (Dan apa pun yang mendahuluinya, ia seperti dihliz bagi yang menempuh jalan menujunya).
Sekian lama para pengkaji terfokus kepada damir iliaihi. Apakah “ia” menunjuk kepada pembahasan al-Ghazali dalam kitab ini mengenai peleburan spiritual (fana’) dan jalan mistik, ataukah damir “ia” merupakan huruf kapital yang menunjuk kepada Tuhan. Ada banyak pendapat mengenai ini.
Ini bisa dimaklumi. Sebab terkadang kita terfokus hanya kepada bagaimana al-Ghazali menjalani kehidupannya, dalam arti beranjak dari satu keadaan ke keadaan berikutnya, dari satu ilmu ke ilmu berikutnya, atau dari jalan empiris menuju sufisme. Ide-ide al-Ghazali terikat ruang dan waktu. Kita menempatkan keseluruhan ide al-Ghazali sesuai dengan perjalanan spiritualnya: apa yang ia tulis lantas meragukannya dalam filsafat, misalnya, setelah memasuki tasawuf, seakan-akan ide filsafat al-Ghazali sudah tidak relevan lagi. Kalimat ini, dengan begitu, diartikan sebagai suatu perjalanan spiritual al-Ghazali menjadi seorang salik menuju bahasan baru atau menuju Tuhan.
Barulah pada tahun 2005, Ibrahim Moosa menulis sebuah buku yang begitu indah, Ghazali and the Poetics of Imagination. Dengan sedikit mengubah sudut pandang terhadap al-Ghazali, dia mulai membangun tesis bukan pada perubahan spiritual al-Ghazali, tetapi memandang semua pencapaiannya baik sebelum ia hidup di jalan tasawuf dan setelahnya sebagai pondasi yang membangun suatu rumah besar. Ide-ide al-Ghazali, meski pun meragukan bagi dirinya, tetapi sejatinya bagi kita dia selalu relevan. Olehnya, apa yang bisa kita pelajari dari al-Ghazali bukan sekadar wa ma qabla dzalika dan li al-salik ilaihi, tetapi perlu juga mempelajari dihliz yang berada di antara keduanya itu.
Kata ini bukanlah asli dari bahasa Arab, entah kapan orang Arab mulai menggunakannya. Ia adalah serapan dari bahasa Persia yang dalam arti sederhananya adalah ruang antara pintu dan rumah. Dalam bahasa kita mungkin bisa disandingkan dengan ambang pintu, sebuah ruang perbatasan antara sisi luar (pekarangan, dunia) dan sisi dalam (rumah, pribadi).
Dihliz, dengan demikian adalah ruang di mana segalanya dimulai: seseorang yang hendak masuk ke dalam rumah haruslah melewati ambang pintu, begitu pula orang yang hendak keluar rumah harus melewatinya. Ia ada di antara pintu (bab) dan rumah (dar). Seseorang tidak dapat berbicara tentang wujud pintu dan rumah, atau berbicara tentang ruang di luar dan ruang di dalam tanpa dihliz. Meski berada di antara, dihliz membingkai semua ruang-ruang lain.
Jika kita memandangnya dari kesempurnaan dan kelayakan rumah, ia terletak di luar. Tapi jika kita memandangnya dari pintu yang mengarah ke jalan, ia terletak di dalam. Sebuah halaman, lorong, beranda, atau sebuah pendopo yang dapat membentuk dihliz. Ia adalah ruang di mana aroma-aroma dari dalam rumah berhembus dan bercampur dengan aroma yang dihasilkan dari luar rumah atau bisa pencampuran dari aroma yang lebih banyak lagi.
Dihliz juga dapat diartikan sebagai ruang liminar (perbatasan) dari dua entri: entri dari luar dan entri ke dalam. Ia menjadi perantara antara ruang luar dan dalam, antara eksoterik (zahir) dan esoterik (batin). Layaknya imajinasi yang berperan seperti penyeberangan, dihliz adalah jembatan yang menghubungkan dua tepian sungai. Penyeberangan itu hakikatnya adalah suatu hermeneutika symbol (ta’wil ta’bir), metode pemahaman yang mengalihbentukkan data indrawi dan konsep-konsep rasional menjadi symbol-simbol dengan membuat mereka berjalan di jalan penyeberangan ini. Dengan begitu, dihliz adalah imajinasi yang memerantarai dunia misteri ke dunia kasat mata atau sebaliknya.
Dihliz menandakan ruang yang begitu hibrid. Setidaknya selalu ada tiga ruang atau lebih yang bergumul: ruang dalam, luar dan ruang di antara keduanya. Hal ini mengindikasikan adanya persilangan atau transfer nilai-nilai yang terus terjadi. Moosa menganalogikan, seseorang yang memasuki pintu setiap rumah haruslah bersikap sopan sambil memelihara tata karma yang patut. Sementara dihliz bukan sepenuhnya ruang privat dan bukan ruang publik.
Ruang antara ini akan selalu kita temukan dalam ide-ide al-Ghazali. Yang paling kentara adalah bagaimana setiap bangunan idenya tidak hanya menunjuk pada satu hal. Misal ketika dia berbicara tentang hukum-hukum syariat, dia akan menjelaskannya sesuai dengan hukum-hukum mazhab Syafi’i. Tetapi berbeda dengan roang-orang yang juga menulis hukum syariat dengan mazhab yang sama, ia akan memadukannya dengan nilai-nilai esoterik. Jadi antara kezahiran dan kebatinan suatu hukum, berkelindan dalam kajian al-Ghazali, dan kita bisa mengambil kedua-duanya.
Hal ini pula yang membuat kita selalu berhadapan dengan semacam graduasi dalam ide-ide al-Ghazali. Dia akan selalu membagi berbagai hal ke dalam beberapa bagian dan tingkatan. Atau dalam aspek yang paling sederhana, dia membagi wilayah jangkauan manusia terhadap pengetahuan Islam ke dalam tiga tingkatan. Orang awam hanya bisa menggunakan beberapa fungsi yang diberikan Tuhan untuk memasuki medan perdebatan agama, berbeda dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan akal; begitu pula orang yang telah dianugerai penyingkapan. Ilmu kalam misalnya, dalam al-Iqtisad fi al-I’tiqad, al-Ghazali mengatakan bahwa ilmu ini bagi sebagian orang bermanfaat dan bagi orang lain dapat mendatangkan madarat.
Karena inilah, kita seakan mendapatkan porsi tersendiri ketika membaca al-Ghazali; kita akan menentukan di mana kita akan masuk ke dalam rumah besar, juga keluar menuju suatu dunia yang sangat besar. Al-Ghazali memberikan kita pilihan sesuai kapasitas masing-masing. Sebab dia memosisikan diri berada di ruang antara, di dihliz, untuk melihat orang-orang yang berada di dalam rumah, sekaligus orang-orang yang berada di dunia luar; atau orang-orang yang berorientasi eksoteris dengan esoteris.
Selama ini kita kesusahan memasuki seluruh bangunan pemikiran beliau. Sebab adanya semacam dualitas, ketidak-konsistenan dalam argumen. Di beberapa tempat ia mendukung suatu pemikiran, di tempat lain ia menolaknya. Di satu tempat ia menggunakan pemahaman logika, di tempat lain ia sangat ketat menggunakan riwayat. Ini, bagi Ibrahim Moosa, tidak bisa hanya menggunakan logika dualitas untuk melihat al-Ghazali. Sebab dia selalu memosisikan diri di ruang antara, tergantung pandangannya sedang mengarah ke dalam rumah atau ke dunia luar.
Bagi Ibrahim Moosa sendiri, dia membangun tesis ini untuk menyimpulkan bagaimana al-Ghazali diterima hampir seluruh manusia, bahkan jika merujuk Montgomary Watt, menjadi orang kedua setelah Nabi Muhammad yang paling berpengaruh dalam sejarah umat Islam. Ini karena ide-idenya bisa diterima dari orang dari derajat mana pun.
Jika kita membalik logikanya, pemikiran al-Ghazali tidak bisa disejajarkan dalam satu rentang waktu: pemikiran terdahulu dihapus dan ditentang pemikiran yang terbaru. Bagi Moosa, ini menandakan, kita mesti menggunakan pemikiran al-Ghazali yang luas itu dalam konteks kita masing-masing, apakah sedang berada di dalam rumah atau di luar, apakah kita sedang mencari peribadatan zahir atau batin; atau justru kita sedang berada di ruang antara itu sendiri. (RM)