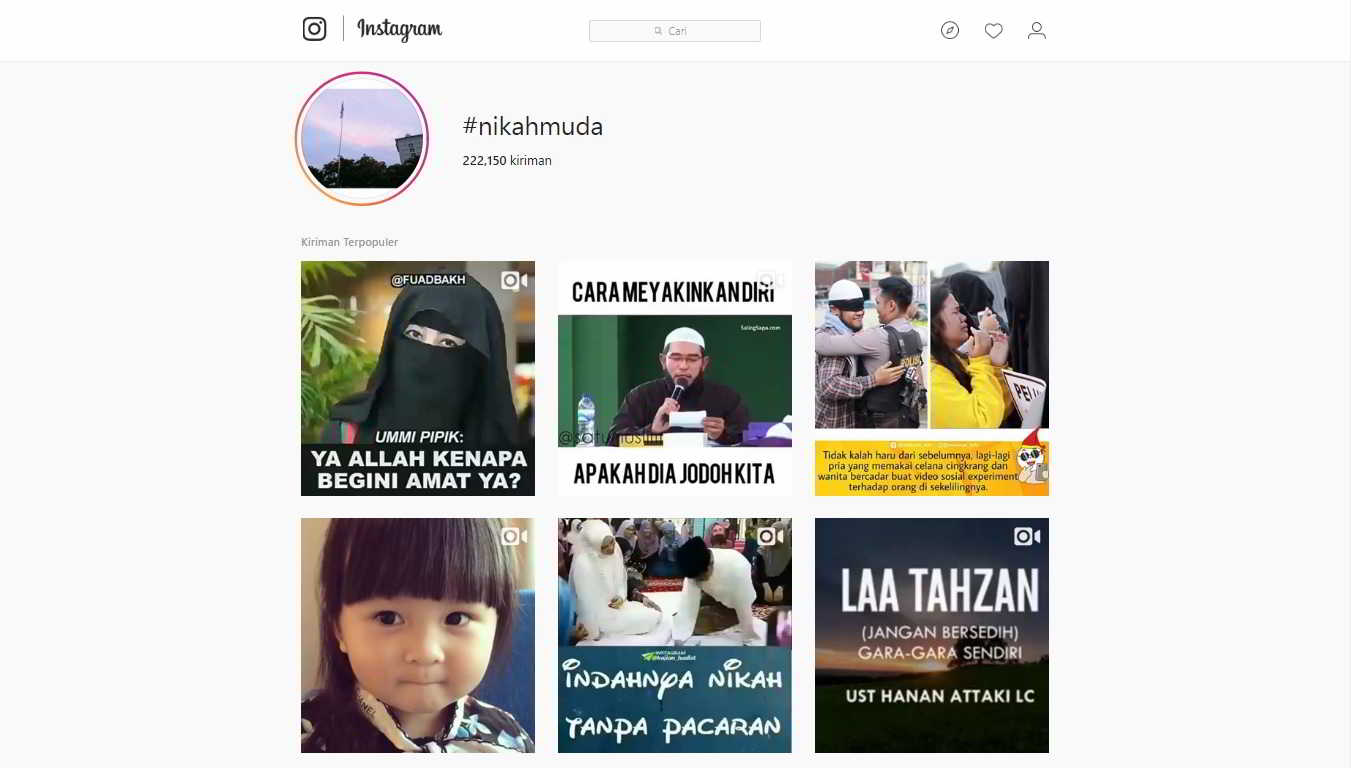Jika kita ditanya, siapakan yang membantu KH. Hasyim Asy’ari dalam mendidikan putra-putrinya? Sudah barang tentu jawabannya adalah sang istri, Nyai Hj. Nafiqah. Sosok ibu yang melahirkan para tokoh yang membawa pesantren kepada dunia yang berkemajuan.
Peran seorang istri dalam memberikan pendidikan pertama untuk anaknya telah menjadi sebuah hikmah dalam Islam, sehingga muncullah adegium “الأُمُّ هِيَ المَدْرَسَةُ الأُوْلَى” seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anaknya. Peranan inilah yang dinilai sebagai bantuan berharga bagi seorang suami. Oleh karenanya, dalam kitabnya yang menjelaskan tentang pernikahan “dlau al-mishbah” pada bab akhir, Kiai Hasyim mengutip hadis yang disampaikan Rasulullah dalam dalam khutbah haji wada’nya, yang sebagaian penggalannya adalah “فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ“ Sesungguhnya mereka (para istri) hanyalah penolong bagimu. Peran di balik layar Nyai Nafiqah inilah yang belum banyak diketahui secara umum.
Bu Nyai Nafiqah dikenal sebagai sosok yang cerdas dan berpikiran maju. Para guru sepuh pesantren Tebuireng (pengajar Madrasah Salafiyah Syafi’iyah era 50-60 an yang mendapat cerita dari para gurunya di Tebuireng) bercerita bahwa Bu Nyai Nafiqah telah dinilai sebagai sosok yang modern pada zamannya. Salah satu buktinya, Bu nyai Nafiqah mampu menguasai bahasa Inggris. Hal ini beliau peroleh karena Bu Nyai Nafiqah tumbuh besar dalam didikan keluarga kiai yang ningrat, mengingat Nyai Nafiqah adalah putri Kiai Ilyas Sewulan Madiun, keturunan dari Kiai Ageng Basyariyah, seorang ulama kharismatik yang memiliki hubungan dekat dengan Pakubuwono II. Berikut ini akan dijelaskan latarbelakang keluarga secara singkat.
Lahir dari Keluarga Kiai yang Ningrat
Kiai Ageng Basyariah atau dikenal dengan nama lain Raden Mas Bagus Harun adalah putra dari Pangeran Nolojoyo, seorang adipati Ponorogo di akhir abad ke 17 M, masa kerajaan Mataram. Dengan kehidupan yang serba kecukupan dan besar di keluarga ningrat, Bagus Harun ternyata lebih memilih untuk mendalami agama Islam di bawah asuhan Kiai Ageng Muhammad Hasan Besari di Pesantren Tegalsari, Ponorogo.
Di sana, Bagus Harun belajar dengan baik, hingga ia dipandang sebagai santri yang paling sakti. Karena alasan ini, ia diminta gurunya untuk mengawal Pakubuwono II kembali ke kerajaan saat terjadinya pemberontakan Mataram. Dengan kesaktiannya, Bagus Harus mampu mengalahkan pemberontak itu.
Sebagai tanda terima kasih, Bagus Harun dihadiahi sebidang tanah kamardikan, payung songsong, dan lampit (tikar yang terbuat dari rotan). Pakubuwono II lantas memberikan gelar Bagus Harun dengan sebutan Kiai Ageng Basyariyah.
Ketika tiba di Ponorogo, Kiai Ageng Basyariyah membuang hadiah payung songsong dan lampitnya, karena ia tidak ingin keturunannya nanti sibuk memikirkan dunia. Karena dalam tradisi kerajaan Jawa, payung songsong merupakan simbol prestis sebagai penanda derajat dan tingkat jabatannya dalam struktur pemerintahan. Hal ini bisa dilihat dalam foto raja-raja, pasti selalu didampingi oleh payung songsong. Ketika Kiai Ageng Hasan Besari mengetahui hal itu, Kiai Ageng Basyariyah pun diperintahkan sang guru untuk mencarinya hingga dapat, sebagai syarat membuka lahan di tanah kamardikan di Madiun. Hingga akhirnya Kiai Ageng Basyariyah berhasil menemukannya tepat di saat malam lailatul qadar, malam yang lebih baik dari serubu bulan. Tanah kamardikan yang dibabat oleh Kiai Ageng Basyariyah akhirnya dinamai Desa Sewulan, yang berasal dari sewu ulan (seribu bulan).
Kiai Ageng Basyariyah lantas membangun masjid dan pesantren di desa tersebut, dengan harapan kelak akan memiliki keturunan yang alim.
Cita-cita luhur para leluhur
Memiliki anak turun menjadi kiai yang negarawan, atau ulama yang umara ternyata telah dicita-citakan oleh leluhur Bu Nyai Nafiqah. Cita-cita tersebut terungkap ketika Kiai Ageng Basyariyah membangun masjid dan pondok pesantren, beberapa saat setelah beliau membuka Desan Perdikan Sewulan tahun 1742. Kiai Ageng Basyariyah turun langsung dalam proses pembangunannya, dibantu oleh sang menantu, Raden Mas Muhammad Santri, Tumenggung Alap-Alap Kuncen, Caruban, Madiun.
Saat proses membangun masjid, Kiai Ageng Basyariyah menginginkan letak masjid didirikan di selatan pengimaman, dengan harapan kelak anak turunnya dapat menjadi seorang yang alim (ulama). Namun sang menantu, Kiai Muhammad Santri, menginginkan letak pengimaman di sebelah utara, dengan harapan keturunannya kelak menjadi negarawan yang dihormati (umara).
Akhirnya disepakati pengimaman masjid dibangun di tengah-tengah. Sehingga kedua harapan tersebut dapat disatukan, anak turunnya nanti dapat menjadi ulama yang umara. Hal ini bisa dilihat dari keturunan Nyai Naqifah yang beberapa menjadi ulama yang umara, seperti KH. Abdul Wahid Hasyim, KH. M. Yusuf Hasyim, KH. Abdurrahman Wahid, dll.
Mendidik putra-putrinya berpikiran maju
Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dalam kitabnya Dlau’ al-Mishbah menjelaskan adab kesebelas dari empat belas adab seorang perempuan adalah : مُشْفِقَةٌ عَلَى أَوْلَادِهَا Sayang kepada anak-anaknya. Salah satu bentuk rasa sayang terhadap anak adalah memberikan pendidikan yang baik. Di lingkungan pesantren, Bu nyai nafiqah terhitung sebagai sosok yang memiliki pemikiran yang maju, melebihi pemikiran para Bu Nyai pesantren pada zamannya. Setidaknya begitulah gambaran yang ditangkap oleh Gus Dur sebagai cucunya yang kala itu menjabat sebagai sekretaris umum pesantren Tebuireng pada medio 1973-1978-an, yang dibagikan kepada Drs. H. Muhsin KS, M.Ag (Pak Muhsin), Wakil Rektor II UNHASY Tebuireng.
Sebagai madrasah pertama, Nyai Nafiqh mendidik para putra putrinya agar dapat berpikir maju. Maka tidak heran meskipun kiai Wahid tumbuh besar di kalangan pesantren yang masih dipandang sebagai kelompok tradisional oleh banyak orang, ternyata mahir bahasa Inggris (di samping bahasa Arab) dan baca tulis latin dengan baik.
Apa yang dilakukan Nyai Nafiqah dengan mendidikan anak-anaknya belajar bahasa asing dan baca tulis latin, akan menjadi wajar mengingat Nyai Nafiqah berasal dari keluarga priyayi (bumiputra) yang pada zaman itu kebanyakan mengirim anaknya ke sekolah milik Pemerintah Hindia Belanda. Lihat saja KH. Muhammad Ilyas, putra Nyai Mardliyyah, kakak perempuan Nyai Nafiqah, yang mendapatkan pendidikan dasarnya di HIS (Hollands Indische School) di Bubutan Surabaya. Muhammad Ilyas muda memungkinkan untuk mengenyam pendidikan di sekolah Belanda yang dikhususkan bagi anak pribumi dari golongan bangsawan dan pegawai negeri tersebut, karena sang ayah yang bernama KH. Qulyubi Probolinggo memang seorang kiai penghulu. Setelah lulus, kakak sepupu Kiai Wahid Hasyim ini lantas melanjutkan belajar di Pesantren Tebuireng. Selama di Tebuireng Muhammad Ilyas muda bersama Wahid Hasyim yang lebih muda tiga tahun, melanjutkan belajar bahasa asing, Inggris dan Belanda.
KH. Wahid Hasyim dan KH. Muhammad Ilyas berupaya untuk menghadirkan sebuah pembaharuan di dunia pesantren. keduanya berhasil mencetak kader santri progresif dengan pikiran inklusif yang sangat handal dalam dunia pergerakan dan organisasi. Para kader Kiai Wahid ini lantas mengisi pos kepengurusan HBNO (PBNU) di masa-masa awal pembentukannya, seperti KH. Mahfudz Shiddiq, dan KH. Abdullah Ubaid. Selanjutnya, kedua kiai muda progresif ini mendirikan Madrasah Nidlamiyah di tahun 1934, dengan komposisi kurikulum 30 persen agama, dan 70 persen umum.
Dari sekolah inilah terlahir para santri yang memberikan sentuhan pembaharuan dalam dunia pesantren, seperti KH. Ahmad Shiddiq dan KH. Karim Hasyim, sosok yang mengenalkan mesin ketik kepada KH. Muchit Muzadi ketika masih mondok di Tebuireng. Belum lagi kader Kiai Wahid yang lain, seperti KH. Masykur, KH. Wahib Wahab, KH. Fatah Yasin, dan KH. M. Dahlan yang semuanya adalah ulama yang menduduki jabatan Menteri mulai Kabinet Amir Syarifuddin II hingga Kabinet Pembangunan. Sebagaimana KH. Wahid Hasyim dan KH. Muhammad Ilyas yang terlebih dahulu menjadi menteri dalam kabinet sebelumnya.
Sebagai orang yang berasal dari pesantren, Kiai Wahid juga tidak canggung untuk memakai jas dan celana laiknya orang barat. Meskipun kiai Wahid tidak pernah mengenyam pendidikan barat, seperti Bung Hatta, Sultan Syahrir, H. Agus Salim dll. Meskipun begitu, gaya berpakaian yang menyerupai Belanda ini telah membuka perdebatan di kalangan kaum sarungan. Lebih-lebih sang ayah, hadratussyaikh sendiri sempat menentang gaya fashion kiai Wahid, Karena dinilai tasyabbuh dengan penjajah. Sebagai intelektual excellent kaum pesantren, pendapat kiai Hasyim tentang larangan berpakaian yang menyerupai penjajah ini didengar oleh kaum pesantren secara umum. Dengan berdalil man tasyabbaha bi qaumin fahuwa minhum, larangan ini menjadi bentuk propaganda dan perlawanan secara kultural kepada penjajah. Kiai Wahid Hasyim yang mempunyai alasan agar lebih diterima oleh kalangan luas, dan harus merepresentasikan orang pesantren di tingkat nasional, akhirnya Hadratussyaikh pun mengizinkannya.
Sebagaimana Kiai Wahid, pemikiran modern Bu Nyai Nafiqah juga turut mewarnai pemikiran putri keduanya, Nyai Khoiriyah Hasyim. Dari kecil, Bu Nyai Khoiriyah telah mendapatkan pendidikan pertamanya dari sang ibu. Selain itu, Nyai Hj. Khoiriyah juga mendapatkan masukan dari ibunya, agar turut serta dalam pengajian Hadratussyaikh yang disampaikan di masjid Pesantren Tebuireng, dengan cara mengikutinya di belakang tabir. Dari sini lah Bu Nyai Khoiriyah di kemudian hari lantas memperjuangkan pendidikan untuk kaum perempuan. Yang paling diingat kaum pesantren adalah tatkala Nyai Khoiriyah mendirikan Madrasah Lil Banat, madrasah pertama di Arab Saudi yang diperuntukkan bagi anak perempuan. Atas kiprah beliau inilah, akhirnya Nyai Khoiriyah mendapatkan penghargaan khusus dari Raja Saudi Arabia berupa sebuah cincin.
Memang sepeninggal suaminya, KH. Ma’shum Aly, Nyai Khoiriyah sempat bermukim di Saudi Arabia setelah menikah kembali dengan KH. Abdul Muhaimin Lasem yang terlebih dahulu mukim di Negara Raja Ibn Saud itu. Setelah menikah (dengan akad nikah yang diwakili oleh KH. Baidlowi bin Abdul Aziz, kakak kandung Kiai Muhaimin), KH. Muhaimin memohon izin untuk dapat mengajak Nyai Khoiriyah menetap di Makkah. Untuk itu, Nyai Khoiriyah harus meninggalkan kedua putrinya yang masih kecil di Seblak. Nyai Khoiriyah pun menerima permohonan itu. Untuk menerima keputusan besar tersebut, tentu tidak akan mudah jika Nyai Khoiriyah tidak memiliki pemikiran maju.
Usaha batiniyah untuk putra-putrinya
Meskipun Nyai Nafiqah memiliki pemikiran yang melampaui zamannya, namun tetap saja beliau adalah anak seorang kiai yang dibesarkan di lingkungan pesantren. Dalam usaha mendidik anaknya, Nyai Nafiqah juga menggunakan pendekatan batiniyah, tirakat dan mujahadah. Salah satunya adalah dengan wasilah bacaan asma’ul husna, dan wiridan di sepertiga malam. Dr. KH. A. Musta’in Syafi’ie pernah bercerita betapa kuatnya Nyai Nafiqah saat wiridan di sepertiga malam. Ketua Dewan Masyayikh Pesantren Tebuireng itu menjelaskan mujahadah yang dilakukan Nyai Nafiqah diperuntukkan bagi keluarga, anak keturuan, serta semua santri Tebuireng. Juga agar kemanfaatan Pesantren Tebuireng dapat dirasakan oleh semuanya. Ada yang unik dalam cara wiridan Nyai Nafiqah di sepertiga malam. Saat wiridan, beliau pasti membawa sepiring kacang hijau yang telah dicampur dengan batu krikil. Sambil lisannya berdzikir, Nyai Nafiqah memilih biji kacang hijau, satu per satu, memilahnya dari batu krikil. Tujuannya hanya satu, agar wiridnya tutuk (selesai), tidak kalah oleh kantuk.
Selain mujahada, Nyai Nafiqah juga usaha tabarruk, ngalap berkah kepada para kiai. Hal ini dapat dilihat ketika Kiai Wahid Hasyim yang masih berusia tiga bulan dibawa oleh Nyai Nafiqah pergi ke Madura untuk menemui Syaikhana Khalil Bangkalan, untuk memenuhi nazar yang dibuat karena Kiai Wahid lahir dalam keadaan sehat.
Saat pergi ke Madura, Nyai Nafiqah ditemani oleh Mbah Abu dengan menaiki Kereta Api. Setelah sampai di Madura Nyai Nafiqah menaiki kendaraan Dokar. Perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki melaju pesantren Syaikhana Khalil. Tekad kuat Nyai Nafiqah untuk tabarukan ini tidak pudar meski mengharuskannya menunggu lama. Ketika turun hujan, Syaikhana Khalil justru tidak mengizinkan Nyai Nafiqah yang sedang menggendong Kiai Wahid untuk masuk ke rumahnya, atau hanya sekedar berteduh di serambi rumah. Bahkan Syaikhana Khalil menyuruhnya untuk tetap berada di luar, hingga semua kehujanan. Mungkin karena tabarruk dengan Syaikhana Khalil inilah Kiai Wahid mendapatkan umur yang berkah. Meskipun meninggal di usia 39 tahun (1914-1953), namun beliau telah menduduki beberapa jabatan strategis di NU dan Pemerintahan dengan segudang prestasi. Peran pentingnya untuk pesantren dan Indoensia tidak dapat disangkal.
Memberikan menu makanan bergizi untuk guru Tebuireng
Hadratussyaikh KH. Hasyim Asy’ari dalam kitabnya Dlau’ al-Mishbah menjelaskan adab kedua dari empat belas adab seorang perempuan adalah لَازِمَةٌ فِي شُغْلِ بَيْتِهَا, Mengurus segala urusan rumah tangga. Peran ini agaknya dimainkan oleh Nyai Nafiqah dengan baik sekali, yaitu memberikan Selain itu, Pak Muhsin, membagi cerita para pengajar madrasah salafiyah Syafi'iyah generasi awal yang mengenang kiprah Nyai Nafiqah dalam menyiapkan menu makanan untuk para guru di pesantren Tebuireng, seperti Kiai Syamsuri Zen yang pernah menjadi kepala sekolah Madrasah Salafiyah Syafi’iyah tahun 60-an, dan Kiai Mahsun Kayangan, seorang guru madrasah tersebut.
Saat masih zaman penjajahan Belanda, antara tahun 1900 hingga 1920, Bu Nyai Nafiqah telah memberikan telur sebagai menu wajib. Perlu diingat bahwa di tahun-tahun tersebut, Pabrik Gula Cukir sebagai perusahaan milik Belanda yang bonafit, tidak pernah menyediakan makan siang untuk pegawainya. Dan kala itu, sebagian besar penduduk Jawa masih menjadikan nasi jagung, singkong dan tiwul sebagai makanan pokok sehari-hari. Maka telur akan nampak menjadi menu istimewa bagi para guru Tebuireng. Baki telur (tempat telur) yang menumpuk di dapur pesantren dapat dilihat para guru. Setelah seminggu, baki telur mulai menumpuk, barulah baki-baki tersebut dibuang. Sarapan untuk para guru biasanya dihidangkan mulai jam 10.00 saat istirahat. Tujuan yang dikemukakan nyai nafiqah sangat sederhana. Pada jam-jam itu, tentu para guru telah mulai merasa lapar, dengan hidangan nasi dan telur, diharapkan para guru bisa semangat kembali untuk mengajar pada sesi yang kedua.
Selain telur, Bu Nyai Nafiqah juga memberikan menu susu sapi untuk para guru Madrasah Salafiyah Syafi'iyah. Susu tersebut diperah dari sapi-sapi Kiai Hasyim sendiri. Sebagian pakannya dipasok dari tetangga pesantren yang memproduksi tahu, rumahnya terletak di sebelah barat Pesantren. Ampas tahunya lantas diminta oleh Kiai Hasyim untuk pakan sapinya. Dalam seminggu, Kiai Hasyim dapat kiriman ampas tahu lima hingga enam kali. Dari sini, kita bisa lihat perhatian Bu Nyai Nafiqah dalam hal pemenuhan kebutuhan gizi untuk para guru pesantren Tebuireng. Sebuah hal yang masih dinilai mahal dan jarang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Mengingat zaman itu, Indonesia masih di bawah penjajahan Belanda. Namun dengan pemikiran majunya, Bu Nyai Nafiqah mampu mengelola menu makan para guru dengan standar menu yang istimewa di zamannya.
Dalam pandangan banyak guru sepuh Tebuireng, Bu Nyai Nafiqah dengan kecakapannya sangat pantas menjadi Bu Nyai pesantren besar, mendampingi KH. Haysim Asy'ari sebagai tokoh Islam dalam lingkup nasional. Pemikiran majunya telah mewarnai pemikiran putra putrinya. Yang mana pada gilirannya, mereka berhasil menghadirkan pembaharuan, serta mengubah wajah pesantren menjadi lebih inklusif. Yang juga berhasil melahirkan kader-kader kiai yang cakap di bidang pergerakan nasional. Maka kiranya tak berlebihan jika Bu Nyai Nafiqah disebut sebagai ibu para pembaharu pesantren. Sepanjang hayatnya, Bu Nyai Nafiqah telah memberikan sepuluh putra-putri kepada KH. Hasyim Asy’ari, sebelum meninggal pada tahun 1920. Allah Yarhamuha.