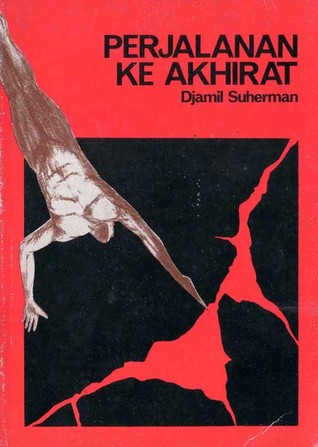Pada 1955-1965, Djamil Suherman banyak menulis tentang kebudayaan pesantren di Indonesia. Tulisan-tulisan itu pernah bersebaran di berbagai majalah Kisah, Sastera, Indonesia, Budaya, Mimbar Indonesia, dan Siasat (Gelanggang). Hidup dan dibesarkan di lingkungan pesantren, membuat gagasan Djamil Suherman sering menarasikan sastra Islam, kebudayaan lokal, dan nasionalisme di berbagai karya sastranya.
Gagasan tersebut dapat kita simak di beberapa karangan prosa maupun puisi yang pernah terbit di Indonesia. Beberapa prosa Perjalanan Ke Akhirat (1985), Sakerah (1985), Pejuang-Pejuang Kali Pepe (1984), dan kumpulan puisi Nafari (1983), Kabar Dari Langit (1988) kebanyakan menyoalkan isu-isu agama tahun 1980-an. Karya tersebut diterbitkan oleh penerbit Pustaka yang pada masa itu memang bertujuan melahirkan buku-buku agama.
Kehadiran karya-karya itu kini menjadi bukti keberhasilan Djamil Suherman untuk mendokumentasikan sejarah tentang tradisi pesantren tradisional dan pengalamannya sebagai santri.
Di antara berbagai karya Djamil Suherman, yang membahas kesejarahan pendidikan di pesantren adalah Pejuang-Pejuang Kali Pepe (1984). Prosa itu mengisahkan pergolakan para kiai dan santri masa kolonialisme di Indonesia.
Narasi Djamil Suherman dalam prosa itu tidak lepas dari pembentukan nasionalisme, perjuangan, perlawanan yang dilakukan santri dan kyai. Mereka memperjuangkan tanah air dengan darah dan tenaga tatkala penggusuran tanah oleh pasukan kompeni (gubernemen) secara paksa.
Ketokohan yang dibentuk oleh Djamil Suherman dalam memperjuangkan tanah air begitu realistis. Kiai Mukmin selaku sesepuh di pesantren Gedangan di pinggiran kali Pepe, menjadi pemangku kebijakan yang memiliki otoritas dalam menentukan sikap, peraturan, dan kekuatan bagi para santri.
Kiai menjadi tokoh penting sebagai pedoman dalam menyikapi berbagai persoalan agama dan sosial. Maka ketika kebijakan dari gubernemen memerintahkan untuk mengosongkan tanah di pesantren, Kiai Mukmin engan menerima dan memilih melaksanakan jihad demi mempertahankan pesantren, kebudayaan, dan tradisi norma sosial.
Keputusan jihad sang Kiai Mukmin begitu mempengaruhi para santri untuk mengikuti jejak sang kiai. Ratusan santri yang dipimpin Muhammad, Asad, Umar, Ismail, dan Ridwan hanya berbekal senjata tradisional bambu dan panah. Mereka merasakan begitu pentingnya membela tanah air demi menjaga tanah pesantren dari penggusuran.
Pertempuran dan penggusuran itu telah menyisakan darah dan kehancuran. Kiai Mukmin dan para santri banyak yang gugur dalam pertempuran melawan pasukan kolonial demi membela kebenaran.
Mengingat
Narasi Djamil Suherman dari karya-karyanya mengingatkan kita pada kesadaran membela tanah air untuk menyebarkan dakwah agama. Lewat lakon santri dan kyai, kita diajak untuk mengingat kembali perjuangan dari kisah pesantren. Meski kini pesantren telah menjadi ruang pendidikan yang mengalami modernisasi, namun beberapa pesantren masih mengajarkan pendidikan kebudayaan lokal.
Di situlah Djamil Suherman ingin membahas betapa pentingnya kesadaran kebudayaan lokal tersebut. Maka bila kita mencermati dalam karya-karyanya, selain mempersoalkan nasionalisme, Djamil selalu menyisipkan masalah kebudayaan yang ada dalam kehidupan pesantren.
Mulai dari kisah kehidupan rutinitas santri, kisah asmara, silat, ngaji kitab, dan sholawat menjadi cara Djamil untuk menggambarkan kehidupan pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berorientasi menyebarkan dakwah agama dengan budaya.
Kesadaran Djamil Suherman pada prosa maupun puisinya tidak pernah menyinggung persoalan politik di pesantren. Ia seolah menjauhkan persoalan politik dari ranah pendidikan pesantren atau malah tidak menemukan persoalan politik pada masa ia menjadi santri. Hal itu begitu jelas ketika Jalaluddin Rakhmat memberikan kata pengantar di novel Pejuang-Pejuang Kali Pepe (1984).
Jalaluddin Rakhmat merasakan perubahan peradaban sistem pendidikan di pesantren mulai tampak sejak tahun 1980-an. Dahulu Jalaluddin Rakhmat sangat mengagumi tokoh kiai dan santri akan kesederhanaan dan ketaatan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada masa lalu. Namun Jalaluddin merasakan dilematis terhadap pesantren yang kini mengalami modernisasi dan berpolitik hingga berdampak kurangnya kesadaran menjaga tradisi pendidikan tradisional dan kebudayaan lokal. Hal itu terjadi lantaran peran kiai dan santri di pesantren memiliki kesibukan berlipat, mengajarkan ilmu dan berpolitik. Kehadiran partai politik di lingkungan pesantren demi mendapat suara tentu sangat mempengaruhi orientasi paradigma pembelajaran di pesantren.
Kita bisa melacak kehadiran partai politik yang memperebutkan suara pesantren di Majalah Tempo edisi 21 Februari 1987. Partai politik Golkar dan PPP saling berebut suara di berbagai pesantren NU untuk memenangkan Pemilu 1980-an. Fenomena beralihnya orientasi politik beberapa pesantren NU di Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur memilih Golkar disebabkan kekecewaan terhadap ulah pemimpin PPP yang tidak mampu memberikan kesejahteraan pesantren.
Hal tersebut dimanfaatkan oleh Sudharmono selaku Ketua Umum DPP Golkar untuk mendapatkan suara dari pesantren NU. Suara dari beberapa pesantren yang telah menerima Golkar salah satunya dari Roudlotun Nasyi’in, Berak Kulon, Mojokerto. Pernyataan itu disampaikan oleh Syihabul Irfan, putra K.H. Mohammad Arif yang mengatakan Golkar lebih banyak memberikan bantuan yang menguntungkan pada umat Islam. Keberhasilan Golkar dalam Pemilu 1980-an, telah tercatat oleh Departemen Agama (1982) bahwa di seluruh Indonesia hampir 5.000-an pesantren telah berhasil memilih partai beringin.
Kehadiran misi politik di lembaga pendidikan pesantren tidak pernah disinggung oleh Djamil Suherman dalam karya sastranya. Meski realitasnya kebanyakan pesantren memiliki misi politik, Djamil sebagai seorang santri seolah engan terlibat dalam manifestasi politik pesantren.
Ia lebih menerima bahwa pesantren hanya sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia yang mampu mengajarkan, kisah nasionalisme, kebudayaan lokal, dan norma-norma sosial. Kesadaran itu yang terasa Djamil ungkapkan kepada masyarakat Indonesia dan para pembaca sastra.