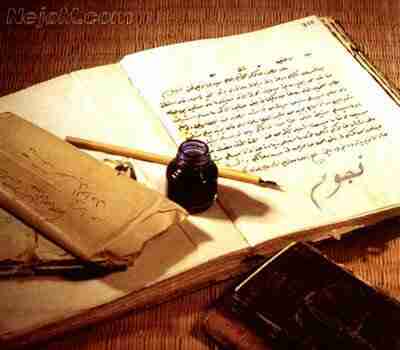Bayang-Bayang Kekuasaan: Kisah Politik Jatah Preman di Indonesia

Pada Mei 1998, Jakarta adalah lautan kemarahan yang membara. Asap dari ban-ban yang terbakar mengepul ke langit, teriakan reformasi mengguncang jalanan, dan gedung-gedung megah Orde Baru menjadi saksi bisu kerusuhan yang menggoyahkan fondasi kekuasaan. Di tengah halai-balai itu, sekelompok pria bertubuh tegap dengan lengan bertato bergerak seperti bayang-bayang di antara kerumunan. Mereka bukan polisi, bukan pula tentara, melainkan preman—penutur bahasa kekerasan jalanan yang di Indonesia masyhur sebagai penguasa dunia bawah.
Dengan tongkat besi dan tatapan yang membekukan, mereka mengintimidasi demonstran, menjaga kepentingan elite yang mulai rapuh. Tatkala Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri, dunia mengira preman akan lenyap bersama reruntuhan rezimnya. Namun, laksana air yang selalu menemukan celah, mereka beradaptasi, menyelinap ke dalam demokrasi baru yang rapuh, membawa warisan kekerasan yang telah mengakar berabad-abad.
Kisah preman bukan sekadar catatan pinggir tentang otot dan ancaman. Ini adalah genealogi sebuah sistem kekuasaan yang telah membentuk politik Indonesia sejak zaman kerajaan hingga era modern: politik jatah preman. Istilah “politik jatah preman” ini saya pinjam dari buku yang sangat menarik karya Ian Douglas Wilson, Politik Jatah Preman: Ormas dan Kuasa Jalanan di Indonesia Pasca Orde Baru (2021). Dalam sistem ini, elite politik memberikan “jatah”—hak ekonomi, politik, atau sosial—kepada aktor kekerasan sebagai imbalan atas loyalitas. Kekerasan bukan lagi kekacauan, melainkan alat yang diatur dengan cermat, disalurkan dalam simfoni kekuasaan nan rumit.
Fenomena ini bukan khas Indonesia. Ia memiliki paralel global: dari condottieri (kapten) di Italia Renaissance hingga mesin politik Chicago abad ke-20, dari milisi di Timur Tengah modern hingga goonda (gangster) di India pasca-kolonial. Di mana pun kekuasaan bertahta, bayang-bayang kekerasan selalu mengintai—setia sekaligus mengancam, sekutu sekaligus musuh.
Patronase Pra-Kolonial
Politik jatah preman berakar pada kerajaan-kerajaan pra-kolonial Nusantara, seperti Majapahit (abad ke-13–15) dan Mataram (abad ke-16–17). Kekuasaan raja bergantung pada jaringan bangsawan lokal dan pemimpin bersenjata yang dikenal sebagai satria atau babadan. Mereka bukan sekadar prajurit, melainkan pengelola wilayah yang menggunakan kekerasan untuk menegakkan otoritas raja, memungut upeti, atau menumpas pemberontakan.
Sebagai imbalannya, mereka menerima “jatah”—tanah, hasil panen, atau hak perdagangan, seperti monopoli rempah-rempah di pelabuhan Banten atau Ternate. Antropolog Clifford Geertz menyebut sistem ini sebagai “teater negara”, di mana kekerasan diatur dalam tarian patronase yang rumit. Satria memiliki otonomi, tetapi hanya selama mereka setia kepada raja. Ketika Majapahit melemah pada abad ke-15, banyak satria berbalik melawan pusat, menjadi “bajak laut darat” yang menguasai wilayah pinggiran, seperti yang dicatat dalam Babad Tanah Jawi.
Sistem ini mencerminkan dinamika universal kekuasaan pra-modern. Di Eropa feodal, ksatria atau baron lokal di Inggris dan Prancis menerima tanah dari raja sebagai imbalan atas layanan militer, namun sering memberontak ketika pusat melemah, seperti selama Perang Mawar (1455–1487). Di Tiongkok kuno, dinasti Han (206 SM–220 M) mengandalkan panglima perang lokal untuk menjaga perbatasan, memberikan otonomi yang kerap berujung pada pemberontakan. Baik di Nusantara, Eropa, maupun Tiongkok, kekerasan terorganisir adalah alat kekuasaan sekaligus ancaman laten. Ketegangan antara pusat dan pinggiran ini mengisyaratkan kerapuhan kekuasaan: loyalitas dibeli dengan jatah, tetapi otonomi mengundang pengkhianatan.
Jago dan Kontrak Kekerasan
Kedatangan Belanda pada abad ke-17 mengubah lanskap kekerasan di Nusantara, tetapi tidak menghapus akar patronase pra-kolonial. Di pelabuhan Batavia yang ramai, Belanda menghadapi tantangan besar: mengendalikan wilayah luas dengan sumber daya terbatas. Untuk itu, mereka mengandalkan jago—pemimpin lokal yang menguasai kampung dengan otot, karisma, dan koneksi. Sering kali keturunan satria atau petani kaya, jago menjadi perantara antara penguasa kolonial dan rakyat, memungut pajak, menjaga ketertiban, dan menghentikan pemberontakan, seperti pemberontakan petani Banten tahun 1750. Sebagai imbalannya, mereka menerima “jatah”—tanah, uang, atau hak monopoli perdagangan, seperti pasar opium atau hasil bumi.
Sistem ini, sebuah “kontrak sosial bayang-bayang,” memungkinkan Belanda mempertahankan kekuasaan tanpa kehadiran militer yang kuat. Akan tetapi, jago adalah sekutu yang oportunis. Ketika Inggris mengambil alih Jawa pada 1811–1816, banyak jago beralih kesetiaan, menunjukkan pragmatisme yang menjadi ciri preman modern. Tahun 1740, jago di Batavia terlibat dalam pemberontakan Tionghoa, memaksa Belanda memperketat kontrol, tetapi tidak menghapus ketergantungan pada mereka.
Paralel global terlihat jelas. Di Italia Renaissance, condottieri—tentara bayaran yang dipekerjakan oleh kota-negara seperti Venesia—menerima “jatah” berupa uang atau hak politik, tetapi sering mengkhianati majikan mereka jika tawaran lebih baik muncul. Di India kolonial, Inggris mengandalkan zamindar—pemimpin lokal yang mengelola pajak dan keamanan—dengan imbalan tanah atau kekayaan, sebuah sistem yang juga rentan terhadap pengkhianatan. Baik di Batavia, Italia, maupun India, aktor kekerasan adalah sekutu yang rapuh, setia hanya selama jatah mereka terjamin. Sistem ini mengungkap kelemahan struktural kekuasaan kolonial: untuk mengendalikan wilayah, Belanda, seperti Venesia atau Inggris, harus merangkul bayang-bayang yang mereka takuti.
Kekerasan di Lautan Revolusi
Proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945 mengubah jago menjadi laskar—pejuang bersenjata yang berjuang melawan Belanda atau, dalam beberapa kasus, bandit yang memanfaatkan kekacauan. Era revolusi (1945–1949) adalah laboratorium kekerasan. Kelompok seperti Laskar Rakyat di Jawa atau Barisan Harimau Liar di Sumatra sering beroperasi di luar kendali pemerintah Republik, menguasai wilayah dengan kekerasan dan memungut “pajak revolusi” dari rakyat. Pemerintah Republik, yang lemah secara militer, terpaksa mengandalkan laskar, memberikan mereka “jatah” berupa senjata, dana, atau hak atas rampasan perang. Namun, setelah kemerdekaan tercapai tahun 1949, banyak laskar menolak dibubarkan. Di Jakarta, kelompok seperti Barisan Banteng bertransformasi menjadi preman yang mengendalikan pasar dan pelabuhan, menantang otoritas negara baru.
Tahun 1950-an, pemerintah Sukarno meluncurkan operasi untuk menertibkan laskar, tetapi banyak yang beralih ke dunia kriminal, menjadi cikal bakal preman modern. Fenomena ini memiliki paralel global. Di Amerika Latin, guerrilleros selama revolusi Meksiko (1910-1920) berjuang untuk kemerdekaan, tetapi sering berubah menjadi bandit setelah perang. Di Afrika pasca-kolonial, seperti Nigeria pada 1960-an, milisi lokal juga menjadi tantangan bagi negara baru, mengisi kekosongan kekuasaan dengan kekerasan. Revolusi Indonesia mengungkap kontradiksi universal dalam pembentukan negara pasca-kolonial: kekerasan diperlukan untuk mencapai kemerdekaan, tetapi kemudian menjadi ancaman bagi negara yang baru lahir.
Puncak Politik
Politik jatah preman mencapai puncaknya di bawah Orde Baru (1966–1998), rezim Soeharto yang dibangun di atas fondasi ketertiban dan ketakutan. Soeharto, seorang jenderal yang pendiam namun licin, memahami bahwa kekuasaan tidak hanya dijaga oleh militer, tetapi juga oleh loyalitas di jalanan. Ali Moertopo, tangan kanan Soeharto dan Kepala Operasi Khusus (Opsus), memainkan peran kunci. Dalam wawancara pada 1972, Moertopo menyebut preman sebagai “tentara tanpa seragam,” sebuah frasa yang mencerminkan pragmatisme dinginnya.
Pada 1970-an, Orde Baru mengorganisasi preman melalui kelompok seperti Pemuda Pancasila, yang menjadi alat politik rezim setelah pembantaian anti-komunis 1965–1966. Dengan seragam oranye-kuning yang mencolok, Pemuda Pancasila menjadi wajah resmi politik jatah preman. Mereka diberi “jatah”—kontrak keamanan, proyek konstruksi, atau hak untuk mengelola pasar malam—sebagai imbalan atas kesetiaan mereka. Antropolog Ian D. Wilson menahbiskan Pemuda Pancasila sebagai “mesin kekerasan” yang memungkinkan Orde Baru menjaga stabilitas tanpa kekerasan langsung dari negara.
Contoh nyata adalah peristiwa Malari 1974, ketika preman dari Pemuda Pancasila dikerahkan untuk membubarkan demonstrasi mahasiswa yang memprotes kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka. Elite kekuasaan bisa mengklaim tangannya bersih, sementara preman menjadi kambing hitam. Sistem ini adalah simfoni yang diatur dengan cermat: preman adalah pemain biola, sementara elit politik memegang batuta.
Namun, simfoni ini memiliki nada sumbang. Politik jatah preman menciptakan monster yang sulit dikendalikan. Pada 1980-an, kelompok-kelompok preman mulai membentuk faksi, bersaing untuk mendapatkan jatah yang lebih besar. Di Jakarta, nama Hercules Rozario Marcal—preman legendaris dari Tanah Abang—menjadi simbol kekuatan jalanan yang hampir tidak tersentuh. Hercules, dengan lengan bertato dan masa lalunya sebagai pejuang di Timor Timur, adalah produk zaman: setia pada kekuasaan, tetapi oportunis yang siap mengkhianati jika jatahnya terancam. Tatkala dia ditangkap pada 1986 atas tuduhan pemerasan, banyak yang melihatnya sebagai peringatan dari rezim bahwa preman harus tahu batasnya.
Politik jatah preman Orde Baru mirip dengan mesin politik Chicago pada abad ke-20, di mana “ward bosses” seperti Richard J. Daley menggunakan geng jalanan untuk mengamankan suara dan menjaga kekuasaan Demokrat. Di Chili era Pinochet (1973–1990), rezim militer juga mengandalkan kelompok paramiliter untuk menekan oposisi, memberikan mereka hak ekonomi sebagai imbalan. Baik di Jakarta, Chicago, maupun Santiago, kekerasan informal diintegrasikan ke dalam sistem politik, memungkinkan elite mempertahankan kekuasaan tanpa noda resmi.
Preman di Era Demokrasi
Tatkala Soeharto jatuh pada 1998, banyak yang berharap politik jatah preman akan ikut runtuh. Reformasi menjanjikan demokrasi, supremasi hukum, dan akhir dari kekerasan politik. Namun, sistem yang mengakar dalam budaya politik tidak begitu saja lenyap. Preman, yang telah menjadi bagian dari ekosistem kekuasaan selama berabad-abad, hanya beradaptasi ke lanskap baru.
Di era reformasi, politik jatah preman menjadi lebih terdesentralisasi. Jika Orde Baru mengelola preman melalui struktur hierarkis seperti Pemuda Pancasila, demokrasi membuka pintu bagi versatilitas baru. Partai politik, yang kini bersaing dalam pemilu, mulai merekrut preman untuk mengamankan kampanye, mengintimidasi lawan, atau memobilisasi massa. Di Jakarta, kelompok seperti Forum Betawi Rempug (FBR) muncul, mengklaim sebagai pembela identitas Betawi sambil beroperasi sebagai preman dengan jatah politik.
Pilkada Jakarta 2017 adalah contoh mencolok. Ketika Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bersaing sengit, kedua kubu dilaporkan menggunakan kelompok preman untuk menggalang dukungan atau mengintimidasi pemilih. FBR dan kelompok serupa menjadi aktor kunci, menawarkan “jasa keamanan” dengan imbalan kontrak proyek atau pengaruh politik. Akan tetapi, reformasi juga membawa perubahan. Preman tidak lagi sekadar pion; mereka menjadi pengusaha kekerasan. Di kota-kota seperti Surabaya atau Medan, preman modern mengelola bisnis parkir, keamanan swasta, bahkan perdagangan narkoba, sambil menjaga hubungan dengan elit politik. Antropolog Joshua Barker menyebut mereka “kapitalis bayang-bayang” yang mengisi celah di mana negara gagal menyediakan keamanan atau layanan publik.
Tokoh seperti John Kei, preman asal Maluku yang mengendalikan jaringan kriminal di Jakarta hingga ditangkap pada 2020 atas kasus pembunuhan, adalah simbol preman modern: setengah pengusaha, setengah penutur kekerasan. Fenomena ini mirip dengan milisi di Timur Tengah, seperti Hashd al-Shaabi di Irak, yang menggabungkan kekerasan politik dengan aktivitas ekonomi seperti perdagangan minyak. Di India pasca-kolonial, goonda juga menjadi alat politik untuk mengamankan suara atau mengendalikan wilayah, sering kali mengelola bisnis ilegal sebagai “jatah.” Demokrasi pasca-konflik, baik di Indonesia, Irak, maupun India, memberikan ruang bagi aktor kekerasan untuk menjadi pengusaha, mengisi kekosongan institusi negara.
Era reformasi mengungkap paradoks demokrasi pasca-kolonial: di satu sisi, ia cukup tangguh untuk menyerap kekerasan tanpa runtuh; di sisi lain, ia gagal membangun institusi yang kuat untuk menggantikan patronase. Premanisme modern adalah cerminan dari ketegangan ini, sebuah tarian abadi antara kekuasaan dan bayang-bayangnya.
Mengapa, setelah berabad-abad sejarah dan dua dekade demokrasi, preman tetap menjadi bagian dari politik Indonesia?
Politik jatah preman bertahan karena lemahnya supremasi hukum. Polisi dan militer, yang seharusnya menegakkan ketertiban, sering kali terlibat dalam jaringan premanisme. Pada 1990-an, laporan Amnesty International mencatat bahwa polisi Jakarta kerap “menyewakan” preman untuk operasi kotor, seperti penggusuran kampung. Hingga kiwari, korupsi dalam institusi penegak hukum memungkinkan preman beroperasi dengan impunitas. Vedi Hadiz menyebut premanisme sebagai “ekstensi logis” dari negara yang gagal menegakkan monopoli kekerasan yang sah. Ini mirip dengan Meksiko modern, di mana kartel narkoba sering bekerja sama dengan polisi korup untuk mengendalikan wilayah.
Premanisme telah menjadi bagian dari imajinasi politik Indonesia. Dalam budaya populer, preman sering digambarkan sebagai pahlawan rakyat. Film-film laga era 1980-an, seperti Si Pitung atau Jaka Sembung, memuliakan preman sebagai penentang ketidakadilan. Di dunia nyata, tokoh seperti Hercules atau John Kei memiliki aura karismatik yang menarik pengikut. Mereka adalah antihero yang, menurut Hadiz, mengisi kekosongan moral di masyarakat yang skeptis terhadap elite. Fenomena ini mirip dengan glorifikasi geng di budaya pop Amerika, seperti dalam The Godfather, atau goonda dalam film Bollywood yang dirayakan sebagai “pahlawan rakyat.”
Premanisme mencerminkan ketegangan antara modernitas dan tradisi. Indonesia, sebagai negara pasca-kolonial, berjuang untuk membangun negara modern dengan institusi yang kuat, tetapi terus bergulat dengan warisan feodal dan patronase. Preman adalah perantara yang menghubungkan dunia formal kekuasaan dengan dunia informal jalanan. Edward Aspinall menyebut mereka “produk dari kontradiksi bangsa” yang ingin melangkah maju, tetapi tetap terikat pada bayang-bayang masa lalunya. Ini mirip dengan India, di mana goonda mengisi kekosongan institusi, atau Afrika Selatan, di mana tsotsi menjadi alat politik di era pasca-apartheid.
Saat Indonesia memasuki dekade ketiga abad ke-21, politik jatah preman menunjukkan tanda-tanda evolusi. Teknologi telah mengubah lanskap. Platform seperti X memungkinkan preman modern membangun citra publik, seperti influencer dengan otot. Kelompok seperti FBR menggunakan akun X untuk memamerkan aksi mereka, dari bakti sosial hingga intimidasi, menciptakan paradoks baru: preman sebagai selebritas. Fenomena ini mirip dengan kartel Meksiko yang memamerkan kekayaan di Instagram atau Hizbullah di Timur Tengah yang mempromosikan citra “pejuang rakyat” di media sosial. Teknologi memperkuat visibilitas aktor kekerasan, tetapi juga membuka ruang bagi pengawasan publik.
Namun, ada harapan untuk perubahan. Gerakan sipil, terutama di kalangan anak muda, mulai menantang politik jatah preman. Demonstrasi mahasiswa pada 2019 melawan revisi UU KPK menunjukkan bahwa generasi baru tidak lagi menerima kekerasan politik sebagai hal yang wajar. Organisasi seperti LBH Jakarta terus mendokumentasikan pelanggaran preman, mendorong akuntabilitas. Di tingkat global, tekanan dari Human Rights Watch untuk reformasi kepolisian dapat membantu mengurangi ketergantungan pada preman.
Arkian, genealogi politik jatah preman adalah kisah tentang kekuasaan, tetapi juga tentang kemanusiaan. Dari satria di kerajaan Mataram hingga preman modern di gang-gang Jakarta hingga di stasiun-stasiun, pelabuhan-pelabuhan hingga pasar-pasar. Mereka adalah aktor dalam drama panjang Indonesia—bukan sekadar penutur kekerasan, tetapi cerminan dari ambisi, kontradiksi, dan harapan bangsa.
Kisah ini bukan hanya tentang Indonesia, tetapi tentang sifat universal kekuasaan. Indonesia, dengan demokrasinya yang rapuh namun tangguh, menawarkan pelajaran: bahwa bayang-bayang kekuasaan hanya bisa diusir dengan keberanian untuk membayangkan dunia yang lebih adil. Seperti yang pernah dikatakan Tan Malaka, “Kemerdekaan bukan akhir, tetapi awal dari perjuangan.” Dalam perjuangan itu, preman mungkin masih menjadi bayang-bayang, tetapi cahaya harapan—dalam bentuk generasi anyar yang menuntut akuntabilitas—mulai menyelinap masuk.