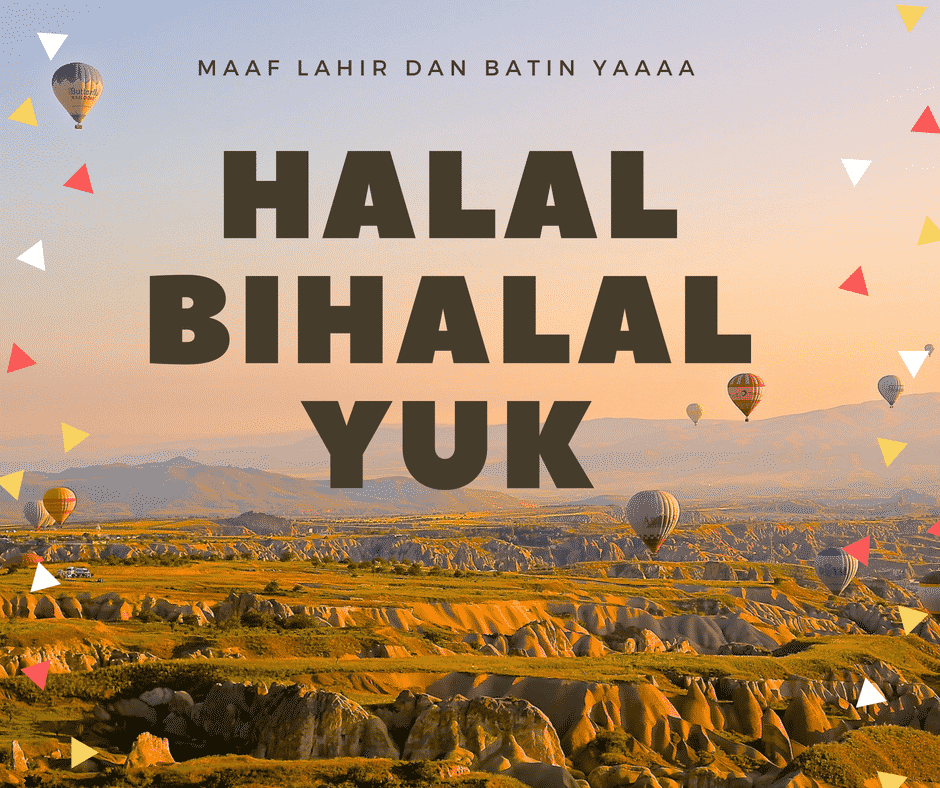Salah satu frasa kunci orang-orang hebat di masa lalu, terutama ulama sufi, di dalam menjalani kehidupan ini adalah konsep “tidak pernah”. Contoh: Jakfar at-Thayyar tidak pernah mabuk di dalam hidupnya, baik sebelum masuk Islam, lebih-lebih setelah masuk Islam.
Yusuf bin Asbath tidak pernah makan makanan yang tidak ia ketahui lebih dulu dari mana berasal. Tujuannya adalah untuk memastikan, apakah makanan tersebut mengandung unsur haram atau tidak. Begitulah, kehati-hatian mereka terhadap sesuatu, terutama makanan, sangat menakjubkan.
Sepintas, kegiatan makan adalah kegiatan kehewanan. Artinya, seekor sapi (sebagai hewan betulan) butuh makan. Manusia (sebagai hewan berpikir) juga makan. Bedanya, manusia punya niat yang tulus dan ikhlas, sembari berdoa. Manusia diwajibkan hanya memakan yang suci dan halal.
Karena itu, makanan yang sehat tidak saja cukup syarat, sebab sehat belum tentu dimasak secara suci. Kentang adalah suci dan halal, tapi tidak jika didapat dari hasil mencuri atau tidak dibersihkan dengan air yang suci-menyucikan. Panjang urusannya, bukan?
Makan adalah peristiwa besar di dalam hidup keseharian. Makan dapat menjadi ‘upacara’ paling berat setelah salat. Pada kenyataannya, makanan adalah aktivitas ragawi yang sifatnya duniawi dan seringkali disepelekan. Dalam Risalatul Muawanah, Imam Al-Haddad mewanti-wanti kita terkait kesucian dan kehalalan rezeki yang ujung-ujungnya akan dimakan.
Jadi, analoginya begini: Jika ada bagian yang haram di dalam pakaian, ia akan membuat salat kita tidak diterima. Lalu—beliau mengajukan pertanyaan retoris—jika untuk hal-hal yang bersifat ragawi saja sampai segitunya hukumnya, bagaimana jika yang tidak suci dan tidak halal itu sampai-sampai bercampur dengan yang kita makan? Ia akan mengalir dalam darah, menjadi daging, menjadi bagian tubuh yang akan digunakan untuk ibadah.
Nabi, melalui hadis-hadisnya, mengatur gaya dan pola makan dengan sangat rinci. Dalam kitab Al-Adzkar susunan Imam Nawawi, doa-doa terkait makan sangatlah banyak. Aturan-aturannya sangat detail, mulai dari anjuran menjilati jari-jemari setelah makan, juga keharusan duduk pada saat makan, hingga urusan minumnya: harus juga duduk dan dengan tiga kali tegukan disertai basmalah dan hamdalah.
Di atas itu, ada pula aturan lainnya, seperti larangan mencaci makanan dan kesunnahan memuji makanan, berbasa-basi untuk tamu agar menikmati makanan, dll.
Sebab itulah, pada tahapan berikutnya, makan bukan lagi aktivitas biasa. Makan menjadi sarana taqarrub yang dapat mendekatkan kehambaan manusia, yang memakan rezeki Allah Yang Maha Menumbuhkan (a antum tazra’unahu am nahnuz zaari’un).
Jika Descartes mengajukan statemen filosofis “Cogito ergo sum” (aku berpikir, maka aku ada), maka Abun Nadjib as-Suhrawardi—sebagaimana dikutip Syaikh Ihsan Jampes dalam Sirajut Thalibin—menyatakan statemen transendental: “Ana akilun, wa ana ushalli” (saya makan, maka saya salat).
Namun demikian, sekarang, gaya hidup manusia terkadang menuntut kita macam-macam, berubah atau bertahan. Maka, aturan yang terbangun sejak dulu itu kadang harus berubah perlahan-lahan. Makan dan minum dianjurkan duduk, tapi bagaimana caranya jika tak ada kursi di standing party?
Habis makan sunnah menjilati jemari dan membersihkan piring sama sekali, tapi bagaimana jika makannya memakai sendok dan garpu? Makanlah hanya jika lapar dan berhenti sebelum kenyang, lalu mengapa kita harus makan tiga kali sehari?
Sejak kecil, kita diajari agar mencuci tangan sebelum makan, baca basmalah dan menutup dengan hamdalah, menyuap kecil dan mengunyah banyak, tidak boleh kekenyangan dan minumnya harus dalam posisi duduk. Tapi, begitu dewasa, mulailah kita lupa itu semua.
Kita baru sadar kembali begitu datang ilmuan atau peneliti yang mendukungnya. Muslim modern ada yang punya kecenderungan begitu. Jadi, setelah Masaru Emoto mengatakan bahwa air merespons terhadap bacaan yang baik, dan Hiromi Shinya menyatakan bahwa enzim melimpah di dalam mulut yang lama mengunyah, barulah kita manggut-manggut menyetujui.
Dengan begitu, dalam Islam, makan bukanlah sekadar mengganjal perut. Ia adalah aktivitas yang sangat serius sehingga wajar apabila aturannya sangat banyak. Dalam hal doa-doa terkait makan saja begitu banyak, di antaranya; doa pada saat menghadapi makanan, doa ketika mulai menyuap makanan, doa ketika lupa tidak berdoa pada suapan pertama, doa untuk orang yang memberi makanan, doa ketika selesai makan, doa agar makanan menjadi berkah, doa setelah minum. Lengkap sekali, bukan?
Inilah sebagian bukti bahwa peristiwa makan itu, yang oleh kita dianggap sebagai kegaitan ragawi-duniawi, sebetulnya mengandung muatan spiritual-ukhrawi kalau kita meniatkannya begitu.
Tapi, ingatlah, setelah Anda, para sufi modern yang sudah mengamalkan doa-doa dan adab makan dari kanjeng Nabi, masih ada satu hal lagi yang harus dibereskan: pastikan Anda dapat menjalani kesufian bukan hanya di meja makan saja, melainkan juga sesudah meninggalkannya, yakni memastikan tidak menambah rusak bumi dengan beban sampah plastik.
Wallahu a’lam