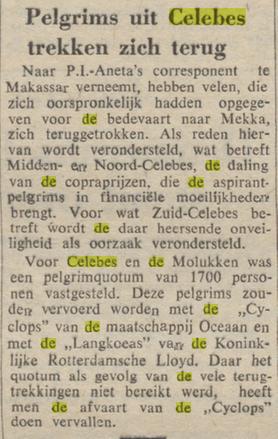
Keinginan untuk menunaikan ibadah haji di tanah suci, tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan umat muslim yang hendak menunaikannya. Padahal, kesiapan seperti fisik, mental, hingga finansial, menjadi komponen penting bagi umat muslim yang hendak menunaikan ibadah haji.
Motivasi menunaikan ibadah haji bagi masyarakat Sulawesi Tengah sendiri, sejak abad ke-19, didasari oleh dua aspek, yakni prestise dan mistis. Ahli linguistik, Nicolaus Adriani bersama etnografer, Albert Christiaan Kruyt, dalam De Baree Sprekende Toradja’s van Midden Celebes yang terbit tahun 1914 menyebutkan, orang-orang di sebelah selatan Teluk Tomini seperti Parigi, Sausu, dan Tojo, pada akhir abad 19, belum terbiasa berhubungan dengan dunia luar, sehingga belum mampu mengatasi ketakutan tentang apa yang ada di luar wilayah mereka. Hal ini kata mereka, membuat masyarakat di wilayah tersebut, belum secara serius mempertimbangkan perjalanan ke Mekkah (baca: berhaji).
Keduanya menulis, hanya dalam beberapa tahun, nampak peningkatan animo di di Sulawesi Tengah, misalnya di Tojo, untuk pergi berziarah (baca: berhaji). Ketakutan akan perjalanan besar ke Mekkah (baca: berhaji), berkurang secara nyata, ketika beberapa orang Tojo melakukan ibadah haji pada tahun 1893/1894, dan kembali ke daerah mereka dalam keadaan makmur. Untuk meningkatkan prestise mereka, para jamaah haji yang kembali ini, berlomba menceritakan semua pengalaman tentang perjalanan mereka.
Selain soal prestise, soal mistisme juga menjadi motivasi sendiri bagi umat muslim di Sulawesi Tengah, untuk menunaikan ibadah haji. Adriani dan Kruyt menulis, bagi mereka yang cenderung religius, perjalanan berhaji merupakan hal yang sangat diinginkan, karena mereka percaya, hal itu akan memberi mereka pengampunan dosa. Namun menurut keduanya, pengampunan dosa, nyatanya bukanlah motivasi utama, mengapa banyak orang ini ingin pergi berhaji. Motif utamanya adalah kemegahan Mekkah yang dinilai misterius, di mana Mekkah diselimuti oleh cerita-cerita misterius.
Mekkah dikatakan sebagai pusat bumi. Semua jiwa orang yang telah meninggal, dikatakan pergi ke Mekkah, dan ini adalah daya tarik misterius yang diberikan Mekkah. Di Mekkah, mereka yang menunaikan ibadah haji, dikatakan seringkali melihat penampakan ayah, ibu dan kerabat mereka yang telah meninggal dunia. Di Baitullah, para roh orang yang telah meninggal dunia ini, dikatakan mendekati para jamaah haji yang menjadi keluarganya dan berjabatan tangan dengan mereka.
Dalam cerita itu disebutkan, isyarat dan roh orang-orang yang telah meninggal tersebut, dikenali dengan tangan mereka yang hangat atau dingin. Orang mati disebutkan datang dari sisi timur Baitullah, sedangkan yang hidup, datang dari sisi Barat.
Kenyataan Tidak Seindah Harapan
Motivasi untuk menunaikan ibadah haji dari dua aspek utama ini, nyatanya memang membuat jumlah jemaah haji asal Sulawesi Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Eric Tagliacozzo dalam The Longest Journey, Southeast Asians and The Pilgrimage To Mecca mencatat, sesuai data jemaah haji asal Hindia Belanda pada tahun 1909-1910, terjadi peningkatan signifikan jumlah jemaah haji asal Celebes (Sulawesi), termasuk di dalamnya Sulawesi Tengah. Dalam catatan itu disebutkan, pada tahun 1909, jemaah haji asal Celebes berjumlah 265 dan setahun berikutnya meningkat menjadi 536. Dalam data yang sama juga dilaporkan, jumlah jemaah haji asal Menado cenderung stagnan, yakni 51 jemaah.
Namun, motivasi untuk berhaji, terkadang tidak selalu berbanding lurus dengan kesiapan, finansial misalnya. N. Adriani dan A.C. Kruyt mencatat, walaupun beberapa orang Tojo yang melakukan ibadah haji pada tahun 1893/1894, dan kembali ke daerah mereka dalam keadaan makmur, berlomba menceritakan semua pengalaman tentang perjalanan mereka, namun tidak banyak yang terdorong untuk pergi mengikuti jejak mereka. Hal ini disebabkan oleh biaya yang besar, yang menyebabkan sebagian besar masyarakat di sana, belum dapat mengimplementasikan niat mereka untuk ikut berhaji. Pada masa itu, para jamaah haji wajib dibekali paspor haji dan harus membayar ongkos naik haji sebesar f110, berdasarkan Resolusi 1825, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda.
Situasi seperti ini sebenarnya mewakili pendapat Eric Tagliacozzo, bahwa haji Asia Tenggara dimulai sebagai fenomena yang kurang lebih individual, yakni sebuah praktik yang dilakukan oleh mereka yang mampu membayar dan yang secara bertahap membawa serta umat Islam lainnya, melalui cara keuangan mereka sendiri. Hal ini kata dia, dilakukan pada masa pramodern, tetapi model ini menyumbang sebagian besar perjalanan haji di periode awal ini.
Kemudian, di zaman kolonial, berhaji menjadi jauh lebih sistematis, dengan adanya perusahaan yang menangani pemberangkatan haji, yang disponsori negara, yang dapat dipesan dan diputuskan sesuai dengan biaya yang dikeluarkan. Jemaah haji Asia Tenggara menurut Eric, mengambil keuntungan dari sistem ini untuk pergi haji dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada sebelumnya, tetapi harga di bawah kondisi dan kebijakan dari kekuatan non-Muslim.
Terakhir, Eric menjelaskan, zaman postkolonial telah melihat sintesis dua pendekatan awal ini, dengan negara yang sangat mengatur urusan haji di kawasan Asia Tenggara, tetapi individu sekali lagi yang menentukan jenis perjalanan yang dapat mereka lakukan. Pendekatan hibrid ini telah menjadi ciri khas haji modern di Asia Tenggara, di mana ritual keagamaan yang sekaligus bersifat individu dan sangat komunal pada saat yang sama.
Pendekatan hibrid terkait urusan haji di periode postkolonial atau pascakemerdekaan di Indonesia, tidk serta merta menyelesaikan persoalan. Kesiapan secara finansial tetap menjadi aspek utama yang harus dipenuhi setiap individu yang hendak menunaikan ibadah haji.
Batal Berhaji Karena Kondisi Keuangan
Salah satu contoh kasus yang menarik adalah para calon jemaah haji asal Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah yang terpaksa mengundurkan diri dari pendaftaran haji, karena kesulitan keuangan. Hal ini terekam dalam catatan surat kabar Java Bode edisi 26 Juli 1952, dengan judul berita Peziarah dari Celebes Menarik Diri.
Dalam berita tersebut, Koresponden Algemeen Nieuws en Telegraaf Agent Schap (Aneta) di Makassar melaporkan, banyak jemaah haji asal Celebes (Sulawesi) yang semula mendaftar untuk naik haji ke Mekah, namun mengundurkan diri. Alasannya diyakini karena jatuhnya harga kopra di Sulawesi Tengah dan Utara, yang membuat calon jemaah haji kesulitan keuangan. Sementara itu untuk wilayah Sulawesi Selatan, ketidakamanan yang ada diyakini sebagai penyebab pengunduran diri tersebut.
Pengunduran diri ini sendiri menyebabkan kapal Cyclops dari perusahaan Ocean yang dijadwalkan mengangkut para jemaah haji tersebut, dibatalkan, karena kuota tidak tercapai. Padahal kuota sebesar 1.700 orang telah ditetapkan untuk Sulawesi dan Maluku, meningkat dari tahun sebelumnya yakni 900 orang, di mana mereka akan diangkut dengan kapal Cyclops dari perusahaan Ocean dan kapal Langkoeas dari Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.
Biaya haji pada masa itu sendiri, sebagaimana diberitakan Algemeen Indisch Dagblad: De Preangerbode edisi 3 Mei 1951, ditetapkan oleh pemerintah bersama pihak perbankan, sebesar Rp6428,70, untuk kelas tiga, lalu penambahan Rp360 untuk kelas dua dan penambahan Rp960 untuk kelas satu.
Biaya di atas termasuk Rp500 untuk pembelian saham di Kongsi Perlajaran Nasional (Nationale Scheepvaart Mij) yang akan didirikan, yang akan mengangkut jemaah haji ke Mekah di masa depan. Biaya ini juga termasuk pelayanan dari kelompok dokter, perawat dan teknisi laboratorium yang bertanggung jawab atas kesehatan para jemaah di Mekah.
Sejarawan Universitas Tadulako (Untad), Wilman D. Lumangino menjelaskan, jatuhnya harga kopra di Sulawesi Tengah dan Utara, yang membuat calon jemaah haji dari kedua daerah tersebut kesulitan keuangan sehingga harus mengundurkan diri dari perjalanan haji, disebabkan oleh pembelian kopra yang tidak berjalan normal. Kata dia, keterlambatan kapal-kapal pengangkut kopra mengakibatkan penumpukan kopra di gudang-gudang kopra milik Coprafonds, sehingga mempengaruhi arus pembelian kopra. Keterlambatan ini sendiri diakibatkan oleh terbatasnya gudang kopra.
“Sehingga tahun 1953, dibangun gudang-gudang kopra di hampir semua ibukota distrik atau sentra-sentra kopra. Sebelumnya, gudang-gudang kopra cuma ada di ibukota kabupaten dan distrik yang menjadi pusat kelapa, seperti Palu, Donggala, Parigi, Tinombo, Moutong, dan Tolitoli,” ujarnya.
Tidak normalnya pembelian kopra ini kata Wilman, menjadi pemicu aktivitas penyelundupan kopra (smokol) terutama di wilayah Pantai Barat Sulawesi Tengah, pada periode itu. Dalam tesisnya, Smokol di Pantai Barat Sulawesi Tengah: Saling-Silang Ekonomi Maritim dan Politik di Masa Transisi, 1947-1967, Wilman menyebut, kopra merupakan sumber pendapatan masyarakat Indonesia Timur pada umumnya, dan Pantai Barat pada khususnya, tahun 1950-an hingga 1970-an. Wilayah Indonesia (bagian) Timur, khususnya Sulawesi, yang hanya memiliki sumber ekspor penting dan mungkin satu-satunya saat itu, yakni kopra, sehingga komoditas ini disebut- sebut sebagai urat nadi perekonomian Indonesia Timur. Apabila kopra tidak memiliki harga jual yang baik, maka rakyat menderita.
Tahun 1952 dikatakan sebagai awal era baru smokol, karena intensitasnya yang meningkat tajam. Bila pada periode sebelumnya, hanya belasan perahu layar yang berangkat dari Pantai Barat menuju Sitangkai, namun kali ini puluhan perahu hilir-mudik di Selat Makassar setiap hari. Aktivitas mereka sangat berpengaruh terhadap pembelian kopra di Indonesia Timur, salah satunya Pantai Barat Sulawesi Tengah. Setelah itu terjadi penurunan drastis dan terus-menerus hingga tahun 1957. Kondisi ini terjadi karena pada tahun-tahun tersebut, Pulau Sulawesi sedang bergolak, akibat adanya pertentangan antara pusat dan daerah.





