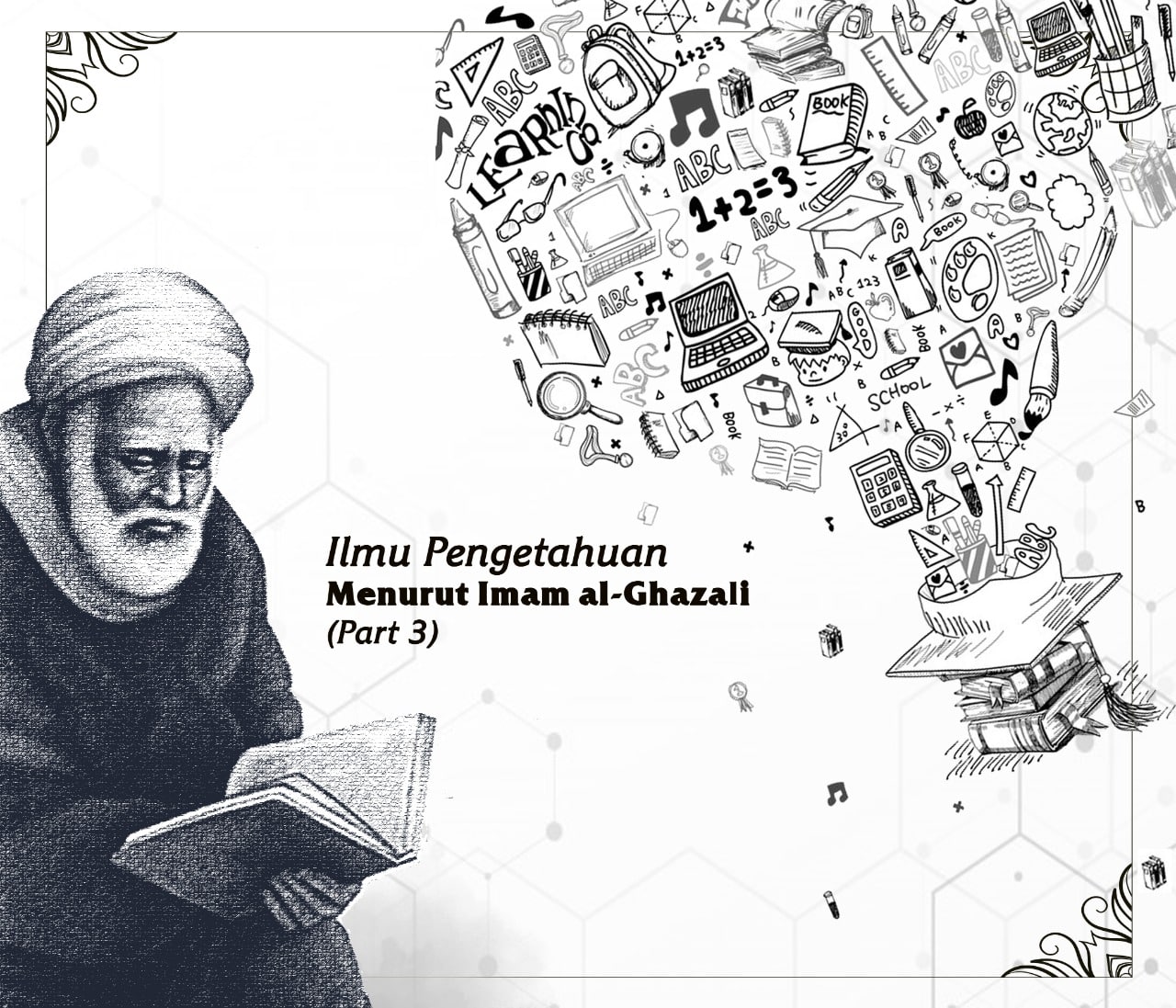Bagaimana ilmu pengetahuan melalui proses revelation itu ditangkap oleh manusia? Isham Pawan Ahmad membuat komparasi tiga kitab al-Ghazali (Iqishad fi al-I’tiqad, Kitab al-‘Ilm, dan al-Maqshad al-Asna fi Syarh Ma’ani Asma Allah al-Husna) untuk menjawabnya.
Dalam kitab Iqtishad, al-Ghazali menolak pemikiran para filosof bahwa revelation kepada Nabi terjadi di dalam batin, di mana kemudian Nabi mengungkapkan dan menerjemahkannya dengan kekuatan imajinatif ke dalam bentuk-bentuk simbolik, seperti bahasa.
Bagi al-Ghazali, pandangan para filosof di atas bertentangan dengan hukum Tuhan itu sendiri. Kemudian, menurut Isham P. Ahmad, al-Ghazali mengafirmasi pandangan klasik bahwa malaikat hadir dalam bentuk fisik, menyampaikan wahyu secara verbatim, dan Nabi menerima revelation tersebut dari sumber eksternal (Isham P. Ahmad, 1998: 101-102).
Dalam Kitab al-‘Ilm, al-Ghazali, menurut Isham Pawan Ahmad, membedakan revelation (wahyu) dari inspiration (ilham). Wahyu disampaikan kepada manusia (Nabi) melalui perantara (malaikat) secara verbatim dan berasal dari sumber eksternal. Sementara inspirasi atau ilham disampaikan kepada manusia, baik berstatus sebagai Nabi maupun bukan-Nabi. Ilham maupun wahyu sama-sama butuh perantara (Isham P. Ahmad, 1998: 114-115).
Lantas, bagaimana Nabi mengomunikasikan dan menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain? Al-Ghazali mengatakan, ilmu muamalah adalah satu-satunya jalan yang mengantarkan kita pada pengetahuan tentang revelation, dan satu-satunya jalan yang Nabi tempuh dalam berkomunikasi dan membimbing umatnya pada Tuhan.
Terkait ilmu mukasyafah itu sendiri, Nabi berbicara pada umatnya secara figuratif (bi al-ramz), menggunakan tanda-tanda (al-tamtsil) dan simbol. Hal itu dikarenakan umat manusia tidak mampu memahaminya, bi qushur afham al-khalq, keterbatasan kemampuan pemahaman (Isham P. Ahmad, 1998: 116).
Dalam kitab al-Maqshad al-Asna fi Syarh Ma’ani Asma’ Allah al-Husna, al-Ghazali tidak lagi membahas aspek-aspek teknik bagaimana revelation itu disampaikan dan diterima, juga tidak soal apakah revelation itu verbatim atau simbolik. Namun, al-Ghazali hanya menekankan bahwa proses transmisi revelation itu membutuhkan media berupa seorang Nabi atau manusia pilihan (Isham P. Ahmad, 1998: 133).
Sementara di dalam kitab al-Risalah al-Ladunniyah, al-Ghazali lebih jauh berbicara proses transimisi revelation ini. Yakni, dengan membahas panjang lebar tingkatan-tingkatan jiwa manusia dalam menghasilkan ilmu pengetahuan (maratib al-nufus fi tahshil al-‘ulum). Bagi al-Ghazali, semua jiwa manusia berpotensi menerima segala jenis ilmu (jami’ al-nufus al-insaniah qabilah li jami’ al-‘ulum) (al-Ghazali, al-Risalah al-Ladunniah, 1328 H.: 32).
Perbedaan satu jiwa (nafs) dengan jiwa lain dalam menangkap segala jenis ilmu hanya disebabkan oleh faktor-faktor yang bisa datang dan pergi, yang berasal dari luar. Al-Ghazali mengutip hadits Nabi yang mengatakan, “manusia diciptakan dalam keadaan lurus, kemudian setan membengkokkannya,” (al-Ghazali, 1328: 32).
Jiwa yang masih bersih dan sehat, tidak pernah bengkok, adalah jiwanya para Nabi. Jiwa mereka mampu memperlihatkan berbagai mukjizat dan mengendalikan alam, serta mengubah keburukan. Karenanya, jiwa para Nabi berperan sebagai dokter jiwa (athibba’ al-nufus) yang mengobati penyakitnya dan mengajak makhluk untuk kepada pada keadaan fitrah yang sehat (al-Ghazali, 1328: 33).
Jiwa-jiwa yang sudah sembuh dari penyakitnya, akibat kecintaan pada duniawi, maka ia akan kembali menjadi fitrah. Ketika sudah sembuh inilah, jiwa-jiwa dapat menerima ilmu ladunni atau ilham atau inspiration. Sementara kebodohan adalah ungkapan bagi jiwa yang sedang sakit karena terlalu lengket pada urusan tubuh material (al-Ghazali, 1328: 34).
Konsep ini penting karena berdampak pada definisi ilmu pengetahuan bagi al-Ghazali. Seseorang yang belajar ilmu bukan berarti menciptakan ilmu yang sebelumnya tidak ada (ijad al-‘ilm al-ma’dum). Tetapi, belajar pada hakikatnya adalah mengembalikan jiwa manusia pada ilmu yang asali dan tersimpan dalam batin (i’adatuha al-‘ilma al-ashliya al-ghariziya).
Belajar adalah kembalinya jiwa pada dirinya sendiri yang paling inti dan mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya ke luar berupa tindakan dengan tujuan menyempurnakan dzat jiwa itu sendiri dan meraih kebahagiaannya (al-Ghazali, 1328: 34).
Dari postulat semacam ini, al-Ghazali membangun ilustarsi tentang perbedaan jiwa yang sehat dan yang sakit. Jiwa yang sehat tidak butuh waktu berlama-lama untuk mendapatkan pengetahuan yang melimpah. Sebaliknya, jiwa yang sakit harus menghabiskan waktu lama untuk mendapatkan pengetahuan yang sedikit (al-Ghazali, 1328: 35).
Isham Pawan Ahmad tidak membahas aspek kejiwaan ini, dalam hubungannya dengan proses ta’allum dan ta’lim. Sehingga pembahasannya hanya terbatas pada persoalan ta’allum rabbani yang terdiri dari wahyu dan ilham.
Sementara upaya-upaya aktif manusia dalam rangka pembersihan jiwa dari dosa-dosa dan maksiat, sebagai persiapan-persiapan menyambut ilham dan ilmu ladunni, baik berupa ta’allum maupun tafakkur, lepas dari perhatian. Lantas, apa hakikat ilmu ladunni itu? [bersambung]