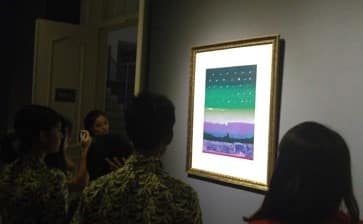Kampung dan Obrolan Pasca Lebaran: Titenono, Gusti Mboten Sare!

Dua pekan pasca Lebaran, saya sekeluarga kembali menyambangi kampung leluhur di Giriwoyo, Wonogiri. Bola mata menikmati ulang panorama tempat muasal ibu saya itu yang bertanah tandus dan terkadang larang banyu. Di balik kehidupan yang sarat kemlaratan itu, menawarkan keguyuban para penghuninya. Mudik kali ini untuk keperluan kirim donga atau kenduri pendak pisan (peringatan satu tahun orang meninggal) simbah saya.
Kala sore hari, sebelum acara tahlilan digelar setelah ngisyak, diadakan bancakan dengan mengundang tetangga kiri-kanan. Dipimpin pak modin, para warga berikut keluarga saya mengepung nasi tumpeng dilengkapi lauk dan segelas air putih. Di bawah kendali “orang pintar” itu, terlayang doa berbahasa Jawa ditujukan kepada Gusti Kang Akarya Jagad. Muaranya, guna memintakan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran pada keluarga saya. Lebih dari itu, acara tersebut untuk mengencangkan ikatan paseduluran di kampung.
Usai diujubne (didoakan), bergegas nasi tumpeng disantap bareng. Sembari memasukkan nasi ke dalam mulut, kami bersama para tetangga ngobrol ringan. Masih dalam suasana syawalan, obrolan mengenai kesan Lebaran tahun ini tetap mendominasi. Saya melemparkan pertanyaan kepada tetangga perihal nasib perantau yang mengembara ke kota. Mereka menjawab, banyak perantau yang balik ke kota, akan tetapi wajahnya tak sumringah. Pasalnya, perantau yang rata-rata bergerak di dunia swasta cukup terpukul akibat daya beli masyarakat melemah. Sementara para korban PHK balik ke perantauan bermodal nekad, ketrampilan terbatas, dan mendamba kedatangan dewi fortuna.
Dari mulut Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi (Detik.com 12/4) diketahui, mudik tahun ini menurun 4,69 persen. Dari hasil pengamatan, sebagian perantau memilih tidak berlebaran di kampung demi penghematan. “Lagi ora usum duit,” keluh kawan perantau dengan logat ndesa. Perekonomian negeri ini memang sedang terpuruk. Bahkan, kian hari nilai tukar rupiah kian merosot, mencapai angka Rp 16.740. Apesnya, pemerintah tampak abai dengan kondisi pahit ini dan masyarakat dibiarkan tercekik lama.
Saya kemudian teringat cerpen “Mudik” yang dianggit Mustofa W Hasyim. Pembaca dapat merasakan kenestapaan keluarga miskin seperti Joko dan Tinah di Jakarta. Mereka sekeluarga tidak mampu berlebaran di tanah asal tahun itu. Alih-alih berbaju baru dan memperoleh uang fitrah, buah hatinya juga turut memendam kepedihan karena kekuatan kantong keluarga anjlok. Bisa dipastikan, tokoh Joko dan Tinah itu di tahun ini jumlahnya berlipat ganda.
Hampir seabad silam, negeri ini saat sebelum dan sesudah Lebaran juga mengalami keguncangan. Tempo itu, dunia internasional diterjang krisis ekonomi yang merontokkan berbagai sendi kehidupan. Jurnalis Kajawen (13 Februari 1932) menggambarkan banyak negara besar laksana tanaman yang hijau segar, tiba-tiba alum (layu). Pemerintah kolonial Belanda dan investor swasta menanam modal lewat jalur perkebunan tanaman ekspor di tanah jajahan dihantam gelombang malaise. Pasar internasional jeblok, tak mampu menyerap hasil industri gula, teh, tembakau, dan kopi. Mereka pun tersungkur.
Berbagai pabrik yang beroperasi di Hindia Belanda ikut terjerebab. Pabrik gula sekelas Colomadu dan Tasikmadu yang digawangi oleh penguasa pribumi Mangkunegaran juga goyah. Leluhur Kanjeng Gusti Bhre (Mangkunegara X) memilih mengurangi jumlah produksi gula ketimbang gulung tikar. Tak ayal, jumlah pengangguran di Vorstenlanden (wilayah kerajaan) melonjak tajam dan tingkat kemiskinan meroket. Binatang ternak dijual murah alias banting harga di pasar hewan pedesaan tetap saja tidak terjangkau oleh masyarakat. Penjualan hewan ternak dipakai oleh pemerintah untuk mendeteksi kondisi kesehatan keuangan di level akar rumput. Lembaga bank terpaksa ikut tutup sementara waktu gara-gara peredaran uang terganggu.
Institusi tradisional juga tidak dapat berkelit dari terpaan krisis. Akibat depresi ekonomi, pengurus Keraton Kasunanan menerbitkan surat edaran untuk bupati, wedana, pembantu wedana, dan pengurus lainnya. Surat edaran disertakan dalam majalah Paprentahan ini menghimbau bahwa tidak boleh memakai gamelan di pesta pernikahan, khitanan, dan sejenisnya. Saat Sura, Maulud, dan Ramadan dilarang saling memberi makanan. Para kawula juga tidak boleh membeli apapun jika tidak benar-benar dibutuhkan. Paku Buwana X sebagai “Raja Jawa” menekankan pula pertanian harus digenjot, dan sedapat mungkin sebidang tanah jangan dibiarkan kosong. Di hari minggu rakyat dapat menenun, mengepang atau membuat barang rumah tangga. Di sekolah desa diberi pelajaran kerajinan tangan. Pengurus istana berpesan, apabila himbauan tersebut diikuti, niscaya mengurangi efek malaise (De Koerier, 27 November 1931).
Awal tahun 1932, Paku Buwana X menyurati Residen Surakarta bahwa dana kerajaan menyusut. Raja khawatir bila mengalami kekurangan biaya operasional kerajaan di masa sulit ini. Lantas, raja menambah kas istana sebesar f10.000 setiap bulan. Penguasa Keraton Kasunanan itu menghindari pesta atau pertemuan yang tidak perlu. Upaya ini ditempuh guna memberi teladan kepada sentana dalem dan bawahan agar terbiasa hidup hemat di masa krisis (De Locomotief, 04 Maret 1932).
Pasar Gedhe yang menjadi barometer ekonomi rakyat ikut terdampak. Toko mebel yang sehari-hari laris tak urung memutus kerja para karyawan dan memulangkan ke tempat asal hingga pasca Lebaran. Ketrampilan seni kriya yang diperoleh di kutharaja (kota kerajaan) dibawa pulang dan dipraktikkan di kampung. Hal ini kelak memicu perkembangan industri kerajinan rotan di Desa Trangsang, Sukoharjo, dan masih lestari hingga kini.
Guna mencegah agar tidak terperosok ke jurang kesengsaraan, maka penggede negara kolonial waktu itu berusaha mengeluarkan berbagai kebijakan. Ambillah misal, mengurangi belanja para pegawai, menaikkan pajak yang terasa berat bagi siapa saja, menggenjot biaya sekolah, serta memporak-porandakan dunia pendidikan dengan dalih penghematan. Aneka kebijakan tersebut ditanggapi secara kritis oleh para anggota Volksraad.
“Ningali ombyaking tiyang wontên ing dintên lêbaran tuwin ing dhawahing dintên taun enggal bangsa Tionghoa…” tulis juru warta kala itu. Sejumput fakta ini menunjukkan bahwa krisis meleset detik itu bertepatan dengan perayaan hari Lebaran dan Imlek. Para batur, profesi pembantu yang sering dinaikkan derajatnya oleh budayawan Umar Kayam, pulang ke pedesaan di Wonogiri, Klaten, Gunung Kidul, dan lainnya. Mereka mudik dengan kisah pilu, alih-alih bercerita tentang kemenangan di tanah rantau. Ekonomi para ndoro yang mayoritas dari kaum priyayi dan pengusaha juga goyah akibat efisiensi dan seretnya perputaran keuangan.
Pola sejarah berulang. Orang-orang di kampung mungkin mudah berdamai dengan keadaan. Mereka terbiasa memupus kekecewaan atas polah-tingkah pemerintah. Dalam jerat kemiskinan berabad lebih, bukan berarti doa mereka tiada gunanya. Mereka kali ini berhak jengkel dengan pemerintah yang bertindak di luar nalar. Komunikasi politik nan ciamik yang seharusnya dijalankan pemerintah untuk meredam emosi rakyat, justru bikin makin naik pitam. Bersamaan ekonomi negara ringkih, tingkat kepercayaan publik dan demokrasi juga merosot, yakni alat kekuasaan dipakai untuk membungkam masyarakat yang bersuara kritis. Wong cilik cukup membatin: titenono, Gusti mboten sare!