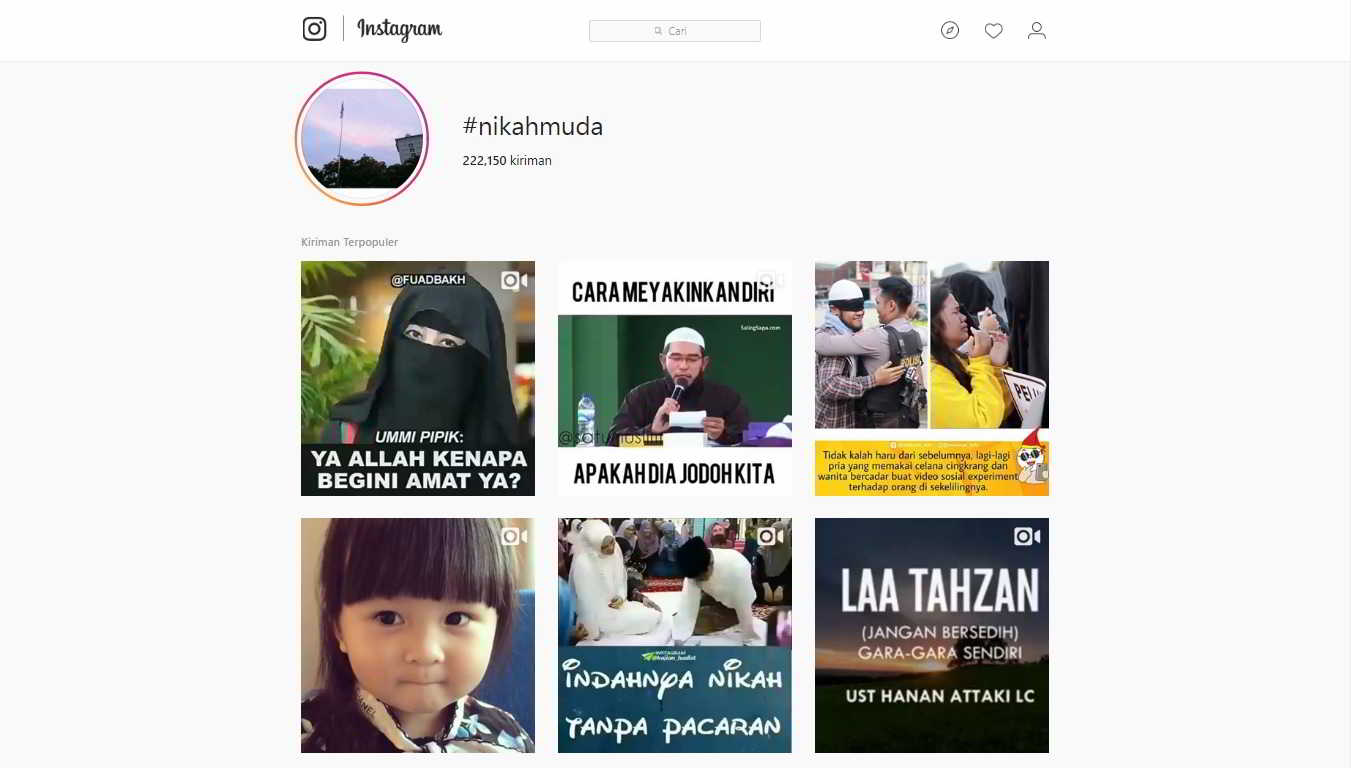Laporan dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 2021 lalu, mengungkapkan bahwa sepertiga perempuan di dunia, atau sekitar 736 juta dari mereka, pernah mengalami kekerasan fisik maupun seksual. Bahkan di daerah konflik, persentasenya kian meningkat seiring dengan belum redanya sejumlah konflik di dunia, termasuk di Ukraina yang hingga kini masih menemui jalan buntu.
Selain Ukraina, situasi konflik di Somalia adalah contoh lain dari kejahatan yang mengorbankan banyak perempuan dan anak-anak selama perang. Menurut Human Rights Watch, para pengungsi internal di Somalia menderita kekerasan seksual dalam bentuk pemerkosaan berkelompok dan bentuk-bentuk pelecehan lainnya di kamp kamp pengungsi Mogadishu.
Human Rights Watch melaporkan bahwa pelecehan itu terjadi di tangan kelompok-kelompok bersenjata, termasuk pasukan pemerintah. Pemerkosaan itu bahkan tidak pandang bulu. Semua perempuan di sana amat riskan menjadi korban. Bahkan pernah terjadi, seorang wanita berusia 23 tahun yang sedang hamil 9 bulan diperkosa beramai-ramai oleh 3 pria berseragam tentara. Perempuan tersebut hanya bisa menderita dalam diam karena mereka takut akan stigma, pembalasan dan bahkan eksekusi.
Kekerasan perempuan dan anak perempuan seperti tadi termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan melanggar prinsip-prinsip dasar HAM Internasional. Pada tahun 1995 The Beijing Platfrom for Action (BPFA) menggarisbawahi penghapusan kekerasan pada perempuan dan anak perempuan dalam situasi konflik bersenjata. Namun hingga kini banyak tantangan yang BPFA hadapi dalam penerapan kebijakannya.
Meski begitu, pihak BPFA berjanji bahwa mereka akan terus berusaha agar amanat yang dibebankan pada mereka dapat berjalan dengan optimal. Hal ini disampaikan oleh perwakilan BPFA Indonesia yang meyakinkan bahwa, terus mengupayakan peningkatan partisipasi perempuan dalam penyelesaian konflik di tingkat pengambilan keputusan untuk pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dan anak di daerah konflik atau di bawah kependudukan asing, dan mendorong perempuan membina budaya perdamaian.
Tidak hanya itu, BPFA juga mempromosikan bentuk-bentuk penyelesaian konflik tanpa kekerasan dan mengurangi kejadian penyalahgunaan HAM sewaktu terjadi terjadi konflik bersenjata. Saat ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bersama instansi dan lembaga swadaya masyarakat peduli perempuan dan anak masih mengoptimalkan Rancangan Aksi Nasional (RAN) Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325.
KPPPA juga bekerjasama dengan Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta untuk menjalankan langkah-langkah konkrit dalam rangka mengatasi persoalan dalam melindungi perempuan dan anak di daerah konflik. Hal yang telah dilakukan KPP & PA tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk menghentikan konflik sosial yang hingga kini masih menimbulkan banyak korban perempuan dan anak seperti di Papua, Aceh, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan daerahlainnya.
Kerjasama KPPPA juga sejalan dengan tindak lanjut Undang-Undang No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (PKS). Secara spesifik, aturan tersebut mengacu pada pasal 2 UU PKS yang merinci asas penanganan konflik yang terdiri dari: kemanusiaan, Hak Asasi Manusia (HAM), kebangsaan, kekeluargaan, kebhinekatunggalikaan, keadilan, kesetaraan gender, ketertiban dan kepastian hukum, keberlanjutan, kearifan lokal, tanggung jawab negara, partisipasi, tidak memihak, dan tidak membeda-bedakan.
Dari asas-asas tersebut, UU PKS mengharuskan kehadiran negara dalam penanganan konflik sosial. Artinya, negara berkewajiban dan bertanggung jawab menyelesaikan konflik dengan memperhatikan kesetaraan gender. Sayangnya, program kebijakan pemerintah yang dicanangkan tadi belum sepenuhnya direalisasikan di lapangan. Contohnya, konflik Ahmadiyah di NTB memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan perempuan yang sudah menjadi bagian dari kebijakan nasional belum menghasilkan mekanisme perlindungan bagi perempuan (Octaviana, dkk 2014).
Konteks konflik sosial di NTB mungkin bukan mengakibatkan luka fisik langsung, tapi menghasilkan perubahan pola kehidupan perkotaan yang dialami para penyintas. Mereka mengalami kekerasan, tetapi mereka mampu bertahan karena pemahaman keagamaan mereka memberikan penguatan. Kalangan anak-anak Ahmadiyah pun turut mengalami perundungan, sedangkan pada orang dewasa terdapat upaya untuk menahan diri terhadap agitasi yang ada.
Permasalahan tersebut terjadi karena menguatnya otoritas religiositas di beberapa wilayah yang kemudian memicu konflik keagamaan dan marginalisasi interpretasi agama minoritas, padahal pemeluk agama minoritas statusnya tetap warga negara dan negara menjamin keberadaan mereka. Sehingga perlindungan warga negara perlu lebih diprioritaskan. Oleh karena itu, pemerintah harusnya dapat hadir sebagai pelindung bagi kelompok-kelompok rentan (perempuan dan anak) selama konflik berlangsung.
Pun, selama masa perdamaian kehadiran pemerintah juga sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman mendasar kepada seluruh warga negara mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama dengan mengikutsertakan tokoh agama dan masyarakat. Selanjutnya sebagai bagian dari komitmen pemerintah, sistem hukum di Indonesia harus segera berbenah menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan diskriminasi gender, diawali dengan mengadopsi prinsip dasar CEDAW.
Tindakan Khusus Sementara (TKS) dapat berupa kebijakan dan program pemerintah, dapat pula melalui implementasi konkrit Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (UU TPKS).Dengan payung hukum yang kuat dan anggaran yang memadai, segala usaha atau program pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan keadilan gender akan lebih dapat terlaksana secara optimal.