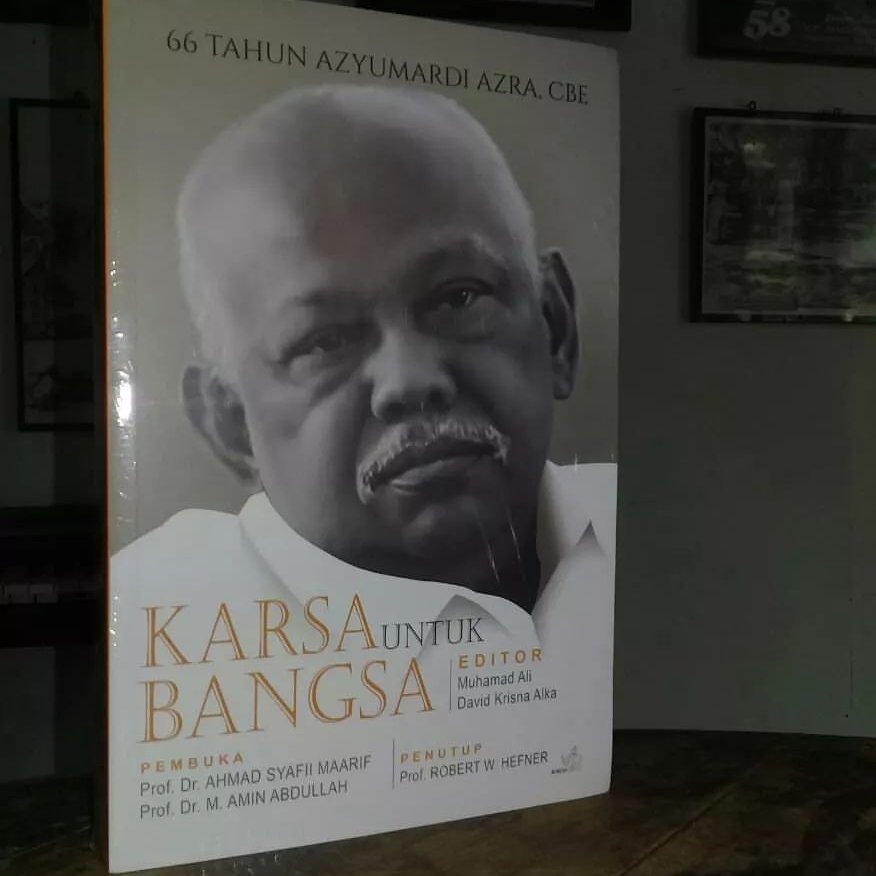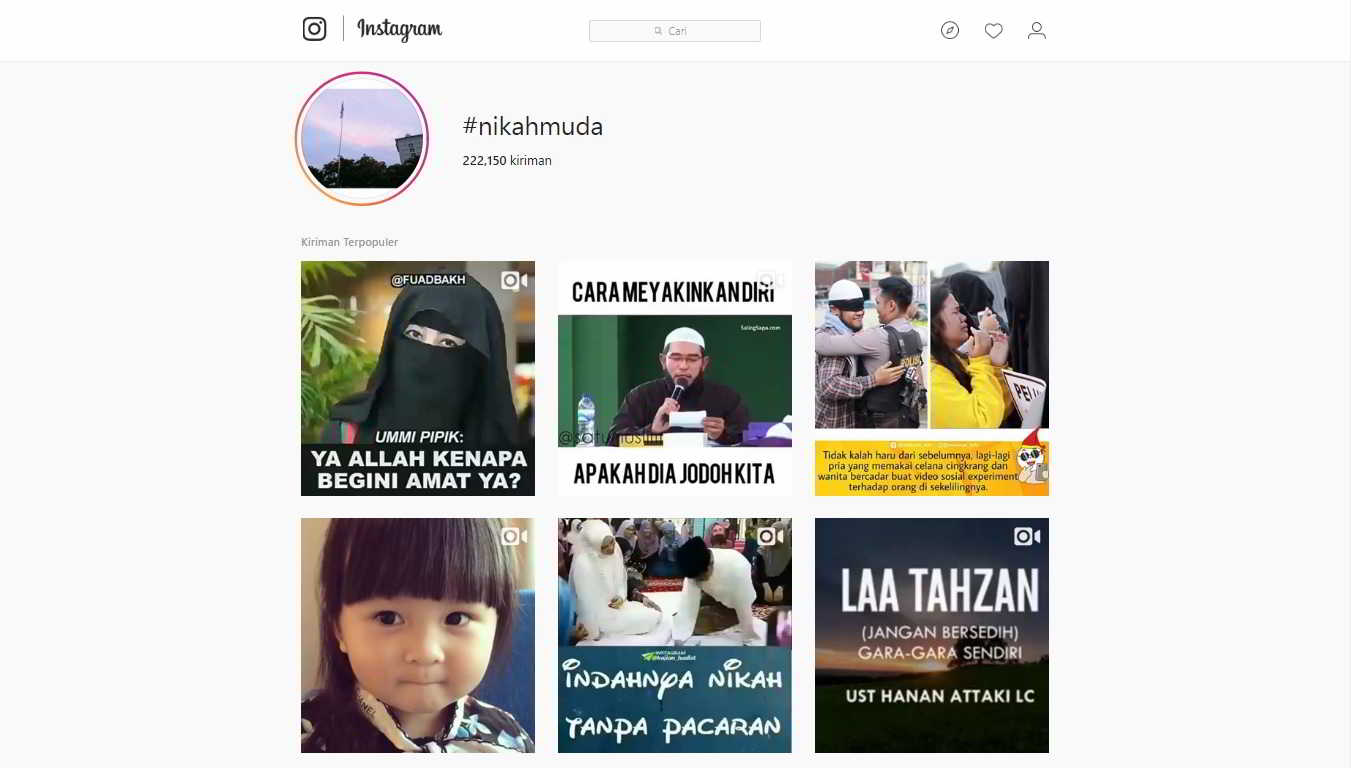Akhir Agustus lalu, sejumlah orangtua di Banjarnegara melaporkan guru mengaji di sebuah pesantren atas tindakan pelecehan seksual terhadap putra mereka. Diketahui, pondok pesantren (ponpes) tempat pelaku mengajar baru berdiri tahun 2019. Hingga saat ini jumlah santri di ponpes tersebut sekitar 200 orang. Ponpes tersebut berada di tiga tempat berbeda, yakni di Kecamatan Banjarmangu, Punggelan, dan Wanadadi.
Berdasarkan pemaparan dari enam korban yang telah ditanyai oleh polisi, modus pelaku diawali dengan memanggil santri yang menjadi target untuk datang ke rumahnya dengan dalih pendalaman materi ngaji. Namun, setibanya di sana, para korban kemudian diperdaya untuk memenuhi hasrat si pelaku.
Tindakan biadab yang dilakukan oleh guru kepada anak-anak laki ternyata tidak satu dua kali terjadi. Meski, jumlah kasus yang menyasar kepada anak laki-laki jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kasus yang menimpa anak-anak perempuan. Problematika kekerasan seksual kepada laki-laki di bawah umur kerap kali tak terungkap. Psikiater anak dan remaja dari RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) dr Fransiska Kaligis, SpKJ mengungkapkan bahwa kasus pelecehan seksual kepada anak-anak laki kerap dilabeli sebagai lelucon. Misalnya, permainan lepas celana yang dilanjutkan dengan menyentil kemaluan korban. Bagi pelaku, apa yang dilakukan hanyalah sebatas bercanda, mayoritas mereka tidak paham bahwa yang mereka lakukan termasuk tindakan pelecehan seksual. Terlebih, individu yang melakukan tindakan tersebut biasanya merupakan senior/kakak kelas/guru atau yang berusia lebih tua dari korban, sehingga ketika yang bersangkutan keberatan atau mengelak, ia akan dilabeli “pengecut”, “cemen”, hingga “mental lemah”.
Di satu sisi, usia anak-anak dan remaja merupakan masa-masa aktulisasi diri yang masih haus akan pengakuan. Dari situ kemudian anak-anak yang menjadi korban akhirnya tak berani untuk melapor dan bercerita karena takut akan dikucilkan oleh kawan-kawannya sendiri. Padahal ketika seorang anak mengalami perasaan tertekan karena dipaksa, itu sudah termasuk pelecehan seksual, tidak bisa dikatakan sebagai bahan tertawaan. Sebab saat korban merasa tertekan dan tak berdaya dengan posisinya yang lebih inferior, pelaku selanjutnya akan lebih leluasa melancarkan tindakan negatifnya.
Melihat situasi tersebut, tidak cukup memiliki regulasi seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk membentengi kasus-kasus sejenis. Santri-santri di Banjarnegara tadi yang tinggal di pesantren dengan akses jauh dari perkotaan tentu memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai pelecehan seksual. Belum lagi persoalan relasi timpang antara ustadz dan santri yang kerap dimanipulasi oleh oknum-oknum tidak bertanggungjawab untuk melancarkan aksinya.
Kondisi ini diperburuk dengan masih terbatasnya UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) atau lembaga penyedia layanan bagi saksi dan korban pelecehan seksual. Namun unit Pelayanan Perempuan dan Anak ini hanya ada di tingkat Polres (Kepolisian Resor tingkat kabupaten/kota), bahkan kadang hanya ada di tingkat provinsi. Menurut KPPPA, saat ini baru 31 provinsi yang memiliki UPTD PPA, serta 200-an di kabupaten/kota. Padahal jumlah kabupaten/kota di Indonesia ada 514. Jadi untuk tingkat kabupaten/kota baru 39 persennya saja.
Permasalahan lainnya yaitu belum semua polisi atau penegak hukum memahami secara komprehensif isu-isu pemenuhan hak korban pelecehan seksual. Bahkan sempat kasus pelecehan seksual yang dilaporkan kepada pihak kepolisian justru ‘memakan’ korban polwan. Kalau sudah begini, pengesahan UU TPKS, tentu belum cukup bukan?
Oleh karena itu, tindakan selanjutnya yang perlu segera dilakukan tidak hanya sebatas pada pembentukan UPTD PPA, tapi juga sosialisasi masif terkait isu-isu pelecehan seksual di semua penyelenggara pendidikan. Dan yang perlu dicatat, tidak hanya sekolah formal di bawah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan saja yang perlu menyelenggarakan pendidikan seksual tadi, tapi semua sekolah formal dan informal yang ada di Indonesia. Sebab, kasus yang disebutkan di awal paragraf tadi terjadi di pesantren yang tidak terdaftar di Kementerian manapun. Sehingga, bila kita hanya terfokus pada sekolah-sekolah tertentu, itu sama saja dengan meminggirkan risiko pelecehan seksual di wilayah-wilayah terpencil.
UU TPKS juga memberi pekerjaan rumah besar bagi aparat penegak hukum terkait delik aduan dan laporan kasus kekerasan seksual terhadap anak. UU ini memberikan jaminan perlindungan cukup menyeluruh bagi anak. Kekerasan seksual terhadap anak bukan lagi delik aduan, tapi menjadi delik laporan. Tapi, dengan masih terbatasnya SDM, tentu perlu upaya menyeluruh untuk mengejar ketertinggalan yang ada.
Poin yang perlu diperthatikan adalah selama ini penegak hukum menindaklanjuti kasus berdasar adanya aduan atau tidak. Berkat UU TPKS, jika kontak seksual tersebut dilakukan terhadap anak atau kelompok disabilitas, aparat sudah bisa bergerak tanpa menunggu aduan. Tapi, bagaimana jika terjadi kekerasan seksual di daerah tertinggal? Yang sulit dijangkau dari pihak penegak hukum, yang wilayahnya sulit sinyal, listrik masih byar pet? Bisa dipastikan korban atau orang yang menyaksikan terjadinya peristiwa tersebut akan mengalami kesulitan untuk melaporkan. Kalau sudah begitu diperlukan kerjasama dengan pihak pemerintah terkecil hingga desa atau bahkan RT/RW untuk bergerak aktif mempromosikan isu ini agar UU TPKS tidak hanya sekadar peraturan formalitas, bukan benar-benar menjadi ‘payung’ hukum yang melindungi kelompok-kelompok rentan termasuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan.