Perempuan Katolik Bernama Terra dan Adab Segala Bangsa
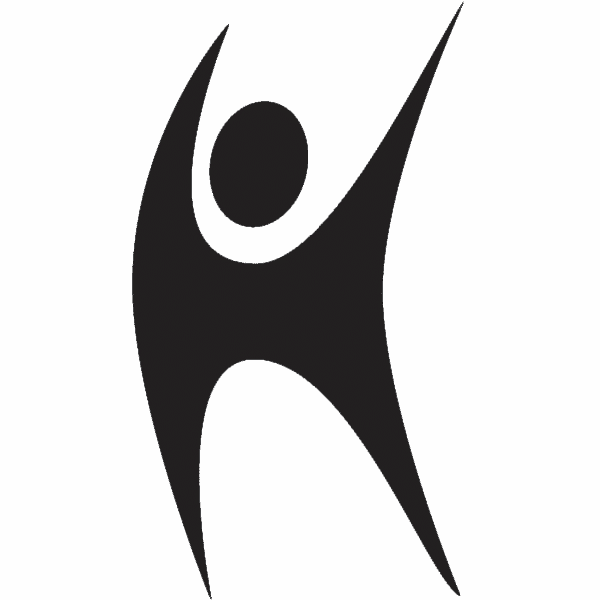
Namanya Terra, puteri guru dan sekaligus karib saya, Dr. St. Sunardi, Ketua Program Studi Doktoral (S3) Seni dan Masyarakat, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Sekarang Terra sedang menempuh pendidikan di satu “pesantren” Katolik di Semarang, sebuah pilihan yang sinergik dengan namanya, yang merupakan motto dari tradisi humanisme dunia, terra aliniea, mendatangi wilayah asing.
Ketika saya menjadi mahasiswa ayahnya, Terra masih di sekolah dasar. Ketika bulan suci Ramadan tiba, ayahnya sibuk mengantarkannya ke toko pakaian muslim di Yogyakarta, Al-Fath, karena Tera mau ikut teraweh dan acara ramadanan dengan tetangganya, meski ia tumbuh formal dalam tradisi Katolik keluarganya.
Terra adalah gambaran semangat kosmopolitanisme segala bangsa, yakni kesiapan menampung keragaman dalam wadah pikiran yang rendah hati, semangat keilmuan, kesederhanaan, dan keramahan.
Saya mengingat Terra karena ingat catatan (dhobitan) masa mondok, terutama ketika meniliki baris-baris dari bab ilmu dalam kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Ghazali ataupun kitab lainnya. Saya kira pengalaman ini tidaklah khas saya, umum dialami kalangan santri. Keterlaluan kalau ada santri yang melupakan syair berikut :
Alaa laa tanaalul ilma illa bisittatin
Saunbiika majmu’uaha bibayanin :
Dzakain, wa hirshin, wasthibaarin wa bulghatin wa irsyaadu ustaadzin wa thuulu zamaanin
Ada variasi lain dari guru Imam Ghazali, yakni Imam Juwaini an-Naishafuri (wafat 1085) :
Dzakaaun, waftiqoorun, wa ghurbatun wa talqiinu ustaadzin wa thuulu zamaanin
Sengaja tidak saya terjemahkan karena ini hafalan luar kepala para santri. Dalam buku tulis, catatan harian dan hati para santri, bait-bait itu tersimpan dengan baik. Saya husnuzhon saja kepada para santri zaman now.
Bait tersebut tertulis di halaman awal dari buku seminal mendiang George Makdisi (wafat 2002), The Rise of Colleges. Ini buku yang harus dibaca oleh siapa pun yang ingin melihat tradisi humanisme Arab yang melompati pagar geografis (Barat-Timur) dan menanggalkan sentimen keberagamaan dan fanatisme kebangsaan.
Makdisi juga mencantumkan ibarah dari Bernard of Chartes ( wafat 1130 M) yang setenaga dengan ibarah Imam Juwaini dan Imam Ghazali:
“Mens humilis (humble mind), stadium quarendi (zeal for learning), vita queita (a quiet life), scrutinium tacitum ( a silent investigation),paupertas (poverty), terra alinea (a foreign land)”. Keenamnya adalah persyarat utama untuk mencapai pengetahuan. Bait ini menjadi motto dalam tradisi humanisme segala bangsa.
Pandangan ideal
Humanisme adalah pandangan ideal tentang manusia yang kemudian terkait dengan tumbuhnya sistem pengajaran dan pendidikan yang membentuk manusia. Humanisme tidak tumbuh dan bangkit di tengah bangsa tertentu, tidak pula dalam tradisi tertentu.
Jika ingin merobek sekat-sekat imaginatif seperti “Barat” versus ‘Timur”, salah satunya adalah dengan menyudahi pandangan bahwa ajaran tentang kemanusiaan ideal itu hanya tumbuh dari serumpun manusia saja.
Harus kita akui, bahwa kecekakan pandangan kemanusiaan kita bermula dari cekaknya pandangan kita akan beragam pandangan kemanusiaan di tengah umat manusia. Ketika ada humanisme Eropa, Arab,India,Cina, maka tentu saja ada humanisme Jawa (Indonesia) atau Afrika.
Saya mengoleksi dua buku tentang humanisme yang ditulis dalam bahasa Indonesia (seharusnya empat,sih): Humanisme dan Sesudahnya : Meninjau Ulang Gagasan Besar tentang Manusia ( Kepustakaan Populer Gramedia,2012) karya F. Budi Hardiman dan Humanisme dan Humaniora: Seri Buku Humaniora Unpar (Universita Prahayangan) yang diedit oleh Bambang Sugiharto ( Penerbit Matahari, Bandung, 2013).
Kedua buku itu sepenuhnya penting, paling tidak alas-kakinya diterbitkan, yakni menelaah ulang humanisme ketika kita sudah tercekik dengan retorika dogmatik agama. Tapi dengan berat hati saya mengkritik kedua buku ini karena hanya menelisik humanisme yang tumbuh dalam tradisi tertentu, baik bangsa maupun agama. Semangat dan imaginasi pemikiran yang melandasi keduanya masih di bawah level buku George Makdisi yang telah saya sebutkan (dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia).
Dalam tulisan ini, saya menyinggung pandangan berbeda tentang humanisme, yakni humanisme yang tidak menekankan tentang asal-usul, baik agama maupun bangsa karena akan menjebak kita jadi asal-asalan.
Maksidi vs Dabashi
Sebetulnya satu alasan saya menulis mengenai humanisme ini karena karena terpicu oleh pertanyaan karib saya, Reza Syihabudi (Kalimantan Selatan) beberapa waktu lalu via whatsapp: apa kritik Hamid Dabashi dalam bukunya, Being A Muslim In The World (Palgrave Macmillan,2013) dan The World of Persian Literary Humanism ( Harvard University,2013) terhadap pandangan guru sekaligus karibanya, Makdisi, soal tradisi adab (yang diterjemahkan Makdisi menjadi “adab humanism’)?
Jawaban saya, bahwa Dabashi menghargai upaya Makdisi memangkas kebiasaan penulis masalah tradisi humanisme sebelumnya yang selalu mengaitkannya dengan pohon kebangsaan seperti “ Yunani” atau “Romawi” karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya.
Apalagi pokok konsentrasi Makdisi dalam bukunya soal pasang-surut dari tradisi adab di tengah masyarakat muslim-Arab di masa lalu yang selalu dikatakan ngutang kepada Yunani dan Romawi. Buku The Rise of Colleges-nya Makdisi melampui itu, dan terobosannya terletak di titik ini.
Kedua, Makdisi membabar data yang sangat detail tentang tumbuhnya kaum “literati” (kurang tepat sebenarnya) di masa awal Arab-Musilm, model dan tradisi pengajaran sastra dan berlanjut kepada pertumbuhan-subur disiplin keilmuwan Islam-Arab yang kemudian dikenal dengan nama ulumuddien.
Karena fokusnya pada pertumbuhan kajian kemanusiaan yang diterjemahkan dalam tradisi sastra, dan kemudian menjadi muasal dari pertumbuhan ilmu hukum, kalam, dan falsafah di tengah Arab-Muslim, Makdisi terjebak ke kubangan sama. Maksidi menekankan aspek hirarki ilmu agama, terutama hukum (fikih), dalam pertumbuhan tradisi humanisme Arab-Islam.
Untuk poin kedua, Dabashi berpendapat bahwa seharusnya tradisi sastra, terutama puisi, adalah tradisi Arab,seperti halnya Persia, yang menjadi sumber utama dari tradisi adab bukan ilmu-ilmu agama, terutama jurispudensi. Bukan terstimulir dari luar semata, terutama kotak imaginatif seperti “Yunani” dan “Romawi” ataupun mitos “Hellenisme Timur” dan “Hellenisme Barat”.
Makdisi alpa menelisik kenyataan ini. Masih dalam poin ini, Dabashi menegaskan bahwa humanisme itu adalah ajaran bumi dalam artian ia bisa tumbuh di tengah sekalian manusia, dan seharusnya tidak dipahami seturut dengan pembagian imaginatif selama ini antara “yang profan-sekular” vis a vis “agama”. Dan masalah ini masih panjang.
Wallahu a’lam bisshowab.




