Jelang Munas Alim Ulama (2): Ulama Aswaja di Lombok Abad ke-18
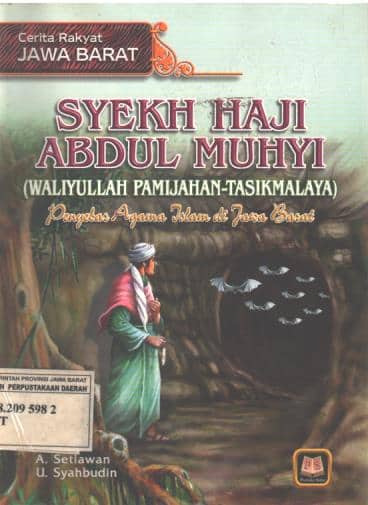
PBNU menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2017 pada 23-25 November 2017 di Lombok Nusa Tenggara Barat. Alif.id turut menyambut hajatan tersebut dengan menurunkan tulisan-tulisan terkait ulama dan terkait Lombok. Tulisan pertama sudah kami terbitkan, kali ini tulisan kedua. Silakan....
------
Ada tiga argumen dari konstruksi kolonial mengenai jaringan ulama. Pertama, menempatkan sentralnya jaringan ulama Jawa (Nusantara) Abad-18 Masehi di Haramain (Mekkah) tanpa menghubungkannya dengan dinamika keislaman di Nusantara pada abad-abad sebelumnya.
Kedua, jaringan ini dianggap sebagai asal-muasal tumbuhnya benih keulamaan dan atau kesarjanaan Islam di Indonesia, karena sebelumnya belum ada. Ketiga, jaringan yang muncul pada akhir abad ke-18 ini dianggap sebagai titik-berangkat dari “Islam yang benar”, yakni Islam yang mengoreksi jenis ‘Islam abu-abu” atau Islam-sinkretik.
Ketiga argumen dari konstruksi kolonial tentang jaringan ulama Jawa abad-18 di Haramain memiliki cacat zahir. Misalnya, masifnya arus perjalanan dari Nusantara ke Tanah Suci pada awal abad ke-18 tidak semata dipicu oleh semangat menunaikan ibadah haji dan memperdalam ilmu agama, tetapi lebih pada sebab menguatnya politik pengawasan kolonial terhadap jaringan ulama di Nusantara. Seperti dimaklumi, sejak abad-16 Masehi akhir, Kolonial Belanda telah mengawasi, mempersempit gerak, dan membasmi jaringan tarekat beserta ajaran tasawufnya untuk menekan militansi dan kuantitas perlawanan pribumi.
Keberadaan jaringan ulama Jawa Abad-18 itu faktual, tetapi harus ditempatkan dalam konteks yang lebih jernih, tidak dalam konteks yang diinginkan oleh kaum kolonial. Bagaimana pun, ulama-ulama Jawa yang mukim di Tanah Suci pada masa itu tetap menjalin hubungan dengan jaringan mereka di tanah air. Produk jaringan ini melahirkan beragam kelompok Islam yang tumbuh di Indonesia sampai saat ini, terutama kelompok tradisional dan kelompok pembaruan (saya tidak memakai istilah modernis di sini).
Banyak perbedaan antara kelompok tradisional dan pembaharuan, tetapi yang paling inti dan sederhana adalah perbedaan soal menerima tasawuf dan tarekat. Mereka yang tradisiona itu disebut juga “aswaja nahdliah”, karena mempertahankan tradisi bersanad, baik fikih, tauhid maupun tasawuf, serta memberi ruang bagi Islam yang didialogkan dengan kebutuhan tanah air dan budayanya. Sementara mereka yang pro pembaruan menolak tasawuf dan negoisasi dengan corak kultural, serta lebih berorientasi pada politik transnasional.
Jaringan keulamaan di Lombok
Pulau Lombok atau dulu disebut sebagai bagian dari Sunda Kecil memiliki senerai panjang jaringan keulamaan sebelum lahirnya organisasi (jamiaah) keislaman seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Satu buktinya, hampir seluruh tuan guru di Lombok hari ini mengaitkan kekerabatannya dengan trah kebangsawanan seperti Bayan, Selaparang dan Pejanggik.
Seperti dicatat Nancy Florida dalam Writing the Past,Inscribing the Future: History as Prophecy in Colonial Java (Duke University Press, 1995), Belanda pada akhir abad-18 Masehi memisahkan pesantren-pesantren, para ulama, dari berbagai hubungannya dengan kalangan Keraton Jawa. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan efektifitas kolonialnyanya.
Artinya, ketika para tuan guru dan kiai menghubungkan diri dengan trah bangasawan, hal itu menunjukkan bahwa di Lombok ada juga tradisi keulamaan yang sejalan dengan tradisi keulamaan di Jawa dan tempat lainnya. Para ulama adalah keluarga bangsawan dan pesantren adalah tempat pendidikan bagi para bangsawan.
Terkait tradisi keulamaan di pulau Lombok, perlu juga saya jelaskan sedikit di sini, bahwa nama Bayan di kaki Gunung Rinjani adalah nama trah atau pam keluarga bangaswan yang terhitung tua dari sejak awal zaman Majapahit, dan diperkirakan sudah memeluk Islam. Muasal trah Bayan ini dari desa Tingkir, di kabupaten Boyolali, Jawa Tengah hari ini. Keluarga Bayan ini sangat dihormati pada zaman Majapahit sehingga salah satu tokohnya,yakni Raden Sengara atau Pangeran Andayaningrat menikah dengan Ratu Pembayun binti Ratu Murdaningrum (istri dari Brawijaya V dan sepupun Sunan Ampel Denta).
Bayan adalah keluarga bangsawan cum ulama. Keluarga Bayan berjejaring secara kekerabatan dan keulamaan dengan Arya Wiraraja (Lumajang),Syeikh Siti Jenar, Sunan Kali Jaga, dan Sunan Ampel Denta sehingga ketika mereka menyebar sampai ke Lombok, trah Bayan lebih dituakan oleh dua trah bangsawan-ulama lainnya, yakni Selaparang dan Pejanggik.
Nama-nama ulama aswaja
Berikut ini adalah beberapa nama ulama Aswaja (ahlus sunnah wal-jamaah) abad ke-18 di pulau Lombok:
Pertama, dari berbagai hagiografi dan catatan terkait dengan sosok Syeikh Muhyi Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat, bahwa beliau lahir pada kisaran tahun 1650 Masehi di Mataram, Lombok daris seorang ayah bernama Lebe Werto-Kusuma yang keturunan Ratu Galuh, Jawa Barat. Sebutan “lebe” adalah sebutan umum di Lombok kepada seorang ulama sebelum ada istilah tuan guru seperti hari ini. Misalnya, masyarakat Sasak mengenal Lebe Walandana, seorang dipercaya sebagai sosok wali keramat yang meninggalkan jejak di sisi barat pantai Lombok Barat. Bahkan sampai tahun 1980-an, beberapa tuan guru masih disebut sebagai “menak-lebe” atau priyayi-ageng dalam bahasa Jawanya.
[caption id="attachment_205599" align="alignnone" width="300"] Makam Syeikh Muhyi (foto: tripadvisor.com)[/caption]
Makam Syeikh Muhyi (foto: tripadvisor.com)[/caption]
Syeikh Muhyi yang dikenal sebagai penyebar ajaran martabat tujuh di Jawa menghabiskan waktu kecil dan remaja di Mataram, sebelum akhirnya ke Gresik, Jawa Timur, dan kemudian melanjutkan perjalanan keilmuwannya ke Aceh. Syeikh Muhyi diinisiasi dalam sejumlah tarekat oleh gurunya, Syaikh Abdul Rauf bin Ali al-Jawi al-Singkili al-Fansuri (lahir 1615 Masehi), seorang ulama sufi kedua setelah generasi Syeikh Hamzah Fansuri di Sumatera, dan dikenal sebagai ulama yang sangat alim dan keramat. Setelah dari Aceh, Syeikh Muhyi ke Cirebon dan kemudian menetap di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat. Karena tingginya pencapaian keulamaannya, Syeikh Muhyi dikenal sebagai Wali Kesepuluh di Jawa.
Kedua, dalam buku Ajaran Tarekat Naqsyabandiyah karangan H.M Nursiah, yang dicetak oleh percetakan Bintang Timor, Pancor, Lombok Timur,tahun 1995 disebutakan sosok bernama Raden Kurani dari trah Selaparang yang pernah belajar kepada Syeikh Yusuf Al-Makassari di Banten. Maklum pada akhir 1600-an ulama keturunan bangsawan Makassar ini berkalaborasi dengan dengan Sultan Ageng Tirtayasa (1650-1695 M) dari kesultanan Banten melawaan VOC Belanda. Nama “Kurani” adalah pemberian Syeikh Yusuf, nama yang diambil dari nama guru Syeikh Yusuf di Haramain, Yakni Syeikh Ibrahim Al-Kurani, seorang ulama Kurdi yang sangat berpengaruh di Tanah Suci pada akhir abad-17 Masehi.
Raden Kurani kembali ke tlatah Lombok saat memuncaknya perlawan sultan Banten terhadap VOC Belanda. Disebutkan, bahwa tokoh ini termasuk generasi awal yang membawa ajaran martabat tujuh dengan penjelasan yang merujuk kepada kitab Tuhfatul Mursalah karya Syeikh Burhanapuri, yang nantinya diberikan penjelasan panjang (syarah) oleh Syeikh Ibrahim al-Kurani dalam kitab Ithafud Dzaaki, ke pulau Lombok. Bukan ajaran martabat tujuh versi loka ala Sunan Kali Jaga, walaupun keduanya memiliki banyak persamaan.
Dalam catatan lain, Raden Kurani ini merupakan salah satu dari empat putera Raden Kautan Mundur dari Selaparang, Lombok Timur. Urutan adik-kakaknya sebagai berikut: Wirabangse, Putra Sari, Kurani, dan Nanglung Baya. Dalam catatan itu disebutkan pula, bahwa kakek Raden Kurani bernama Kyai Aji memiliki bersambung sanad keilmuwannya dengan Syeikh Syamsuddin Sumatrani, seorang pelanjut ajaran Wujudiyah Syeikh Hamzah Fansuri di Aceh. Syeikh Syamsudin Sumatrani dikenal memiliki banyak karya, seperti Jauharul Haqaiq, Risalah Tubayyin Mulahdzhaatil Muwahiddin fi Dzikrillah, Syarah Rubai Hamzah Fansuri,dan lainnya.
Ketiga,berbeda dengan dua sosok sebelumnya, di desa Sekarbela, karang Pule, Mataram, terdapat sosok ulama yang sangat alim dan keramat bernama Tuan Guru Mustafa Kamal. Diperkirakan lahir pada pertengahan 1700-an, Tuan Guru Mustafa Kamal adalah tokoh yang berperan penting dalam membentuk desa Sekarbela sebagai salah satu desa dengan tradisi kepesantrenan yang sangat kuat, dan menurunkan ulama Aswaja sampai hari ini. Sekarbela yang dikenal sebagai salah pusat kerajinan dan perdagangan perhiasan memiliki tradisi ilmu alat (nahwu-shorof dan balaghah) dan fikih yang sangat disegani di pulau Lombok sampai detik ini.
Tiga ulama ini yang bisa disebutkan sebagai generasi ulama Aswaja menjelang akhir abad ke-19 di pulau Lombok. Selain ketiganya terdapat beberapa ulama lainnya, tetapi tiga sosok ini dipilih karena lebih untuk membuktikan adanya jaringan keulamaan Nusantara sebelum akhir abad-19 Masehi. Wallahul ‘alam bishowab.




