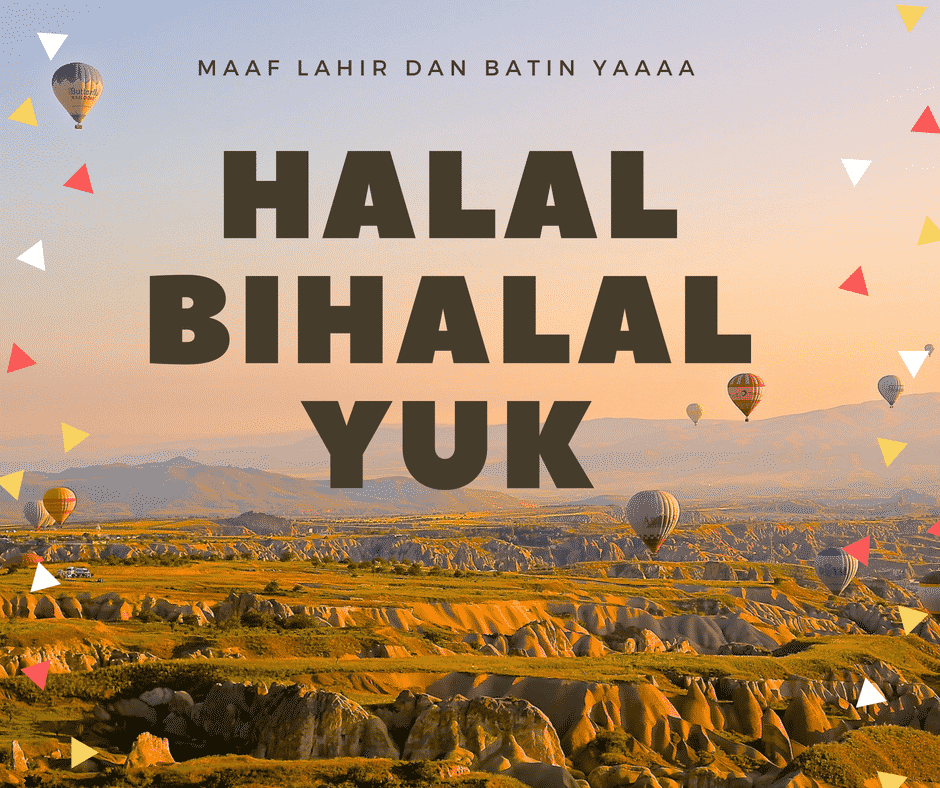Belakangan Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto giat meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah-sekolah. Ia ingin memastikan bahwa program prioritas pemerintahannya itu berjalan baik. Dengan pamrih anak-anak Indonesia itu terjamin asupan gizi-nya agar kelak mampu tumbuh sehat, cerdas dan memiliki masa depan yang lebih baik.
Bagi Prabowo makanan bergizi punya korelasi dengan kecerdasan otak dan bergaransi pada cerahnya masa depan anak-anak Indonesia kelak. Namun, apakah persoalan pangan benar-benar punya korelasi dengan kualitas pendidikan, utamanya tingkat kecerdasan seorang anak? Apakah kebijakan pemerintah ini tepat sasaran atau malah meleset.
Kebijakan ini memantik pelbagai macam reaksi dari masyarakat. Pro dan kontra hadir ditengah kehidupan masyarakat luas. Salah satu afirmasi positif datang dari Cendekiawan Nahdlatul Ulama yaitu, Ulil Abshar Abdalla. Ia menulis pandangannya dalam kolom Analisis Politik Harian Kompas 16 Januari 2025 berjudul Janji Politik Prabowo dan Sinisme Publik. Di kolom itu, Ulil menjabarkan panjang kali lebar tentang pendapatnya terkait salah satu janji politik Prabowo pada masa kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) silam.
Ulil cukup terkesan dengan kecepatan realisasi janji politik Prabowo itu. Menurutnya langkah cepat ini harus diapresiasi sebab janji politik ini dinilai mahal dan sangat kompleks dalam manajemen pelaksanaannya juga anggaran untuk program itu. Ia juga menyoroti respon sinis publik terhadap agenda besar itu. Baginya publik terlalu menaruh rasa skeptis berlebih terhadap janji politik para politisi kita.
Ia menulis, “Bahkan sejak lama sudah muncul gejala sinisme publik terhadap para politisi karena janji-janji politik yang mereka suarakan itu hanya sebagian kecil atau malahan sama sekali tidak ada yang ditunaikan. Ketika mendengar kampanye politisi dalam perhelatan pileg, pilpres atau pilkada, publik sudah mulai pasang kuda-kuda: janji apalagi ini?”. Di akhir kolom, Ulil menyerukan sebuah anti-tesis, “Ditengah-tengah sinisme publik yang begitu meluas terhadap janji politik para politisi itu. Tiba-tiba ada janji yang benar-benar ditunaikan dan dalam waktu yang relatif cepat”.
Pendapat Ulil Abshar Abdalla tidak sepenuhnya salah, namun perlu mendapat koreksi sahaja. Persoalan tentang realisasi janji politik seorang politisi itu sudah menjadi keharusan dan tanggung jawab moral-sosial mereka. Sebagai pemangku kebijakan, seorang politisi seyogyanya mampu melahirkan program yang universal (mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat) juga sesuai kebutuhan riil dan paling fundamental ditengah masyarakat. Pertanyaannya kini yaitu apakah program MBG itu sudah relevan dengan permasalahan mendasar masyarakat kita? Program itu malah terlihat latah, terkesan buru-buru dan sejatinya tak ada hubungannya dengan masalah fundamental yang mengidap sistem pendidikan kita.
Preseden Masa Lalu
Dalam tonggak sejarah pemerintahan di Indonesia, kita belum pernah menemui preseden yang serupa dengan program MBG. Sebagai seorang pemerhati sejarah, kita selalu belajar bahwa sejarah sering memberi kita pembelajaran tentang peristiwa heroisme, romantika, tragedi maupun pengalaman minor yang jarang terungkap. Sejarah menawarkan lanskap lain dalam memandang suatu peristiwa.
Program MBG memang belum mempunyai akar kesejarahan di masa lalu. Hal ini malah memantik kita untuk menelisik tentang apa saja konsumsi makanan para tokoh bangsa terdahulu. Apakah pangan yang mereka makan dahulu memiliki kandungan gizi tinggi sehingga mampu melahirkan pikiran maupun gagasan besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Kita mendapati beragam kisah unik dalam kehidupan para tokoh terdahulu. Salah satu contohnya datang dari Mahbub Djunaidi, ia merupakan tokoh yang mempunyai banyak sumbangsih di bidang jurnalistik, politik Islam dan sastra di Indonesia. Mahbub dalam salah satu romannya berjudul Dari Hari ke Hari mengisahkan tentang makanannya saat kecil. Waktu itu, ia sekeluarga sedang dalam pengungsian di Kota Solo.
Ia menulis,”atas nama penghematan, semua makan bubur, demikian keputusan ayah. Bagaimanapun, bubur masih bagian lebih lanjut daripada nasi, artinya derajatnya lebih tinggi dari jagung apalagi gaplek. Bubur dapat menghemat sepertiga beras, bahkan jika dibuat lebih encer bisa menghemat seperlima konsumsi beras tiap harinya”. Kecamuk revolusi yang berkobar di seluruh penjuru Indonesia membuat keluarganya harus melakukan penghematan. Terbukti berkat konsumsi bubur tiap harinya, Mahbub dapat tumbuh menjadi salah satu orang hebat di zamannya. Ia mampu menjadi jurnalis, aktivis politik sampai sastrawan dalam satu tarikan nafas.
Bergayung sambut, pengalaman serupa juga dialami oleh Kiai Abdul Hamid Sumbergirang yang kemudian masyhur dikenal sebagai Kiai Hamid Pasuruan. Kiai Hamid mengisahkan perjuangannya sewaktu sedang menimba ilmu di Pondok Pesantren Tremas Pacitan. Waktu itu, uang saku kiriman dari ayahnya di Lasem hanya cukup untuk membeli nasi thiwul sebagai pemenuhan kebutuhan pangannya. Berangkat dari nasi thiwul ini-lah, Kiai Hamid mampu tumbuh menjadi seorang Kiai kharismatik yang menguasai segudang keilmuan Islam meliputi ilmu Fiqh, Hadits dan Tafsir. Ia juga terkenal dengan pelbagai karamah-nya sebagai waliyullah.
Peristiwa tentang pangan saat masa menempuh pendidikan juga kita dapati dalam kisah perjalanan seorang Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sewaktu menimba ilmu di salah satu kampus di Baghdad. Cerita itu dapat kita temukan dalam buku berjudul Biografi Gus Dur Garapan Greg Barton (2002). Di buku itu, Barton mengisahkan “dalam rangka penghematan uang beasiswa, Gus Dur waktu itu gemar membeli kepala ikan kemudian diolah menjadi kari kepala ikan yang lezat. Di Irak, orang-orang tidak memakan kepala ikan dan menganggap barang itu sebagai limbah untuk pakan hewan peliharaan”. Dengan cerdik, Gus Dur mampu memanfaatkan limbah tersebut guna memenuhi kebutuhan pangan dan gizi-nya bersama teman seperantauannya. Ide dan gagasan besar Gus Dur tentang demokrasi, perdamaian dan pemikiran tentang agama yang terbuka (inklusif) agaknya berasal dari olahan kepala ikan tersebut, selain didukung lewat lingkungan intelektualisme yang mendukung.
Masalah Pendidikan Kita
Jika kita ingin berbicara lebih jujur dan memandang suatu hal secara objektif. Sejatinya, masalah fundamental yang menjangkit ekosistem pendidikan kita bukanlah kurangnya pasokan gizi seorang murid tatkala sedang belajar. Permasalahan mendasar itu terletak pada buruknya lingkungan intelektualitas dalam sistem pendidikan kita. Mulai dari minimnya ketersediaan buku di rak-rak perpustakaan maupun ketersediaan ruang literasi itu sampai nihilnya kegiatan akademis yang erat bersinggungan dengan buku. Hal demikian tentu sangat mempengaruhi minat (etos) baca masyarakat akademik kita.
Sederet permasalahan dalam ekosistem pendidikan kita tak berhenti disitu. Kita juga sering dihadapkan dengan permasalahan teknis dan non-teknis lainnya meliputi jaminan kesejahteraan guru, peningkatan kualitas guru sampai kurangnya distribusi guru di daerah pelosok tertinggal dan terluar.
Arkian, program MBG nyatanya belum menyentuh akar permasalahan dalam sistem pendidikan kita. Berkaca dari pengalaman para tokoh bangsa terdahulu, bahwa tingkat kecerdasan seseorang tidak diukur lewat asupan gizi yang mereka makan setiap harinya. Tingkat kecerdasan itu mereka asah lewat giat tinggi dalam belajar dan juga didukung oleh lingkungan intelektual yang mendukung. Di beberapa momen, kecerdasan seseorang didapat dalam kondisi keterpurukan, serba kesusahan bahkan dalam kondisi perut keroncongan. Bukan datang lewat kondisi serba kecukupan dan kemudahan. Begitu!